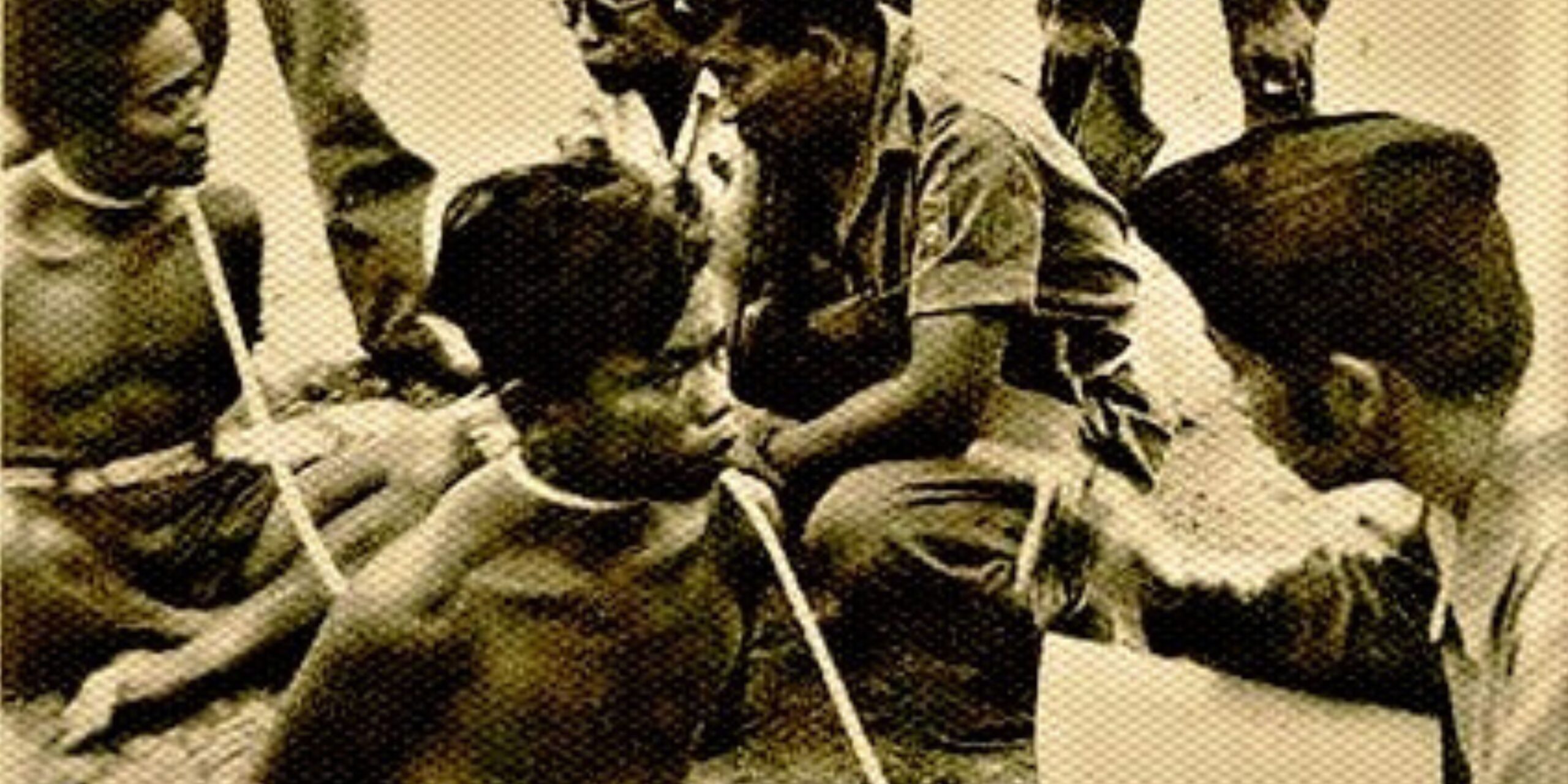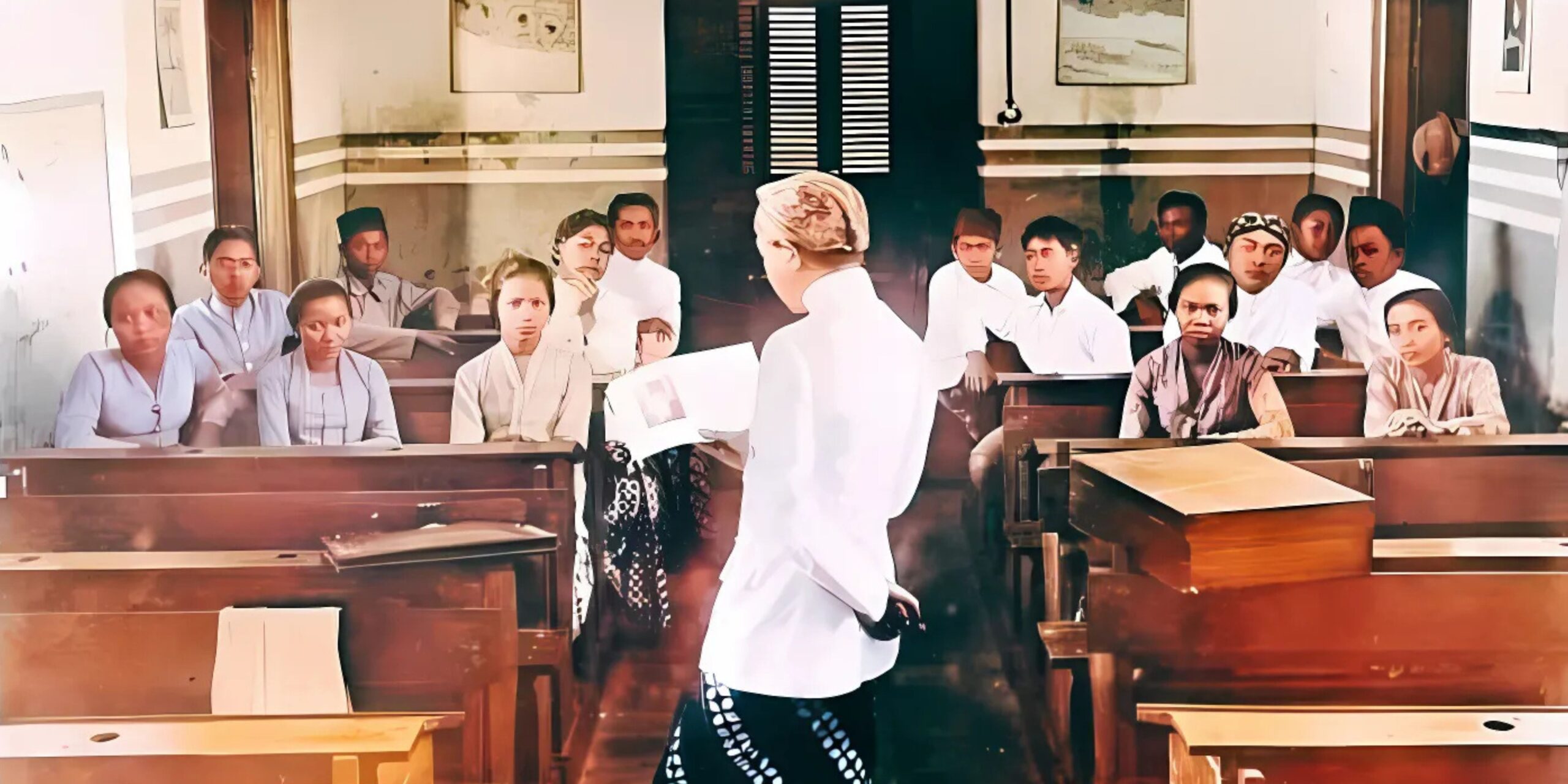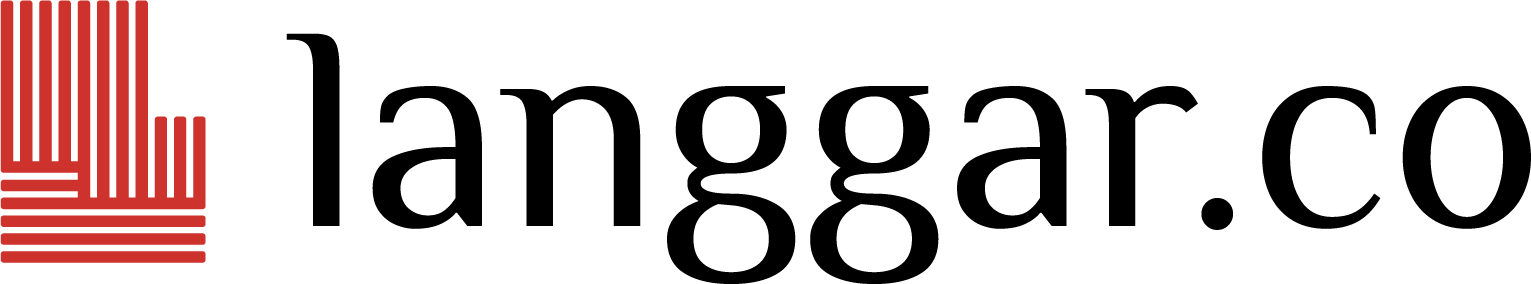Sewulan dan Lahirnya Raja: Sebuah Kisah yang Terlupakan
Selama bertahun-tahun, beredar sebuah narasi yang diyakini sebagai asal-usul Perdikan Desa Sewulan. Cerita yang diwariskan secara lisan ini menyebut bahwa tanah perdikan diberikan oleh Pakubuwono II sebagai bentuk balas jasa...