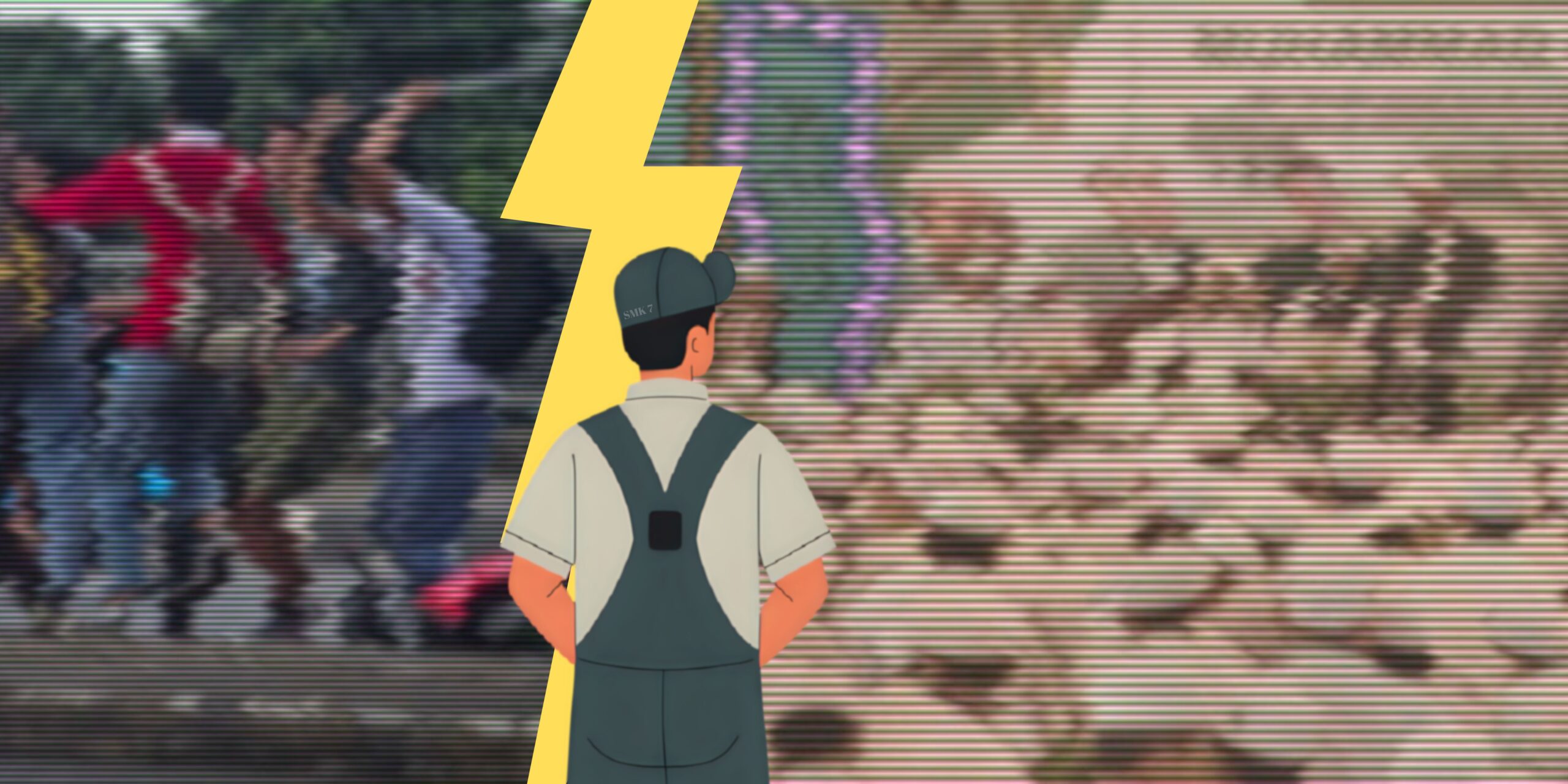
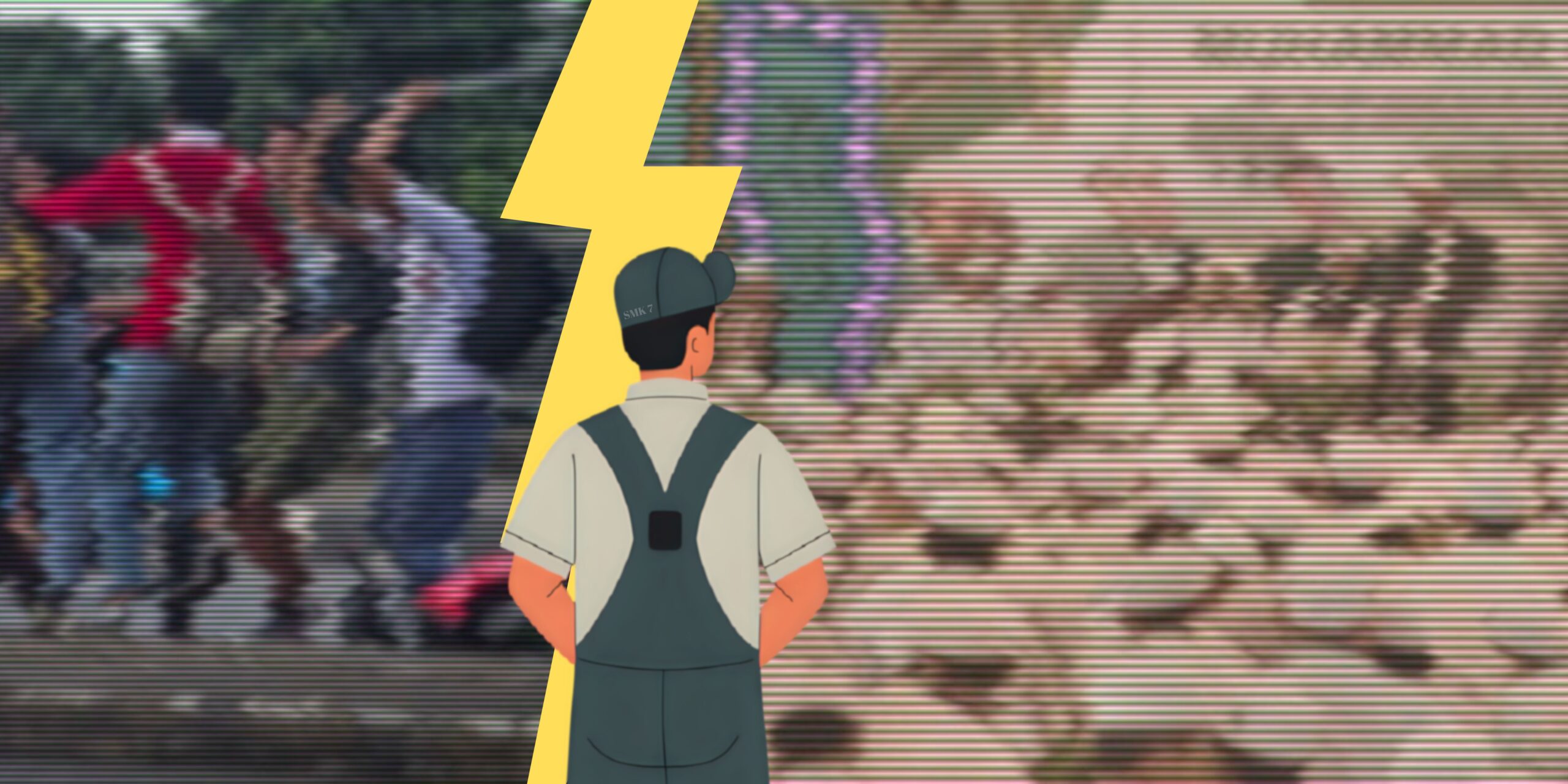

Membantah Pembacaan Sulak atas SGA
I Esai kritis A.S. Laksana—atau Sulak, “Hantu Pohon Seno Gumira dan Sastra yang Bersuara” di...

Wayang Menak: Upaya Manusia Sasak Menggali Hakikat Kediriannya
Jika ditanya, tradisi atau budaya apa yang paling tepat untuk menyampaikan koreksi atas jalannya suatu...

Tradisi Malamang: Antara Ritus Komunal dan Makna Sosial
Sejak tahun 2021, tradisi malamang yang dipraktikkan oleh masyarakat Minangkabau, khususnya wilayah Padang Pariaman, Sumatra...

Raga Kayu, Jiwa Manusia: Wayang Golek dan Upaya Menerjemahkan Islam
Lima tahun lalu, saya mendapati buku ini dari pemberian seorang teman setibanya di Bandung....

Jimat, Pemberontakan, dan Kaum Kolonial
Sejak arus modernisme melanda kehidupan di Bumi Nusantara, segala hal yang berbau klenik, mistis, atau...

Yang Luluh Lebur Merindu: Kumpulan Puisi Helmi Y. Haska
YANG LULUH LEBUR MERINDU akulah ngengat liar itu yang berputar-putar di sekitar cahayamu (yang kini...

Menambang Esai di Sukorejo
“Korjooo! Korjoooo! Korjoooooooooooooo!” Kernet berpeci hitam nasional itu memekik seraya membenturkan cincinnya ke besi pegangan...

Cerita Hantu Sebagai Politik Ingatan
Saya belum terlalu lama mengikuti konten-konten di kanal media sosial Gen Alfarizi, tapi saya cukup...

Aksara dan Imperialisme Budaya
Suatu ketika, saya berkesempatan mengunjungi perpustakaan Mangkunegaran, Solo. Biar kelihatan ngintelek, saya serius menanyakan dokumen...

Kematian yang Penuh, Ada Magma dalam Tubuhku. Catatan atas The Death of Dance oleh Fitri Setyaningsih
Kematian dance dikabarkan terjadi di Sakatoya Collective Space, padukuhan Jaranan, Panggungharjo, Sewon, Bantul. Kematian itu...

