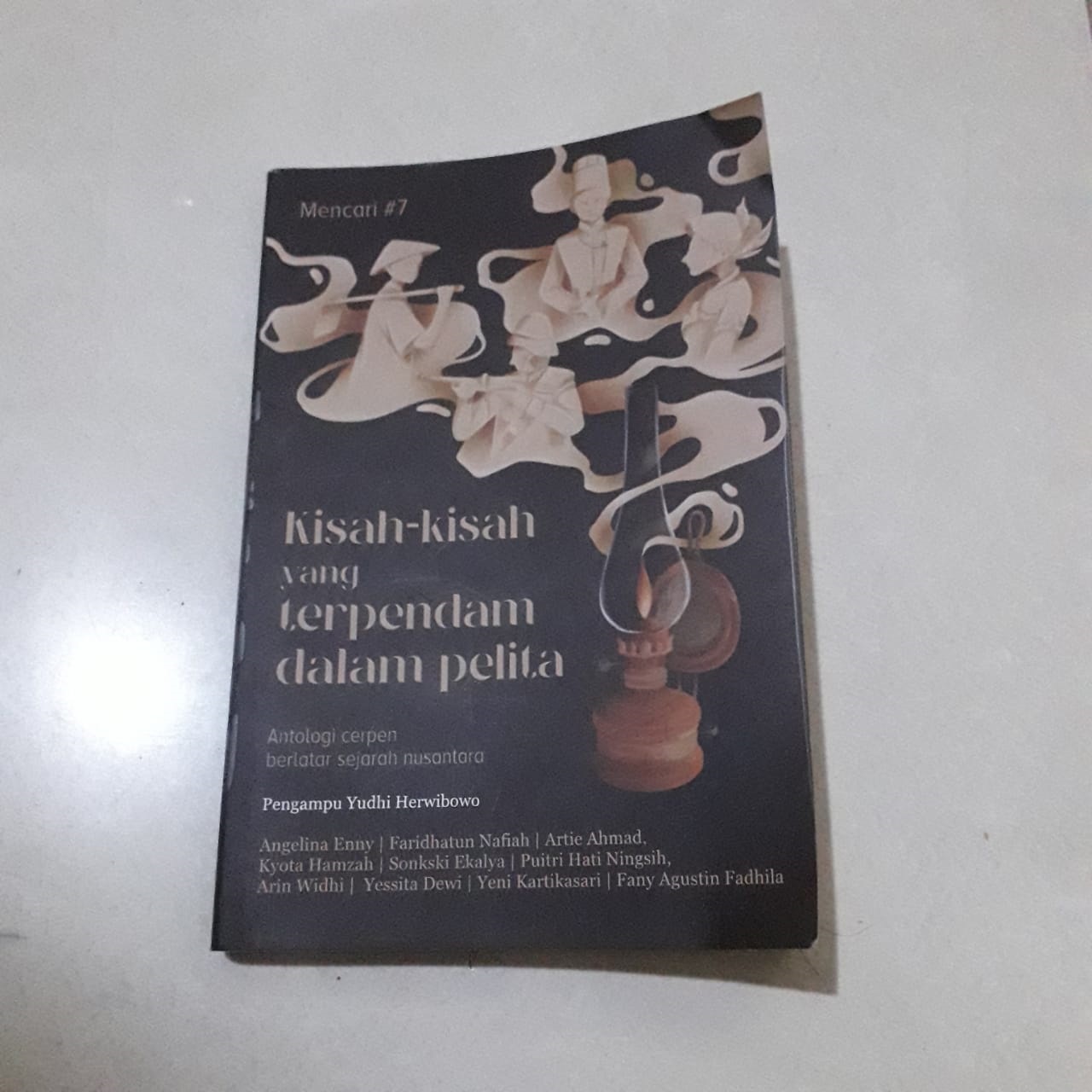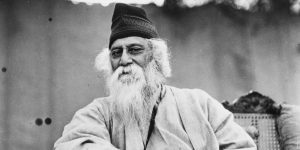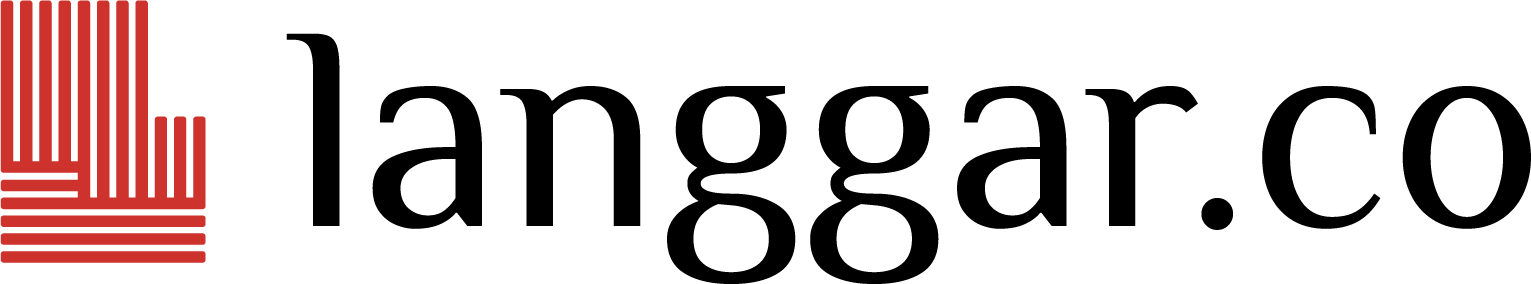Orientasi “Islam Nusantara”: Melahirkan Insan (Kamil) Nusantara!
“Islam Nusantara” dan Tempatnya dalam Sejarah Islam Dunia Saya pernah punya pengalaman tersinggung dan marah, namun tidak tahu kepada siapa (mungkin mesti ditujukan kepada diri...
“Islam Nusantara” dan Tempatnyadalam Sejarah Islam Dunia
Saya pernah punya pengalaman tersinggung dan marah, namun tidak tahu kepada siapa (mungkin mesti ditujukan kepada diri sendiri), ketika membaca buku Karen Armstrong berjudul Islam A Short History yang terbit pertama kali tahun 2000 dan dalam edisi Indonesia tahun 2002. Buku sejarah yang “lengkap dan ringkas” ini berkisah tentang pasang surut sejarah Islam di dunia yang fana ini, disertai kronologi dari mulai zaman Jahiliyah dan lahirnya Nabi Muhammad SAW (abad VI–VII M) sampai dengan era Muhammad Khatami, Presiden Iran yang pada tahun 1998 membebaskan pemerintahannya dari fatwa Khomeini atas Salman Rushdie yang novelnya dianggap menghina Nabi Muhammad SAW. Armstrong juga berbicara tentang problem minoritas muslim di Eropa dan Amerika, wacana tentang “negara Islam modern”, “fundamentalisme” dan sejenisnya. Tapi “aneh” tak ada satu pun kata Indonesia disebut dalam bukunya itu apalagi mengenai sejarah keislamannya maupun dilema-dilema dan eksperimentasi keberagamaan penduduk muslimnya, yang konon terbesar di dunia ini. Apa makna dari fakta ini? Paling tidak kita tahu bahwa eksperimentasi umat Islam Indonesia, yang berakar pada “Islam Nusantara”, masih sering diabaikan atau belum menemukan (ditemukan) makna dan tempatnya yang layak dalam peta dunia Islam.
Adakah yang bisa disebut “Islam Nusantara”? Adakah bedanya dengan “Islam di tempat lain”, juga bagaimana kaitannya dengan “universalisme Islam”? Apakah “Islam Nusantara” hanya efek atau gema dari “pusat dunia Islam”? Sejauh mana kita bisa membicarakan karakteristiknya? Apakah kita bisa berbicara tentang era kodifikasi (asrut tadwin)dari “Islam Nusantara” itu? Bagaimana kita menentukan korpus-korpus yang menjadi rujukan otoritatif periode (juga konfigurasi) sejarah yang membentuknya? Apakah “Islam Nusantara” mempunyai “manhajul fikr” yang spesifik, atau bahkan unik? Bagaimana kita mesti membincangkan, meneladani, dan mengembangkannya untuk konteks zaman sekarang? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas tentu saja membutuhkan elaborasi yang komprehensif dan pendekatan yang multidisipliner, sekaligus merupakan agenda kerja kolektif suatu generasi. Ruang untuk menjawabnya pun tentu bukanlah artikel yang sangat terbatas semacam ini. Oleh karena itu, di sini saya tidak berpretensi untuk menjawab tuntas persoalan itu. Namun hanya menyampaikan hipotesis yang bisa saya sampaikan berdasarkan pembacaan kritis terhadap naskah-naskah dan kitab-kitab karya ulama nusantara abad-abad lalu (abad XVI–XIX), dengan berbagai konteks historisnya.
Adakah yang bisa disebut “Islam Nusantara”? Adakah bedanya dengan “Islam di tempat lain”, juga bagaimana kaitannya dengan “universalisme Islam”? Apakah “Islam Nusantara” hanya efek atau gema dari “pusat dunia Islam”? Sejauh mana kita bisa membicarakan karakteristiknya? Apakah kita bisa berbicara tentang era kodifikasi (asrut tadwin)dari “Islam Nusantara” itu? Bagaimana kita menentukan korpus-korpus yang menjadi rujukan otoritatif periode (juga konfigurasi) sejarah yang membentuknya? Apakah “Islam Nusantara” mempunyai “manhajul fikr” yang spesifik, atau bahkan unik? Bagaimana kita mesti membincangkan, meneladani, dan mengembangkannya untuk konteks zaman sekarang? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas tentu saja membutuhkan elaborasi yang komprehensif dan pendekatan yang multidisipliner, sekaligus merupakan agenda kerja kolektif suatu generasi.
Tampaknya perdebatan para ahli untuk berteori tentang “kapan mereka ke Nusantara”, “dari mana awalnya”, “siapa pembawanya” dan “apa sekte keagamaannya” tidaklah mesti dibaca sebagai semacam perlombaan lari atau teka-teki untuk mencari satu pemenang yang paling cepat dan paling benar. Tetapi hendaknya dinikmati seperti puzzle di mana setiap penemuan teori dianggap sebagai “satu yang tidak sempurna”, yang harus dicarikan potongan teori lainnya untuk digabungkan atau dihubung-hubungkan atau dikombinasikan dengan berbagai cara, baik menyamping, menyilang, atau memutar, sehingga memperoleh bentuk atau gambar yang semakin mendekati kesempurnaan, demikian terus-menerus. Oleh karena tidak dapat dibayangkan, bahwa lslam masuk ke Nusantara pada satu waktu tertentu, dari satu tempat tertentu, oleh seorang atau sekelompok orang dengan profesi, motif, dan identitas keagamaan yang homogen, kemudian secara linear berkembang dan menyebar ke seluruh Nusantara, ini jelas tidak realistis. Pembawa Islam ke Nusantara berasal dari wilayah yang beragam, dari Arab, India, Campa, Tiongkok, Persia, Asia Tengah, dan lain-lain, dengan status, profesi dan motif serta mazhab yang berbeda-beda, dan walau pun waktunya beragam (antara abad VII–XV), tapi bisa jadi mereka semua adalah sama-sama yang “pertama”, karena konteks wilayah mereka pertama kali mendarat yang berbeda-beda.
Pedagang Arab Muslim zaman Khalifah Ustman bin Affan (jadi jelas dia bukan Sunni/Syiah/Khawarij/Muktazilah) yang singgah di Palembang atau Barus (Sumatera Utara) mungkin saja dia (sengaja atau tidak sengaja) mengislamkan satu-dua orang di sana atau meninggalkan salah satu anggota rombongan di sana, dan ia bisa disebut sebagai pembawa Islam yang pertama di Nusantara. Lalu, ketika pada abad IX ada serombongan “pelarian politik” Syiah yang dikejar-kejar pasukan Dinasti Umayyah mendarat di Perlak (Aceh Timur) membangun komunitas Muslim dan mendirikan kerajaan Islam di sana, mereka juga bisa disebut yang pertama membawa Islam ke sana. Demikian pula antara abad X–XII, ketika pangeran Dinasti Umayyah atau Abbasiyah beserta pasukannya yang Sunni, atau dari Dinasti Fatimiyah yang Syiah, entah karena perpecahan politik wilayahnya masing-masing atau karena berekspansi (diaspora) lalu mendarat di berbagai wilayah Aceh lainnya, dan membangun kerajaan Islam yang lain. Atau juga ketika Syekh “Samsu Zen” datang ke Kediri pada abad X–XI dan menjadi guru rohani Prabu Jayabaya. Atau ketika rombongan Fatimah binti Maimun datang ke Gresik dari Persia lalu membangun komunitas muslim di sana. Demikian pula, para sufi yang mengembara pada abad-abad berikutnya dan menyebarkan Islam ke berbagai wilayah Nusantara lainnya (Jawa, Kalimantan, Sulawesi, atau Lombok) yang belum ada umat Islamnya di sana, mereka dalam derajat tertentu juga bisa disebut yang pertama membawa Islam ke Nusantara.
Oleh karena itu, setelah kita kombinasikan dengan berbagai teori “kedatangan lslam” di atas yang perlu kita lakukan adalah menempatkannya dalam konteks “sejarah dunia” khususnya “dunia Islam” waktu itu di satu sisi, dan di sisi lain “sejarah lokal-Nusantara” sendiri pada waktu yang bersamaan. Tentu saja, maksud konteks sejarah di sini dalam pengertian studi sejarah yang multidisipliner, meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dengan demikian, kita akan memperoleh “gambar” tentang sejarah “Islam Nusantara” secara lebih jelas dan hidup. Kemudian, di dalam “gambar hidup” itulah kita menempatkan dan melakukan pembacaan secara kreatif, produktif, terhadap teks-teks keagamaan dalam berbagai bentuknya, yang ditulis oleh para ulama Nusantara. Sehingga gambar hidup itu semakin hidup, dan dari situ kita bisa lebih mengenali karakteristik dari “Islam Nusantara” secara lebih baik.
Oleh karena itu, setelah kita kombinasikan dengan berbagai teori “kedatangan lslam” di atas yang perlu kita lakukan adalah menempatkannya dalam konteks “sejarah dunia” khususnya “dunia Islam” waktu itu di satu sisi, dan di sisi lain “sejarah lokal-Nusantara” sendiri pada waktu yang bersamaan.
Dalam kerangka ini, “Islam Nusantara” yang bisa diartikan sebagai kultur Islam yang berkembang dalam konteks Nusantara yang khas, terutama pada abad XIII–XIX M, dapat menjadi wilayah studi yang penting. Untuk itu, ia mesti dibedakan dengan studi “Islam lokal” dan “Islam lndonesia” karena muatan, konteks, dan kronologi historisnya yang memang berbeda. Walaupun ketiganya berkaitan erat dan saling mengandaikan namun studi “Islam Nusantara” masih lemah. Padahal sesungguhnya studi “Islam Nusantara” adalah wilayah studi yang semestinya dikembangkan untuk menjadi jembatan kreatif antara studi “lslam lokal” dengan “lslam lndonesia”.
Tasawuf, Spirit Ibnu Arabi dan Karakteristik “Islam Nusantara”
Sepertinya perubahan dahsyat “dunia” di abad XIII – ketika bangsa Mongolia menghancurkan pusat terpenting dari kebudayaan Islam era Bagdad, serta menundukkan sebagian besar Asia dan menyusup ke dalam wilayah Eropa, dan dengan demikian menghentikan tata susunan politis yang telah lama mapan dan membinasakan wilayah-wilayah luas kebudayaan (termasuk di sini paradigma ilmu keagamaan) yang telah sangat berkembang – justru menghasilkan, berkebalikan dengan pembinasaan itu, terjadinya suatu peningkatan aktivitas mistik, gagasan-gagasan, spiritualitas, dan literasi puitis. Tidak hanya dalam dunia Islam, tetapi juga seluruh Eropa dan Asia, termasuk wilayah Nusantara.
Tak pelak lagi, salah satu sumber utama dalam “kebangkitan spiritual dunia” tersebut adalah ajaran-ajaran, hikmah-hikmah, serta skema “futuhat” dari seorang pengembara, ahli hadis, fikih, teolog, pemerhati politik, filosof, dan sastrawan, Syekh Muhyiddin lbnu Arabi yang lahir di Murcia Spanyol tahun 1165 M dan wafat di Damaskus, Syria tahun 1240 M. Ahmad Sirhindi yang biasanya dianggap penentang Ibnu Arabi, harus mengakui: “Para sufi sebelum lbnu Arabi bila mereka membicarakan perkara ini hanya menyinggung sedikit saja dan tidak menguraikannya panjang lebar. Para sufi sesudah dia memilih mengikuti jejaknya dan menggunakan peristilahannya. Kita yang datang kemudian ini juga memanfaatkan berkah orang besar ini dan belajar dari pandangan-pandangan mistisnya. Semoga Tuhan memberikan kepadanya pahala yang terbaik bagi jasanya”.
lbnu Arabi[1] tumbuh di lingkungan Sunni, pada masa Dinasti Al-Muwahidun, di Andalusia. Beliau belajar Quran, hadis, tasawuf, teologi, fikih, dan ilmu-ilmu kebahasaan kepada para sufi Barat (Maghrib) dan ulama-ulama Malikiyyah yang memang dominan di sana dan juga para ulama Dzahiriyyah pengikut Ibn Hazm. Demikian pula beliau berguru kepada para sufi dan ulama Timur (Masyriq). Namun, beliau tidak terikat pada satu mazhab mana pun. Sistem-sistem mazhab itu tidak dijadikan “kerangkeng” bagi jiwanya sendiri atau pada jiwa orang lain para pengikutnya, namun justru jadi titik tolak “pengembaraan” spiritualnya. Dalam pengembaraan spiritual itu, hatinya menjadi lentur, luwes dan mengembang luas, sehingga dia bisa mengatasi perbedaan-perbedaan berbagai sistem keyakinan dan syariat, baik di kalangan internal umat Islam, antar agama-agama Ibrahimiah, antar agama-agama langit dan bumi, bahkan para ateis, dan mengajak mereka bersama-sama memasuki dan menempuh “agama cinta”.
Intoleransi dalam menghadapi perbedaan-perbedaan dalam masalah agama seperti termanifestasi di dalam mazhab-mazhab fikih, yang disebabkan karena ulama berhenti pada segi lahir dari ajaran dan dipasangi dengan kesempitan jiwa yang melahirkan sikap fanatisme ekstrim terhadap mazhab, dalam pandangan lbnu Arabi merupakan musibah terbesar dan rintangan terberat dalam beragama, yang mesti dikritik dan diatasi:
“Allah telah menjadikan perbedaan pendapat dalam menyikapi persoalan hukum sebagai rahmat bagi para hamba-Nya dan kelonggaran (ittisa’) atas perintah-Nya yang mereka laksanakan demi kebaikan mereka. Namun terkait, dengan orang-orang yang mengikuti fukaha di zaman kita, para fukaha ini telah melarang dan mempersempit apa yang telah diperluas Hukum Suci bagi mereka. Mereka mengatakan pada pengikut mazhab mereka, misalkan ia seorang Hanafiyyah; “jangan mencari rukshah (hal yang meringankan) dari Syafi’i mengenai persoalan yang tengah kamu hadapi”; dan demikian seterusnya. Ini musibah terbesar dan rintangan terberat dalam masalah agama. Allah berfirman: ‘Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan’ (QS. Al-Hajj (22): 78). Hukum telah menyatakan kebenaran status siapapun yang berijtihad untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang mengikutinya. Tapi zaman kita, para ahli hukum telah mencela ijtihad dengan menyebutnya sebagai upaya mendorong umat untuk menghina agama. Bagi mereka, ini tindakan yang sangat bodoh.”[2]
Oleh karena itu lbnu Arabi mendorong dirinya sendiri dan murid-muridnya untuk mengatasi kemandekan beragama dengan mengembangkan aspek-aspek penalaran lahiriah di mana setiap persoalan hukum agama berhenti di situ. Manusia mesti mengembangkan sisi lain dari kehidupan yaitu dimensi batin yang mesti dieksplorasi:
“Aku berniat, jika Allah memberi umur panjang menyusun sebuah kamus penting yang akan membahas semua persoalan hukum yang berkisar pada aspek aspek lahirnya: pertama-tama dengan merumuskan dan menguraikan setiap persoalan dari sudut pandang lahir, lalu menelaah kedudukannya terkait dengan sisi batin manusia (hukumuha fi bathin insan).”[3]
Walaupun Ibnu Arabi tidak berkesempatan mewujudkan niatnya, namun di dalam Futuhat, beliau meluapkan beratus-ratus halaman untuk membahas rukun Islam dan persoalan hukum yang sedang berkembang pada massanya. Ibnu Arabi mempertimbangkan sekaligus mengabsahkan pertimbangan akal dalam kaitannya dengan syariat hukum Islam, menghargai pluralitas yang berkembang, dengan tujuan sistemik untuk seluas mungkin meringankan beban taklif setiap muslim. Kelonggaran “ekstrem” ini, mesti dipahami dalam konteks keseluruhan ajarannya yang berkaitan dengan fungsi kasih sayang (rahmaniyah) yang beliau tanamkan pada dirinya. Hal ini tidak bisa ditafsirkan sebagai sebentuk “kebebasan tiranis”, karena Ibnu Arabi tetap mempertahankan keteguhan luar biasa dalam melaksanakan syariat:
“Aku yakin bahwa aku termasuk orang yang berpegang teguh kepada Allah dan tidak mengkhianati perjanjian (mitsaq)… Ke sanalah aku membimbing manusia, dan berlandaskan prinsip inilah aku mendidik murid-muridku. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang mengikat sebuah perjanjian (‘ahd) bersama Allah dan menerima ajaran yang kusampaikan untuk mengkhianati perjanjian itu, terlepas dari besar-kecilnya manfaat yang diperolah. Aku tidak mengizinkannya untuk melakukan hal itu, bahkan atas nama keringanan hukum (rukhshah) yang membenarkannya untuk melakukan hal itu tanpa dosa.”[4]
Dalam kedisiplinan yang tinggi dalam memegang mitsaq dan ‘ahd bersama Allah yang dicintai dan mencintainya, dengan bertumpu secara kukuh pada syariat yang diyakininya, namun dengan toleransi yang tinggi terhadap pluralitas syariat –syariat yang ada di dunia, yang diyakininya semua berasal dari Allah, Ibnu Arabi bersyair, mengajak seluruh agama, kepercayaan, dari segenap bangsa dan bahasa, dalam perbedaan-perbedaan, untuk bersama-sama bersatu dalam tajribah rohaniah (eksperimentasi rohani), melalui jalan cinta menuju Sang Maha Cinta:
Hatiku telah siap menerima segala bentuk
Menjadi padang rumput bagi rusa, biara bagi para rahib
Menjadi candi bagi penyembah berhala, kakbah bagi para thaifiin
Menjadi alwah bagi Taurat, dan mushaf bagi Quran
Aku beragama dengan agama cinta, ke mana pun kendaraannya mengarah
Cinta adalah agamaku dan keyakinanku[5]
Berkah Ibnu Arabi, seperti yang disampaikan Ahmad Sirhindi di atas, tampaknya terletak tidak hanya pada pencapaian rohaninya pada makam yang sangat tinggi, tetapi Ibnu Arabi meninggalkan catatan-catatan yang lengkap dan detail menstrukturkan segala pengalaman rohani, insight-insight dan “penglihatan” batinnya terhadap segala maujud dalam semua martabatnya, di dalam segenap lapis-lapis alamnya, dengan segenap interkoneksitas di antara yang maujud itu menjadi sistem wujud yang lengkap, terus membentuk mata rantai hingga pada intinya, pusat segala pusat: “Sang Wujud Mutlak, Sumber dari segala sumber wujud, Yang sekaligus menjadi tempat kembalinya segala sesuatu, Dia Yang Awal dan Akhir, Yang Dzahir dan Yang Batin”. Semua catatan Ibnu Arabi tersebut dimaksudkan sebagai pengajaran untuk semua manusia, karena pada akhirnya, di dalam sistem wujud tersebut, manusia yang mampu mewujudkan kesempurnaan dirinya, “Insan Kamil”, menduduki derajat yang sangat mulia dan tertinggi sebagai Cermin Tuhan, sebagai puncak manifestasi dari Sang Wujud.
Ajaran-ajaran yang sangat kompleks tersebut, menjadi lebih sederhana dan semakin populer, berkembang ke berbagai penjuru, ketika disistemkan dan diberi penjelasan oleh murid dan penerjemah utama Ibnu Arabi, yaitu Shadr Al-Din Qunawi yang membentuk dan membingkai dalam nama “Wahdlatul Wujud”. Sementara gagasan tentang “Insan Kamil” menjadi populer dan mendapat sambutan yang luas, setelah dikembangkan dan disistematisasikan oleh Abdul Karim ibn Ibrahim al-Jili (w. 805 H) di dalam kitab Al-Insanul al-Kamil, fi Ma’rifatul Awakhir wal Awail. Pandangan-pandangan tentang sistem “Wahdatul Wujud” dan konsep “Insan Kamil” tersebut, kemudian diringkas lagi menjadi skema tentang manifestasi-manifestasi Dzat, di dalam aforisme-aforisme yang juga memuat panduan “praktis-operasional” untuk mengenali “Kesatuan Wujud” tersebut oleh Muhammad ibn Fadlullah al-Burhanpuri (w. 1620 M) melalui kitabnya yang sangat terkenal Tuhfatul Mursalah Ila Ruhin Nabi yang berlaku di wilayah Nusantara disebut “Martabat Alam Tujuh”, karena menjelaskan tentang tujuh martabat manifestasi wujud Tuhan yang disebut ke dalam istilah-istilah teknis: “Ahadiyah”, “Wahdah”, “Wahidiyah”, “Alam Arwah”, “Alam Mitsal”, “Alam Ajsam”, dan “Alam Insan Kamil”. Di luar kitab-kitab ini, dan kitab-kitab lain yang banyak mengulas ajaran-ajaran Ibnu Arabi, sebetulnya jauh lebih banyak penyebaran lagi pengaruh Ibnu Arabi yang dibawa oleh para sufi dari berbagai jaringan tarekat-tarekat ke berbagai penjuru dunia, tidak melalui tulisan-tulisan, melainkan melalui laku dan praktik.
Pandangan-pandangan tentang sistem “Wahdatul Wujud” dan konsep “Insan Kamil” tersebut, kemudian diringkas lagi menjadi skema tentang manifestasi-manifestasi Dzat, di dalam aforisme-aforisme yang juga memuat panduan “praktis-operasional” untuk mengenali “Kesatuan Wujud” tersebut oleh Muhammad ibn Fadlullah al-Burhanpuri (w. 1620 M) melalui kitabnya yang sangat terkenal Tuhfatul Mursalah Ila Ruhin Nabi yang berlaku di wilayah Nusantara disebut “Martabat Alam Tujuh”, karena menjelaskan tentang tujuh martabat manifestasi wujud Tuhan yang disebut ke dalam istilah-istilah teknis: “Ahadiyah”, “Wahdah”, “Wahidiyah”, “Alam Arwah”, “Alam Mitsal”, “Alam Ajsam”, dan “Alam Insan Kamil”.
Nusantara tampaknya menjadi salah satu tempat di mana berkah dari Futuhat Ibnu Arabi tersebut, tidak semata-mata dikutip dan diajarkan sehingga berguna, melainkan dieksperimentasikan di dalam ruang historis yang riil, sehingga tidak saja membentuk jiwa bangsa ini, tetapi juga jejak kultural yang nyata.[6] Namun di sini saya tidak mengatakan bahwa para guru sufi “pengemban berkah” ajaran Ibnu Arabi-lah pembawa Islam pertama dan menyebarkannya ke seluruh Nusantara. Namun yang ingin saya katakan adalah bahwa melalui merekalah berbagai “gelombang” Islam yang datang susul-menyusul ke berbagai wilayah Nusantara, dengan segala pertentangan aliran/mazhab dan afiliasi politik, perbedaan suku bangsa, profesi, motif, dan kedudukan sosial mereka semua, tidak membuat wilayah Nusantara ini semata-mata menjadi “tempat penampungan pengungsi dan pelarian politik”, atau hanya menjadi objek penderita dari perluasan wilayah pertikaian politik di negeri lain, atau hanya menjadi negara boneka, taklukan dan koloni bangsa asing. Para guru sufi itu, pada umumnya bertransformasi menjadi manusia kreatif, yang mengolah perbedaan-perbedaan, merangsang sintesis-sintesis antarkultur dan langsung maupun tak langsung ikut “menciptakan” identitas baru secara terus menerus. Kita tahu, yang lahir pada masa-masa itu adalah kerajaan-kerajaan Islam yang berdaulat, dari mulai Pasai, Aceh Darussalam, Deli, Aru, Minangkabau, Palembang, Jambi, Banten, Cirebon, Demak, Pajang, Mataram, Banjarmasin, Makassar, Bugis, Buton, Bima, Dompu, Selaparang, dan seterusnya. Mereka muncul dengan adat/identitas kulturalnya yang beragam, ekspresi kesenian yang kaya dan bermakna, sastra-sastra suluk dan didaktik yang bermutu tinggi, etika-etika sosial dan lingkungan yang penuh hikmah dan sebagainya.
Nusantara tampaknya menjadi salah satu tempat di mana berkah dari Futuhat Ibnu Arabi tersebut, tidak semata-mata dikutip dan diajarkan sehingga berguna, melainkan dieksperimentasikan di dalam ruang historis yang riil, sehingga tidak saja membentuk jiwa bangsa ini, tetapi juga jejak kultural yang nyata.
Membangun Tatanan Sosial-Politik: Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Adat
Di dalam sebuah salinan manuskrip[7], dijelaskan tentang “akta” pendirian Kerajaan Aceh Bandar Darussalam pada tanggal 12 Rabiulawal 913 Hijriah dan “Pohon Kerajaan” yang di-istikhar-kan (diupayakan) oleh paduka Sri Sultan ‘Alaidin Johan ‘Ali Ibrahim Mughayat Shah[8], Yang disebut “Pohon Kerajaan” atau dasar kerajaan adalah sebagai berikut:
“Bahwasanya kita semua satu negeri, satu bangsa, dan satu kerajaan, dan satu ‘alam (bendera) dan satu ajaran yakin Islam dengan mengikuti syari’at Nabi Muhammad SAW atas jalan Ahlussunnah Waljama’ah dengan mengambil hukum dari pada Qur’an dan Hadits Nabi dan Qiyas dan Ijma’ ‘alim ulama Ahlussunnah Waljamaa’ah dengan hukum, dengan adat, dengan reusam, dengan qanun yaitu syara’ Allah, syara’ Rasulullah, dan syara’ kami bernaung di bawah panji-panji syari’at Nabi Muhammad SAW dari dunia sampai akhirat dan dalam dunia sepanjang masa.
… (dilanjutkan dengan deskripsi 21 pasal kewajiban rakyat Aceh)
(penutup)… mudah-mudahan Insya-Allah Ta’ala dapat selamat bahagia segala umat manusia dalam negeri Aceh Bandar Darussalam khususnya dari Aceh jajahan takluk umumnya yaitu supaya menjadi manusia yang baik dan berkelakuan tabiat yang baik secara tertib sopan majelis dan hormat yang mulia yang sempurna dengan berkat syafa’at Nabi SAW supaya peliharalah bangsa kami Aceh dari pada mara dan bahaya dengan selamat sejahtera bahagia sepanjang masa dan jauh dari pada lembah kehinaan dan kesusahan sepanjang hidupnya supaya terpelihara negeri kami Aceh dan bangsa Aceh dengan usaha yang baik supaya dapat meraih kesenangan bersama-sama yaitu antara rakyat dengan kerajaan dengan tabah dan tawakal kepada Allah Ta’ala dapat … kebajikan bersama-sama dengan saudara Islam yang dalam negeri Aceh dan berkasihan dengan mengikut syara’ Allah dan syara’ Rasulullah dan syara’ kerajaan yang mufakat dengan Qur’an dan Hadits dan Qiyas dan Ijma’ulama Ahlussunnah Waljama’ah r.a. dan hukum adat dan hukum qanun dan hukum reusam.
Syahdan bermula maka barang-siapa yang tidak mengikut dan tidak menurut seperti yang tersebut itulah Ijma’ sabda mufakat kerajaan kami Aceh ke atas tiap-tiap mereka itu yang mungkar dengan dua hukum yaitu syara’ dan hukum adat. Sekianlah sabda mufakat kerajaan kami Aceh Bandar Darussalam Madinatussultan Al-Asyie Al-Kubra dan jajahan takluknya.”
Banyak hal menarik dari isi manuskrip di atas, dan kita dapat menganalisisnya dari berbagai sudut pandang. Pertama, tentu saja informasi tentang wacana ”Ahlusunnah Wal Jama’ah” yang dalam konteks ini dilegalisasi menjadi dasar kerajaan Aceh. Lepas dari sahih tidaknya isi manuskrip ini bahwa Kerajaan Aceh waktu itu bermazhab Sunni, karena informasi lain menyebutkan pada abd XV-XVI M, Kerajaan Aceh yang bermazhab Syiah mengirimkan ekspedisi ke Pariaman, Sumatera Barat, dipimpin oleh Pangeran Burhanuddin Syah,[9] tapi bahwa wacana “Ahlusunnah Wal Jama’ah” vis a vis Syiah di luar Jawa, khususnya Sumatera, sudah berlangsung sejak lama sekali. Sebuah informasi mengatakan sejak abad IX M, pada masa Kerajaan Perlak.[10] Di dalam perdebatan tentang “Pembaharuan Aswaja di Lingkungan NU” (di Jawa) beberapa tahun lalu, aspek historisitas seperti itu hilang, tidak dapat dikenali. Tampaknya ada missing link, karena hampir semua penulis dalam hal ini mengatakan “gelap”. Padahal di dalam kitab-kitab kuning melayu (arab-pegon) yang ditulis oleh para ulama “al-Jawi”, seperti Syekh Abdurrauf Singkel, Syekh Abdusshamad al-Palimbani, bahkan Syekh Muhammad Nafis al-Banjari, mereka seringkali menyebut paham mereka sebagai “Ahlusunnah Wal Jama’ah”. Hal menarik lainnya adalah informasi mengenai hubungan genealogis antara sultan-sultan Aceh dengan Kesultanan Bani Seljuk di Bagdad, bahkan nasab mereka sampai pada Iskandar Zulkarnain. Ini tentu saja membutuhkan ilmu dan pembahasan tersendiri.
Namun yang menarik bagi saya dan relevan dengan konteks tulisan ini – lepas dari ke-sunni-an atau ke-syiah-an Kerajaan Aceh – adalah karakteristik tentang hubungan agama dan kerajaan di satu sisi, dan hubungan antara syara’ dan adat di sisi lain. Bagaimanakah watak dari hubungan-hubungan ini? Apakah bersifat formal dan totalitarianistik, dengan menjadikan Aswaja satu-satunya ukuran untuk semua aspek kehidupan? Dalam hal ini, Aswaja dalam pengertian yang bagaimana? Kalau kita memperhatikan kedua puluh satu pasal-pasal di dalam “Pohon Kerajaan” tersebut akan tampak bahwa hubungan-hubungan itu tidaklah totalitarianistik seperti yang diklaim para pendukung penerapan Syariat Islam dewasa ini. Menarik memperhatikan bahwa hanya tiga dari dua puluh satu pasal itu yang “langsung” berkaitan dengan agama (Aswaja), dan ini pun bersifat keilmuan, yaitu kewajiban rakyat untuk belajar dan mengajar ilmu agama Islam syariat Nabi Muhammad SAW atas mazhab Ahlusunnah Wal Jama’ah, kewajiban untuk menjauhkan diri dari pada mengajar dan belajar ilmu kaum 72 golongan di luar Ahlusunnah Wal Jama’ah, kewajiban memegangi mazhab Syafi’i (qaul jadid) dalam setiap kasus hukum syara’, kecuali darurat, boleh memegangi mazhab yang tiga. Satu lagi pasal yang berkaitan dengan syara’, namun lebih berwatak etis, karena berisi larangan pengunaan harta zakat untuk keperluan masjid atau meunasah karena itu berarti mengambil hak fakir miskin, dan keharusan bersegera membagikannya kepada ashnaf yang delapan.
Namun yang menarik bagi saya dan relevan dengan konteks tulisan ini – lepas dari ke-sunni-an atau ke-syiah-an Kerajaan Aceh – adalah karakteristik tentang hubungan agama dan kerajaan di satu sisi, dan hubungan antara syara’ dan adat di sisi lain.
Sebagian besar pasal berisi tentang kewajiban (penguatan) ekonomi seperti bertani utama lada (juga lainnya), belajar mengajar pandai emas, tembaga, ukir-ukiran bunga, khusus perempuan untuk pandai menenun kain sutera, kain benang, menjahit, menyulam, melukis bunga pada pakaian (dan lain sebagainya), juga ada kewajiban (unik) untuk belajar mengajar berdagang di dalam maupun luar negeri dengan bangsa asing, … kewajiban untuk belajar … mengukir kayu, batu bata dengan memperhatikan komposisi (pasir, tanah liat, kapur, air kulit, batu karang yang ditumbuk, dll.), juga belajar mengajar indang emas, juga kewajiban memelihara ternak segala macam. Kemudian, ada beberapa pasal dengan “Pengaman dan bela diri/negara” seperti kewajiban selalu membawa senjata, belajar ilmu kebal, dan belajar menggunakan senjata. Kemudian, menarik juga adanya pasal-pasal tentang kultur/adat, yakni kewajiban setiap tahun untuk menyelenggarakan khanduri (kenduri) laut di bawah kewenangan penuh Amirul … yaitu Panglima Laut, khanduri (kenduri) blang (sawah) pada tiap-tiap di bawah kewenangan penuh Panglima Meugoe dengan Kejruen Blang (Pejabat Urusan Sawah) khanduri maulid Nabi yang mana waktunya diatur bergiliran satu sama lain dalam jangka waktu tiga bulan agar bisa saling mengunjungi. Juga ada kewajiban (unik) dalam setiap membangun rumah/meunasah/balai/masjid, untuk memasang kain warna merah putih pada tiap tiang di atas puting di bawah bara’.[11] Juga ada kewajiban yang saya kira lebih dekat kepada Syiah yaitu larangan kepada rakyat untuk memakai kain, sutera, payung dan lain-lain yang berwarna kuning atau hijau,[12] karena warna-warna itu khusus untuk keluarga kerajaan dan syarif-syarif Bani Hasyim dan Bani Muththalib yang silsilahnya bersambung kepada Sayidina Hasan dan Husein, putera Fatimah, cucu Rasulullah SAW.
Karakteristik yang penting dicatat lagi di sini adalah kesejajaran dan keseimbangan hubungan antara syara’ dan adat. Di dalam dua paragraf yang terakhir terdapat penegasan tentang hubungan yang erat antara syara’ dengan hukum adat, hukum qanun dan hukum reusam. Seperti tercermin di dalam isi pasal-pasal di atas, hukum antara syara’ dan adat benar-benar erat tak terpisahkan, tidak saling bertentangan atau saling intervensi satu sama lain.[13] Di dalam masyarakat sampai sekarang masih sering dikutip ungkapan-ungkapan tradisional: Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Laksamana, Reusam bak Putri Phang (Adat adalah kewenangan Sultan Iskandar Muda, Hukum adalah kewenangan Syekh Abdurrauf, Qanun adalah kewenangan Laksamana dan Reusam adalah kewenangan Puteri Pahang). Sayang sekali, makna hubungan-hubungan yang sejajar dan tidak saling intervensi, namun tetap berkaitan erat, tidak bertentangan dan tidak terpisahkan ini, sulit sekali terpahami dan justru makna sebaliknya tercermin di dalam UU NAD yang lalu. Demikian pula dengan ungkapan lain: Hukom ngon adat, lagee dzat ngon sifeut (Hubungan hukum syara’ dengan adat adalah tak terpisahkan, seperti dzat dan sifat), sering direproduksi namun dengan makna yang kehilangan konteks dan kerangka pemaknaannya.
Seperti tercermin di dalam isi pasal-pasal di atas, hukum antara syara’ dan adat benar-benar erat tak terpisahkan, tidak saling bertentangan atau saling intervensi satu sama lain.
Tentang hubungan syara’ dan adat dengan karakteristik sebagaimana dibicarakan di atas, tampaknya tidak hanya berlaku di Aceh saja. Di berbagai wilayah lain di Nusantara, seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Lombok kecenderungan seperti itu juga merata. Saya pernah membaca suatu naskah dari Barus[14] (Sumatera Utara) yang mengisahkan antara lain terjadinya peperangan yang terus-menerus antara kerajaan pesisir dengan pedalaman, yang kemudian dalam suatu perundingan damai yang juga dihadiri wakil dari Kerajaan Pagaruyung Padang, Sumatera Barat, ditengahi oleh seorang “Syekh dari Singkil”, dengan memakai formula “Adat basandi Syara’, Syara’ basandi Adat”.[15]
Pada umumnya kita sulit mendapatkan klarifikasi terhadap asal-usul, makna, dan paradigma dari ungkapan-ungkapan tradisional seperti di atas. Namun menurut saya, ungkapan-ungkapan di atas menunjukkan satu karakteristik “Islam Nusantara” yang dipengaruhi oleh spirit dan berkah futuhat Syekh Ibnu Arabi. Di dalam kitabnya, al-Futuhatul Makiyyah, Ibnu Arabi ketika membicarakan ber-tajalli-Nya nama-nama Tuhan, “al-Mudabbir”, “al-Mufashil” dan “ar-Rabb”, seperti terungkap dalam ayat al-Qur’an, dalam kaitannya dengan keseimbangan hukum realitas melalui penataan kerajaan secara baik (ishlahul mamlakah), demi suatu maslahat, sejalan dengan makna ayat “wa likullin ja’alna minkum syir’atan wa minhaja” (dan bagi setiap umat, Kami jadikan sebuah syir’ah dan minhaj), mengatakan:
“Sesungguhnya Allah menjadikan ketentuan-ketentuan untuk memperbaiki kerajaan (ishlahul mamlakah) ke dalam dua bentuk: pertama, as-siyasatul hikamiyah (kebijakan lokal/adat) yang sebetulnya berasal dari ilham Allah, namun tidak disadari oleh perumusnya, dan kedua adalah as-siyasatu as-syar’iyyah (ketentuan syara’).[16]
Jadi, dari sini kita tahu, kenapa hubungan antara adat dan syara’ itu mesti sejajar, seimbang, dan tak terpisahkan, karena pada hakikatnya keduanya berasal dari Allah. Bedanya, yang satu melalui ilham kepada jenius lokal atau filsuf atau cerdik pandai, dan satunya lagi langsung berupa tasyri’ melalui wahyu kepada Nabi. Keduanya penting, tidak semata-mata demi keseimbangan alam, tetapi juga demi kemaslahatan. Dalam ajaran Ibnu Arabi, yang disebut kemaslahatan bersifat nyata dan langsung, yaitu terpenuhinya kebutuhan warga kerajaan. Ukuran kebesaran seorang raja adalah seberapa banyak dalam setiap hari ia dapat menyelesaikan masalah dan kebutuhan warga yang diajukan kepadanya. Demikian pula sebaliknya, kalau seorang raja berbuat zalim atau membunuh seorang warganya, maka itu berarti ia sedang menghancurkan kerajaannya sendiri.
Jadi, dari sini kita tahu, kenapa hubungan antara adat dan syara’ itu mesti sejajar, seimbang, dan tak terpisahkan, karena pada hakikatnya keduanya berasal dari Allah. Bedanya, yang satu melalui ilham kepada jenius lokal atau filsuf atau cerdik pandai, dan satunya lagi langsung berupa tasyri’ melalui wahyu kepada Nabi. Keduanya penting, tidak semata-mata demi keseimbangan alam, tetapi juga demi kemaslahatan.
Jalan Pembentukan Integritas dan Kesejatian Diri (Insan Kamil):
Sejauh ini, saya menggambarkan paham “wahdatul wujud” dengan tokoh utamanya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi sebagai “katalisator” yang paling berpengaruh dalam pembentukan karakteristik “Islam Nusantara”. Mungkin akan ada yang mempertanyakan, bagaimana bisa begitu? Bukankah paham itu tertolak di Nusantara, juga di dunia Islam pada umumnya? Pertanyaan semacam ini bukan mengada-ada, karena kita memang lebih sering disuguhi gambar dengan segala citranya yang menempatkan paham ini dan tokoh-tokohnya sebagai “antagonis” di dalam sejarah “Islam Nusantara”. Semua ini tampaknya berpangkal pada “cerita” di dalam babad, serat, suluk, atau legenda rakyat tentang eksekusi hukuman mati terhadap tokoh-tokoh yang dianggap sesat dan membuat kekacauan di masyarakat karena menganut paham ini di berbagai wilayah Nusantara: Syekh Siti Jenar di Jawa pada abad XV–XVI, Syekh Hamzah Fansuri di Aceh abad XVI–XVII, dan Syekh Abdul Hamid Abulung di Martapura (Banjarmasin) pada abad XVIII. Menarik, cerita-cerita itu mempunyai plot dan latar panggung yang hampir mirip, yaitu ada tokoh penyebal, yang bidah, membuat onar masyarakat, kemudian ia dipanggil raja untuk dimintai keterangan, tapi malah menunjukkan kebidahannya, sehingga kemudian oleh Ulama/Wali yang otoritatif, diadili dan divonis sesat, lalu dijatuhi hukuman mati dan seluruh pengikut-pengikutnya dikejar-kejar, disuruh tobat, ditangkap atau dibunuh.
Sejauh ini, saya menggambarkan paham “wahdatul wujud” dengan tokoh utamanya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi sebagai “katalisator” yang paling berpengaruh dalam pembentukan karakteristik “Islam Nusantara”. Mungkin akan ada yang mempertanyakan, bagaimana bisa begitu? Bukankah paham itu tertolak di Nusantara, juga di dunia Islam pada umumnya? Pertanyaan semacam ini bukan mengada-ada, karena kita memang lebih sering disuguhi gambar dengan segala citranya yang menempatkan paham ini dan tokoh-tokohnya sebagai “antagonis” di dalam sejarah “Islam Nusantara”.
Cerita-cerita ini terus bertahan, walaupun sesungguhnya banyak mengandung paradoks dan anakronisme sejarah, sebagian mungkin karena “dijaga” dan “dinormalkan” melalui asumsi-asumsi akademis, walaupun sesungguhnya berupa klaim atau kesalahpahaman yang rapuh. Sebagai contoh, misal apa yang ditulis Dr. Simuh di dalam disertasinya Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ronggowarsito:
“Di kalangan para penganut paham Manunggaling Kawula-Gusti, memang ada segolongan kecil yang berpaham pantheisme, yang memandang bahwa hakekat alam, manusia dan Tuhan, adalah sama. Yakni serba Tuhan, yang dianut oleh Ibnu Arabi, Hamzah Fansuri, Samsudin Pasai, dan dalam cerita Serat-Babad Syekh Siti Jenar. Namun, sebagian besar pengikut paham Manunggaling Kawulo-Gusti, masih mempertahankan perbedaan antara Tuhan yang wajib disembah, dan kawulo yang wajib menyembahnya. Seperti halnya Husain Ibn Mashur Al-Hallaj, Abdurra’uf al-Singkili, Ar-Raniri, dan lain-lain.”
Satu paragraf singkat dan padat dari dari Dr. Simuh di atas menunjukkan beberapa hal tentang asumsi-asumsi dan stereotip terhadap paham “Manunggaling Kawulo-Gusti”, istilah Jawa untuk menyebut “Wahdatul-Wujud”. Beserta “pemetaan” beberapa tokohnya dan pembedaan “aliran/varian” di dalam paham “Manunggaling Kawulo-Gusti” itu sendiri antara panteisme (paham serba Tuhan) yang berarti cenderung meninggalkan “syariat” dengan para pengikut yang tetap memegangi “syariah” dan masih mempertahankan perbedaan antara Tuhan yang wajib disembah dan hamba yang wajib menyembahnya.
Dengan mengikuti model penilaian seperti di atas, kita sebetulnya dengan mudah bisa menunjukkan beberapa kesalahan dalam kesimpulan pada paragraf di atas atau yang sejenisnya. Beberapa kutipan dari ajaran-ajaran Ibnu Arabi dalam kitab al-Futuhatul Makkiyyah pada pembahasan-pembahasan di awal sudah cukup untuk menunjukkan kesalahan ini. Juga, kalau kita baca sendiri secara langsung, ajaran-ajaran Hamzah Fansuri, guru sufi abad XVI ini, di dalam kitab kita Syarabul ‘Asyikin, Asrarul ‘Arifin, dan sebagainya, maka stigma di atas jelas sekali kesalahannya. Barangkali dua kutipan dari Kitab Syarabul ‘Asiqin ini bisa mewakili ajaran-ajaran Hamzah Fansuri:
Barangsiapa tiada menurut fi’ilnya (Nabi), ia itu naqis (kekurangan) dan sesat hukumnya, karena shari’at [dan tariqat] dan haqiqat pakaian Nabi. Apabila kita tinggalkan suatu daripada tiga itu, naqis hukumnya. Adapun barangsiapa mengerjakan sembahyang fardlu, dan puasa fardu, dan makan halal, dan meninggalkan haram, dan berkata benar, dan tiada laba, dan tiada dengki, dan tiada minum tuak, dan tiada mengumpat orang, dan tiada mengadu-ngadu, dan tiada zina, dan tiada ujub, dan tiada riya’, dan tiada takabbur – banyak lagi mithalnya ini – ia itu memakai shari’at. Kerana perbuatan itu perbuatan Muhammad Rasulullah (shalla’llahu ‘alaihi wa sallam) yogya kita turut supaya dapat kita ke dalam tariqat, karena tariqat tiada lain daripada shari’at[17].
Demikian juga kalau kita baca secara langsung tanpa apriori ajaran Syamsuddin al-Sumatrani (wafat tahun 1630 M), pensyarah Hamzah Fansuri, dalam kitab Tibyan Mulahadhatil Muwahhid wal Mulhid fi Dzikrillah, maka tidak ada perbedaannya dengan isi kitab Nuruddin Ar-Raniri: Hujjatus Shiddiq li Daf’iz Zindiq. Beberapa disertasi sudah ditulis di Indonesia yang menunjukkan tuduhan-tuduhan terhadap Ibnu Arabi, Hamzah Fansuri dan Syamsuddin al-Sumatrani selama ini adalah suatu kezaliman.[18] Agus Sunyoto juga tidak saja telah mensistematisasi ajaran tasawuf Syekh Siti Jenar di dalam proporsinya dan menunjukkan ketauhidannya, bahkan mendekonstruksi sejarahnya untuk mengatasi secara meyakinkan berbagai keterbatasan atau penyimpangan yang menyembunyikan realitas di dalam babad-babad.[19]
Keyakinan saya bahwa spirit Ibnu Arabi[20]-lah yang menjadi “katalisator” terpenting (baik secara intelektual maupun spiritual) dalam pembentukan karakteristik “Islam Nusantara”, juga didukung oleh fakta bahwa – sejauh bisa ditelusuri – keseluruhan korpus karya Ulama-ulama Nusantara (abad XV–XIX), baik yang akrab di lingkungan kaum santri atau pesantren, maupun yang dipegangi di lingkungan kaum abangan (Keraton dan sekitarnya), baik di Jawa maupun di luar Jawa, menunjukkan derajat keterpengaruhan yang tinggi terhadap ajaran-ajaran Ibnu Arabi. Di luar naskah-naskah sejenis Babad, yang persis “sejarah” dan sejenis kisah atau epos, seperti Serat Menak atau Hikayat Amir Hamzah, maka hampir kesemuanya berupa naskah-naskah suluk, tasawuf, yang bersifat didaktis, teoritis maupun praktis. Dan kalau kita baca secara seksama, akan tampak bahwa semuanya berakar pada paham “Wahdatul-Wujud”, bermuara pada upaya membuka jalan bagi pembentukan “Insan Kamil”, manusia sempurna. Siapa “Dia”? Ia yang di dalam dirinya sendiri sudah merealisasikan segala kemungkinan yang mungkin bisa dicapai oleh makhluk. Sehingga dapat menjadi teladan untuk setiap orang, sebab, pada kenyataannya, setiap makhluk terpanggil untuk merealisasikan kemungkinan-kemungkinan yang ia bawa sejak lahir sesuai dengan nama Ilahi yang menjadi Rabb-nya yang khusus. Bagaimana mencapainya? Mari kita baca sekali lagi puisi Hamzah Fansuri di atas:
“Ketahuilah anak Adam/ Engkaulah haqiqat ‘alam
Isyiqmu jangan kau padam/ Supaya dapat berpayung iram
Campurkan yang empat ‘alam/ Hancurkan di laut dalam/
Syar’iy nabi yang khatam/ Kerjakanlah daim siang dan malam.”
Catatan Kaki:
[1] Untuk pembacaan terhadap Ibnu Arabi, disamping bercermin pada syarah-syarah tradisi, saya juga berhutang pada buku biografi intelektual dan spiritual Ibnu Arabi yang ditulis oleh Claude Addas, Mencari Belerang Merah, terj. Zaimul Amin. (Jakarta: Serambi, 2004). Juga kepada analisis Nasr Hamid Abu Zayd, Hakadza Takallama Ibnu Arabi (Beirut: al-Markazuts Tsaqafil Arabi. 2004), cet II.
[2] Al-Futuhat Makkiyah, Kairo, 1293 H. Juz I, h. 392
[3] Futuhat, Juz I. H. 334.
[4] Futuhat, I, hlm. 723.
[5] Adz-Dzakhairul A’laq fi Syarh Tarjumanil Asywaq, tahqiq: Muhammad Abdurrahman al-Kurdi, Kairo, 1968.
[6] Masa-masa yang paling dinamis dalam Ashru at-Tadwin “Islam Nusantara” memang antara abad ke-15-ke-18, tepat beriringan dengan kemunculan karya-karya “implementatif” Al-Jili dan Al-Burhanpuri di atas. Pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, Sunan Kalijaga dkk menghasilkan karya-karya yang tidak hanya menerjemahkan konsep-konsep seperti “Insan Kamil” dan “Maratibul Wujud” saja, tetapi secara kreatif juga mengembangkan dan mengkontekstualisasikan dengan kultur Jawa yang ada saat itu, seperti yang selama ini dikenal sebagai suluk-suluk pesisiran, Serat Menak, Serat Martabat Alam Pitu, dan sebagainya. Pada dekade berikutnya, Hamzah Fansuri muncul dengan syair-syair dan prosa-prosa yang menggelora tentang hakikat wujud dan jalan-jalan menuju pembentukan “Insan Kamil”, peralihan abad berikutnya, tampil Syekh Syamsuddin al-Sumatrani, abad ke-17 muncul Syekh Abdurra’uf al-Singkili, Mbah Mutamakin Kajen dan Syekh Yusuf al-Makassari yang cemerlang dan abad berikutnya, abad ke-18, kita bertemu dengan Syekh Abdushomad al-Palimbani dan Syekh Muhammad Nafis Banjar.
[7] Salinan manuskrip ini adalah kitab Tadzkiratul Tabaqat, Qanun Syara’ Kerajaan Aceh, susunan Syekh Syamsul Bahri, yang disalin oleh Tengku di Mulik Sayyid Abdullah al-Jamalullail atas titah Tuanku Ibrahim al-Mulaqqab Paduka Sri Sultan ‘Alaiddin Mansyur Syah pada tahun 1272 Hijriah. Untuk informasi ini, saya berterima kasih kepada Prof. Dr. T. Ibrahim Alfian.
[8] Di dalam sebuah manuskrip lain, yang tersimpan di Universitas Kebangsaan Malaysia, ada diceritakan tentang kedatangan kabilah dari Bagdad sebanyak 500 orang pada tahun 510 Hijriah atau 1116 Masehi di bawah pimpinan Makhdum Abi Abdillah Syaikh Abdurrauf al-Mulaqqab Tuan di Kandang Syaikh Bandar Darussalam dan membawa agama Islam kepada penduduk kampung Pande di Aceh. Putranya ialah Sultan Johan Syah yang menjadi Sultan di kampung Pande, dan seterusnya sampai kepada Johan Ali Ibrahim Mughayat Syah ini. Manuskrip tersebut juga menyebutkan bahwa sultan-sultan Aceh ialah zuriah Sultan Iskandar Zulkarnain melalui cabang Turkestan, Bukhara, yang dimulai dari Sultan Malik Ilik Khan Syah Saljuq. Untuk data ini, saya berterima kasih kepada Prof. Dr. T. Ibrahim Alfian.
[9] Slamet Muljana, Sriwijaya (Yogyakarta: LKIS, 2006). Jejak dominasi Syiah masih dapat dikenali di daerah-daerah Pariaman, Jambi dan Bengkulu sampai saat ini, yang setiap tanggal 10 Muharram menyelenggarakan Festival Tabut untuk memperingati peristiwa Karbala, dan konon tradisi ini dimulai sejak zaman Burhanuddin Syah.
[10] Baca laporan hasil seminar masuknya agama Islam di Indonesia, A. Hasjmy, dkk., Medan, 1969, yang kesimpulan-kesimpulan terpentingnya banyak mendasarkan pada sebuah naskah Idzharul Haq fi Mamlakati Perlak yang mengkisahkan tentang kedatangan “armada” dari Persia di Perlak pada abad VIII–IX M, dan berhasil mendirikan kerajaan Islam yang pertama di sana. Naskah ini juga banyak bercerita tentang perkawinan-perkawinan “politik” antara pendatang-pendatang Muslim itu dengan keluarga “pemegang otoritas lokal”, dan kemudian membangun silsilah raja-raja di Perlak dan bersambung ke Pasai dan Malaka. Juga, pada akhirnya, sultan-sultan Aceh.
[11] Sampai sekarang, di berbagai desa di Jawa, saya masih melihat banyak orang yang memasang kain/bendera merah putih pada blandar, ketika membangun rumah, (mungkin) tanpa tahu asal-usulnya.
[12]. Menurut informasi, di Banjarmasin masih ada “tabu” bagi orang kebanyakan untuk mengenakan pakaian dengan warna kuning dan hijau.
[13] Bandingkan dengan karakteristik hubungan-hubungan itu di dalam UU NAD atau RUU Pemerintahan Aceh yang sekarang.
[14] Jane Drakard, Hikayat Raja-raja Barus (Jakarta; Gramedia, 1998).
[15] Bandingkan dengan slogan Sumatera Barat saat ini yang berubah menjadi “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” (ABSSBK), yang juga belum ada penjelasan resminya tentang asal-usul dan kerangka pemikirannya, baik secara filosofis maupun praktisnya.
[16]Futuhat, juz 1.
[17] Baca Disertasi Dr. Kautsar Azhari Noer tentang Ibnu Arabi, dan Disertasi Dr. Abdul Hadi WM, tentang Hamzah Fansuri. Kedua disertasi ini diterbitkan oleh Penerbit Paramadina
[18] Lihat novel-novel sejarah Agus Sunyoto tentang Syekh Siti Jenar, jilid 1–7 diterbitkan LKIS Yogyakarta.
[19] Sekali lagi, saya ingin menegaskan bahwa yang saya maksud dengan spirit atau “futuhat” Ibnu Arabi di sini, bukanlah semata-mata kitab-kitab Ibnu Arabia atau murid-murid/pengikutnya langsung, melainkan ini berkaitan dengan posisi “unik” ajaran-ajaran Ibnu Arabi di antara ajaran-ajaran sufi sebelum dan sesudahnya, yang “merangkum” keseluruhannya tanpa menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada, bahkan menempatkannya dalam “martabat”-nya masing-masing. Jadi, maksudnya lebih kepada keseluruhan para sufi dan ajaran-ajarannya di dalam perbedaan varian di antara mereka, dan mungkin pertentangan-pertentangan di antara mereka juga, yang sudah “dirangkum” oleh Ibnu Arabi.
*Tulisan ini merupakan bagian dari salah satu tulisan dalam buku “Islam Berkebudayaan; Akar Kerarifan Tradisi, Ketatanegaraan, dan Kebangsaan”, (Pusataka Kaliopak: 2019).