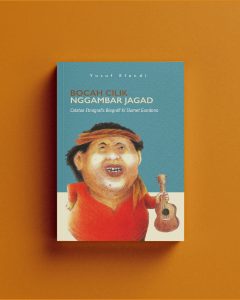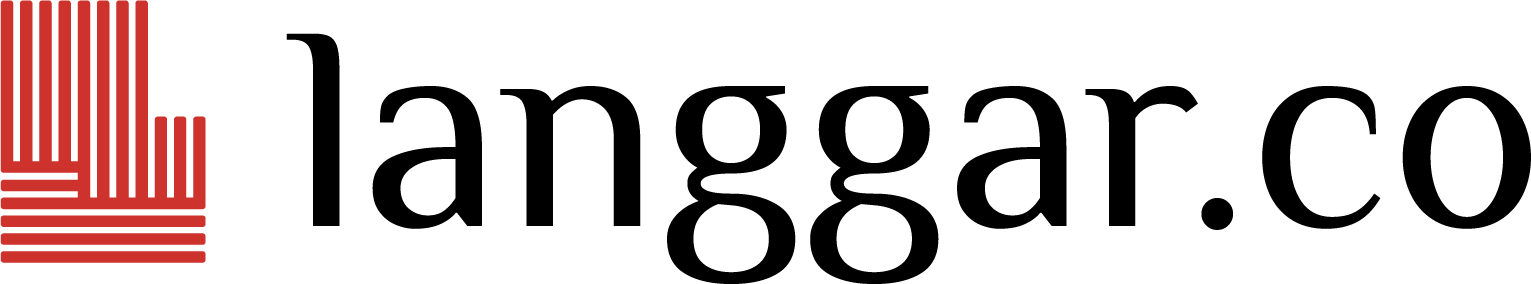Ngilmu: Gerak Ontologis Sangkan-Paran
Sun…akarya tembang suluk Liring suluk ika Sesinden ing para wali Aja kemba lestarining sangkan paran (“Suluk Sontrang”, Pucung, Pada ke-1) Saya mungkin adalah seseorang...
Sun…akarya tembang suluk
Liring suluk ika
Sesinden ing para wali
Aja kemba lestarining sangkan paran
(“Suluk Sontrang”, Pucung, Pada ke-1)
Saya mungkin adalah seseorang yang kelewat intim mendalami filsafat, bahkan terhitung begitu emosional. Sehingga dalam takaran tertentu, apa yang tidak memenuhi atau malah tidak menjawab secara memuaskan pertanyaan-pertanyaan intim yang berkecamuk dalam diri dengan sendirinya akan saya sisihkan dan tangguhkan. Termasuk salah satunya unggunan pengetahuan filsafat, tepatnya fisafat Barat yang dulu saya geluti selama tujuh tahun di Filsafat UGM. Bahkan malah sempat meluber terus hingga beberapa tahun setelah lulus kuliah. Apa yang kurang dari apa yang saya pelajari selama kuliah yakni saya merasa tak terlalu mengerti “filsafat” atau setidaknya “pemikiran filosofis” masyarakat saya sendiri—dalam pengertian sebagai pandangan dunia plus bangun paradigma, kategori, maupun titik tekan yang ingin disodorkan. Akhirnya belokan pengetahun—sebut saja begitu—harus segera saya lakukan. Dan tentu ini belum sepenuhnya dalam keadaan mantap. Namun, ia bisa menjadi awal yang membahagiakan.
Ngilmu seperti yang tertulis pada judul materi paper ini adalah salah satu uji coba untuk sebuah eksplorasi menggali khasanah filsafat masyarakat sendiri. Dan saya tak berpretensi untuk berhasil secara memuaskan membangun arsitektur kerangka dasarnya dalam satu kesatuan bangun utuh filsafat (sayangnya saya masih menggunakan istilah yang ingin saya hindari ini) yang darinya saya berharap bisa menunjukkan ke-khasan bangun pandangan dunia konsepnya khususnya dalam tradisi Jawa, dan oleh karenanya ingin saya beberkan pada kesempatan kali ini. Dengan usaha ini kita akan sedikit bisa mengerti, atau setidaknya bisa merasakan, bahwa konsep ngilmu dalam tradisi Jawa punya bangun filosofis yang khas atau berbeda, atau setidaknya ia muncul dari suatu pandangan dunia masyarakat tertentu yang oleh karenanya harus dijelaskan menurut kriteria pandangan dunia yang dihayati—sifatnya bisa parsial sekaligus universal pada saat bersamaan. Dan dari skema tersebut bisa terdeteksi bangun-susunnya, yang melaluinya akan terlihat eksplisitasinya akan sebuah “filsafat” atau setidaknya “pandangan filosofis” yang berbeda, yang oleh karenanya harus dijelaskan secara berbeda dari saudaranya yang bernama “filsafat Barat”.
Dalam membahas konsep ngilmu, saya akan bertolak dari “Serat Wedhtama” dimana salah satu kutipan serat ini begitu terkenal terutama terkait bait “ngilmu iku kelakune kanthi laku”, plus beberapa tambahan penjelasan serat, wirid, maupun suluk—seperti dikenal dalam perbendaharan genre sastra Jawa—untuk mengukuhkan dan menguatkan apa yang saya sodorkan maupun kerangkakan. Saya juga akan menunjukkan bahwa ngilmu—sebagaimana kata ini diserap dari bahasa Arab bahkan bahasa Al-Qur’an—sebenarnya masih dipahami dalam kerangka pandangan dunia tersebut, tepatnya tasawuf, setidaknya seperti tereksplisitkan dalam teks-teks seratnya. Namun, sayangnya belakangan hari para sarjana Barat juga orang Indonesia berpendidikan berusaha sekuat tenaga untuk menempatkan ngilmu di luar dari kerangka bingkai pandangan dunia tersebut, dimana peran Islam yang saat serat itu ditulis sudah menjadi penyangga—meminjam bahasa Ricklefs—“penyatu identitas ke-Jawaan”. Dan dari situ kita bisa melihat, bagaimana ia berbeda secara spesifik dengan unsur-unsur bangun pemikiran filsafat Barat—karena masih menempatkan pandangan dunia agama tertentu sebagai sebuah aksioma dalam merumuskan maupun suatu usaha mengeksplisitasi gagasannya, bahkan laku, mistik, maupun filosofisnya.
Sangkan Paraning Dumadi
Gagasan mendasar pemaknaan tentang keberadaan hidup Jawa sebenarnya mengumpul dalam sebuah ungkapan terkenal ihwal “sangkan praning dumadi”. Sebuah ungkapan yang ingin mengingatkan keberadaan ontis manusia serta tujuan teleologis akhinya selama ia hidup atau ber-“ada” di dunia ini. Bahwa keber-‘ada’-an manusia atau yang maujud ini (secara harafiah bermakna yang di-‘ada’-kan atau yang di-‘jadi’-kan/dumadi dari asal kata dadi) hanyalah bersifat sementara. Urip mung mampir ngombe. Begitu kata orang Jawa. Keberadaannya hanya menjalankan titah dari yang Maha-Kuasa dan oleh karenanya ia sebagai yang di-ada-kan harus pertama kali menyadari dari mana ia berasal (sangkan: sangka ngendi) dan kemana tujuan hidup akhir berakhir (paran; parane ngendi); Asal dan tujuan kembali manusia (sangkan paraning dumadi), yang hal ini selaras dengan konsep mendasar Islam Innalillahi wa inna ilaihi rajiun (kita dari-Nya akan/sedang kembali menuju Nya).

Jadi dalam kerangka keber-ada-an hidup manusia Jawa ia sedang dalam sebuah “perjalanan” besar dari Allah menuju Allah, alias sebuah gerak dari yang di-ada-kan (dumadi/maujud) menuju yang Ada atau yang mengadakan (dadi/wujud). Yakni sebuah perjalanan manusia dari sejak ia berada dalam kandungan menuju kematian, atau perjalanan dari-Nya menuju-Nya. Dan oleh para wali tanah Jawi dulu “perjalanan” besar ini—yang dalam bahasa Jawanya sepadan dengan kata laku, mlaku, lelaku, lelakon yang artinya secara harafiah memang berarti “berjalan” atau “perjalanan”—sering diterjemahkan dalam sebuah neologi (istilah baru) yang dintrodusir para wali bernama “suluk” yang juga dalam bahasa Islam—merupakan istilah kunci dalam tasawuf—juga secara harafiah berarti “berjalan” atau “perjalanan”. Namun harus diingat perjalanan hidup atau lelakon hidup manusia tersebut, layaknya sebuah drama seperti dipentaskan dalam pewayangan (yang biasanya mementaskan sebuah lakon tertentu), berada dalam spectrum jasadi mapun ruhani, awalnya dari-Nya dan akhirnya menuju-Nya. Dalam bahasa suwargi Damardjati Supajar, perjalanan atau lakon hidup atau suluk manusia tadi berada dalam bingkai lahir-bathin dan awal-akhir—ingat seluruh 4 kata ini berasal dari bahasa Arab. Alias perjalanan manusia ini bukan melulu perjalanan ragawi dan intelektual semata, melainkan sebuah perjalanan ruh (baca: bathin) yang sedang ingin menuju kembali pada-Nya.
Untuk mengafirmasi kata laku atau lakon merupakan padanan atas kata suluk, dulu para Wali Tanah Jawi menggunakan kata suluk untuk menamai sebuah genre tembang Jawa (terutama sekaralit) bernama macapat. Seperti diceritakan Nancy K. Florida dalam “Writing Traditions in Colonial Java: The Question of Islam” (Michigan Press: 1997)—seorang antropolog yang berjasa besar memfilmkan dan mengkatalogisasi seluruh isi tiga naskah Jawa Keraton Solo, Mangkunegaran, dan Radya Pustaka di tahun 1980an—terdapat setidaknya dua genre dalam kesusateraan Jawa, yakni yang pertama berebentuk (1) puisi-tembang bernama genre “suluk” (macapat), sedangkan (2) yang kedua berbentuk prosa atau eksposisi teoritis disebut “wirid” (ini juga istilah penting dalam tasawuf). Itu dicontohkan beberapa karya misalnya, “Suluk Sontrang”, “Suluk lonthang”, “Wirid Hidayatjati”, dll
Penamaaan suluk (perjalanan) sebagai genre tembang macapat yang merupakan genre utama untuk menulis kesusateraan serat maupun babad di Jawa terkonfirmasi dari makna seperti penamamaan yang sering kita kenal dalam tembang macapat, yakni dari Maskumambang (dalam kandungan), Mijil (lahir), Sinom (anak muda), Kinanthi (ditemani perkembangan ilmu dan moralnya), Asmaradana (asmara), Gambuh (menikah), Dandhanggula (mengalami pasang-surut, jatuh-bangun kehidupan), Durma (mendermakan diri kepada masyarakat), Pangkur (mundur dan mengambil jarak atas gemerlap dunia), Megat-ruh (terlepasnya ruh kita, alias wafat), dan terkahir Pucung (jasad kita dibungkus kain kafan). Yakni sebuah perjalanan (suluk) kehidupan manusia dari semenjak dalam kandungan hingga menuju kematian saat jasadnya di-pucung, dikafani. Sebuah lelaku atau suluk menjalani sangkan paraning dumadi-nya.
Maka tak ganjil jika saat dalam pementasan pewayangan kulit purwa, saat sang dalang seolah sedang meliukkan suaranya layaknya seorang yang sedang menembang juga dinamai “suluk” (tembang), sepadan dengan penamaan genre kesusateraan tembang bernama tembang macapat (suluk) yang dibedakan dengan genre prosa yang disebut wirid. Hal ini sekaligus membantah pengasalan salah seorang javanolog Theodore Pigeaud dalam “Javansche Volsvertoningen” (Volkslectur Batavia: 1938, 56), yang mengasalkan kata suluk dari istilah “uluk” atau “muluk” yang berarti suara meninggi. Karena dalam sebuah perjalanan besar tersebut manusia harus mengawasi unsur (nafsu) yang empat dalam dirinya (macapat/membaca empat) agar ia lolos dari jebakan dunia dalam rangka perjalanan hidupnya menuju kembali pada-Nya. Yakni agar diri sejatinya menjadi sumbu pusat (pancer) yang menjadi kendali dalam mengantur laku perjalanannya (sedulur papat, lima pancer). Atau dalam kalimat lain, ia bisa mendirikan dan menunggalkan (sifat/asma) Tuhan dalam dirinya. Yakni sebuah lelakon besar menyadari sangkan paraning dumadi-nya dan bisa menjemput keutuhan maupun kesempurnaan kemanusiaannya dan siap kembali secara mulus pada-Nya saat mati (kasidan Jati).
Hal ini dibenarkan bait-bait yang saya kutip di awal paragraph seperti tertera dalam “Suluk Sontrang”, Pucung, Pada pertama (Simuh; 1889), yang terjemahananya;
“Sun… akarya Tembang Suluk
Liring suluk ika
Sesindhen ing para wali
Aja kemba lestarining sangkan-paran”
Saya… mengarang tembang suluk
Maksud suluk itu
(Adalah) nyayiannya para wali
Jangan ragu meneguhkan sangkan-paran
Oleh karenanya tembang-tembang Macapat (sekar alit) sering diatribusikan kepengaranganya bahkan kepada para wali tanah Jawi, misalnya durma dikarang oleh Sunan Bonang, Dhandhanggula dikarang oleh Sunan Kalijaga, Mijil dan Megatruh dikarang oleh Sunan Giri-Prapen, Maskumambang oleh sunan Majagung, dst. Karena jika kita mau jujur memeriksa, sebenarnya memang tak ada genre macapat (sebagai sebuah tembang) di Jaman Majapahit—setidaknya secara defenitif, meski mungkin prototype sudah ada. Model kesusasteraan di Jaman Majapahit hanya mengenal setidaknya dua genre yakni genre Kakawin dan genre Kidung (juga ada satu lagi kesusasteraan Parwa) yang oleh Javanolog macam Zoetmulder dipandang sebagai sebuah genre sastra yang ditulis dalam bahasa Jawa-kawi yang berbeda dari bahasa Jawa modern di masa para wali tanah Jawi hingga Mataram, yang metrum tembangnya mengikuti rima suara panjang-pendek Sansekerta (India), alias berbeda dengan metrum macapat yang kita kenal hari ini. Ia, serat, suluk,wirid, dan babad—kesemuanya ditulis dalam format tembang-puisi macapat, kecuali tentu wirid—sebenarnya jika kita jujur adalah merupakan produk di masa Jawa Islam. Dan bahkan diyakni sebagai hasil Ijtihad kebudayaan para wali Tanah Jawi, termasuk di dalamnya wayang.
Nah, penamaaan suluk—yang secara harafiah berarti “perjalanan”—sebagai sebuah genre tembang Macapat adalah merupakan gambar yang disodorkan ihwal perjalanan sangkan-paraning dumadi manusia semenjak ia dalam kandungan hingga ia akhirnya dibalut kain kaffan, persis seperti penamaan dalam nama sekar dalam tembang Macapat. Namun, karena perjalanan itu begitu genting, penuh dengan jebakan jala-indera gemerlap dunia, ia harus diusahakan secara lahir-bathin, jasadiah maupun ruhaniyah. Maka tak aneh misalnya kita mengenal tradisi “selamatan bayi” (baca: Salamah–Islam) dilakukan sejak dini oleh masyarakat Jawa dari mulai sepasaran kelahiran hingga mitoni (tujuh bulan) atau sering disebut “tingkeban”. Tingkeban berarti perkembangan janin bayi dianggap sudah titi-jangkep, dimana secara jasadi, ruh telah bersarang dalam diri bayi, alias sudah lengkap (titi dan jangkep) disebut sebagai manusia—persis seperti digambarkan dalam “Serat Wirid Hidayat Jati” (Ronggawarsita) ihwal perjalanan ruh di bulan ketujuh sesuai konsep martabat tujuh-nya Ibn Arabi. Dalam perjalanan ruh pada janin tersebut harus dibarengi dengan doa dan selamatan. Ini juga berlaku saat manusia meninggal, alias saat perjalanan ruh berpulang kehadirat-Nya dimana Ia juga harus diiringi oleh “doa” dan “slametan” sesuai gambaran perjalanan ruh dalam skema martabattujuh seperti dijelaskan Ronggawarsita dalam Wirid.

Selain itu, sebenarnya penamaan sekar macapat bisa juga kita rangkai dalam pembacaan serupa. Disebut macapat karena dalam perjalanan sangkan-paran-nya, manusia harus dengan sungguh memperhatikan unsur empat atau “membaca empat” (maca papat) nafsu dalam diri ruhaniyahnya (lawamah/hitam, supiyah/kuning, amarah/merah, mutmainah/putih) atau sering disimbolisasikan dengan sedulur papat lima pancer yang dalam perkembangan umur manusia memiliki gradasi tantangan, jebakan, dan penangannnya secara lebih khusus. Saat masih muda misalnya (sinom), karena nafsunya yang masih menggelegak dalam usaha mengenali atau sedang mengeksplorasi kelebihannya sebagai manusia (jalan marga utama), ia seharusnya ditemani (kinanthi) perkembangan moral-spiritualnya dengan disiplin yang lebih bernuansa “hitam-putih” (syariat), agar ia tak kebablasan hingga justru menjerumuskannya pada jalan menyimpang yang merusak eksplorasi kelebihan (kemanusiaan)-nya.
Juga misalnya saat nikah (gambuh). Nikah adalah pranata sosial yang paling kuat sebagai kawah candradimuka yang memaksa seseorang untuk menundukkan ego dan diri rendah-nya, karena ia akan diuji untuk suatu tanggungjawab lebih dalam usaha mencari penghidupan dalam sebuah relasi masyarakat serta telah mengalami jatuh bangunnya proses tersebut (dhandhanggula) yang memang menuntut sikap kedewasaan tertentu. Oleh karenanya, jika ia lolos dalam olah penundukan diri ini ia akan “bisa” mendermakan baktinya (durma) kepada sesama karena telah lepas dan mengatasi pamrih diri dan egotisme diri rendahnya.
Makanya terdapat konsep penting dalam idiom Jawa untuk menggambarkan perjalanan penundukan nafsu empat sesuai tahapannnya, seperti (1) nanding sarira (membandingkan kelebihannya dengan yang lain) saat remaja, (2) ngukur sarira (mengukur batas capaian kelebihan serta kekuarangannya dengan yang lain) saat muda-menjelang dewasa, yang akan mengantarkannya pada kondisi (3) tepa sarira atau tepa selira, yakni bisa menakar atau menerapakan ukuran orang lain pada diri kita sendiri alias bisa mengambil sudut mental kebenaran atau perasaan orang lain (kedewasaan), tidak egois dan kekanak-kanakan. Oleh karenanya kedewasaan berarti seseorang telah mengatasi dan menundukkan pamrih diri dan nafsu egotismenya. Dengan capaian penundukan “diri rendah” tersebut dengan sendirinya akan mengantarkan seseorang mengenali dirinya pada tahap (4) mulat sarira hingga mawas dhiri. Orang yang telah bisa mengenali dirinya ia akan mengenal tuhannya. Man Arafa nafsahu ngarafa robbahu (ma’rifat; ngilmu makripat).

Karena penundukan diri tersebut merupakan bagian jenjang laku jasadi-ruhaniyah, maka orang Jawa mendisiplinkan laku penundukan ego tersebut (suluk/macapat) setidaknya dalam tiga hal; (1) yakni melalui disiplin strata bahasa berjenjang meninggi (bahasa ngoko-madya-krama-inggil) yang membuatnya sanggup menempatkan dirinya dalam skema andhap-asor (tidak menggunakan karma inggil untuk dirinya sendiri/ merendahkan diri sendiri), juga disiplin gerak tubuh yang telah diatur dalam tata-krama dan unggah-ungguh (menunduk jika melewati orang tua, dll), juga (2) menajamkan atau tepatnya “menghaluskan rasa” melalui olah-seni dalam wujud gamelan, tari, dll agar bisa menundukkan karsa-tubuh dan gejolak rasa yang tak terkendali menuju tercapainya rasa halus, hingga (3) melalui jalan tapa, laku-prihatin, puasa, riyalat, mengurangi makan-tidur-seks, mutih, kungkum, tarak-brata, lelana, dll. Oleh karenanya dalam pengertian poin ketiga ini kata “laku” atau “lelaku” (spiritual) sering dilekatkan—persis seperti arti sepesifik kata suluk dalam istilah Tarekat. Karena ia sedang menunjuk usaha penundukan nafsu empat dan egotisme diri rendahnya dalam sebuah perjalanan panjang sangkan paran agar mulus menjalani lelakon hidup. Urip mung saderma nglakoni.
Sejauh pengalaman saya membaca serat, suluk, babad, dan wirid dalam khasanah kesusateraan Jawa, saya menemukan bahwa seluruh ajaran pengetahuan dan ilmu Jawa berpusar pada pengetahuan ihwal mengenal akan diri sendiri, alias laku diri, yang sering dibahasakan secara berbeda seperti mawas dhiri, mulat sarira, hingga pangawikan pribadi. Yakni sebuah usaha untuk mengenali dirinya sendiri dalam skema sangkan paran—tentu dengan cara menundukkan nafsu empat dalam dirinya (macapat), sehingga ia bisa mengutuhkan kedirian kemanusiaanya agarnya ia ketemu dengan diri sejatinya (jati diri). Agar ia bisa mengutuhkan atau menyempurnakan kemanusiaannya (janma utama atau insan kamil).
Ngilmu Iku…
Saya akan mulai mengutip bait Wedhatama yang begitu popular dalam tradisi Jawa, tentu dengan versi yang agak lengkap, terutama pada bait (pada) pertama tembang Pucung (3),
“Ngilmu iku
Kelakone kanthi Laku
Lekase lawan kas
Tegese kas nyantosani
Setya budya pengakese dur angkara”
Ilmu itu
Tercapainya dengan cara laku (olah diri)
Permulaannya dengan sungguh-sungguh
Maksudnya sungguh2 mengukuhkan tekad (utk)
Setia (terus-menerus) mengolah-budi (dalam) memberantas angkara-murka (sumber keburukan)
~~~
“Angkara gung
Neng Angga anggung
Gumulung
Gegolonganira, triloka leker kongsi
Yen den umbar ambabar dadi rubeda”
(Yakni) Angkara besar
Yang bertempat dalam diri (badan), yang selalu
Bergulung-gulung
Yang jenis-jenisnya menjangkau/menempati tiga dunia dalam diri (tempat representasi nafsu berpusar)
Karena jika dibiarkan merebak menjadi bahaya
Ilmu itu tercapainya dengan laku. Apa makna laku di sini? Ada banyak sekali buku dan sarjana mengartikan laku di atas sebagai “perbuatan” atau bahkan “praktik” dalam pengertian umum. Namun ini hanya setengah benar, karena ia tak mewakili penjelasan teks Wedhatama secara utuh. Padahal banyak sekali acuan kata laku yang sebenarnya telah disediakan dalam keseluruhan teks, dimana pengarang Wedhatama telah memberi kerangka acuan makna yang menyebar dalam teks sebagaimana kata laku bisa ditemukan di sekujur teks.
Sebut saja misalnya di awal pupuh Sinom sebelum pupuh Pucung pada bait “ngilmu iku” disebutkan:
“Nulada laku tama
Tumrap wong tanah Jawi
Wong Agung ing Ngeksi ganda
Panembahan Senapati”
Meneladani laku utama
Untuk masyarakat Jawa
Orang besar dari Mataram
Panembahan Senapati (pendiri Mataram)
Eksplisit di bait tadi, sang pengarang menyebut acuan kata laku yang seharusnya menjadi acuan mengartikan kata laku. Yakni sebuah usaha meneladani laku utama dari seorang raja pendiri mataram, Panembahan Senapati. Apa yang dimaksud kata laku (utama)? Penjelasan ini ada pada bait setelahnya,
“Kepati amarsudi
Sudane hawa lan nepsu
Pinesu Tapa-brata
Tanapi siang ratri
Memangun Karyenak Tyas ing Sasama”
Berusaha keras melatih
Menguranggi hawa-nafsu
Mengusahakan laku tapa-brata (prihatin)
Serta di siang hari maupun malam hari (selalu)
Menciptakan rasa enak di hati sesama
Laku seperti sudah saya jelaskan di awal-awal halaman, berkait dengan olah-diri untuk menundukkan nafsu lewat jalan tapa-brata, tafakkur, prihatin, mengurangi hawa nafsu, hingga selalu berusaha menciptkan rasa enak di hati sesama. Sebuah laku atau riyalat ruhaniah untuk menundukkan ego diri. Seperti dicontohkan Senapati, di saat sepi berkelana tanpa bekal apa-apa sebagai laku prihatin/tafakkur (kala kalaning ngasepi, lelana teki-teki) untuk menyelusuri batas terdalam kehendak diri (nggayuh geyonganin kayun), yakni dalam rangka mencapai hati-pikiran yang “hening” (kayungyun eninging tyas), senantiasa laku-prihatin, teguh mengurangi makan dan tidur (sanityasa pinrihatin, puguh cegah dhahar lawan nendra). Setiap keluar dari rumah, berkelana ke tempat sepi agar ia tahu kejelasan kehendaknya (mrih pana pranaweng kapti), untuk mencapai puncak kelembutan hati (tis-tising tyas marsudi), agar menjadi ahli mengolah budi bersih (mardawaning budya tulus), mengusahakan keutamaan hati (mesu reh kasudarman), dll. Dikarenakan laku keras tadi, yakni saat di pinggir samudera, seperti dikisahkan pada sosok Senapati, ia kejatuhan anugerah ilham lembut dari Tuhan (Sruning brata ketaman wahyu dyatmika).
Malah yang lebih eksplisit, makna kata laku sebenarnya sudah disebut dan dijelaskan secara gamblang dalam bentuk tahapan, atau tingkat-tingkat berjenjang menaik seperti tercantum dalam skema Serat Wedhatama, yakni dari (1) Sembah Raga (disebut sebagai permulaan laku atau amagang laku), (2) Sembah Cipta/Kalbu (juga disebut laku lanjutan/uga ingaran laku), (3) Sembah Jiwa (yang disebut sebagai puncak tertinggi laku/pepunthoning laku), dan terkahir (4) Sembah Rasa (pada titik ini tidak ada laku karena tidak ada lagi petunjuk/ dadine wis tanpa tuduh, kecuali hanya berpandu pada tekad kuat/ mung kalawan kasing batos).
Hal ini semakin menguatkan dan mengafirmasi tesis awal saya bahwa kata laku juga bermakna persis dengan kata suluk. Karena jika melihat tahapan yang telah disebut di atas, hanyalah merupakan bahasa orang Jawa untuk mengajarkan tahapan suluk dalam tasawuf berjenjang empat, yakni (1) syari’at atau sembah raga, (2) tarekat atau sembah cipta/ kalbu, (3) hakikat sebagai sembah jiwa, (4) ma’rifat atau sembah rasa. Nanti kita akan melihat bahwa setiap kriteria untuk menunjukkan setiap karakter tahapan laku dalam jenjang ini memiliki kriteria seperti dipahami dalam jenjang suluk dalam tradisi tasawuf. Plus beberapa kata dan kalimat yang menguatkannya. Yang saya ingin tunjukkan, Wedhatama tidak ingin sedang keluar dari bingkai Islam.

Jika kita sebelumnya membaca laku (olah diri) dalam kerangka membaca nafsu empat (macapat), maka pembacaan 4 tahapan laku juga bisa terkerangkai dalam tahapan ini. Karena ia bertujuan untuk mengolah unsur diri yang berjumlah empat sebagai fakultas diri yang dilekati oleh empat nafsu yang telah disebut di awal, yakni raga, cipta, jiwa, dan rasa. Ini juga mengafirmasi kesejajaran konsep laku dalam pengertiannya sebagai usaha untuk mengolah empat unsur diri, agar empat unsur itu manunggal dalam diri, sehingga akan mencipta kualitas manusia utama (jalma utama atau insan kamil). Dan yang lebih ditekankan bahkan dalam olah diri atau laku dalam tradisi Jawa selalu berkait tujuan “dunia” ini (dalam pengertian mempercantik dunia), seperti tercantum gelar kalifatullah raja Jawa Islam. Para raja Jawa menjalankan laku dan tarak-brata untuk menjadi sumbu dunia/ mangkurat/pakubuwana/hamengkubumi, agar bisa menebar kebaikan dunia, setidaknya di tingkat normatifnya.
Oleh karenanya kualitas dari olah laku spiritual Jawa pertama bertujuan untuk menegakkan unsur kemanusiaan, alias untuk kepentingan dunia ini, dan bukan merupakan usaha eskapisme murni. Meski harus kita akui, karena tujuan ini, konsep ini juga mengilhami praktik “menyimpang” tanda kutip jika digeret oleh praktik massal orang awam. Segera kita akan menuju empat tahapan olah diri ini yang disebut oleh Wedhatama sebagai laku mengolah budhi (amasah mesu budi), yang sungguh selaras dengan defenisi “budaya”, jika ia diartikan sebagai “mendayakan budi” (budi daya/budhya). Kata “budaya” dalam pengertian mendayakan cipta, karsa, rasa, manusia (meski hanya tinggal tiga unsur, tidak ada jiwa) sebenarnya juga masih merupakan bagian dari definisi laku atau suluk. Namun visi Jawa lama masih menyangkutkan olah tersebut dalam skema sangkan-paran kembali menuju-Nya.
Laku Raga
Apa wujud laku olah diri dalam rangka sangkan paran kembali pada tuhan tersebut? Yakni (1) sembah raga, yakni sebentuk usaha mendisiplinkan raga kita, beserta dorongan kehendak-kehendak yang muncul alias karsa dari sifat alamiah raga itu. Alias dorongan nafsu alamiah seperti dimiliki oleh hewan. Tanpa kedisiplinan ragawi, kemantapan ruhani sulit dicapai. Oleh karenanya Wedhatama menekankan bahwa cara ampuh untuk menundukkan dorongan dan tubuh wadag ini yakni dengan displin berulang yang telah tertentu waktunya(wantu wataking wewaton). Bahkan teks ini menekankan disiplin lima waktu dalam sehari dalam waktu sholat (kang wus lumrah limang wektu), dan cara bersucinya melalui air-wudhu (sesucine asarana saking warih). Hal ini sekaligus mengafirmasi bahwa tahapan awal laku (amagang laku) dimaksudkan dalam pengertian syariat, atau tahapan awal suluk. Dalam pemahaman ini syariat adalah bagian awal tahapan laku mengolah diri kemanusiaan kita (lire sarengat iku kena uga ingaranan laku).
Laku ragawi ini serta dorongan karsa yang muncul darinya harus ditundukkan dalam sebuah disiplin yang ajeg dan telaten (dingin ajeg kapindhone ataberi). Agar orang tidak terjerumus dalam praktik merugikan orang lain seperti mencuri, merendahkan orang lain, dan berzina, orang tidak perlu menunggu kesadaran akan bahaya dan dampak dari perilaku yang muncul. Melainkan Ia harus dicegah oleh aturan “hitam-putih” bernama syariat. Juga seperti sesuai gerakan sholat, olah-disiplin-raga ini bisa membuat raga menjadi lebih sehat (nyenyeger badan mrih kaot), yakni dengan gerakan dalam sholat yang dijalankan membuat aliran darah menjadi lancar yang memicu jernihnya hati kita (tumrah ing rah memarah antenging ati), dan oleh karenanya bisa menghilangkan keruwetan pikiran (antengin ati nunungku angruwat ruweding batos).
Laku Cipta/Kalbu
Laku menundukkan diri pada wilayah cipta, pada hakikatnya, adalah menajamkan cipta/akalnya agar tetesan pengetahuan menujunya (patitis tetesing kawruh). Alias menjernihkan pikiran dari godaan hawa nafsu, keinginan yang telah disusun secara lebih kompleks oleh pikiran dan imajinasi, yang membuatnya tidak bersifat obyektif dalam menilai kenyataan yang diselimuti keinginan, pamrih, dan nafsu-nafsu subyektifnya. Oleh karenanya cara bersuci pada tahap laku ini adalah bukan dengan menggunakan air-wudhu (sesucine tanpa banyu), melainkan melalui usaha mengurangi atau meredam godaan gejolak nafsu yang menggelegak (mung nyunyuda mring hardening kalbu). Hal itu harus dilakukan dengan menata pikiran dari godaan-godaan nafsu secara teliti, hati-hati (pambukane tata titi ngati-ati), ajeg, telaten, dengan cara pembiasaan (atetep telaten atul), dengan bantuan jangkar bernama waspada (tuladan marang maspaos).
Kewaspadaan terhadap nafsu-keinginan-pamrih yang bisa mengganggu jernihnya akal dalam menilai baik dan buruk tidak hanya akan mengantarkan seseorang akan kenyataan obyektif apa adanya, melainkan juga akan meningkat pada “kesejatian penglihatan” (mring jatining pandulu) yang tindak perbuatannya akan menapaki tangga jalan bertahap bertingkat kenyataan/maqam (panduk ing ndon dedalan setuhu). Kata jalan (dedalan) mengingatkan saya pada tahapan tarekat (yang secara berarti berarti jalan) yang ingin dimaksudkan pada tahap olah diri ini. Makanya dalam tradisi awal memasuki tarekat, orang diminta untuk menjalankan amalan khusus dari mulai berpuasa, amalan khusus, sholat malam, zikir, dll yakni dengan kadar lebih dari orang kebanyakan, agar ia lebih terlatih menekan godaan nafsu, pamrih yang dapat menggagu penilaian akal sehatnya sebagai pandu menilai baik-buruk.
Bahkan Jika amaliah khusus dilakukan secara lurus (lamun lugu legutane reh maligi), biasanya ia akan mendengar suara-suara sayup-sayup seolah dari kejauhan (lageane tumaluwung), sebagai tanda terbukanya tingkatan alam (kenyataan) lain di atas pengenalan cipta seperti wadagnya (wenganing alam kinaot). Godaan menundukkan pamrih, ego, nafsu di level cipta atau kalbu ini lebih kompleks karena keinginan alamiah itu telah ditempeli gagasan yang membuatnya susah dikenali, sehingga ia tak mudah lagi untuk ditundukkan. Makanya ia diminta dengan kewaspadaan melalui amalan khusus, yang membuatnya tidak menyerah dalam olah laku penundukan ini (den awas den emut mring pamurung lelakon).
Laku Jiwa
Laku olah diri Jiwa oleh Wedhatama disebut sebagai tahapan akhir dari laku (ing arananan pepunthoning laku), yakni sebuah laku yang berkaitan dengan dunia batin (kelakuwan kang tumrap kang bangsa batin). Dalam olah diri ini ia harus bisa menjelmakan yang maha suksma dalam diri setiap detik harinya (mring hyang suksma sukmanen seari-ari). Dalam bahasa yang lebih profan ia diminta untuk terus me-reorientasikan tujuan hidupnya kepada tuhan dalam rangka perjalanan sangkan-paran menuju-Nya; bahwa dunia ini sementara, bahwa dunia ini bukan tujuan, dll. Oleh karenanya cara bersuci dalam olah ini yakni dengan cara awas dan juga ingat (sucine lan awas emut). Alias dalam bahasa kita adalah “zikir”, mengorientasikan seluruh tindakan dalam kehidupan ini hanya pada-Nya yang akan memberi arah tujuan akhir yang jelas (paran).
Dengan tahapan berjenjang olah diri yang menempati puncak laku ini ia akan bisa mengggulung setiap nafsu dan dorongan alamiahnya, juga keinginan nafsu yang telah disofistifikasi oleh gagasan, pikiran, dan angan-angan (pamrih diri, egotism, diri rendah, godaan setan) yang sifatnya bisa lebih kompleks. Dalam bahasa Wedhatama, pada tahap ini, orang telah bisa mengarah, meringkas atau meringkus, menali, dan merangkul “tiga jagad” (triloka) yang secara simbolis merupakan tempat tiga golongan nafsu tersebut bersemayam (ngangkah ngukud ngiket ngruket triloka kakukud).
Oleh orang Jawa, tiga jagad (triloka) itu sering dinamai (1) baitul makmur (guruloka) yang berada di kepala, yang melecut sifat ingin menang sendiri, ingin mewah, ingin menonjol, sombong, dll (2) baitul mukarram (endraloka) yang bersemayam dalam dada/hati yang melecut sifat dengki, marah, iri, dan yang terakhir (3) baitul mukaddas (janaloka) yang bersemayam dalam kemaluan yang memunculkan rasa sahwat, tertarik wanita, dll. Ketika tiga golongan nafsu ini diitundukkan Jiwanya akan bersih dari kemelekatannya pada dunia. Alias jiwanya telah lurus menghadap-Nya (rasakna kang tuwajuh). Ia akan bisa merasakan alam hakikat (senyatane iku kanyatan kaki). Yakni tenggelam dalam alam yang menghanyutkan juga melingkungi (keleme mawi limut), dan mendapat ilham/hidayah dari dalam alam tersebut (kalamatan jroning alam kanyut). Diri yang telah menundukkan seluruh golongan nafsu dalam tubuhnya akan mendapat secercah cahaya yang menghidupkan dan menerangi budi dan akhlak-nya (ana sejatining urub, urub pengarep uriping budi), sebuah terang semburat yang menerangi (sumirat sirat narawung), layaknya bintang yang bersinar (kang pindha kartika byor).
Laku Rasa
Laku tahap terakhir sebenarnya bukan lagi merupakan laku. Karena tidak lagi ada petunjuk (dadine wis tanpa tuduh), kecuali hanya bekal tekad batin atau keadaan batin yang khusus (mung kalawan kasing batos). Ia yang telah melewati tahapan laku dirinya, Ia berharap akan mendapatkan kerelaan dan rahmat Allah (wus kakenan nugrahaning Hyang widhi), seperti halnya keadaannya sendiri yang telah menerima, pasrah, dan hanya percaya pada pedoman aliran gerak takdir (amung kandel kumandel marang takdir), karena diri rendahnya benar-benar terkendali. Penglihatan batinnya telah menyibak tabir hijab (pambukaning warana, ingkang buka ing kijabullah), dimana ia telah merasakan (rasa jati) dan sampai pada saripati kehidupan ini (sembah rasa karasa wosing dumadi). Dan pengetahuannya, oleh karenanya, ia simpan rapat di dasar hatinya (sinimpen telenging kalbu), sehingga “rasa sejati” akan menyusup ke dalam dirinya (sumusuping rasa jati) yang akan menjadi pandu dalam menjalani hidup.
Inilah yang disebut dalam baris puisi Wedhatama pada baris sebelum kalimat “ngilmu iku kelakone kanthi laku” sebagai “ilmu makripat”, atau dalam bahasa verbatim serat ini “sudah bersemayam penglihatannya pada ma’rifat (wus manggon pamucunge mring makripat). Ia tak lagi ragu ketunggalan sifat-sifat dan asma Allah yang telah bersemanyam dalam diri/tauhid wujud (tan samar roro-roroning atunggil). Secara tersirat usaha laku untuk mengedalikan empat unsur dalam diri (raga, cipta, jiwa, rasa), dalam bahasa lain, adalah usaha untuk “mensyahadatkan raga”, pikiran, jiwa, dan rasa kita. Makanya tak aneh jika untuk menyebut empat laku tersebut pengarang Wedhatama menyebut dengan istilah “sembah”.
Jadi “Ilmu iku kelakone kanthi laku” bermakna ilmu (sejati) itu tercapainya melalui olah diri yang dengan sungguh-sungguh dan tekad yang kuat mengolah suluruh bagian dari diri untuk memberantas segala angkara murka atau nafsu yang bersemayam dalam diri kita, yang merupakan sumber kejahatan dan keburukan di dunia ini. Olah diri tersebut dilakukan dalam sebuah tahapan laku berjenjang-menaik mengolah unsur empat dalam diri kita, layaknya sebuah tahapan suluk dalam empat tahapan dalam tradisi tasawuf, yakni (1) laku raga, syariat, (2) laku cipta, tarekat, (3) laku jiwa, hakikat, dan (3) laku rasa, ma’rifat, yang oleh bahasa verbal Wedhatama ke-empatnya dinamakan “sembah”. Artinya setiap usaha mengolah diri tiap bagian unsur dalam diri dimaknai bukan semata profan untuk memaksimalkan potensi kedirian manusia, melainkan ia ditempatkan pada garis kontinum “perjalanan besar” sangkan-paran hidup ini yang pada akhirnya akan kembali pada-Nya.
Tahapan laku atau olah diri ini dijalankan dengan cara (1) mendisplinkan dorongan nafsu-nafsu tubuh jasmani (raga/karsa) melalui disiplin dan aturan syariat, (2) menajamkan pikiran/cipta dengan cara waspada atas keinginan egotis pikiran, pamrih subyektif yang bisa mengganggu kejernihan pikiran kita dalam mengenali kenyataan secara jujur agar dapat memilah kebenaran dan kebatilan (3) selalu mengembalikan orientasi jiwa kita pada tujuan hidup akhir kepada-Nya dengan cara mengingat-Nya, yang dengan itu (4) rasa (sejati) akan bisa menjadi pandu dalam menjalani tugas mulia kita di dunia yang akan dipertanggungjawabkannya saat ia kembali pada-Nya.
Ngilmu, Janma Utama
Dapat kita simpulkan bahwa seluruh rangkaian penjelasan Ilmu melalui jalan laku diri, seperti digariskan Wedhatama adalah dalam rangka untuk mengutuhkan kedirian kemanusiaannya (mengkono Janma utama). Dengan bahasa lain ilmu dicapai untuk mengubah kedirian manusia menjadi mahluk yang berbudi utama, atau meghasilkan manusia dengan moralitas utuhnya. Hal ini persis dengan tujuan keseluruhan Wedhatama ditulis (jinenjer ing wedhatama), yakni agar tak kurang cadangan “air ngilmu” yang digunakan untuk mengolah budi (mrih tan kemba kembenganing pambudi), juga agar berhasilnya hingga titik terdasar suatu perbuatan yang didasarkan ilmu luhur (mrih kertarta pakartining ngilmu luhung). Caranya adalah mengenali diri sendiri, atau dalam bahasa Serat ini “tenggelam dalam membaca ayat diri” (manganyut ayat winasis), hingga titik terdalam hakikat diri (wasana wosing jiwangga) yang menghantarkannya pada rasa sejati (ma’rifat).

Sungguh sayang jika sudah berumur tua tapi tak mengenali “rasa” (tan mikani rasa), sungguh akan membuatnya “sepi”, “hambar”, persis seperti ampas tak kentara (yekti sepi asepa lir sepah samun). Karena makna tua berarti berarti telah diam hawa nafsunya, dan telah menunggalkan tauhid-wujud (lire sepuh sepi hawa awas roroning atunggil), yang dengan bekal itu ia bisa disebut sebagai manusia yang telah waspada pertanda samar dalam hidup (wus waspadeng semu), bahkan telah sanggup menunggalkan pertanda samar (pasemon) tersebut dalam diri dan tindakannya (wis bisa nuksmeng pasang semu), dalam rangka menangkap pasemon agung dari kegaiban Tuhan yang maha suci (pasamoaning hebing kang maha suci) yang telah tergelar dalam ayat diri dan semesta. Seorang manusia yang telah menangkap dan melihat alam diri dan semesta sebagai semata manifestasi wujud Allah yang tergelar (wujudulloh sumrambah ngalam sakalir/tajalliyat).
Makanya, pencapaian ilmu seseorang pasti diikuti oleh perubahan kualitas moral-spiritual dan kedewasaan seseorang. Orang Jawa punya ungkapan spesifik dalam menyebut keadaan seseorang yang belum memenuhi tuntutan moral Jawa yakni dengan istilah “durung Jawa” (belum Jawa), yang sering dialamatkan pada tingkah laku anak-anak (belum dewasa). Jadi ilmu pasti menyeret seseorang—dalam frame pengertian usaha mengolah diri kemanusiaanya—pada tingkat kedewasaaan moral-spiritual bahkan material yang sering disebut telah menjadi orang (dadi wong).
Makanya seluruh parameter untuk menandai kualitas manusia pandai maupun bodoh dalam Wedhatama selalu terkait dengan moral, juga ruhaniyah, dan bukan dalam kepandaian kognitif semata. Kualitas dan ciri orang bodoh misalnya ditandai oleh Wedhatama dengan ciri dan sifat seperti tak mau dianggap bodoh (lumuh ingaran balilu), jika berbicara tanpa dipikir (nora nganggo peparah lamun angling), tidak mau direndahkan dan inginnya selalu unggul (lumuh asor kudu unggul), sombong, dan sering sesumbar (semengah, sesongaran). Ciri kebodohan ini biasanya menyebabkan nalarnya tak berkembang dan acak-acakkan (nora mulur nalare ting saluwir). Metafornya seperti “gua gelap sepi diterjang angin yang mengeluarkan suara mendengung dengan erangan-erangan tanpa henti” (kadi gua kang sirung, sinerang maruta, gumarenggeng nggereng anggung gumrunggung)
Begitu juga saat mencirikan orang yang telah mencapai ilmu yang sejati yang telah meresap dalam hati, Wedhatama menyebut dengan kualitas moral seperti selalu waspada dalam sebuah pertemuan terhadap perkataan dan gelagat yang samar (waspadeng semu) dengan berusaha berbicara dan bertindak dengan cara menyamarkan atau menyembunyikan dalam sebuah tanggap-ucapan manis (sinamun in samudana, sesadon ing adu manis), dan berusaha menanggapi perkataan orang bodoh dengan cara mengalah dan menutupi kedunguan lawan bicaranya (si wasis waskhita ngalah, ngalingi marang si pingging). Orang seperti ini justeru akan gembira jika dianggap bodoh (bungah ingaranan cubluk), malah senang hatinya jika dihina (sukeng tyas yen denina), tidak seperti si dungu yang selalu “mendengung” ingin diagung-agungkan dipuji setiap hari (nora kaya si punggung anggung gumurunggung ugungan sedina-dina).
Oleh karenanya kualitas moral (akhlak) ini dalam bingkai sangkan-paran sebenarnya merupakan saripati puncak dari tujuan agama, persis seperti digariskan Islam. Karena agama dalam bahasa Wedhatama harus bisa mengangkat kemuliaan manusia dalam usaha mempercantik baju akhlaknya (agama ageming aji). Ia harus bisa mengantarkan manusia menuju inti-saripati akhlak (mring atining tata-krama) yang merupakan pakaian Agama suci ini, Islam (gon-anggon agama suci).
Kenapa saya menyebut Islam bukan yang lain? Karena petunjuk di sekujur teks Wedhatama memang membenarkannya. Itu ditandai dengan ungkapan rendah hati penulis yang menceritakan pengalaman saat muda yang sempat mencicipi dan terserap dalam dalam mengaji agama (duk maksih taruna, sedhela wus nglakoni aberap maring agama), yaitu belajar pada hukum syariat yang diajarkan para haji (maguru anggering kaji). Dan bahkan sang pengarang merasa tak pantas—sebagai ungkapan rendah hati dan status sosial sebagai anak raja yang digariskan melalui trah kesatria—untuk menjadi seorang penghulu masjid ahli agama yang secara umum waktu itu dipilih berdasar garis keturunan dan trah (tuwin ketib suragama pan ingsun nora winaris).
Malah, selain petunjuk kerangka syariat, hakikat, tarekat, ma’rifat yang ingin ditekankan dalam laku Islam sebagai penanda bingkai agama yang ingin ditunjuk, saya melihat kritik yang dilayangkan Wedhatama juga masih dalam bingkai agama tersebut. Misalnya ia mengkritik perilaku orang Islam yang terbelit dan melulu berpusar pada formalitas syari’at (anggung anggubel sarengat), tanpa memahami hakikat syariat sebagai penyaring tindak buruk (saringane tan den wruhi). Wedhatama bahkan menyebut lebih khusus empat dasar Islam sunni (ahlussunnah wal jamaah) sebagai pandu dalam melayangkan kritiknya, yakni (1) Qur’an/dalil (2) Hadis/dalil, (3) Ijma’, dan (4) Qiyas (sarengat, dalil dalaning ijmak, kiyase nora mikani). Empat dasar Islam ini jika tak dijadikan pandu dan tak dikenali secara utuh, akan menyebabkan, seperti dicontohkan serat ini, yakni saat membaca khutbah jum’at dimanis-maniskan, tapi dengan nada mengumandang, dan intonasinya seperti berperang (kalamun maca kutbah, lelagone dandanggendis, swara arum ngumandang cengkok palaran).
Serat ini juga mengkritik kecenderungan sebagian “santri dul” (terutama di daerah selatan sepanjang pesisir Pacitan) yang sering memperlakukan pengetahuan agama sebagai ajang bahan unjuk-wicara dan perbantahan (anggere pada nyalemong); syariat dicampur aduk dengan laku batin yang justru membuat bingung, ingin cepat-cepat tahu, seolah anugerah “cahaya tuhan” sudah ia dapatkan (kesusu arsa wruh cahyaning Hyang kinira den karuh) yakni tanpa melakukan olah tahapan yang telah dijelaskan di muka. Bahkan ada yang memahami agama pada level permukaan, alias keluar dari bingkai pembentukan akhlak, alias dengan memaknai dasar Islam yang berhenti hanya sebatas lafal (amaknani rapal), yakni seperti dicontohkan Wedhatama seperti kelakuan seorang sayid keluaran Mesir (kaya sayid weton mesir) yang seringkali meremehkan kemampuan (beragama) manusia lain (pedhak-pendhak angendhak gunaning janma). Persis seperti anak muda yang tidak ada hentinya dalam kesenangannya berbicara kesana-kemari (nora uwus, kareme anguwus-uwus), padahal intinya tidak ada (owose tan ana), seperti Buto—representasi tokoh pewayangan yang belum menundukkan diri rendahnya—yang sedang naik darah senang menganiaya (kaya buto, buteng betah nganiyaya).
Oleh karenanya Wedhatama ditulis untuk tujuan menghindar dari jebakan memahami pemahaman agama yang tidak mengantarkannya pada budi luhur seperti dicontohkan dalam kritik yang dilayangkan serat ini. Bahkan dalam skema empat tahapan laku untuk menundukkan golongan nafsu yang bersemayam dalam tubuh sebagai syarat mencapai ilmu (sejati), sang pengarang telah bisa mendeteksi dampaknya. Orang yang mengolah ilmu dengan tidak menautkan pada penundukan nafsu diri, dengan sendirinya akan terjerembab pada semata pengetahuan superfisial belaka. Ilmu yang dihasilkan hanya ada dalam ujaran dan diskursus (kawruhe mung ana wuwus), bahkan perkatannya ditinggi-tinggikan dan bahkan nyrempet-nyrempet barang-barang gaib (wuwuse gumaib-gaib), seolah-olah omongan tinggi seperti para wali (muluk ujare kaya wali), padahal dibantah sedikit melotot matanya, alisnya mengkerut alias marah (kasliring tithik, mencereng alise gathik). Malah, pengetahuannya ia salah-gunakan untuk tujuan pamrih kepemilikan harta-benda (dadi kawruhe kinarya ngupaya kasil lan melik). Itulah yang disebut serat ini sebagai “ulama telur” (pandhita antiga), luarnya seolah putih bersih padahal di dalamnya kuning.
Akhirnya, saya harus katakan, Ngilmu dalam tradisi Jawa pada prinsip dasarnya adalah laku untuk menyempurnakan diri untuk keutuhan kemanusiaanya sebagai penuntun menjalani “perjalanan besar” (laku/suluk) hidup sangkan-paran kita yang pada akhirnya akan kembali pada-Nya. Dari olah kemanusiaan ini, dimana diri rendah telah berhasil ia tundukkan, kualitas kemanusiaannya menjadi utuh. Dan laku ilmu tersebut akan menuntun manusia pada kualitas akhlak utama, yang tidak saja akan “menciptakan rasa enak terhadap hati sesama” (memangun karyenak tyasing sesama), melainkan juga ikut “mempercantik semesta” (memangun hayuning bawana), alias memberi rahmat bagi alam semesta apapun bentuk, warna, dan agamanya.
Yakni sebuah ilmu yang akan bisa memberi obor yang akan mengantarkan kedekatan kita alias “obor-kedekatan” pada Allah (kang minangka colok celaking Hyang widhi). Dimana ibarat perjalanan seseorang dalam menapaki jalan yang sangat berbahaya, Ia mendapat pandu obor yang menerangi jalannya agar tak tersesat dalam perjalanan kembali pada-Nya (yeku dalaning kasidan), alias lolos secara mulus dalam perjalanan pulang, wafat (kasidan jati). Ngilmu yang akan mengubah wujud alamiah kehewanan diri manusia (dumadi) menjadi manusia utuh yang bergerak secara wujud kembali pada wujud hakiki (dumadi-dadi/maujud-wujud). Singkat kata, Ngilmu adalah gerakan ontologis manusia menuju “perjalanan” pulang dalam garis sangkan-paran kembali pada sang pemilik wujud (Allah). Hu Allah.
Irfan Afifi (pejalan)
Cepokojajar, Senin 18 Februari 2019.