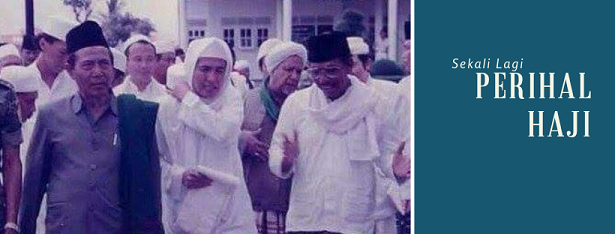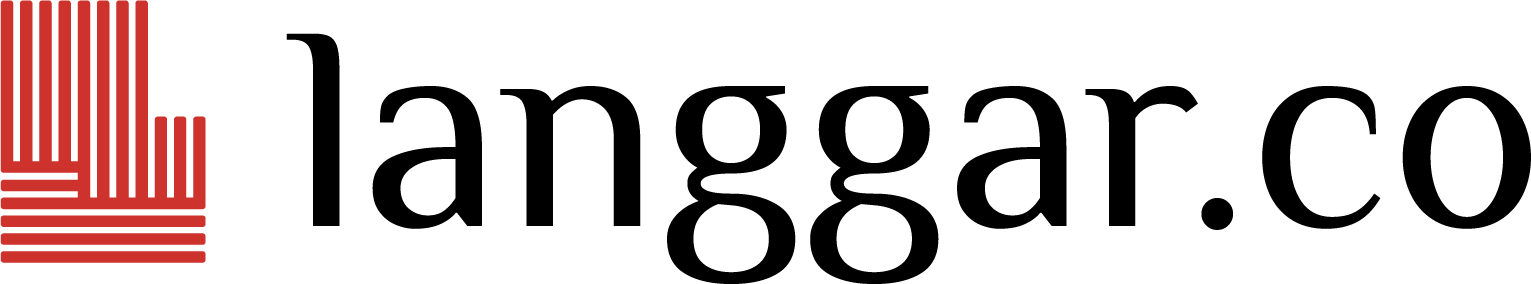Sekali Lagi Perihal Haji
Pada musim haji tahun ini ipar saya merasa beruntung bisa menjalankan ibadah haji. Beruntung sudah diberi kelancaran dan keselamatan dari mulai berangkat ke Makkah sampai...
Pada musim haji tahun ini ipar saya merasa beruntung bisa menjalankan ibadah haji. Beruntung sudah diberi kelancaran dan keselamatan dari mulai berangkat ke Makkah sampai kembali lagi ke rumah, ke tanah air Indonesia. Berjumpa lagi dengan suami, anak, dan keluarga.
Ipar saya beruntung karena tidak sedikit jamaah haji yang mendapat halangan. Halangan berupa musibah dan perkara lain yang mengkhawatirkan, seperti terpisah dari jamaah, tersesat tak tau arah penginapan, atau musibah lain seperti kecelakan jatuhnya alat berat yang menimpa jamaah haji pada tahun haji sebelumnya. Ipar saya juga beruntung karena ia bisa berangkat haji dalam kesempatan yang baik, di usia muda, di zaman serba mudah di mana calon jamaah haji tidak perlu lagi menghabiskan waktu setengah tahun di lautan, di atas kapal yang tidak sepenuhnya aman. Tidak jarang kapal karam dihantam ombak atau terdampar di pantai tak dikenal. Ia juga beruntung bisa berangkat cepat, di tengah antrian haji yang begitu panjangnya itu. Karena antrian panjang, tak sedikit calon jamaah haji yang baru bisa berangkat setelah usia mereka sudah sepuh.
Bagi umat Islam Indonesia, ibadah haji sejak lama mempunyai peranan amat penting. Bahkan ada kesan bahwa orang Indonesia lebih mementingkan haji daripada bangsa lain, dan penghargaan terhadap para haji (muslim yang pernah menunaikan ibadah haji) memang lebih tinggi. Bisa diukur dari panjangnya antrian calon jamaah haji dan panggilan “pak haji” atau “bu haji/hajah” bagi muslim yang pernah menunaikan ibadah haji.
Sebenarnya bukan hanya karena haji adalah salah satu bagian dari syariat Islam saja, atau sebagai ibadah yang dijanjikan ganjaran yang melimpah, tapi juga karena ibadah haji dan seorang haji dulu pernah menjadi tanda perlawanan atas kolonialisme, sebagai perangsang antikolonialisme dan juga tanda kedudukan atau kecakapan seseorang atas ngelmu atau ilmu agama.
Sebab menjadi tanda kecakapan dan perlawanan itu, dulu pemerintah kolonial Belanda menaruh perhatian khusus kepada calon jamaah haji. Sampai kemudian pemerintah kolonial mengutus orang-orang terbaiknya berangkat ke Makkah untuk mempelajari apa itu ibadah haji, seorang haji, dan hal-hal yang terkandung di dalamnya. Nama van der Plas dan Snouck Hurgronje termasuk bagian dari utusan itu. Mengenai Snouck Hurgronje tentang Haji, Anda bisa baca dalam tulisan Bagus Pradana berjudul Perihal Haji, yang dimuat dalam langgar.co.
Agak belakangan banyak juga yang menulis tentang Ibadah Haji ke Mekkah, dan apa saja yang bersinggungan dengannya. Misalnya dalam Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat (2012), Martin Van Bruinessen juga menulis satu bab tentang Haji. Dalam judul Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci: Orang Nusantara Naik Haji, ia menyebut beberapa fakta sejarah masa lampau tentang haji dan menariknya fakta-fakta itu tidak jauh beda dengan kenyataan yang bisa kita lihat sekarang ini tentang Haji. Seperti melimpahnya jumlah jamaah haji, jamaah yang memutuskan tinggal lebih lama di Makkah untuk menuntut ilmu, untuk bekerja dan yang lainnya. Dalam Les relations entre les Pays-Bas e le Hidjaz (Hubungan Belanda dengan Hijaz) Van der Plas yang pernah menjabat konsul Belanda di Jiddah itu mencatat, bahwa sekurang-kurangnya ada 10.000 jiwa orang Indonesia yang menetap di sana.
Martin mencatat; Di antara seluruh jamaah haji, orang Nusantara-selama satu setengah abad terakhir- merupakan proporsi yang sangat menonjol. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, jumlah mereka berkisar antara 10 dan 20 persen dari seluruh haji asing, walaupun mereka datang dari wilayah yang lebih jauh daripada yang lain.
Martin juga mengutuip catatan dari Jacob Vrendenbregt, dalam artikelnya, The Haddj: Some off its features an functions in Indonesia, yang menyebut; pada dasawarsa 1920-an sekitar 40 persen dari seluruh haji berasal dari Indonesia.
Pada masa itu jumlah haji dari Indonesia memang sangat besar karena beberapa tahun sebelumnya orang Indonesia tidak bisa naik haji sama sekali. Setelah Sultan Turki memproklamirkan jihad pada tahun 1915, pemerintah Hindia Belanda melarang orang naik haji sampai perang berakhir tahun 1918. Oleh karena itu banyak orang yang terpaksa menunda beberapa perjalanan haji mereka secara massal berangkat ketika haji diizinkan lagi.
Selain jamaah haji yang pulang pergi, ada juga jamaah haji yang kemudian memutuskan bermukim di Makkah atau Madinah. Orang Indonesia yang tinggal bertahun-tahun atau menetap di Makkah pada zaman itu cukup banyak. Keterangan ini bisa kita lihat dari catatan Snouck Hurgronje. Hurgronje yang menghabiskan waktu sekitar lima bulan di Makkah pada tahun 1885 itu mencatat bahwa di antara bangsa yang berada di Makkah, orang ‘Jawah’ (Asia Tenggara) merupakan salah satu kelompok terbesar. Sekurang-kurangnya sejak tahun 1860, bahasa Melayu merupakan bahasa kedua di Makkah, setelah bahasa Arab.
Catatan Hurgronje di atas bisa kita bandingkan dengan catatan-catatan lain, catatan yang ditulis oleh orang ‘Jawah’ sendiri. Seperti catatan perjalan yang ditulis oleh pelopor sastra Melayu modern, Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi. Abdullah naik haji jauh sebelum Snouck berangkat ke Makkah, yaitu pada tahun 1854, tidak lama sebelum kapal layar digantikan kapal api.
Selain Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi, masih banyak ulama-ulama atau murid-murid mereka yang berasal dari Nusantara yang mukim atau menetap di sana, yang setelah merasa cukup mencari ilmu lalu memutuskan kembali ke kampung halamannya. Mereka yang pulang itu lalu mencatat apa saja yang didengarnya dan dilihatnya di Makkah. Tidak sedikit yang menulis karya tulis ilmiah dan catatan-catatan lain yang sifatnya lebih khusus, seperti biografi atau manaqib yang ditulis untuk kalangan terbatas, untuk murid dan keluarganya.
Salah satu catatan khusus itu ditulis oleh Kiai Muhammad ibn Sulaiman, yang mencatat perjalanan pendidikan ayahnya sendiri, Syekh Sulaiman. Dalam catatan itu ia menyebut Syekh Sulaiman pernah berangkat Haji sebanyak enam kali. Kemudian di Makkah dia mengambil baiat tarekat Syadzili kepada Syekh Shalih Kamal. Lalu ia juga jumpa dengan dua guru tarekat Syadzili yang juga murid dari Syekh Shalih Kamal, yaitu Kiai Idris Jamsaren ulama asal Surakarta/Solo, dan Kiai Ahmad Nahrawi al Makki ulama yang berasal dari Banyumas, Jawa Tengah.
Belanda mencatat banyak orang yang telah berangkat ke Makkah tidak kembali lagi. Antara tahun 1853 dan 1858, jamaah haji yang pulang dari Makkah ke Hindia Belanda tidak sampai separuh dari jumlah orang yang telah berangkat haji. Tidak kembali bisa karena memutuskan menetap di sana, atau karena kematian. Simbah Syarifah, Buyut Putri saya meninggal di perjalanan. Jenazahnya ditenggelamkan di dasar laut.
Perangsang Antikolonialisme
Seperti biasa, selain membawa pulang doa yang dianggap mujarab, jamaah haji akan pulang membawa oleh-oleh bermacam-macam ujudnya. Ada kurma, kismis, manisan buah Tin, lalu air zam zam sajadah, dan tasbih. Oleh-oleh itu nantinya akan dibagikan kepada kerabat sanak saudara, dan tamu yang berkunjung ke rumahnya. Sebuah tradisi yang melekat hampir di semua daerah dan sudah lama berjalan.
Dulu pada tahun 2006, kita masih bisa menemui pasar tradisional yang berada tepat di sebelah masjidil haram. Pasar itu oleh jamaah haji Indonesia disebut dengan Pasar Seng. Persis dengan pasar di seputaran tempat peziarahan yang kita kenal di Indonesia, seperti lorong jalan masuk menuju Masjid Ampel Surabaya, pedagang-pedagang itu menjajakan beraneka ragam barang dagangan. Mulai dari kurma, pacar, perhiasan, sampai dengan kadal mesir untuk jamu kuat (stamina). Dari semua dagangan itu, ada dagangan yang hampir selalu tersedia di setiap toko, yaitu tasbih.
Meski sekarang sudah jarang orang menggunakan tasbih, bisa jadi karena sudah tidak lagi mengamalkan wirid, atau karena ada tasbih digital yang lebih praktis, tapi masih saja banyak jamaah haji yang memilih tasbih sebagai oleh-oleh. Ini menjadi bukti, bahwa Makkah dan Madinah menyimpan sejarah panjang mengenai gerakan kaum tarekat, yang identik dengan tasbih, ciri utamanya senang berzikir atau mengamalkan ilmu, dan wiridan atau bacaan zikir tertentu yang diijazahkan oleh seorang guru atau mursyid. Gerakan tarekat inilah yang cukup kental mewarnai sejarah ulama Nusantara lulusan Haramain.
Makkah sebagai pusat kosmis, titik temu antara dunia fana kita dengan alam supranatural, memainkan peranan sentral. Tidak hanya diziarahi sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga dikunjungi untuk mencari ilmu, dan legitimasi politik. Sebagai tempat untuk mencari ‘legitimasi politik’ dapat kita lihat dari catatan sejarah yang menyebut pada pertengahan abad ke-17 raja-raja Jawa mulai mencari legitimasi ke Makkah.
Pada tahun 1630-an, raja Banten dan raja Mataram, mengirim utusan ke Makkah, antara lain, mencari pengakuan dari sana dan meminta gelar ‘sultan’. Agaknya raja-raja tersebut beranggapan bahwa gelar yang mereka peroleh dari Makkah akan memberi sokongan supranatural terhadap kekuasaan mereka (Martin Van Bruinessen, 2012). Pengakuan Syarif Besar, yang menguasai Haramain (Makkah dan Madinah) dipercaya memiliki pengaruh spiritual atas seluruh Dar al-Islam, termasuk Mataram dan Banten yang berada jauh di pulau Jawa.
Rombongan utusan dari Banten itu pulang pada tahun 1638, dan utusan Mataram datang agak belakangan pada tahun 1641. Beberapa waktu kemudian, pada tahun 1674, untuk pertama kalinya seorang pangeran Jawa pergi haji ke Makkah. Ia adalah putra Sultan Ageng Tirtayasa (Banten), bernama Abdul Qahar, yang belakangan dikenal sebagai Sultan Haji.
Makkah sebagai pusat ilmu atau ngelmu, juga disinggung dalam banyak catatan. Seperti misalnya dalam karya berbahasa Melayu, Hikayat Hasanuddin, yang dikarang sekitar tahun 1700 Masehi. Sunan Gunung Jati mengajak anaknya:
“Hai anakku ki mas, marilah kita pergi haji, karena sekarang waktu orang naik haji, dan sebagai pula santri kamu tinggal juga dahulu di sini (mukim) dan turutilah sebagaimana pekerti anakku!”
Dalam hikayat itu juga disebutkan bagaimana Sunan Gunung Jati (salah satu dari anggota dewan ulama di Jawa, Walisongo-Sembilan Wali) mengajari putranya cara menjalankan ibadah haji, dan ibadah lainnya, seperti thawaf, mencium hajar aswad, dan mengunjungi para syekh atau guru-guru di Makkah dan Madinah. Dari para guru tarekat yang diziarahinya, Sunan Gunung Jati dan putranya melakukan baiat tarekat Naqshabandiyah yang disebutnya ajaran ilmu sempurna.
Dalam mitologi Jawa juga menyebut cerita tentang Makkah sebagai pusat spiritual. Ini ada dalam Legenda Tengger yang diceritakan ulang dalam Tengger en de Tenggereezen oleh J.E. Jaspert. Dalam Legenda Tengger itu, disebutkan Aji Saka yang dikenal sebagai pencipta aksara Jawa, kalender Jawa (tahun saka) dan undang-undang Jawa, pernah pergi ke Makkah dan memperoleh ilmu dari Nabi Muhammad saw. Menurut Legenda Tengger, Aji Saka pada awalnya memperoleh ilmu dari Antaboga, sang raja naga. Setelah dikembalikan ke rumah kakeknya, Kiai Kures (Quraisy), sang kakek melihat cucunya luar biasa cakap. “Tetapi ada satu yang lebih cakap dari ia, “ Ujar Antaboga, “namanya adalah Muhammad dan tempat tinggalnya adalah di Makkah. Kirimlah cucumu kepada beliau agar menambah ilmu.” Aji lalu dikirim ke Makkah, dan di sana berguru kepada Nabi Muhammad saw. Setelah selesai belajar, Muhammad memberikannya sebuah kropak (buku lontar) dan pangot (pisau untuk menulis atas lontar), dan mengirimnya kembali ke Timur.
Martin dalam buku yang sama, juga menulis daftar beberapa nama orang Indonesia yang telah naik haji dan mencari ilmu di tanah Suci. Seperti Syaikh Yusuf Makassar berangkat ke Makkah pada tahun 1644 dan baru kembali ke Indoneisa sekitar tahun 1670. Di Makkah Syekh Yusuf belajar kepada banyak ulama besar, terutama ulama tasawuf, ia memperoleh ijazah untuk mengajar beberapa terekat. Selain mempelajari ilmu tasawuf, ia juga mempelajari filsafat, ilmu kalam dan yang lain.
Selain mengajarkan tarekat Khalwatiyah, ia juga punya peranan politik penting sebagai penasehat Sultan Ageng Tirtayasa. Ketika Kompeni Belanda mencoba menyingkirkan Sultan Ageng, Syekh Yusuf membawa pengikutnya ke gunung dan memimpin gerilya melawan Belanda selama hampir dua tahun, sampai akhirnya ditangkap dan dibuang ke Seylon, Sri Lanka.
Selain Syekh Yusuf masih ada banyak lagi orang Indonesia yang pergi haji, mencari ilmu di Makkah-Madinah, lalu pulang berjuang untuk tanah airnya. Dalam Mekka, Snouck Hurgronje mencatat bagaimana orang dari seluruh Nusantara ikut membicarakan perlawanan Aceh terhadap Belanda, dan bagaimana mata mereka dibuka mengenai penjajahan Belanda, maupun Inggris dan Prancis atas bangsa-bangsa Islam. Martin menyebut, saat itu para Haji hidup beberapa bulan dalam suasana antikolonial, yang sangat berbekas.
Pemberontakan petani Banten 1888 dan pemberontakan Sasak 1982 melawan Bali disebut diilhami oleh pengalaman tokoh-tokoh yang pernah tinggal di Makkah.
Dalam, Jogjakarta under Sultan Mangkubumi, 1749-1792, M.C. Ricklefs menyebut pada tahun 1772, seorang ulama kelahiran Palembang yang menetap di Makkah menulis surat kepada Sultan Hamengkubuwono I dan kepada Susuhan Prabu Jaka. Isinya, rekomendasi bagi dua orang haji yang baru pulang dan mencari kedudukan. Dalam pendahuluan surat itu ada pujian terhadap raja-raja Mataram terdahulu yang telah berjihad melawan Kompeni. Surat-surat ini dapat dibaca sebagai anjuran untuk meneruskan jihad melawan penjajah.
Ulama-ulama seperti Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfudz Tremas, dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, yang mengajar di Makkah pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, mengilhami gerakan agama di Indonesia dan mendidik banyak ulama yang kemudian berperan penting di tanah air.
Dari contoh di atas kita melihat beberapa fungsi sosiologis haji. Orang Indonesia mencari ilmu di Haramain (Makkah dan Madinah) dan setelah pulang ke tanah air mereka mengajarkan kepada masyarakat ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari. Sebagian dari mereka merasa tidak cukup hanya mengajar saja, mereka juga merasa perlu membuat wadah untuk menyatukan sesamanya. Maka lahirlah organisasi-organisasi Islam seperti Sarekat Islam (SI), Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kiai Hasyim Asy’ari dan Kiai Ahmad Dahlan, keduanya adalah alumni Haramain, murid dari Nawawi Banten, Mahfudz Tremas dan Ahmad Khatib Minangkabau.
Saya sepakat dengan Martin van Bruinessen, bahwa Islamisasi di Indonesia sudah berlangsung sejak abad ke-13 dan masih terus berlanjut sampai sekarang. Entah siapa yang pertama-tama membawa Islam ke Indonesia, apakah orang India dari Gujarat, Arab, atau malah Cina (soal Cina, bisa lihat penjelasan Buya Hamka), yang jelas sejak abad ke-17 peranan utama dimainkan oleh orang Nusantara sendiri yang telah belajar di tanah suci.
*****
Bagus Sigit Setiawan
Kartasura, September 2018