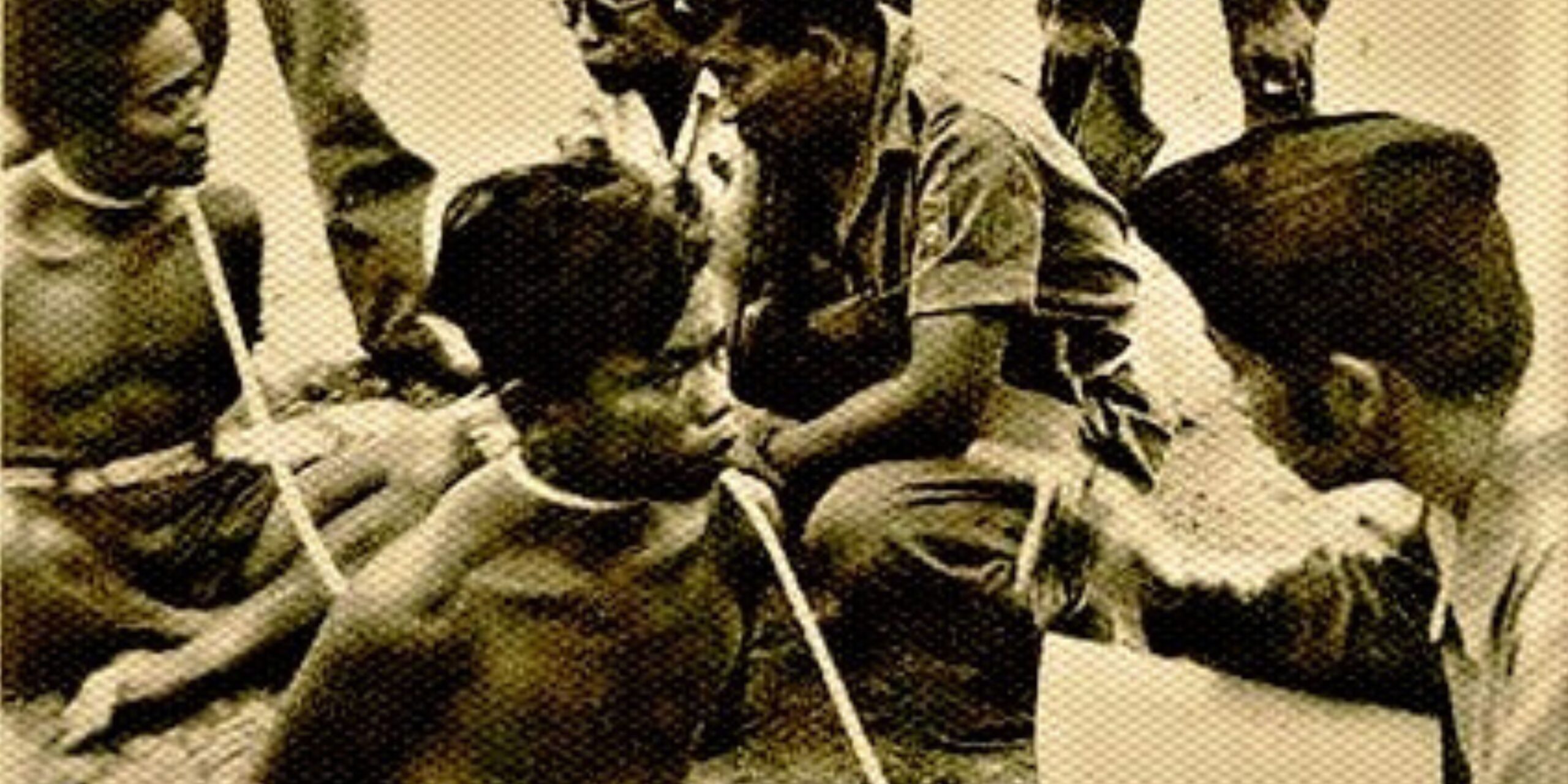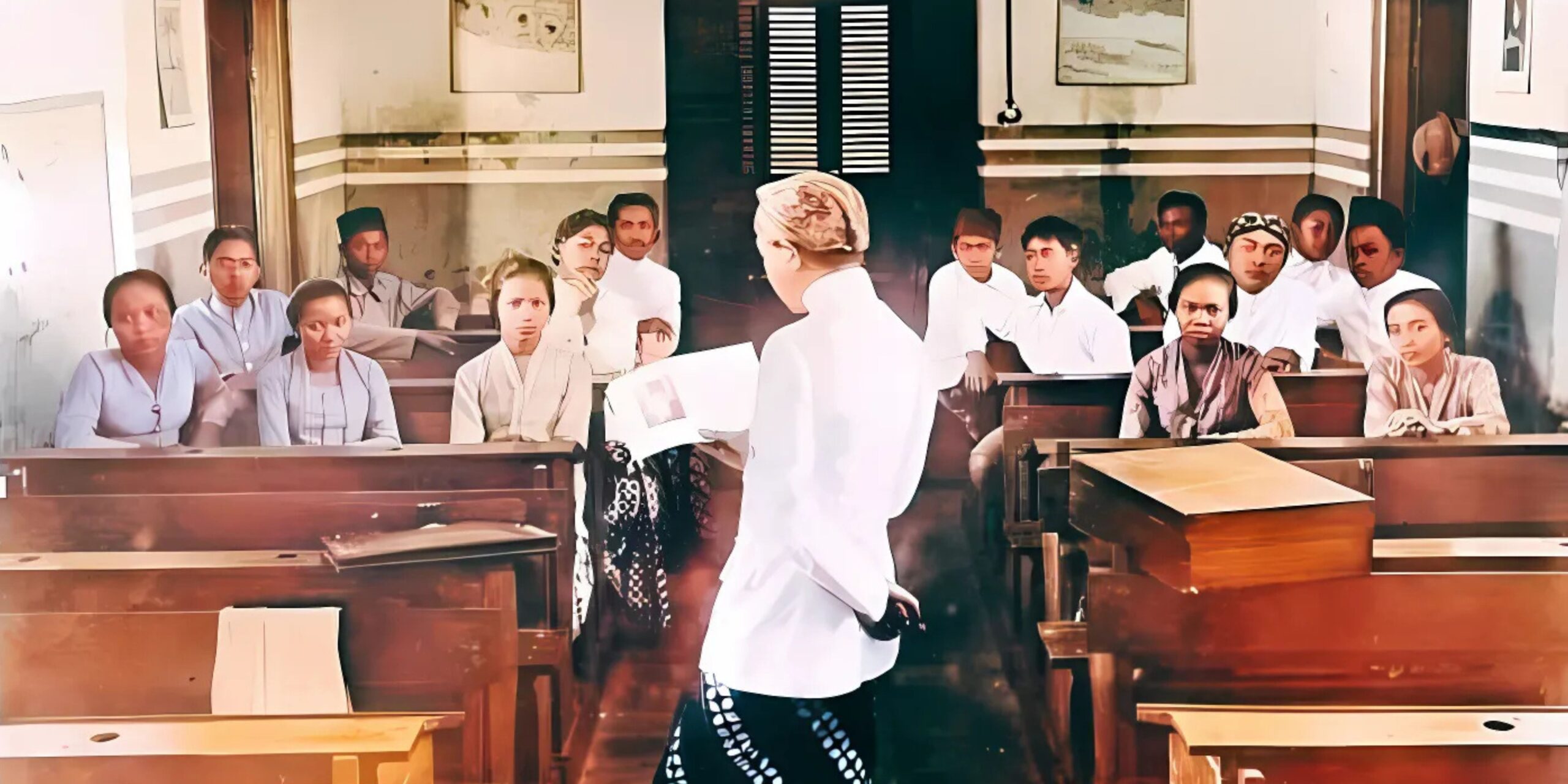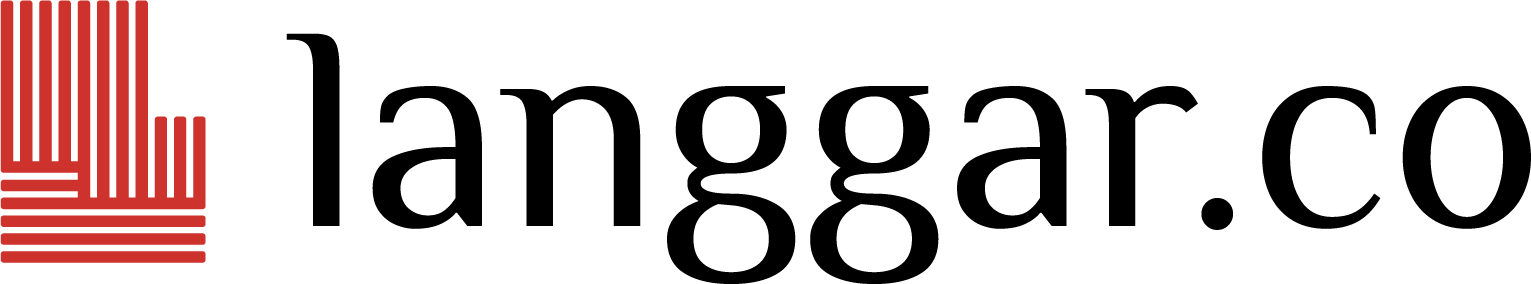Pandangan Orientalisme dan Mentalitas Inlander
(Sebuah Tanggapan untuk P Dr Alexander Jebadu, SVD) “MEREKA datang dengan Alkitab dan agama mereka. Mereka merampas tanah kami dan menghancurkan semangat kami, dan sekarang mereka mengatakan kepada kami bahwa...