“Siapa Pemimpin Kita?” Lakon “Petruk Dadi Ratu”
Tanda Seru dalam Jagat Kebudayaan Kita Salah satu peristiwa yang menyedot perhatian dan energi bangsa kita selama hajatan Pemilu 2019 kemarin adalah maraknya atribut bertuliskan...
Tanda Seru dalam Jagat Kebudayaan Kita
Salah satu peristiwa yang menyedot perhatian dan energi bangsa kita selama hajatan Pemilu 2019 kemarin adalah maraknya atribut bertuliskan kalimat tauhid yang dijadikan identitas kelompok pendukung salah satu kontestan peserta pilpres. Mereka menganggap itu sebagai pelaksanaan perjuangan umat Islam. Tentu saja terjadi pro-kontra terhadap hal tersebut, terkait persoalan apakah kalimat tauhid itu murni untuk “mengEsakan Tuhan” atau merupakan lambang dari organisasi terlarang HTI dan ISIS. Dan apabila itu murni kalimat tauhid, layakkah ia dijadikan atribut dan asesoris eksterior untuk kebanggaan suatu kelompok dengan menafikan bahkan mengeliminasi kelompok lainnya yang tidak sepaham? Bagaimana semestinya memperlakukan kalimat tauhid?
Puncak dari pro-kontra terhadap hal tersebut adalah terjadinya insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang menyusup di dalam arena peringatan Hari Santri 2018 di Garut Jawa Barat. Sontak terjadi “gempa sosial-politik” secara nasional yang seandainya waktu itu tidak ditangani secara tepat, sangat mungkin akan terjadi konfrontasi yang berskala luas dan menimbulkan instabilitas situasi politik nasional.
Tulisan ini tidak akan membicarakan hiruk-pikuk peristiwa tersebut secara sosial-politik, melainkan menjadikannya sebagai pintu masuk untuk membicarakan problem kebudayaan kontemporer kita dan menganalisa akar masalahnya melalui perspektif wayang purwa. Lebih dari sekedar peristiwa politik sesaat, peristiwa maraknya atribut bertuliskan kalimat tauhid dalam berbagai bentuknya serta wacana yang bersaing mengiringinya adalah sebuah symptom yang menandai suatu krisis di dalam kebudayaan kita dewasa ini.
Bagaimana kita akan memahami situasi kebudayaan kontemporer kita ini, dan menyikapi serta menempatkan perilaku diri kita di dalamnya? Dengan merujuk ke mana kita melakukannya? Dalam perspektif penikmat wayang purwa, maka pertanyaannya adalah “lakon apa sesungguhnya yang sedang berlangsung sekarang ini …?”.
Lakon apa sesungguhnya yang sedang berlangsung sekarang ini …?
Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Beriringan dengan peristiwa pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang terjadi pada 22 Oktober 2018 bertepatan dengan peringatan HSN itu, dalam bulan November 2018 ada insiden “kecil” namun sempat menjadi perbincangan hangat secara nasional yaitu pemasangan poster “Raja Jokowi” di beberapa kota di wilayah Jawa Tengah dengan gambar Jokowi dengan memakai mahkota raja di kepalanya. Poster-poster tersebut viral di medsos dan cukup ramai diperbincangkan.
Tak ayal, beberapa petinggi PDIP turun tangan melacak sumber dari poster tersebut karena dicurigai sebagai bentuk kampanye hitam dan bahkan dari pihak Bawaslu juga tak ketinggalan. Namun yang relevan untuk tulisan ini adalah respon dari seorang elit politisi nasional dari Partai Gerindra, FZ yang langsung menulis puisi menyindir “Raja” Jokowi tersebut dengan memparodikannya sebagai “Petruk Dadi Ratu” (Petruk jadi Raja). Dalam pandangan FZ, melalui asosiasi tersebut, Jokowi adalah pemimpin negara yang tidak layak karena tidak mempunyai kapabilitas, seperti dalam lakon wayang “Petruk Dadi Ratu”, sehingga tatanan dan keadaan negara saat ini kacau tidak menentu arahnya.
Lebih lanjut FZ menambahkan bahwa “wahyu keprabon” yang menempel pada Jokowi ini hanya sesaat, dan nanti akan segera ketahuan yang sebenarnya. Puisi dan komentar FZ di atas segera mendapatkan respon balik dari beberapa pihak yang simpati terhadap Jokowi, seperti dari seorang akademisi UI dan seorang dalang asal Jawa Tengah. Mereka memberikan tafsiran lain terhadap makna lakon “Petruk Dadi Ratu” ini.
Mereka memberikan tafsiran lain terhadap makna lakon “Petruk Dadi Ratu” ini.
Bagi mereka lakon “Petruk Dadi Ratu” ini adalah sebuah kritik, reaksi dan interupsi dari rakyat terhadap praktek oligarki kekuasaan negara yang selama ini didominasi oleh para elit ksatria (militer) untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka serta para konglomerat. Jokowi sebagai representasi rakyat (tukang kayu) menjungkir-balikkan tatanan yang selama ini hanya menguntungkan para elit ksatria, dan dengan itu berlangsunglah proses keseimbangan dengan ditegakkannya kembali moralitas dan perilaku yang melenceng.
Terkait lakon ini pula, penulis jadi ingat punya pengalaman ketika pada awal tahun 2014 ditunjuk oleh KH.A. Mustofa Bisri (Gus Mus) untuk membantu mengkoordinasi rangkaian acara Mahrajan Wali-Wali Jawi yang diselenggarakan di Demak yang puncak acaranya adalah pagelaran wayang kulit di Pendopo Kabupaten Demak. Penulis diminta untuk menentukan lakon wayang beserta dalangnya. Dan “entah” bagaimana pertimbangannya yang utuh, tetapi jelas sama sekali tidak ada pemikiran yang terkait dengan kontestasi antar kandidat dalam Pilpres 2014 pada waktu itu yang kebetulan akan diselenggarakan pada bulan Juli 2014, sementara agenda Mahrajan ini diadakan pada bulan Februari 2014, lakon yang dipilih (dan direstui Gus Mus) adalah Petruk Dadi Ratu dengan dalangnya (alm) Ki Enthus Susmono. Penulis masih ingat, dan baru menyadarinya lagi sekarang ini, bahwa waktu pagelaran itu berlangsung ada seorang tokoh nasional yang berkomentar spontan, “wah, ini berarti Pilpres nanti yang akan jadi presiden adalah Jokowi”.
Maksud tulisan ini tidak untuk menilai tentang benar salahnya perdebatan tentang fenomena Jokowi sebagai Presiden yang diasosiasikan dengan lakon Petruk Dadi Ratu, serta penjelasan dari masing-masing pihak baik pendukung maupun penentangnya, tentang makna dan maksud dari Lakon tersebut.
Tulisan ini lebih dimaksudkan sebagai refleksi pribadi penulis sendiri tentang makna dan signifikansi lakon Petruk Dadi Ratu dalam konteks kehidupan pribadi maupun masyarakat (kebudayaan) kita. Penulis berpendapat bahwa pagelaran wayang kulit itu sesuatu yang utuh, setiap unsurnya terkait satu sama lain, dan yang terpenting dalam hal ini adalah keutuhan alur cerita dan hubungan-hubungan antar tokoh di dalamnya. Dari proses tersebut terbentuklah makna dan nilai-nilai yang bersifat dinamis, baik yang bersifat eksternal-sosial maupun yang bersifat internal-spiritual.
Kerangka Lakon “Petruk Dadi Ratu”[1]
Ada kerajaan “tiban” yang bernama Loji Tengara. Kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Whelgeduelbeh, atau disebut juga dengan Prabu Thong Thong Sot tersebut tiba-tiba menjadi sangat terkenal. Hal itu dikarenakan, selain rajanya kocak dan unik serta penuh kontradiksi, ia juga sangat sakti mandraguna. Semakin hari semakin ramai orang-orang pada datang. Banyak raja dan ksatria menjalin persahabatan, bahkan sebagian dari mereka ada yang merelakan diri untuk mengabdi kepada Sang Raja kaya tersebut. Tentu saja hal tersebut membuat raja Hastina, prabu Duryudana resah serta khawatir.
Bagaimana nanti jika kerajaan Loji Tengara menggelar jajahan dan menyerang kerajaan Hastina. Untuk itu, sebelum apa yang dicemaskan terjadi, Prabu Baladewa dan Adipati Karna juga Patih Sengkuni serta warga Kurawa diutus untuk menaklukkan dan mengusir Prabu Whelgeduelbeh. Diibaratkan api yang sedang besar-besarnya, sulit untuk dipadamkan, demikian juga daya kekuatan serta kesaktian Sang Raja Tiban tersebut tidak dapat dikalahkan. Prabu Baladewa, Adipati Karna, Patih Sengkuni dan prajurit Kurawa tak berdaya melawan Prabu Whelgeduelbeh.
Kerajaan Loji Tengara kemudian melanjutkan kejayaannya dengan menantang dan menyerang Kerajaan Amarta yang didukung oleh Kerajaan Mandura dan Dwarawati, di mana para ksatria pilih tanding dari para pandawa juga tidak mampu menghadapinya. Amarta pun ditaklukkan, di mana Baladewa, Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa bertekuk lutut di hadapan Prabu Thong Thong Sot. Kresna, Setyaki dan Gatotkaca lari dari pertempuran menyelamatkan diri. Para dewa dari Kahyangan Jonggring Saloka juda tidak berdaya untuk membantu para pandawa dan mengalahkan Prabu Thong Thong Sot.
Tatanan pun menjadi porak poranda dan terbolak-balik.
Tatanan pun menjadi porak poranda dan terbolak-balik. Kerajaan Amarta menjadi kerajaan terjajah, para ksatrianya telah diubah menjadi pembantu dan pelayan raja dari Kerajaan Loji Tengara tersebut. Dalam situasi kacau tak menentu tersebut, Kresna kemudian mendatangi Semar di Padepokan Karang Kadempel mengadukan masalah krusial yang sedang menimpa kerajaan.
Semar pun kemudian menyelidiki keadaan dan segera mengajak Gareng dan Bagong untuk bersama-sama menuju Amarta yang sedang dikuasai oleh Prabu Thong Thong Sot untuk menghadapinya. Demi melihat para punokawan datang, ribut dan sendagurau ala Bagong dan Gareng, sontak Prabu Thong Thong Sot terharu-sadar dan segera berubah wujud menjadi Petruk ! Situasi pun segera berubah drastis, dan tatanan pun kembali kepada keseimbangannya.
Kaitan dengan Lakon Mustokoweni
Benarkah yang menjadi Prabu Thong Thong Sot yang sakti tak tertandingi itu adalah Petruk? Dan kalau benar itu adalah Petruk, kenapa dia bisa begitu sakti dan “lupa diri” sedemikian rupa? Para penikmat dan pemerhati wayang pasti tahu, bahwa lakon Petruk Dadi Ratu itu terkait erat tak terpisahkan dari lakon sebelumnya yaitu Mustokoweni. Dan seringkali para dalang menggabungkan dua lakon itu dalam satu sanggit.
Dikisahkan, pada suatu saat para Pandawa 5 bersaudara sedang sibuk membangun candi di pertapaan Saptarengga, tempat para leluhurnya dimakamkan. Tidak lupa, Pandawa juga mengundang saudara sekutu mereka para ksatria Mandura dan Dworowati, Kresna dan Baladewa untuk ikut membantu mereka.
Di tengah kesibukan mereka itu, terjadi sesuatu di istana Amarta. Sesosok mirip Gatutkaca mendatangi keputren Cintakapuri, tempat Drupadi istri Yudhistira berdiam. Dia mengaku diutus Pandawa mengambilkan Pusaka Jamus Kalimasdha untuk keperluan pembangunan candi. Tanpa curiga, Drupadi memberikan Pusaka Jamus Kalimasadha kepada sosok mirip Gatutkaca itu, yang segera membawa Pusaka Jamus kabur keluar istana.
Srikandhi yang baru datang kaget dan curiga melihat hal ini. Ia segera mengejar Gatutkaca tersebut, dan terjadilah perkelahian seru keduanya. Srikandhi gagal merebut pusaka tersebut, tetapi berhasil memaksa membongkar identitas palsu Gatutkaca, yang ternyata adalah samaran dari Dewi Mustokoweni atau Mustokowati, puteri dari Kerajaan Ngimaimantaka, adik dari Prabu Bumiloka.
Srikandhi bergegas menuju pertapaan Saptarengga untuk memberitahu situasi gawat ini kepada para Pandawa, karena tanpa Jamus Kalimasadha maka dipastikan kekuatan Pandawa akan rapuh dan dengan mudah akan dihancurkan oleh musuh mereka para Kurawa.
Berita ini tentu saja mengagetkan para Pandawa dan semua tamu yang hadir, yang waktu itu sedang melakukan doa dan puja mantra Pengiriman untuk leluhur mereka. Situasi pun menjadi kacau. Pada saat itulah datang seorang pemuda bernama Bambang Priambada, yang mengaku diutus ibunya Endang Rara Wilis untuk mencari bapaknya, yaitu Raden Janoko (Arjuna).
Kedatangan pemuda ini disambut hangat oleh para Pandawa, terutama Arjuna yang segera memeluknya.
Kedatangan pemuda ini disambut hangat oleh para Pandawa, terutama Arjuna yang segera memeluknya. Arjuna pun segera menguji kesetiaan dan kesaktian anaknya dengan mengutusnya untuk pergi ke Kerajaan Ngimaimantaka merebut kembali Pusaka Jamus Kalimasadha. Singkat cerita, maka terjadilah pertarungan sengit di atas awan antara Bambang Priambada dengan Mustokoweni, mereka saling menipu dan memalsukan diri.
Singkat cerita, Priambada akhirnya berhasil merebut Jamus Kalimasadha dan Mustokoweni terjatuh tak berdaya dari ketinggian awan, tubuhnya meluncur ke bawah dengan pakaian terkoyak. Terdorong oleh rasa kasihan dan menjaga kesopanan, Priambada menolong Mustokoweni dengan menangkap tubuhnya, dan di akhir cerita, keduanya justru saling mencintai dan akhirnya menikah.. Tanpa disadari, pada saat-saat tersebut Pusaka Jamus Kalimasadha pun terlepas dari genggaman Priambada …
Pada titik inilah kemudian lakon berlanjut kepada lakon “Petruk Dadi Ratu”. Dalam satu versi, pada saat terlepas dari genggaman Priambada, Sanghyang Wenang mengambil Pusaka Jamus Kalimasadha tersebut dan menyerahkannya kepada Petruk. Pada saat itulah, muncul kemudian Kerajaan Tiban Lojitengara dengan rajanya yang koplak Prabu Thong Thong Sot. Dan tampaknya versi ini yang ditampilkan Ki Enthus waktu di Demak.
Versi lain Jamus Kalimasadha tidak terlepas, tetapi oleh Priambada dititipkan kepada Petruk yang ikut membantu dia di dalam pertempurannya dengan Mustokoweni. Oleh Petruk pusaka ini kemudian disimpan di dalam iket kepalanya, dan serta merta terjadi perubahan di dalam kesadaran dan pribadi Petruk yang segera berubah menjadi Prabu Thong Thong Sot.
Paradigma dan Kunci-kunci Simbolis Memaknai Lakon Wayang
Sebelum memaknai kisah dan menguak simbol-simbol yang ada di dalam lakon di atas, kita perlu terlebih dahulu untuk memahami paradigma yang ada di balik pagelaran lakon wayang kulit agar pemahaman kita lebih utuh. Pagelaran wayang kulit diciptakan oleh para walisongo untuk tujuan tontonan sekaligus tuntunan bagaimana menjalani hidup di dalam suatu tatanan, baik tatanan sosial maupun tatanan di dalam diri (mikrokosmos) dalam hubungannya dengan alam semesta (makrokosmos). Tuntunan ini merupakan rambu-rambu perjalanan diri di dalam menggapai kesempurnaan, yang berguna untuk semua kalangan. Di dalam agregat perjalanan masing-masing individu dalam menggapai kesempurnaan inilah secara serentak kemakmuran wilayah dan lingkungannya akan ikut meningkat.
Bubukane dennya nedhak, nukil Srat Kalimasada, pan katedhak ing dalancang, dados ringgit beber nama. Kalampahan jaman purwa, kang dados kalangenannya, ingkang amengku nagara, ila-ilane punika. Anggemahaken ing desa, barekat mupakat barkat, ing ratu tumrah sapraja.
(Pada mulanya lakon wayang ini dinukil dari Serat Kalimasada, yang dipindah di atas kertas, sehingga menjadi pertunjukan wayang beber, namanya. Lakonnya diolah dari cerita di zaman purwa, menjadi hiburan para pemangku negara, untuk memakmurkan desa, menjadi penuh berkah dan mufakat dari sang raja dan seluruh rakyat negeri).
~~~
Dari wayang beber yang sederhana kemudian dikembangkan menjadi wayang kulit dengan perangkat yang lebih kompleks untuk menunjang tata pertunjukannya sekaligus melengkapi simbol-pralambang sebagai penguat makna yang dihadirkannya. Mari kita baca bait yang cukup panjang terjemahan dari tembang Megatruh di dalam Serat Centini di bawah ini[1]:
[…]
2. Dengan pelahan Kidang Wiracapa berkata, Adikku Kulawirya, mengenai pengertian yang sempurna, arti mendalam dalam pertunjukan wayang, dan kenyataan dalam batin,
3. (maklumlah) oleh manusia sempurna itu dijadikan sasmita (lambang) yang menunjuk kepada Tuhan. Dalang dan wayang diberinya tempat (arti) yang sejati, yaitu sebagai cara menggambarkan bagaimana Tuhan itu bertindak. Orang bijak membuat perumpamaan sbb.
4. Kelir itu jagad yang kelihatan, wayang-wayang yang ditancapkan di kiri dan kanan menggambarkan golongan makhluk-makhluk Tuhan. Batang pisang ialah bumi. Blencong adalah lampu kehidupan. Gamelan ialah keserasian antara peristiwa-peristiwa.
Kelir itu jagad yang kelihatan, wayang-wayang yang ditancapkan di kiri dan kanan menggambarkan golongan makhluk-makhluk Tuhan.
5. Makhluk-makhluk Tuhan bertumbuh, tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka semua menghalangi pemandangan. Manusia yang tidak menerima bimbingan tidak melihat Tuhan sesungguhnya, tetapi terkandas dalam rupa dan warna.
6. Pandangannya kabur dan tidak menentu, lenyap dalam ketiadaan, karena ia tidak melihat kenyataan. Ia tersesat di dalam jalan penuh kesukaran, ia tidak tahu kesempurnaan dalam pengertian, arti sejati mengenai apa yang ditonton.
7. Keindahan tulisan ini (yaitu alam semesta yang tercipta) menimbulkan rasa rindu. Itulah tulisan hati, ungkapan dahsyat kehendak yang tidak berbeda dengan Dia sendiri. Manusia itu entah pergi ke Selatan atau ke Timur, entah ke Utara atau ke Barat,
8. entah ke atas atau ke bawah, Tuhan tidak dijumpainya. Bila Anda ingin menyelami kenyataan dengan cara yang tepat, selamilah lambangnya, yaitu dalam nama-nama Hyang Widhi, dalam ungkapan kehendakNya yang tidak mengenal rintangan,
9. yang tidak menyimpang (tidak berbeda dengan) dari Dzat Yang Mahaluhur yang berkuasa menciptakan dan meraja, pemerintahanNya lestari. Dialah Tunggal tidak tercampur sesuatu yang lain. Kesucian Tuhan yang melihat segalanya.
10. sempurna, tak berubah. Ia hidup dalam kemuliaan kehendakNya, kehendak itu tidak mempunyai hati (sebagai organnya). Terbakar oleh rasa rindu dalang mulia membuat gagasan, Ia ingin dilihat.
11. RahasiaNya diungkapkanNya lewat lambang-lambang. Rupanya Ia lalu terbagi, tetapi di luar Dia tidak ada sesuatu. Lambang yang mulia itu menunjukkan tersembuyinya hakikat Ketuhanan sejati, utuh dalam kemurniannya yang tak tercampur.
12. Ia disebut Kunhi Dzat, namanya la ta’ayyun (tidak terinci), berasal pada dirinya sendiri …
[…]
18. Inilah, adikku, suatu ungkapan simbolis mengenai ilmu tertinggi, pewartaan mengenai kebijaksanaan yang diselami hingga hakikat yang sejati. Bila mendengar perumpamaan mengenai dalang dan wayang supaya jangan salah paham mengenai apa yang kau tonton.
19. Arti ajaran luhur ini, adikku, ialah begini. Yang Mahasuci adalah dalang yang luhur. Ia menciptakan kita semua. Sebelum kita dilahirkan dari kandungan ibu kita,
20. Ia telah menentukan segalanya sehingga tak dapat diubah, kebahagiaan dan kecelakaan, hidup panjang atau pun pendek, kegagalan maupun keberhasilan, itu semua sudah dibagikan pada saat kita masih terdapat sendirian dalam rumah
21. tersembunyi, diliputi oleh selubung dan tidak kelihatan. Pada saat benih keluar, ceritanya sudah tamat. Tidak berlebihan, tidak berkekurangan, berkat kebijaksanaan Dia Yang melihat segalanya.
22. Yang Maha Luhur itu ialah dalang yang mulia. Penampilan lahiriah, pembagian menurut golongan-golongan makhluk-makhluk materiel serta penampilan segala sesuatu yang ada, itulah wayang-wayang di kelir. Sang dalanglah yang menguasai lakonnya.
23. Dalang sejati juga sama dengan sang raja yang menguasai perbuatan semua makhluk yang hidup. Oleh Yang Agung diberi pewahyuan (harfiah: tanda, petunjuk) mengenai takdir, alam dan tabiat manusia.
24. Raja itu berfungsi sebagai selubung bagi Yang Agung. Ia mengikuti takdirNya yang tertulis di “lokil makpul” Ia sendiri tidak berkuasa terhadap takdir, ia hanya menyetujui lakonnya.
25. Kata-kata yang mengiringi lakon itu boleh diucapkannya sendiri. Tetapi raja tidak dapat mengubah nasib kawulanya, apakah direndahkan atau ditinggikan, disiksa atau dilimpahi anugerah,
26. Itu semua sudah ditakdirkan oleh Hyang Widi serta digerakkan. Sebelum digerakkan di kelir, sudah disusun menjadi sebuah lakon.
27. Apakah sang raja memberi ganjaran atau siksa, apakah ia menolak seorang atau memilihnya, melimpahkan anugerah atau membuangnya, menyelesaikan dengan cepat atau menunda, itu semua kehendak Dia yang Mahatahu.
28. Kehendak Tuhan tersembunyi di dalam hati sang raja. Dialah yang melaksanakan kehendak itu dan dengan demikian manunggal dengan Tuhan karena perbuatannya. Dengan mengawasi rakyatnya pandangan raja mencakup segala sesuatu sehingga itu nampak baginya dengan bantuan Yang Mahatahu.
29. Raja memeriksa rakyatnya seperti seorang dalang memeriksa wayang-wayangnya. Tak ada sesuatu yang terselubung atau tersembunyi. Perbuatan baik dan buruk setiap orang, besar ataupun kecil, itu semua dilihatnya.
30. Dengan demikian si dalang sungguh merupakan (gambaran sejati) sang raja. Raja itu wakil Sang Nabi, sang Nabi Yang Maha Agung. Bila kita memandang raja atau Nabi, kita seolah-olah memandang Yang Maha Agung.
31. Begitulah, adikku Kulawirya, arti mendalam mengenai ilmu tentang aspek lahiriah dalam agama hukum yang disampaikan oleh Sang Nabi. Mengenai ikhtisar aspek batin,
32. itu terdapat bila kita memandang diri kita sendiri. Dalang dan wayang, gamelan, kotak (untuk menyimpan wayang-wayang), batang pisang, kelir dan lampu
33. menjadi satu dalam satu wujud. Si Dalang adalah kehidupan sendiri, kehidupan halus. Yang dimaksudkan dengan kehidupan ialah budi; adapun budi itu ialah yang dimaksudkan dengan dalang yang mahatahu.
Si Dalang adalah kehidupan sendiri, kehidupan halus.
34. Perbuatan, gerak-gerik dan ucapan badan itulah arti sejati wayang-wayang. Badan mengalami peristiwa-peristiwa yang sudah ditentukan (lakon).
35. Sungguh menakjubkan, Yang Maha Agung menentukan saat rasa memasuki (badan). Rasa itu sebetulnya roh kudus, yang menyinari kehidupan wayang-wayang, lagu dan dialog dalam lakon.
36. Masuknya suksma ke dalam badan ialah masuknya dalang dalam wayang-wayang. Raga dan jiwa demikian manunggal, sehingga tidak lagi dapat dibedakan kedua unsurnya.
37. Pikiran hati diambil alih dan dituturkan oleh mulut, raganya yang berbicara, dengan kata-kata keras atau tenang. Bicaranya budi tak dapat didengar, hanya ragalah yang merasakannya.
38. Demikianlah kita, makhluk-makhluk dikuasai oleh budi, oleh kehidupan sendiri. Segala sesuatu yang kita alami ialah lakon pertunjukan wayang. Kita sendirilah tontonannya.
39. Penonton menjadi saksi mengenai segala sesuatu yang hidup. Baik buruknya badan bagi penonton yang melihat dengan seksama dan jauh sekitarnya bagaimana hidup itu menampilkan diri, hanya berwujud mengalami secara pasif skema peristiwa yang sudah pasti (lalakon).
40. Penonton tidak melihat sang dalang, hanya wayang-wayang yang bergerak dan berbicara. Rupanya merekalah yang berbicara, tetapi orang tidak melihat sang dalang yang menggerakkan wayang-wayang.
41. Demikianlah pandangan yang sempurna dan mendalam (mengenai wayang).
[…]
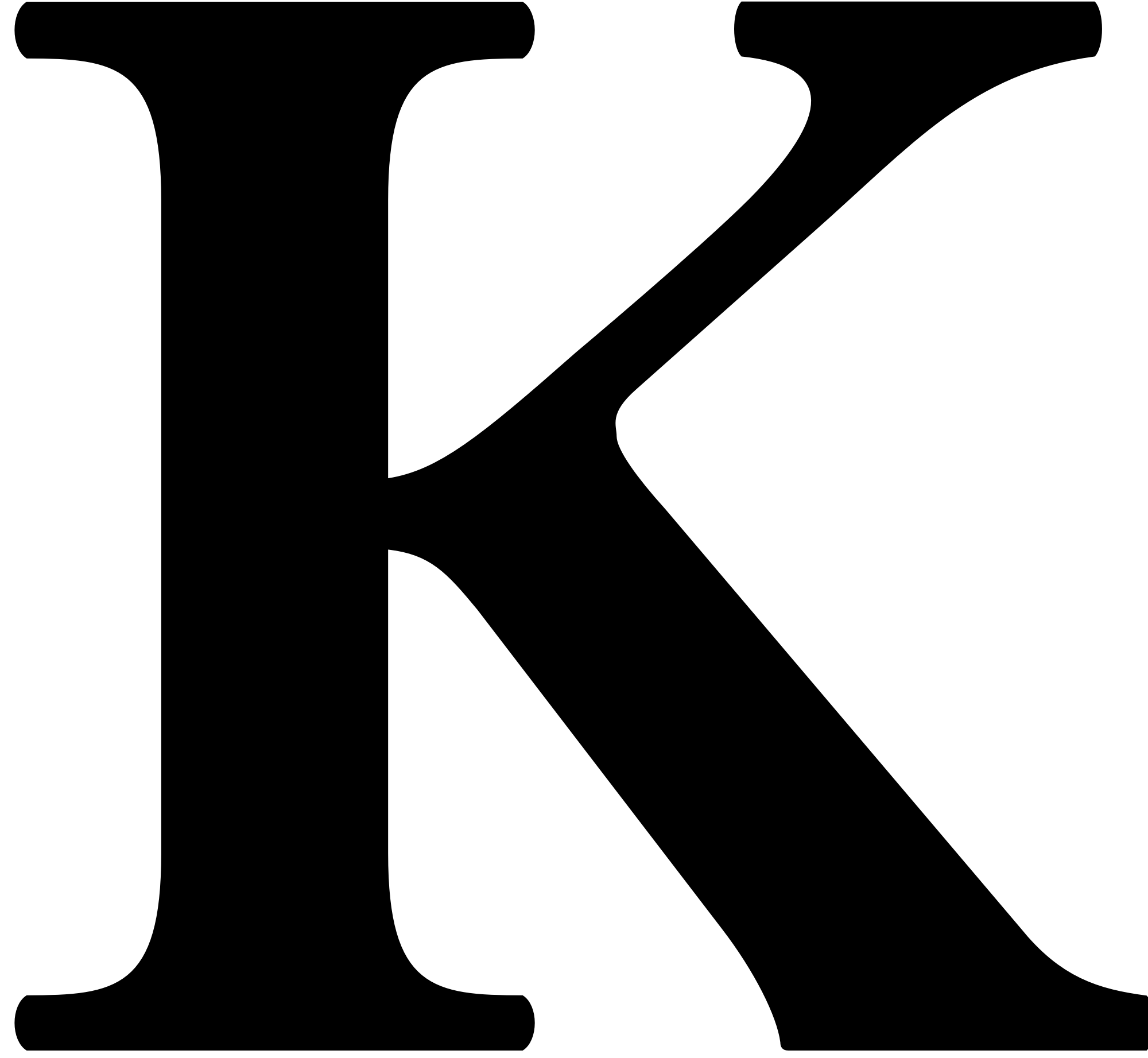 utipan puisi yang cukup panjang di atas dengan jelas menunjukkan kepada kita bagaimana menikmati dan memahami pagelaran wayang secara bijak. Keseluruhan dari unsur pagelaran wayang adalah pralambang untuk mengenali Tuhan dan menggambarkan bagaimana hubungan antara Tuhan, manusia dan alam semesta terjadi dan berlangsung secara dinamis.
utipan puisi yang cukup panjang di atas dengan jelas menunjukkan kepada kita bagaimana menikmati dan memahami pagelaran wayang secara bijak. Keseluruhan dari unsur pagelaran wayang adalah pralambang untuk mengenali Tuhan dan menggambarkan bagaimana hubungan antara Tuhan, manusia dan alam semesta terjadi dan berlangsung secara dinamis.
Dengan keindahannya yang memukau, penonton dirangsang kerinduannya untuk bergerak mengenali dan mendekati Tuhan. Dijelaskan juga di atas adanya 2 (dua) jalan untuk mengenali Tuhan, yaitu secara lahiriah (syari’at), ketika yang kita lihat adalah sisi depan kelir, yaitu rincian gambaran yang terpisah-pisah antara dalang, wayang, kelir, debog, blencong dan gamelan.
Kemudian secara batiniah (hakikat), ketika kita melihatnya dari sisi belakang kelir, sehingga yang terlihat hanyalah bayang-bayang dan semuanya menyatu di dalam satu kesatuan. Bayang-bayang yang tampak di dalam kelir itu hakekatnya adalah bayang-bayang kita sendiri. Di sini penulis ingin menambahkan bahwa bayang-bayang tersebut adalah gambaran unsur-unsur diri kita.
Adanya 2 (dua) jalan untuk mengenali Tuhan, yaitu secara lahiriah (syari’at), ketika yang kita lihat adalah sisi depan kelir. Kemudian secara batiniah (hakikat), ketika kita melihatnya dari sisi belakang kelir.
Pada setiap pembukaan pagelaran wayang, jejer I sang dalang di dalam janturannya menyebutkan “ka eka adi dasa purwa” yang berarti kesatuan mulia dari mula sepuluh. Sepuluh adalah angka dasar, dan untuk menjadi 100 atau 1000 mesti didasari 10. Dengan kesatuan dari 10 inilah akan memunculkan negeri yang gemah ripah loh jinawi. Ungkapan ini merupakan kode dari penonton untuk mencari dan mengamati hubungan-hubungan unsur yang 10 itu.
Mari kita cari dan kenali. Sepuluh tokoh utama wayang menggambarkan 10 (sepuluh) unsur/organ utama di dalam diri. Sebagaimana 10 tokoh ini merupakan pelaku utama di dalam pagelaran wayang, maka 10 unsur diri ini pula yang menentukan kepribadian kita. Pandawa lima adalah bayangan/simbol dari panca indera, organ luar tubuh kita.
(1) Yudistira adalah Pernafasan. (2) Bima adalah pendengaran, (3) Arjunaadalah Penglihatan, (4) Nakula adalah Lidah, dan (5) Sadewa adalah Kulit. Sementara 4 (empat) tokoh lainnya melambangkan unsur/organ dalam tubuh yang tak terlihat: (6) Karna adalah Keseimbangan, (7)Sembadra adalah Perasaan, (8) Kresna adalah Pikiran dan (9) Baladewa adalah Batin kita. Dalang, yang tidak terlihat di dalam kelir, adalah Ruh (0) yang hadir sebagai unsur kesepuluh, menggerakkan diri kita untuk mengarungi jagat kehidupan.
Apakah kita selama ini menyadari kehadiran dan gerak-gerik 10 tokoh itu di dalam diri kita? Bagaimana mereka saling menunjang harmonis atau saling mengabaikan, bertentangan dan konflik? Kesatuan harmonis di antara mereka tentu akan membuahkan perilaku kita yang mengarah kepada kebenaran, dan sebaliknya pertentangan di antara mereka cenderung akan menghasilkan tindakan kita yang mengarah kepada kesalahan/kesesatan, yaitu kepada kemenangan para kurawa yang merupakan simbol dari kecenderungan jahat di dalam diri kita yang berjumlah 100 ini.
Bagaimana mereka saling menunjang harmonis atau saling mengabaikan, bertentangan dan konflik?
Melalui Pagelaran Wayang, para wali memberikan kepada kita kunci-kunci untuk mengharmoniskan kesatuan unsur-unsur utama diri, dan bagaimana memenangkan pertarungan terhadap para kurawa. Dalam hal ini, Jamus Kalimasada adalah pusaka utama Pandawa, yang mesti melekat pada Yudistira, yang membuat mereka tak terkalahkan.
Jamus Kalimasada adalah simbol dzikir, eling atau ingat kepada keagungan Tuhan, sementara Yudistira adalah Pernafasan kita. Hal ini mengandung ajaran bahwa kunci utama kesatuan unsur di dalam diri kita adalah apabila dalam setiap tarikan nafas kita mesti dibarengi upaya dzikir atau ingat kepada Tuhan, sebagai ungkapan syukur yang melekat dalam diri.
Jamus Kalimasada adalah simbol dzikir, eling atau ingat kepada keagungan Tuhan, sementara Yudistira adalah Pernafasan kita.
Dzikir atau ingat kepada Tuhan bukanlah ucapan Lidah, tetapi mesti menggema di dalam Batin. Oleh karena itu, di dalam wayang, batin kita yang dilambangkan oleh tokoh Baladewa, ia berkulit putih, dan selama berlangsungnya Bharatayudha dia mesti diikat di dalam goa “Gerojogan Sewu” (seribu air tejun). Sebuah ajaran kunci, bahwa untuk mengalahkan angkara murka yang berjumlah 100 itu, batin kita mesti putih/suci oleh guyuran “air terjun dzikir” yang kekuatannya 1000 atau 10 kali lipatnya.
Kesatuan harmonis antara Yudistira dan Baladewa (1 + 9 = 10), atau Pernafasan dengan Batin di dalam diri kita ini pada gilirannya akan menerangi dan mendorong unsur-unsur lain di dalam diri supaya menyatu harmonis. Karna atau Keseimbangan kita akan bekerja keras untuk menyatukan hubungan-hubungan kompleks antara Penglihatan, Pendengaran, Perasaan, dan Pikiran. Buah dari keseimbangan itu semua adalah keputusan-keputusan yang mengarahkan kepada ucapan dan tindakan diri kita yang seimbang dan berorientasi kebenaran.
Buah dari keseimbangan itu semua adalah keputusan-keputusan yang mengarahkan kepada ucapan dan tindakan diri kita yang seimbang dan berorientasi kebenaran.
Setelah mengenali 10 tokoh utama wayang yang merupakan pralambang dari 10 unsur diri itu, maka kita perlu mengenali pula terhadap para punokawan. Mereka adalah Semar, Petruk,Gareng dan Bagong. Seperti dapat kita pahami dari sebutan dan peran mereka sebagai punakawan (panakawan) di dalam pagelaran wayang, maka mereka adalah pamomong, teman sekaligus pembimbing, yang setia mendampingi dan mengarahkan kepada kebenaran dan kemenangan.
Berbeda dengan Togog yang mendampingi para ksatria jahat, maka punokawan (Semar dan anak-anaknya) ini diceritakan selalu mendampingi para ksatria yang baik, yang selalu melakukan tapabrata dan berjuang menegakkan kebenaran. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa inilah pralambang yang menggambarkan perwujudan dari janji Tuhan di dalam al-Qur’an: wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana (barang siapa bersungguh-sungguh di dalam mencari(kebenaran)Ku, maka aku sungguh akan membimbing mereka kepada jalan-jalan yang mendekatkan kepada-Ku).
Dalam konteks pagelaran wayang, hal ini mengandung makna bahwa orang yang berusaha menyatukan 10 unsur dirinya secara benar dalam kesatuan yang harmonis, maka akan datang punokawan sebagai pembimbing untuk tetap konsisten di dalam jalan menuju Tuhan.
Makna dan Signifikansi Lakon Petruk Dadi Ratu
Demikianlah, kalau kita akan menghayati lakon wayang “Petruk Jadi Ratu” kita mesti mulainya dari lakon “Mustokoweni” lebih dahulu. Dengan mengenali jalinan tokoh-tokoh dalam keutuhan ceritanya, dan mengurai pralambang-pralambangnya, maka kita akan menemukan akar permasalahan di dalam lakon ini.
Lakon adalah peristiwa yang kita alami. Demikianlah, pandawa lima menggambarkan panca indera kita yang terdiri dari Yudistira sebagai pernafasan kita, Bima pendengaran, Arjuna penglihatan, Nakula indera perasa dan Sadewa kulit kita. Ditambah dengan Kresna dan Baladewa maka tergambar pula unsur-unsur penting lain dari diri kita, yaitu pikiran dan batin atau semangat kita.
Dikisahkan dalam lakon Mustokoweni (hilangnya Jamus Kalimasadha)mereka semua sedang sibuk membangun candi di dalam kompleks makam leluhur. Candi adalah dimensi materialistik dari tujuan atau target hidup, sedangkan leluhur adalah pralambang dari kewibawaan kita.
Dikisahkan dalam lakon Mustokoweni (hilangnya Jamus Kalimasadha) mereka semua sedang sibuk membangun candi di dalam kompleks makam leluhur.
Maka (jangan-jangan) ini adalah kisah kita semua, yang sedang total sibuk meningkatkan kewibawaan dengan capaian-capaian yang terukur secara materialistik: seperti jabatan, pangkat, kedudukan, fasilitas-fasilitas yang mewah, kekayaan, kecantikan, ketampanan dan seterusnya.
Maka dalam situasi seperti itu, orientasi hidup kita dapat menjelma menjadi nafsu-ambisi kekuasaan dan kemegahan duniawi (dilambangkan Mustokoweni) yang dengan licik mengkamuflase diri kita (menyamar Gatutkaca) untuk mengalihkan secara paksa (mencuri) tujuan dan orientasi keikhlasan dan pengabdian ketuhanan kita (Pusaka Jamus Kalimasadha).
Untungnya ketajaman rasa kita (Srikandhi) mencium gelagat ketidakberesan ini, mencari tahu sumber masalahnya dan segera menggugah diri kita untuk segera sadar. Namun ambisi untuk menggapai kemegahan duniawi masih jauh lebih kuat pengaruhnya.
Bambang Priyambodo kemudian datang dan maju untuk ke medan laga.
Bambang Priyambodo kemudian datang dan maju untuk ke medan laga. Bambang Priambodo, adalah anak dari Arjuna dan Supraba, pralambang dari mata dan cahayanya. Ini artinya menjadi buah dari kesatuan pengamatan inderawi yang tajam dan cemerlangnya cahaya hati kita. Ini yang perlu kita upayakan (Priambodo), untuk memenangkan pertarungan melawan nafsu-kekuasaan-kemegahan duniawi kita. Nafsu memang tidak bisa dihilangkan, oleh karena itu setelah ditundukkan, ia mesti dikendalikan untuk diberi arahan positif ( makna kawin), agar kelanjutan hidup kita nanti bisa lebih bermanfaat dan realistis.
Namun demikian, resiko masih ada dan kelengahan diri masih terus mengintai. Dinamika di dalam menata hidup sehari-hari sedemikian tinggi dan keras. Saling pengaruh antara keteguhan dan konsistensi diri dengan tekanan faktor-faktor dari luar begitu dinamis. Dalam dinamika yang tinggi itu, diri kita sering lengah. Jamus Kalimasadha (orientasi ketuhanan) justeru tidak kita lekatkan pada Yudistira (setiap tarikan nafas) untuk mengikat batin kita (Baladewa) bertapa menjernihkan diri dalam ingatan yang tak putus (grojogan sewu), namun malah terlepas, terlupakan.
Kelengahan diri ini ternyata bisa berakibat fatal. Terjadilah lakon Petruk Dadi Ratu, disorientasi dan kelengahan diri secara cepat-tak terduga bisa menimbulkan gejala lupa diri dan ketenggelaman diri dalam realitas palsu (hiperrealitas). Dalam realitas politik hal ini bisa berupa keterjebakan dalam proxy war.
Muncullah di sini Prabu Whelgeduelbeh atau Prabu Thong Thong Sot: sikap semau gue, menang-menangan, inkonsisten, penuh kontradiksi sekaligus nonsense, kosong nilai-nilai.
Muncullah di sini Prabu Whelgeduelbeh atau Prabu Thong Thong Sot: sikap semau gue, menang-menangan, inkonsisten, penuh kontradiksi sekaligus nonsense, kosong nilai-nilai. Hal ini karena ketiadaan Jamus Kalimasadha (lupa Tuhan) telah mengakibatkan disintegritas diri yang parah. Daya ilahiyah yang menjaga kebenaran/keksatriaan laku kita (Punokawan) pun menjauh dan terpecah: Semar, Gareng dan Bagong kembali ke Karang Kadempel.
Sementara Petruk terpisah sendiri dari saudara-saudara dan bapaknya, tidak kuat mengemban pusaka Jamus Kalimasadha, sehingga energinya berbalik menjadi negatif dan destruktif. Prabu Thong Thong Sot menjadi sakti mandraguna tak terkalahkan melawan para ksatria pilih tanding seperti Adipati Karna, Arjuna, Bima, Kresna dan Baladewa adalah ungkapan ‘halus’ untuk gejala kebal dan abai terhadap fakta, nasehat, pertimbangan akal dan semangat introspeksi. Bahkan lebih dari itu, semua ksatria itu justru ditaklukkan dan diperbudak olehnya.
Kresna dan Gatotkaca bisa melepaskan diri dari situasi keterjajahan oleh Prabu Thong Thong Sot, dan lari untuk menemui Semar dan anak-anaknya.
Untungnya, ada solusi di dalam lakon ini. Kresna dan Gatotkaca bisa melepaskan diri dari situasi keterjajahan oleh Prabu Thong Thong Sot, dan lari untuk menemui Semar dan anak-anaknya. Kresna adalah pralambang dari kecerdasan dan kebijakan pikiran (intelektualitas) dan Gatotkaca (anaknya Bima, pendengaran) adalah pralambang jauhnya jangkauan untuk mengakses sumber informasi.
Kesatuan antara intelektualitas dan validitas data, dapat mengarahkan kita pada kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, Semar adalah pralambang penjaga keseimbangan dan kebijaksanaan dalam perkataan dan tindakan, Gareng adalah pralambang dari penjaga semangat instropeksi untuk melihat kekurangan diri dan Bagong adalah pralambang kemanunggalan perilaku dengan norma dan kehendak Tuhan.
Demikianlah, kesatuan antara para ksatria dan punokawan inilah yang pada akhirnya bisa mengalahkan Prabu Thong Thong Sot, melalui gabungan antara ketepatan di dalam mendefinisikan situasi, merumuskan urutan langkah dan kebijaksanaan di dalam implementasinya serta tidak meninggalkan pendekatan yang manusiawi. Prabu Thong Thong Sot pun lenyap, dan muncullah Petruk kembali bersatu dengan para saudara dan bapaknya. Tatanan pun kembali pulih, keseimbangan antara yang mikrokosmos dan makrokosmos kembali terjalin harmonis, semuanya berorientasi kepada pengabdian kepada Tuhan.
Tanceb Kayon
Akhirnya perlu penulis tegaskan, bahwa semangat utama dalam menikmati pagelaran wayang kulit adalah perjalanan ke dalam diri. Melalui upaya mengenali dan menghidupkan unsur-unsur diri sendiri, menjalin dan mengharmoniskan hubungan antar unsur-unsur tersebut sebagai satu kesatuan sehingga terbangun integritas diri di dalam menapak jalan kerinduan kepada Kesejatian yang penuh Kasih dan Keagungan. Bayang-bayang di dalam kelir itu tidak menunjuk kepada orang lain di luar sana, melainkan ke dalam diri di sini.
Salam,
Piyungan, 24 April 2019
[1] Banyak versi dan sanggit atas lakon ini. Untuk deskripsi kerangka ini penulis mengutip dan mengolah sebagian dari reportase Berita Tembi teradap pagelaran wayang kulit lakon tersebut oleh dalang Ki Cermo Sutejo yang ditulis oleh Herjaka HS (www.tembi.net/2017/19/5/), menggabungkannya dengan sebagian dari balungan lakon oleh dalang Jlitheng Suparman (akun facebook: Jlitheng Suparman) dan ingatan penulis terhadap pagelaran lakon tersebut oleh Ki Enthus Susmono di Demak serta sumber-sumber lain.
[2] Centini V, 349-367 dikutip dari P.J. Zoetmulder, Manunggaling Kawulo Gusti, Jakarta, Gramedia, tahun 2000, hal: 290 – 294








