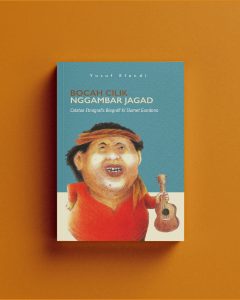Ketika saya kecil memulai mengaji di langgar, nenek cerita bahwa dulu cara ngajinya berbeda meski kitabnya sama: Turutan. Nenek saya rajin jamaah di langgar sebagaimana warga kampung lain yang sepuh-sepuh sehingga tahu proses mengaji anak-anak.
“Biyen ora alip ba’ ta’ sa’, tapi alip be te se, Cung” cerita nenek. “Terus, ora alip patkah a, alip kasrah i, alip dommah u, a i u, tapi alip jabar a, alip jer i, alip pes u, a i u,” tambah nenek.
Tentu saja waktu itu saya tidak menanggapinya lebih jauh, selain merasa “kok berbeda ya”. Lalu saya anggap cara ngaji nenek sudah kuno. Fathah, kasrah, dan dlammah lebih tepat daripada jabar, jer, pes. Alif, ba’ ta’ lebih tepat daripada alip, be, te, se. Saya pikir ini wajar, karena guru ngaji dengan sendirinya akan dianggap lebih otoritatif bagi anak-anak soal bagaimana ngaji ketimbang orang tuanya yang bukan guru ngaji. Apalagi sebelumnya ibu dan bapak saya sendiri yang sudah mengajari alif ba’ ta’ alif fathah a, dan seterusnya itu sebelum saya ikut mengaji di langgar.
Beranjak dewasa ketika semakin banyak membaca, baru saya mulai paham bahwa cerita nenek bisa jadi petunjuk akan pengaruh Islam gaya Persia begitu kuat di Jawa. Ditambah cerita tentang masuknya Islam lewat jalur Persia yang sangat kental dengan sufisme menemukan titik terangnya. Meski tentu saja Persia bukan satu-satunya jalur.
Dalam kitab Centhini atau Suluk Tambangraras yang berisi tentang perjalanan spiritual seorang salik dengan tokoh utama Syekh Amongraga, ada sepenggal kisah soal bagaimana santri mengeja Al Qur’an atau huruf Arab dengan jabar, jer, pes itu. Mari kita simak kutipan Serat Centhini Jilid 6 dari Agus Wahyudi halaman 170:
“Lam jabar la, kap pes mim kum, dal jer ya dii, nun pes nu, kaf pes mim kum. Lakum diinukum. Wawu jabar wa, lam jer li, ya’ jabar ya, dal jer ya’ nun diin. Waliyadiin.”
Tentu saja aslinya di Persia disebut “zabar”, hanya karena orang Jawa tidak mengenal aksara “za” jadinya “ja”. Sebagaimana huruf-huruf lain yang tidak ada dalam lisan Jawa lain seperti “fa” “tsa” “kha” “dza”, dan sebagainya., yang kalaupun diadakan harus memberi tanda khusus dalam aksara Jawa yang dikenal dengan istilah “Rekanan”.
Menariknya adalah, di kampung saya, rupanya model eja jabar jer pes itu masih bertahan sampai era nenek yang lahir era penjajahan Jepang (1940an), meski ibu saya yang lahir awal Orde Baru sudah tidak mengenalnya.
Saya tidak tahu sekarang apakah cara eja zabar jer pes yang masih digunakan di lingkup Persia-Khurasan itu apakah masih bertahan di kampung lain di Jawa atau tidak. Sebagaimana saya juga belum tahu apakah peralihan jabar, jer, pes menandai pergeseran corak keberislaman yang semakin fiqhi, dengan jalur lain yang bukan Persia, tapi langsung ke Hijaz atau Kairo via jalur Yaman.
Turutan: Hijai dan Abjadi
Awal mengaji, saya dibelikan kitab Turutan dengan sampul warna kuning bergambar masjid. Saya lupa apakah itu terbitan Toha Putra Semarang atau Menara Kudus. Yang pasti itulah kitab pertama yang saya punya. Dan saya yakin, Turutan pernah jadi kitab paling populer di tanah Jawa setelah Alquran itu sendiri. Namun, kepopuleran Turutan itu memendam misteri. Ketika mulai lancar membaca huruf Arab dan kenal nama-nama kitab kuning, saya baru tahu kalau nama kitab Turutan itu “Qaidah Baghdadiyah”. Setidaknya, itu yang tertulis di sampul kitab. Misterinya adalah sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang menyusun kitab itu. Saya hanya bisa menduga bahwa dari namanya pasti berkaitan dengan Baghdad, pusat kekhalifahan Abbasiyah. Menariknya, istilah “Baghdad” itu sendiri berasal dari bahasa Persia kuno yang berarti “anugerah Tuhan”. Persis orang India menyebut Tuhannya dengan istilah “Baghvan” (Sanskrit: भगवान, Urdu: بھگوان).
Era Abbasiyah ini memang dianggap Golden Age dalam sejarah kebudayaan Islam, sebuah era ketika berbagai jenis keilmuan berkembang dengan semarak. Dan perkembangan itu, karena umat Islam membuka diri bahkan memburu aneka keilmuan dari berbagai penjuru, baik dari Yunani-Romawi, Persia, atau India. Ketika ortodoksi semakin menguat era akhir Abbasiyah yang dipungkasi dengan peristiwa penyerangan bangsa Mongol, dunia Islam seperti kembali memasuki era kegelapan hingga sekarang.
Mengaji dengan “metode Baghdad” itu sendiri dimulai dari mengenal huruf hijaiyah “Alif, Ba’, Ta” (ا ب ت) kemudian pengejaan “Alif fatha A (اَ), Ba’ fathah Ba (بَ)” dan seterusnya hingga “Abjad hawwaz…” (ابجد هوز). Baru dilanjut membaca Alfatihah dan surat-surat pendek juz 3 dari Alquran yang urutannya dibalik, dari an-Nas sampai an-Naba.
Saya pribadi, barangkali karena lebih mengenal metode itu lebih dulu, sebut saja metode Baghdad atau metode eja, merasa jauh lebih nyaman daripada metode baru yang saat ini menyebar seperti Iqra, Ummi, dan seterusnya. Saya juga sempat mengaji Iqra di TPA di masjid tapi mokel sebelum sampai lulus jilid 6. Kini ternyata metode Iqra, Ummi dan sejenisnya itu sepertinya berhasil menggeser metode Turutan. Bahkan, saya terkejut ketika mengetahui bahwa di langgar-langgar itu metode Turutan sudah banyak ditinggalkan.
Model urutan “Alif, ba’, ta’, tsa’, jim, ha, kha, …” (ا ب ت ث ج ح خ ) yang ada di awal Turutan itu dikenal dengan Hijai atau Hijaiyah. Penyusunnya adalah Nashr ibn ‘Ashim, seorang murid Abu Aswad ad-Duali. Kriteria penyusunan huruf berdasarkan morfologinya. Ba’ (ب) mirip dengan ta’ (ت) dan tsa’ (ث), lalu jim (ج) dengan ha’ (ح) dan kha’ (خ). Dal (د) dengan dzal (ذ), ra’ (ر) dengan za’ (ز), sin (س) dengan syin (ش), dan seterusnya. Nasr bin ‘Ashim juga yang meletakkan titik-titik pembeda antar huruf yang bentuknya sama. Misalnya ba’ (ب) dengan titik satu di bawah, ta’ (ت) dengan titik dua di atas dan tsa’ (ث) dengan tiga titik di atasnya, dan seterusnya. Sehingga, kasus salah baca yang pernah berakibat fatal akan terhindarkan.
Pernah ada cerita populer ketika seorang pimpinan mengutus utusan dengan membawa surat yang tertulis “faqbalu” (فاقبلوا) yang artinya “terimalah”, tapi karena tanpa ada titik yang membedakan antara fa’ dengan qaf, ta’ dengan ba’ sehingga oleh penerima dibaca “faqtulu” (فاقتلوا) yang artinya “bunuhlah.” Jadi ketika utusan itu dibunuh, akibatnya terjadi perang antara dua kelompok itu.
Untuk itulah, Nashr bin ‘Ashim, atas perintah Hajjaj bin Yusuf, seorang panglima perang Muawiyah, memberi titik pembeda antara huruf yang bentuknya sama. Dan kini kita mewarisinya menjadi huruf Hijaiyah yang jumlahnya 30 itu, dengan memasukkan “lam alif” (لا) dan kemudian menjadi perdebatan.
Adapun sebelum Hijaiyah, bangsa Arab mengenalnya dengan sebutan “Abjadi” (ابجدي). Abjadi ini juga bisa kita cari padanannya dengan alfabet Yunani, alfabet Ibrani, atau alfabet Arami. Urutan Abajadun atau alif ba’ jim dal, mirip dengan urutan alpha beta gamma delta () dalam Alfabet Yunani. Alif/alfa artinya adalah sapi, ba’/beta/beth artinya rumah, jim/gamma artinya tongkat lempar, dal/dalet artinya pintu, dan seterusnya. Kemiripan itu wajar jika menengok pendapat banyak sejarawan yang menyatakan bahwa asal usul dari huruf Arab memang dari abjad Arami yang berhubungan dekat dengan alfabet Yunani karena sama-sama diturunkan dari abjad Fenisia. Ke Timur, abjad Arami punya turunan banyak aksara di Asia Selatan, seperti aksara Brahmi yang kemudian menurunkan aksara Devanagari di India sekarang. Di Jawa, aksara Brahmi ini menjelma jadi Hanacaraka.
Urut-urutan Abjadi inilah yang pada era Bani Umayyah disusun ulang dengan modifikasi oleh Nasr bin ‘Ashim jadi Hijai yang sekarang lebih populer di dunia Islam, sebagaimana bisa dilihat di awal kitab Turutan. Meski begitu, di akhir kitab Turutan alias Qaidah Baghdadiyah sebelum masuk al-Fatihah ternyata juga masih dicantumkan Abjadi. Abajad hawwaz … (ابجد هوز) dan seterusnya.
Ingatan saya atas abjadi cukup melekat karena sering dinyanyikan ayah saya. Abajadun hawazun hathayakun lamanun… dan seterusnya. Urutan abajadun hawazun itu menurut bapak saya sendiri adalah untuk menunjukkan angka. Dan benar saja, baru di kemudian hari saya tahu bahwa urutan abjad hawwaz itu dijadikan sebagai simbol angka yang urutannya disesuaikan. Alif (ا) = 1, ba (ب) = 2, jim (ج) = 3, dal (د) = 4, ha (ه) = 5, waw (و) = 6 za’ (ز) = 7, … ya (ي) = 10, ka (ك) = 20, la (ل) = 30, dan seterusnya hingga ghain (غ) = 1000. Ini lebih tepatnya:
أبجد هوز حطي = 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10
كلمن سعفص قرشت = 20—30—40—50—60—70—80—90—100—200—300—400
ثخذ ضظغ = 500—600—700—800—900—1000
Rumus Abajadun, atau semacam numerologi Arab, itu rupanya banyak digunakan para ulama kuno dalam penamaan atau penyimbolan. Misalnya untuk menamai kitab atau penyimbolan asma-asma Allah dengan angka-angka dari Abajadun itu. Banyak kitab klasik menjelaskan numerologi tersebut, khususnya kitab-kitab yang berhubungan dengan mistisisme Islam.
Ada keterangan menarik dari Ibn Arabi dalam al-Futuhat al-Makkiyah mengenai cara menamai anak agar terbuka pikirannya untuk keberuntungan dunia akhirat, yakni dengan menamai anak agar selaras dengan asma-asma Allah. Metode ini dikenal dengan hisab jummal.
Misalnya, Muhammad Nur Khaliq (محمد نور خالق) terdiri Muhammad (محمد) = 40 + 8 + 40 + 4 = 92, Nur (نو ر) = 50 + 6 + 200 = 256, Khaliq (خالق) = 600 + 1 + 30 + 100 = 731. Jadi totalnya 92 + 256 + 731 = 1079. Nah, dari angka 1079 ini bisa Anda urai menjadi beberapa angka yang menyimbolkan beberapa asma Allah yang dijumlahkan. Asma Allah yang sudah ketemu bisa dijadikan bacaan zikir khusus, atau jadi rajah, atau jadi patokan karakter. Caranya juga bisa sebaliknya, dari angka-angka yang berasal dari asma Allah, bisa kita breakdown menjadi nama anak-anak. Total angka dari nama seseorang juga bisa dijadikan patokan sebagai angka-angka keramat yang punya hubungan khusus.
Selain digunakan untuk pembuatan nama-nama itu, juga digunakan untuk penulisan rajah-rajah. Saya punya ingatan awal yang cukup kuat tentang rajah yang ditulis oleh Kiai langgar ketika saya sedang sakit dan ibu memintakan doa kesembuhan. Mbah Kiai langgar itu lalu memberi kertas bertuliskan angka untuk ditaruh ibu saya dalam gelas dikasih air untuk saya minum. Karena penasaran, setelah minum saya membuka kertasnya dan bertuliskan angka-angka. Angka-angka seperti itu juga saya dapati dalam kitab Mujarobat atau yang sejenis atau bisa ditemui di pasar oleh penjual buku, dan biasanya menjual buku cerita hantu, komik siksa neraka, kisah-kisah asmara, atau cerita humor sufi.
Pergumulan Arab Jawi Latini
Abajadun ini rupanya kalau kita mau telisik dalam penanggalan Jawa, rupanya punya jejak. Dalam kalender Jawa kita kenal dengan berbagai windu, yakni windu Sengara, windu Sancaya dan sebagainya. Sementara dalam satu windu ada 8 tahun, ada nama-nama tahun ternyata diambil dari abajadun, yakni tahun Alip, Ehe, Jim Awal, Je, Dal, Be, Wawu, dan Jimakir.
Sejak kapan penamaan penanggalan Jawa yang seperti itu? Ini butuh pelacakan yang lebih teliti. Mungkin saja bersamaan dengan konversi penanggalan Jawa dari Saka yang lunisolar ke qamariyah (murni lunar) dengan tetap mempertahankan perhitungan tahun yang sudah terlewati. Namun bisa juga itu sudah berlangsung pada era sebelumnya, yakni zaman Demak. Lebih tepatnya kita serahkan saja pada para sejarawan. Yang jelas, ternyata budaya pergumulan Arab dengan Jawa sudah sedalam itu.
Pergumulan Jawa/Arab bisa kita kenali misalnya dalam kisah Ajisaka yang secara alegoris menggambarkan perjumpaan antara budaya Jawa dengan Arab, yang bahkan dituangkan dalam kisah larik-larik Hanacaraka itu sendiri. Namun jika kita tahu bahwa aksara Hanacaraka adalah turunan dari aksara Brahmi (Abogida = Abajadun) lewat Pallawa lalu Kawi, sementara aksara Brahmi adalah turunan dari Aramia, maka antara Hanacaraka dengan Huruf Hijaiyah masih bertemu dalam satu induk: Aramia. Di Jawa, pergumulan lebih dalam bisa dilihat dari serat-serat yang ditulis para wali, yang kadang memakai aksara Hanacaraka kadang huruf Pegon atau Jawi (yang merupakan turunan dari huruf Arab, laiknya huruf Arab Persia dan Urdu).
Baik aksara Jawa atau huruf Arab dalam masyarakat masih dianggap punya dimensi mistik di dalamnya. Aksara Hanacaraka sering dimodifikasi untuk dijadikan mantra, misalnya dengan merapalkannya 3x dengan urutan terbalik: Ngathabagama…. Ini sangat berbeda dengan huruf Latin yang relatif profan. Sangat jarang ditemui rajah-rajah yang ditulis dengan huruf Latin. Mungkin saja karena kita mengenal huruf Latin dari Eropa yang sudah sekuler. Ini mirip sekali dengan jarangnya mantra-mantra, setidaknya yang saya pelajari, yang berbahasa Indonesia. Kebanyakan kombinasi dari Arab atau Jawa.
Waktu remaja, sambil menggembala kambing, saya pernah eksperimen mencoret-coret dengan batu kapur atas jalan menuju kampung yang baru selesai diaspal. Jadi tulisannya kelihatan sangat mencolok. Yang satu saya tulis dengan huruf Latin, yang sebelahnya huruf Arab, dengan tulisan yang artinya sama: “jalan desa, silahkan lewat.” Uniknya, mayoritas pengendara sepeda berusaha menghindari agar tidak melindas tulisan Arab, tapi untuk tulisan Latin mereka lindas saja. Bahkan ada ibu-ibu yang rela setengah berhenti untuk menghindari melindas tulisan Arab itu sambil memarahi saya. Tentu saja waktu itu saya tertawa dalam hati.
Uniknya, mayoritas pengendara sepeda berusaha menghindari agar tidak melindas tulisan Arab, tapi untuk tulisan Latin mereka lindas saja.
Secara pribadi, sesungguhnya saya lebih akrab dengan huruf Arab daripada Latin. Apalagi aksara Jawa meski saya sudah kenal sejak TK diajari kakek. Tapi karena relatif tidak digunakan, jadi kemampuan Hanacaraka pas-pasan. Beda dengan huruf Arab yang pernah mengisi kehidupan saya dengan waktu yang lumayan lama. Artinya, lingkungan sekitar saya akrab dengan huruf Arab. Bapak saya sampai sekarang masih buta huruf Latin. Paling hanya bisa menulis namanya sendiri untuk ditulis di amplop ketika mau menghadiri hajatan keluarga. Tapi bapak tidak buta huruf Arab, setidaknya bisa membaca Al Qur’an dengan lancar. Selain itu, pendidikan saya sejak kecil juga didominasi huruf Arab/Pegon. Mulai Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah lalu Tsanawiyah, beranjak remaja ketika malam sekolah di Madrasah Diniyah, dan mengaji di luar sekolah formal itu.
Buku catatan saya waktu sekolah lebih banyak didominasi huruf Arab, apakah berbahasa Arab atau Pegon alias Arab Jawi. Misalnya catatan saya tentang beberapa mata pelajaran “umum” waktu SMA seperti Sejarah atau Sosiologi yang didiktekan oleh guru, ternyata banyak yang saya tulis dengan huruf Pegon. Dan kalau dipikir-pikir, selain lebih irit halaman, juga relatif mudah untuk dibawa sebagai contekan ketika ujian. Relatif jarang ada guru yang mencurigai. Meskipun secara pribadi saya tidak suka mencontek. Saya cenderung kurang peduli apakah nilai raport saya baik atau buruk. Namun, melihat guru pengawas ujian yang tidak curiga ketika saya mencontek jadi kesenangan tersendiri. Sebentuk kelicikan anak remaja.
Baru ketika beranjak dewasa, khususnya saat kuliah, huruf Latin menjadi semakin dominan. Bahkan sudah sangat jarang membaca huruf Arab/Pegon, apalagi aksara Jawa. Coba membaca manuskrip saja sudah pegal bukan main rasanya. Saya tidak tahu apakah ini menunjukkan bahwa saya benar-benar sudah ter-Latin-kan? Dan apakah itu perlu disesali?
Suatu hari di pojok Nol KM setelah saya aksi demonstrasi di Jalan Malioboro, saya pernah membaca suatu pepatah yang cukup melekat di benak saya. “Jawa digawa, Arab digarap, Barat diruwat.” Saya berefleksi, apakah Jawa masih saya bawa atau sudah benar-benar saya tinggal? Arab sudah saya garap atau saya abaikan? Barat sudah jadi bagian jiwa saya tanpa harus ruwatan? Saya tidak tahu. Bahkan apakah refleksi yang seperti itu dibutuhkan atau tidak, saya juga tidak tahu.
Bangsa Jawa ini sejak dulu memang mengalami berbagai peralihan aksara. Dari Pallawa, lalu Kawi dan Hanacaraka, kemudian Arab Pegon, hingga kini didominasi Latin. Dunia memang selalu berubah, termasuk Jawa. Cara mengaji juga berubah, dari alip jabar a sebagaimana cerita nenek dan juga dalam serat Chentini, lalu alif fathah a dengan Turutan sebagaimana saya kecil, hingga sekarang dengan model Iqra atau Ummi yang tanpa mengeja.
Saya teringat ungkapan pujangga Jawa Raden Ngabehi Ranggawarsita, “Ela elo wong Jawa kari separo”. Barangkali rasa kehilangan memang suatu keniscayaan, tapi bukankah itu justru awal perubahan yang juga keniscayaan? Saya pikir kita butuh semacam kesadaran, bahwa kita memang tak pernah lengkap sehingga selalu butuh orang lain. Seperti legenda Aji Saka yang terekam dalam aksara Hanacaraka tentang dua utusan yang sama digdayanya berjumpa atau berselisih, apakah akan mati semua atau berhasil melebur menjadi sesuatu yang baru, masih menjadi pertanyaan yang menuntut jawaban sepanjang sejarah peradaban manusia.
Editor: Mohammad Hagie
Baca juga tulisan sebelumnya;
Cerita dari Langgar (1)