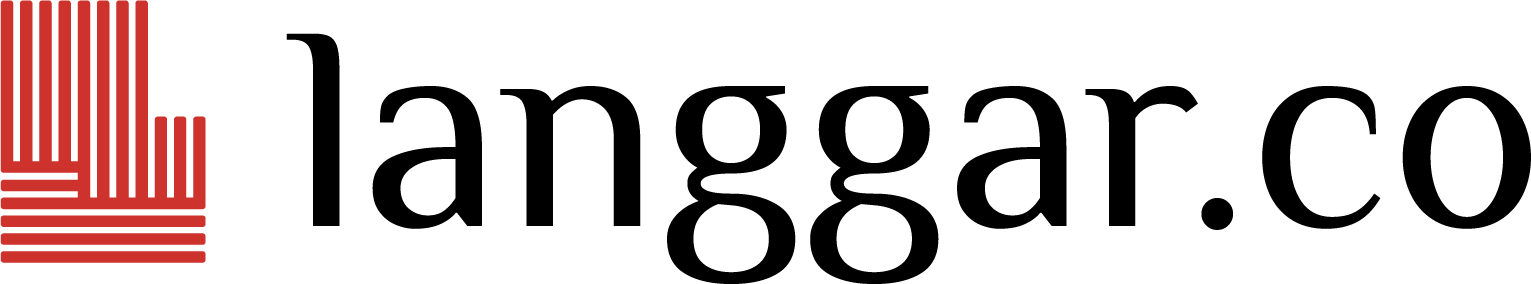Genealogi Islam Jawa: Kritik Historiografi Pascakolonial (Bagian I)
Ringkasnya, tanpa kajian genealogis, mustahil historiografi bisa melakukan otokritik terhadap narasi sejarah alternatif yang ditawarkannya; begitu pula, tanpa kajian historiografis, genealogi ibaratnya tubuh tanpa kaki, yang tidak mempertanyakan dimensi masa lalu dari teks-teks akademis yang dikritiknya.
Pengantar
Penulis ingin mengawali tulisan ini dengan sebuah asumsi: Islam Jawa merupakan diskursus kolonial; yang artinya, sebagai suatu entitas eksperiental, Islam Jawa sebenarnya tidak pernah ada, kecuali bahwa ia sengaja diciptakan sebagai suatu paradigma akademis—untuk tidak mengatakan ‘streotipe’—yang digunakan dalam memahami Islam dan/atau Jawa secara universal. Dalam banyak kajian antropologi, sosiologi, maupun studi agama, Islam Jawa cenderung dipahami dalam dua definisi: (1) Islam lokal (local Islam) yang berarti bahwa Islam Jawa merupakan bentuk lain dari Islam yang dipraktikkan oleh masyarakat tertentu dalam lokus tertentu, yakni Jawa atau (2) agama sinkretis (syncretic religion) yang berarti bahwa Islam Jawa pada awalnya merupakan perilaku keagamaan masyarakat Jawa yang dulunya menganut tradisi Animisme-Hindu-Budha, namun belakangan dianggap memiliki kesamaan dengan ajaran mistisisme Islam.
Masalah pertama pada definisi Islam Jawa sebagai Islam lokal adalah kenyataan bahwa proses asimilasi kebudayaan pada hakikatnya sudah inheren dalam agama Islam, termasuk juga mungkin dalam agama-agama lainnya. Artinya, tidak ada Islam Jawa; yang ada adalah Islam yang memanifestasikan diri di dalam kebudayaan dan masyarakat Jawa. Dengan kata lain, Islam Jawa pada definisi pertama pada hakikatnya adalah Islam itu sendiri. Sementara itu, masalah kedua pada definisi Islam Jawa sebagai agama sinkretis adalah kenyataan bahwa definisi tersebut berasal dari tradisi teologi Protestan yang dibawa oleh para antropologis dan sosiologis Barat. Mereka, tanpa sadar, menggunakan perspektif teologi ketika berbicara tentang sinkretisme agama Jawa.
Artinya, tidak ada Islam Jawa; yang ada adalah Islam yang memanifestasikan diri di dalam kebudayaan dan masyarakat Jawa. Dengan kata lain, Islam Jawa pada definisi pertama pada hakikatnya adalah Islam itu sendiri.
Formulasi masalah di atas kemudian akan membawa pada masalah lain yang perlu dirumuskan: Jika memang tidak ada agama Jawa yang disebut Islam Jawa, agama abangan, agama Jawi, dan seterusnya itu, lalu apa sebenarnya yang sedang digambarkan oleh para sarjana Barat selama ini? Tentu saja bukan ‘Islam’, karena para sarjana tersebut selalu menempatkan agama Jawa sebagai agama yang berbeda dari Islam pada umumnya, khususnya di Semenanjung Arabia. Ada dua kemungkinan yang bisa dilacak dari masalah ini. Pertama, Islam Jawa yang selama ini kita pelajari pada hakikatnya merupakan pengalaman eksperiental mereka; singkatnya, Islam Jawa merupakan cara berpikir Barat memahami dunia non-Barat (Timur). Sehingga, konsep mengenai Islam Jawa pada hakikatnya hanyalah berisi konstruk kebudayaan Jawa yang fragmenter. Kedua, sebagai konsekuensi dari poin pertama, pemahaman kita atas kebudayaan Jawa ternyata bersifat non-eksisten, tersembunyi, atau sengaja disembunyikan, karena hampir seluruhnya dari tradisi tersebut disalahartikan sebagai bagian dari agama Jawa, dan hal ini—ironisnya—telah terjadi sekian lama.
Situasi ini sekaligus juga akan membawa pada masalah ketiga yang lebih spesifik dan filosofis: Mengapa dalam perkembangan diskursus kesarjanaan Barat itu, Islam Jawa menjadi sedemikian ‘kolonial’? Pertanyaan ini melahirkan asumsi lanjutan bahwa salah satu penyebab suburnya konsepsi kolonial Islam Jawa adalah karena minimnya—untuk tidak mengatakan ‘absennya’—kajian historiografi pascakolonial atas kerja-kerja kesarjanaan Barat yang menempatkan sumber-sumber Islam dan Jawa (baik manusia maupun teks-teksnya) dalam sudut pandang yang sama-sekali berbeda dari kajian-kajian akademis pada umumnya. Masalah ini tentu saja bukan tanpa alasan, karena naskah-naskah Jawa kuno (hikayat, babad, serat, dan sebagainya) cenderung diposisikan tak lebih sebagai sumber sekunder yang arbitrer, campuran fiksi dan fakta, mitologi dan aktualita, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan standar akademik dan dunia kesarjanaan Barat. Pun juga, akibat dari superioritas sumber akademik Barat di Jawa, manusia Jawa / Islam terus-menerus disubjuguasi dalam xenophobia akademis sebagai ‘yang-lain’ dan ‘yang-asing’ bagi mereka.
Baca: Akademi Barat: Pengalaman Meneliti Islam Jawa | Verena Meyer Baca juga: Tasawuf Jawa dan Pendekatan Cocokologi
Islam Jawa: Mengapa Perlu Kajian Genealogi?
Ceramah Mark Woodward tentang “Sejarah Agama-Agama” memulai kegelisahan penulis untuk melakukan riset tentang Islam Jawa. Awal tahun 2014, ia mengajar penulis di Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada, sebuah program studi setara S2 yang fokus kajiannya adalah studi lintas agama, dialog agama-agama, dan tradisi agama lokal. Salah satu momen penting yang bisa diingat dari perjumpaan penulis dengan pengarang Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta (1989) itu adalah ketika ketika ia menyebut ‘Mbah Maridjan mendalami tradisi Jawa meskipun ia seorang Muslim taat’ (2010: ). Istilah yang agak menganggu di sini adalah kata meskipun, karena ia justru memperlihatkan suatu ketegangan antara percaya pada tradisi pra-Islam di satu sisi dan penerimaan terhadap ajaran Islam di sisi lain. Pernyataan Woodward ini persis dengan yang ditulis oleh Robert Wessing (2010: 0: 60) bahwa sebagaimana di tempat-tempat lain di Indonesia … kepercayaan terhadap ilmu sihir ini mengakar kuat di Jawa Timur meskipun mereka memeluk Islam (Like elsewhere in Indonesia … belief in sorcery is deeply ingrained in East Java, adherence to Islam notwithstanding) (garis bawah dari penulis). Apa sebenarnya yang sedang dibayangkan oleh Woodward ketika menyebut identitas ganda dari Mbah Maridjan itu? Apa pula yang dibayangkan oleh Wessing ketika ia—dengan nada yang tampaknya ‘agak terkejut’—menyebut kepercayaan terhadap ilmu sihir ternyata harus bersanding dengan keyakinan terhadap Islam?
Dalam artikelnya berjudul “Javanese Religion, Islam or Syncretism: Comparing Woordward’s Islam in Java and Beatty’s Varieties of Javanese Religion” (2013), Agus Salim memperlihatkan perdebatan teoretis antara Woordward dan Andrew Beatty yang menurutnya bahwa yang pertama lebih menekankan sinkretisme Islam, yang berarti bahwa Islam di Jawa adalah adopsi atas tradisi Hindu dan Buddha yang telah lama berkembang, sementara yang kedua menekankan tradisi mistisme Islam lokal, yang berarti bahwa Islam di Jawa adalah suatu praktik kejawen yang memiliki tradisi mistisisme tersendiri yang bersinggungan dengan tradisi mistis agama-agama lain, termasuk sufisme Islam. Woodward mencoba menelusuri lebih dalam mistisisme Jawa, sementara Beatty menggunakan perspektif antropologi murni yang menekankan singularitas dan partikularitas praktik kejawen sebagai salah satu elemen dari berbagai praktik mistisisme agama-agama formal pada umumnya, termasuk Islam itu sendiri. Di sini, alih-alih memperlihatkan heterodoksi atas Islam, penulis melihat Beatty justru menggunakan asumsi ortodoksi untuk memperlihatkan kuatnya pengaruh Islam di tanah Jawa hingga mampu mengakomodir praktik kejawan ke dalam tradisi sufisme, suatu penilaian yang khas ditemukan dalam berbagai riset di perguruan tinggi Islam pada umumnya. Pertanyaannya, benarkah heterodoksi dan ortodoksi Islam ini yang merepresentasikan Islam Jawa yang sebenarnya?
Persis di titik inilah, muncul sejenis pemakzulan betapa pendekatan terhadap Islam, khususnya dalam konteks masyarakat Jawa, dipenuhi dengan ‘tradisi kepakaran ilmiah yang penuh streotipikal,’ sebuah streotipe akademik yang diwariskan secara turun termurun sejak triktomi Geertz ‘Santri-Abangan-Priyayi’ melalui tesisnya yang problematis tentang ketidakmungkinan ‘masyarakat Jawa untuk menjadi Muslim yang sebenarnya’….
Merenungkan pernyataan Woodward, Wessing, dan Beatty ini sekilas mengingatkan penulis pada buku Orientalism (1978) karya Edward W. Said yang pernah penulis terjemahkan ke dalam versi bahasa Indonesia empat tahun sebelumnya di Pustaka Pelajar. Dalam buku ini, Said memperlihatkan bagaimana diskursus kolonial, utamanya pada akhir abad ke-17, telah sedemikian masif mengkonstruksi pengetahuan kita atas fenomena ke-Timur-an (dalam hal ini, Islam). Persis di titik inilah, muncul sejenis pemakzulan betapa pendekatan terhadap Islam, khususnya dalam konteks masyarakat Jawa, dipenuhi dengan ‘tradisi kepakaran ilmiah yang penuh streotipikal,’ sebuah streotipe akademik yang diwariskan secara turun termurun sejak triktomi Geertz ‘Santri-Abangan-Priyayi’ melalui tesisnya yang problematis tentang ketidakmungkinan ‘masyarakat Jawa untuk menjadi Muslim yang sebenarnya’ (it is very hard, given his tradition and his social structure, for a Javanese to be a ‘real Moslem’…) (Geertz, 1960: 160). Streotipe ini telah mengakar kuat, bahkan jauh sebelum tulisan Geertz itu menjadi bacaan wajib para mahasiswa antropologi, ketika Van Leur (1955) pernah membayangkan Islam di Jawa sebagai ‘glasir porselin yang tipis dan mudah pecah’ (… a thin, easily flaking glaze) (van Leur, 1955: 168).
Apa yang dilakukan oleh Salim, dan juga riset-riset lain yang sejenis dari para sarjana Indonesia selama 1 dekade terakhir (Sila, 2011; Jamhari, 2000; Jamhari, 2002; Prasetyo, 1994; Safriani, 2012) memperlihatkan bahwa ‘truisme’ ilmiah yang diperlihatkan oleh sebagian sarjana Barat selama ini memiliki implikasi tertentu terhadap konseptualisasi kita tentang agama dan kebudayaan, termasuk Islam Jawa itu sendiri. Ironisnya, truisme itu kini menjadi bagian dari cara kita berpikir tentang dan memperlakukan Islam Jawa dalam ranah akademia. Kritik terhadap truisme tersebut akan dilakukan dengan menampilkan genealogi konseptual dari Islam Jawa, lalu melacak sejarahnya dalam kerangka historiografis yang memosisikan sejarah sebagai sebuah narasi, dan karenanya konsep Islam Jawa tak pernah tunggal untuk didefinisikan. Dengan demikian, tulisan ini, pertama-tama, bersifat kritis karena ia berusaha memberikan kritik terhadap bangunan epistemologis atas asal-muasal (genealogi) Islam Jawa dalam penulisan sejarah (historiografi) di Indonesia.
Kritik genealogis pertama-tama bisa dilakukan dengan melacak perkembangan diskursus Islam Jawa dalam sejarah studi-studi Jawa pada umumnya. Islam Jawa merupakan konsep utama yang sering digunakan dalam kajian tentang Jawa, baik secara etnografis maupun historis, selain juga bahwa Islam Jawalah yang turut membentuk kerangka berpikir para sarjana Barat tentang Jawa itu sendiri. Tanpa bermaksud berlebihan, bisa dikatakan bahwa tanpa Islam Jawa, kajian tentang Jawa (Javanese Studies) hampir mustahil dilakukan. Kritik genealogis ini ditempuh pertama-tama dengan menguji bagaimana para sarjana Javanese Studies menggunakan konsep Islam Jawa tersebut. Artinya, ia tidaklah berusaha mendeskripsikan Islam Jawa, melainkan mendeskripsikan bagaimana Islam Jawa itu dipahami. Kerja semacam ini diharapkan bukan hanya dapat menjelaskan bagaimana asal-muasal konsep tersebut lahir dan digunakan, melainkan juga dapat menyajikan problem-problem epistemologis yang melatarbelakangi lahirnya konsep tersebut dalam sejarah perkembangan kajian Jawa selama ini.
Dengan demikian, Islam Jawa merupakan produk dari diskursus kolonial; singkatnya, penulis berusaha melihat asal-muasal munculnya diskursus tentang Islam Jawa selama ini dalam dunia kesarjanaan Barat. Asal-mula diskursus ini muncul dalam spektrum kesarjanaan Barat yang berusaha memahami dan menyingkap ‘misteri yang tersembunyi’ dari kebudayaan Timur. Dengan demikian, secara historis, konsep ‘Islam Jawa’ merupakan hasil dari persentuhan diskursif antara dua kebudayaan yang berbeda, suatu persentuhan di mana satu kebudayaan tertentu berusaha mendeskripsikan kebudayaan lainnya dalam cara pikir kebudayaan asal. Persentuhan diskursif ini menemukan relevansinya dalam kajian genealogis karena kajian ini berusaha memetakan konsep Islam Jawa dalam kerangka akar muasal epistemologisnya. Hanya dengan cara inilah, kita akan menyadari bahwa konsepsi kita tentang agama Jawa selama ini ternyata berasal dari para penjelajah Barat, dan demikianlah—sebagaimana yang sudah lama disinggung Edward W. Said—kajian terhadap Timur selalu berasal dari keinginan Barat untuk memahami sekaligus menguasai Timur ‘dari jauh’.
Dengan demikian, secara historis, konsep ‘Islam Jawa’ merupakan hasil dari persentuhan diskursif antara dua kebudayaan yang berbeda, suatu persentuhan di mana satu kebudayaan tertentu berusaha mendeskripsikan kebudayaan lainnya dalam cara pikir kebudayaan asal.
Genealogi juga memberi ruang bagi analisis lebih lanjut terhadap konsep-konsep yang digunakan oleh para sarjana Barat untuk mendeskripsikan agama di Jawa, konsep-konsep yang dengannya Islam Jawa didefinisikan sedemikian rupa. Kerangka konseptual yang membentuk bangunan epistemologis Islam Jawa—harus diakui—umumnya berasal dari tradisi Barat. Sebagai outsider, mereka yang berusaha memahami kebudayaan Jawa pada akhirnya terjebak pada berbagai representasi, jika bukan misinterpretasi, atas Islam Jawa. Kajian genealogi dapat menunjukkan bagaimana deskripsi atas Islam Jawa itu ternyata dipenuhi oleh deskripsi kolonial Barat. Sehingga, bisa dikatakan bahwa baik sebagai agama sinkretis (syncretism) maupun Islam lokal (local Islam), Islam Jawa adalah produk kolonial yang implikasinya adalah mengharuskan penulis untuk menyajikan suatu perspektif alternatif, dari sudut pandang pascakolonial, yang akan menempatkan konsep-konsep tersebut sebagai produk kuasa-pengetahuan kolonial.
Selanjutnya, konsep Islam Jawa secara genealogis mulai terlembagakan secara akademis dan ‘saintifik’ oleh para sarjana Barat pada abad 19. Pada periode ini, dimulailah kajian-kajian akademis terhadap kebudayaan dan agama Jawa. Pada abad ini pula muncul para sarjana Barat (Geertz, Steenbrink, Ricklefs, Laffan, dan sebagainya) dan sarjana Indonesia(is) yang berusaha mengkonseptualisasikan Islam Jawa dalam suatu kontestasi akademis yang tak berkesudahaan, dan setelah semua ini kita bisa melihat bagaimana Islam Jawa mulai dijadikan bahan kajian dan diskusi ilmiah dalam forum-forum akademis. Periode ini pula menandai munculnya istilah ‘sinkretisme’ atau ‘Islam lokal’ untuk mendeskripsikan Islam Jawa, suatu istilah yang familiar di kalangan para sarjana Javanese Studiesatau pengkaji mistisisme lokal saat itu.
Tahun 2015, dalam sebuah seminar internasional di Jakarta, penulis yang saat itu mempresentasikan paper berjudul “Contesting Double Genealogy: Representing Rebellion Ambiguity in Babad Tanah Jawi” seketika menyebut istilah ‘sinkretisme Jawa’ untuk memperlihatkan silsilah ganda Mataram yang berasal dari trah Majapahit (Batara Guru) dan Demak (Nabi Adam).Spontan, Annabel Teh Gallop dari British Library yang ketika itu menjadi reviewer berkomentar dengan nada ‘terguran’, “Kita perlu berhati-hati menyebut istilah sinkretisme untuk mendefinisikan agama Jawa, karena istilah ini agak problematik” (We have to be really careful of mentioning ‘syncretism’, because this term is quite problematic). Penulis pun menyadari bahwa, pada tahap tertentu, diskursus kolonial tentang sinkretisme Islam Jawa ternyata telah sedemikian jauh tertanam dalam ke(tidak)sadaran penulis selama ini.
Penulis pun menyadari bahwa, pada tahap tertentu, diskursus kolonial tentang sinkretisme Islam Jawa ternyata telah sedemikian jauh tertanam dalam ke(tidak)sadaran penulis selama ini.
Selain itu, artikel-artikel yang terbit di berbagai jurnal akademis Indonesia, baik yang berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, juga tak mau kalah dalam upayanya mendefinisikan Islam Jawa dalam konteks mistisisme. Asumsi yang mereka bangun umumnya adalah kedekatan praktik kejawen dengan praktik sufisme dalam Islam, dan karenanya mereka mencari bukti-bukti spesifik yang dapat menghubungkan kedua praktik tersebut dalam satu istilah terkenal yang sebagian berbunyi: Islam lokal (local Islam). Sehingga muncullah konsep-konsep, seperti Islam lokal Mandar, Islam lokal Gorontalo, Islam lokal Madura, dan seterusnya. Bahkan, sebagian prodi keislaman di Perguruan Tinggi Islam juga sudah mulai mengajarkan dan menawarkan matakuliah “Islam dan Budaya Lokal”, yang di dalamnya menawarkan kurikulum tentang Islam lokal, lokalitas Islam, Islam dan tradisi setempat, dan seterusnya. Singkatnya, ada upaya diskursif untuk mendefinisikan Islam Jawa sebagai suatu ‘agama lokal’ tertentu yang berjalin kelindan dengan tradisi agama Islam.
Fenomena di atas tentu memunculkan satu masalah filosofis lain yang perlu diajukan: dari mana dan mengapa muncul istilah “Islam Jawa”? Pertanyaan ini, sayangnya, belum banyak dieksplorasi sebagai suatu kajian genealogis dan historiografis yang serius. Istilah “Islam Jawa” sudah cenderung diterima secara taken for granted, sedikitnya, dalam dua aspek: a) sebagai agama Jawa (Javanese religion) yang cenderung diposisikan sebagai Islam lokal dan turunan dari agama Islam formal di satu sisi, dan b) sebagai agama sinkretis (syncretist religion) yang cenderung diposisikan sebagai adopsi atas tradisi Animisme-Hindu-Budha di sisi yang lain. Masalahnya, baik sebagai agama Jawa maupun sebagai sinkretisme, Islam Jawa tetaplah merupakan istilah yang problematik untuk mendeskripsikan masyarakat Jawa yang beragama Islam atau Muslim yang hidup dalam kultur Jawa itu sendiri.
Pertanyaan pun muncul: Apakah Islam Jawa benar-benar Islam, katakanlah sebagai Islam lokal (local Islam), atau ia adalah sistem keyakinan animisme atau Hindu-Buddha yang hanya berwajah Islam (syncretist Islam)? Diskursus Islam Jawa dalam perspektif yang pertama berasal antara lain dari pendapat Christiaan Snouck Hurgronje, orientalis asal Belanda, yang lama tinggal di Aceh. Menurut Hurgronje, yang berbeda dari pendapat para orientalis lain yang menekankan pada sinkretisme, Islam Jawa tidak bisa dipahami kecuali melalui pemikiran teologis Islam itu sendiri. Sayangnya, analisis ini problematik karena bukan hanya ia memiliki masalah epistemologis tersendiri suntuk menjelaskan Islam Jawa, melainkan juga karena ia gagal menjembatani Islam sinkretis dan Islam lokal sebab kedua istilah ini merujuk pada dua hal yang berbeda.
Sementara itu, diskursus Islam Jawa dalam perspektif kedua bisa dilacak antara lain melalui pandangan M.C. Rickleffs (2006, 2007, 2012) tentang mystic synthesis yang merujuk pada proses Islamisasi di pulau Jawa pada abad ke-14 sampai abad ke-19 Masehi. Ricklefs berusaha keras melacak sejarah Islamisasi di Jawa pada periode tersebut, salah satunya, dengan mengasosiasikan Islam Jawa dengan tradisi Hindu Buddha dan mistisisme Islam dari Timur Tengah (Hadramaut), suatu usaha rekonsiliasi identitas yang menemukan bentuknya pada awal abad ke-17 pada masa Sultan Agung Mataram. Sebagaimana upaya Hurgronje, usaha Rickleffs ini juga bermasalah karena sinkretisme—sebagaimana kritik yang pernah disinggung Annabel Teh Gallop—tak pernah benar-benar mampu mendeskripsikan agama Jawa sebagai sebagai suatu pengalaman objektif. Lalu, jika benar bahwa mereka—sebagaimana penulis—tidak pernah benar-benar mampu mendeskripsikan apa itu Islam Jawa, lalu apa sebenarnya yang sedang mereka gambarkan selama ini? Apakah Islam Jawa benar-benar ada?
Pertanyaan di atas juga membawa penulis pada tesis lainnya bahwa Islam Jawa merupakan entitas eksperiental yang subjektif, dan hanya orang-orang yang mengalamilah yang paling mungkin mendeskripsikan secara personal apa itu Islam Jawa. Sayangnya, dalam sejarah genealogi Islam Jawa selama ini, belum ada satu riset komprehensif yang berusaha menghubungkan bukti teoretis dan pengalaman empiris tentang adanya agama Jawa yang sinkretis atau mistis itu. Absennya studi yang menjembatani dua hal tersebut membuat penulis menyadari bahwa saintifikasi Islam Jawa sebagai suatu konsep diskursif merupakan hasil dari pengalaman eksperimental para sarjana Barat, sehingga apa yang dialami oleh Hurgronje, Woodward, Geertz, Rickleffs, dan sarjana-sarjana lain yang terepresentasi dalam konsep-konsep yang mereka bangun pada hakikatnya tak lebih sebagai suatu gubahan akademis yang dibuat untuk membantu mereka memahami Islam Jawa. Artinya, hanya dengan “Islam Jawa” atau “Islam sinkretis” atau “agama Jawa” atau “Islam lokal” dan sejenisnya, mereka bisa merepresentasikan pengalamannya bersentuhan dengan sebagian kecil realitas Jawa itu sendiri secara teoretis dan membangunnya dalam suatu kerja kepakaran akademis.
Artinya, hanya dengan “Islam Jawa” atau “Islam sinkretis” atau “agama Jawa” atau “Islam lokal” dan sejenisnya, mereka bisa merepresentasikan pengalamannya bersentuhan dengan sebagian kecil realitas Jawa itu sendiri secara teoretis dan membangunnya dalam suatu kerja kepakaran akademis.
Baca: Rumusan Islam Politiek Snouck Hurgronje Baca juga: Tarekat Akmaliyah dan Malamatiyah di Jawa
Islam Jawa: Mengapa Perlu Kajian Historiografis?
Dengan demikian, apa yang perlu dilakukan adalah menempuh jalan memutar dengan pertama-tama melacak asal-usul (origins) diskursus Islam Jawa dalam perkembangan studi-studi kesarjanaan Barat, lalu kemudian menawarkan suatu perspektif alternatif berupa historiografi pascakolonial untuk menjelaskan problem epistemologis dari sumber-sumber Barat itu secara historis sekaligus mengilustrasikan beberapa kemungkinan narasi historis yang sengaja (di)hilang(kan) dari cerita besar tentang Islam Jawa. Strategi kedua digunakan karena penulis melihat, sebagaimana yang telah diuraikan sejak awal, bahwa diskursus Islam Jawa umumnya hanya muncul dalam kajian antropologi kebudayaan (cultural anthropology) dan studi agama (religious studies). Pada pendekatan pertama, Islam diperlakukan sebagai hasil dari proses negosiasi kultural dan stratifikasi sosial di antara para anggota masyarakat Jawa. Sementara itu, pendekatan kedua memosisikan Islam sebagai suatu praktik ritual keagamaan yang sangat terkait dengan konsep-konsep teologis di dalamnya.
Sayangnya, memisahkan kedua pendekatan tersebut dan—dengan demikian—mengabaikan pendekatan lain (historiografi) berarti melupakan kontribusi peran filolog dan sejarahwan dalam mengkonstruksi konsep Islam Jawa melalui berbagai naskah klasik. Masih jarang upaya historiografis yang dilakukan secara serius untuk mempertanyakan perkembangan diskursif konsep Islam Jawa dalam kerangka sejarah. Jika pun ada, kajian-kajian tersebut umumnya masih berusaha membuktikan sumber asali dari peristiwa tertentu, misalnya, kapan persisnya Islam muncul di tanah Jawa, apa saja peristiwa-peristiwa yang luput dari penulisan sejarah Islam di tanah Jawa, tetapimasih belum ditemukan suatu upaya sistematis untuk melacak asal-muasal (genealogi) diskursus Islam Jawa melalui kajian atas penulisan sejarah (historiografi) atas Islam Jawa itu sendiri, dan tulisan ini adalalah satu satu upaya menuju ke sana. Jika pun ada, historiografi tersebut umumnya tetap berkiblat dan—meskipun berusaha keluar—terjebak pada paradigma Eropa / Neerlando-sentris.
Tahun 2014, Studia Islamika, sebuah jurnal internasional berbasis di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengadakan konferensi bertema “Southeast Asian Islam: Legacy and Interpretation”, sebuah tema yang dalam kontekstulisan initampaknya sangat relevan. Konferensi yang dilaksanakan untuk memperingati hari jadi Studia Islamika yang ke-20 itu menawarkan satu rekomendasi penting, antara lain, tentang pentingnya melakukan kajian Jawa dalam perspektif warisan masa lalu (legacy). Rekomendasi tersebut relevan bagi tulisan ini karena sebagian riset genealogis yang telah disebutkan di awal tidak benar-benar memadai untuk memberikan jalan keluar dari jebakan orientalis atau universalitas agama, tidak pula ia menawarkan satu interpretasi baru bagi kita untuk melihat masa depan studi Jawa.
Dalam satu esainya, “Mencari Historiografi Islam yang Mandiri” (2018), Ahmad Nasih Luthfi, sejarahwan dan editor Etnohistori, pernah mengajukan dua pertanyaan penting yang kira-kira bunyinya seperti berikut: “Pertama, bisakah kita membuat periodeisasi sejarah Islam Indonesia yang mandiri (yang non-kolonial sentris)? Jika memang bisa (membuat historiografi tanpa melibatkan realitas makro kolonial), realitas macam apa yang dapat kita peroleh?” Pertanyaan Luthfi ini, yang senada dengan perdebatan mutakhir di kalangan sejarahwan lain (seperti, Purwanto & Adam [2013]; Purwanto[2006]; Margana, dkk. [2017]), penting karena ia membuka arah baru bagi penulisan sejarah alternatif, suatu penulisan sejarah yang tidak hanya berusaha keluar dari jebakan diskursus kolonial, melainkan juga menawarkan suatu perspektif historiografi yang ideal, yang menjadikan sumber-sumber arkaik Jawa sebagai data primernya atau—setidaknya—memosisikan penulis Jawa sebagai subjek yang menulis ‘Islam’nya sendiri.
Yang dilakukan oleh Geertz, Woodward, Hurgronje, serta para pengkritiknya, mulai dari para sarjana Barat, seperti Steenbrink, Laffan, Asad, dan Boogert hingga sarjana Indonesia, seperti Azra, Salim, Jamhari, Ali, Prasetyo, Burhanuddin, serta para Indonesianis lainnya jelas memberi peta tersendiri bagi perkembangan kajian Islam Jawa, namun—sejauh pengamatan penulis—kajian mereka pada umumnya berbasis pada antropologi murni atau sejarah agama, yang meskipun menggunakan literatur sejarah, umumnya hanya mengutip karya sastra Jawa sebagai ilustrasi atau sumber sekunder semata, bukan sebagai titik pijak bagi pengembangan analisis selanjutnya.
Tidak hanya itu, sebagian kajian antropologis dan historis mereka masih menjadikan sumber-sumber akademik dari para sarjana Barat atau—paling banter—arsip-arsip VOC sebagai pilihan utama, suatu pilihan yang tentu saja dilematis: di satu sisi sumber-sumber tersebut bukanlah sumber arkais atas Jawa karena merupakan produk dari representasi dan interpretasi penulisnya atas Jawa, sementara sumber-sumber sejarah tentang Jawa sendiri yang berasal dari babad, hikayat, atau pun serat dianggap tidak memenuhi standar ‘kepakaran ilmiah-akademis’ (penuh mitos dan fiksi) yang disebabkan justru antara lain oleh berbagai streotipe yang berasal dari sumber-sumber yang pertama disebutkan itu.
Dengan demikian, dibutuhkan suatu disiplin tertentu yang mampu menghubungkan kajian genealogis dengan kerja historiografis, suatu disiplin yang akan membantu kita memahami bagaimana masa lalu seringkali dibentuk oleh pengalaman masa kini. Kerja historiografis semacam ini juga akan menjelaskan munculnya berbagai streotipe yang tampaknya cukup berbahaya bagi pandangan kita saat ini tentang Islam (dan) Jawa, dan karena itulah riset untuk menguji streotipe-streotipe itu mutlak dibutuhkan. Kerja semacam ini, tentu saja, bukanlah tugas yang mudah, namun jauh lebih tidak mudah lagi jika streotipe-streotipe itu mengakar jauh hingga masuk ke dalam narasi besar sejarah kita saat ini.
Dalam konteks historiografis, representasi atas Islam Jawa tidak cukup hanya dilihat dari bagaimana para sarjana Barat mengkonstruksi Islam Jawa pada saat ini, melainkan juga dari cara mereka mengkonstruksi Islam Jawa pada masa lalu. Dalam artikelnya berjudul “De-colonising Indonesian Historiography” (2004), Henk Schulte Nordholt menyebut bahwa it is not enough to look at these narratives [narratives on national ethnic or religious identities] in terms of representations only; we also need to uncover the genealogies which have constructed and [re]produced these texts (Tidak cukup bagi kita untuk melihat narasi-narasi besar tentang identitas religius dan etnik hanya dalam kerangka representasi; kita perlu menyingkap genealogi yang mengkonstruksi dan mereproduksi teks-teks semacam ini dalam sejarah). Mengutip apa yang dikatakan oleh Bernard Cohn (1987), kajian genealogis (tentang bagaimana sejarah dimediasi oleh kebudayaan) dan kajian historiografis (tentang bagaimana kebudayaan dimediasi oleh sejarah) bisa memberi pijakan kuat untuk mengenalisis bagaimana streotipe, pandangan, dan asumsi orang dalam mengkonseptualisasikan masa lalu, serta kategori-kategori apa saja yang mereka gunakan untuk mengklasifikasikan dunia. ‘Islam Jawa’, harus diakui, merupakan hasil dari dualisme proses semacam ini.
Selain itu, narasi besar atas Islam Jawa umumnya diproduksi oleh literatur-literatur yang ditulis oleh para sarjana Barat, literatur-literatur yang—sebagaimana telah disinggung di awal—semata menghasilkan metanarasi yang penuh bias dan streotipikal, sehingga dibutuhkan suatu produk narasi lokal yang berasal dari literatur Jawa sendiri atas sejarah masa lalunya, dan historiografidalam hal inimenjadi perspektif penting untuk mengurai kompleksitas narasi lokal tersebut dengan menawarkan—meminjam istilah J.J. Ras (1987)—testimoni internal dari teks-teks lokal itu. Sumber-sumber sejarah yang berasal dari dan ditulis oleh para pujangga Nusantara sebaiknya perlu ditempatkan sebagai literatur yang secara struktural menjelaskan Islam Jawa menurut pandangan hidup orang Jawa itu sendiri. Meskipun sebagian kalangan berasumsi bahwa naskah-naskah, seperti Babad, Hikayat, atau Serat, dipenuhi oleh berbagai unsur mitos, naskah-naskah itu bisa menjadi catatan historis atas Islam Jawa yang bisa digunakan oleh para sejarahwan untuk menulis tentang sejarah Islam Jawa.
Akan tetapi, masalah ini pada akhirnya harus beradapan dengan suatu kenyataan: historiografi tetaplah sebuah representasi atas sejarah; dan sebagaimana sebuah representasi, ia tak akan pernah benar-benar mampu menampilkan narasi yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Untuk itulah dibutuhkan suatu perspektif historiografi alternatif yang mampu mempertanyakan representasi para sejarahwan atas narasi yang ia bangun, baik yang bersumber dari literatur-literatur sarjana Barat maupun dari teks-teks sastra itu sendiri. Hal ini lah yang menjadi alasan mengapa kajian historiografi pascakolonial, yang menurut Prakash (1992: 8) berusaha mempertanyakan secara radikal segala bentuk pengetahuan dan identitas sosial yang telah didominasi oleh dominasi sarjana Barat (…to force a radical re-thinking and re-formulation of forms of knowledge and social identities authored and authorized by colonialism and western domination), menjadi satu keniscayaan tesendiri.
Historiografi pascakolonial berusaha mengungkap narasi-narasi kecil yang sengaja dihilangkan dalam narasi panjang sejarah penulisan Islam Jawa oleh para sarjana Barat. Historiografi semacam ini tentu relevan dihubungkan dengan kajian genealogis, karena kajian ini dapat membantu kita melacak perkembangan epistemologis dari konsep-konsep yang turut membentuk penafsiran kita atas Islam Jawa.
Dengan demikian, perlu adanya kajian historiografi pascakolonial yang menjadi fondasi teoretis untuk menganalisis Islam Jawa, sementara kajian genealogis menjadi kanopi metodologis untuk melacak miskonsepsi atas Islam Jawa yang selama ini dibangun oleh para sarjana Barat, baik mereka yang menjadikan literatur Jawa sebagai sumber primer maupun mereka yang nyaris sama sekali tidak mengutip literatur Jawa untuk membangun konsepnya tentang Islam Jawa. Ringkasnya, tanpa kajian genealogis, mustahil historiografi bisa melakukan otokritik terhadap narasi sejarah alternatif yang ditawarkannya; begitu pula, tanpa kajian historiografis, genealogi ibaratnya tubuh tanpa kaki, yang tidak mempertanyakan dimensi masa lalu dari teks-teks akademis yang dikritiknya.
Asumsi-asumsi inilah yang menuntun penulis untuk melacak genealogi Islam Jawa, pertama-tama sebagai suatu konsep yang definisinya tidak tunggal, penuh dengan miskonsepsi dan logika yang inkosisten, dan cacat epistemologis dalam berbagai karya-karya antropologi sarjana Barat, untuk kemudian membandingkannya dengan karya-karya historiografis para sarjana Barat dan Indonesia yang menjadikan karya-karya sastra arkaik Jawa, seperti Babad Jaka Tingkir, Babad Tanah Jawi, Serat Centhini, Serat Cabolek, dan sebagainya sebagai sumber utama mereka. Singkatnya, tulisan ini ingin mempertanyakan asal-muasal (genealogi) konsep ‘Islam Jawa’ yang banyak ditemukan dalam teks-teks akademis sarjana Barat di satu sisi, sekaligus menunjukkan bagaimana genealogi tersebut dipertanyakan dalam teks-teks akademikorang Jawa sendiri yang notabene merujuk pada sumber-sumber arkaik utama dalam tradisi penulisan sejarah Islam Jawa di sisi yang lain.
Bersambung….