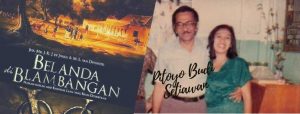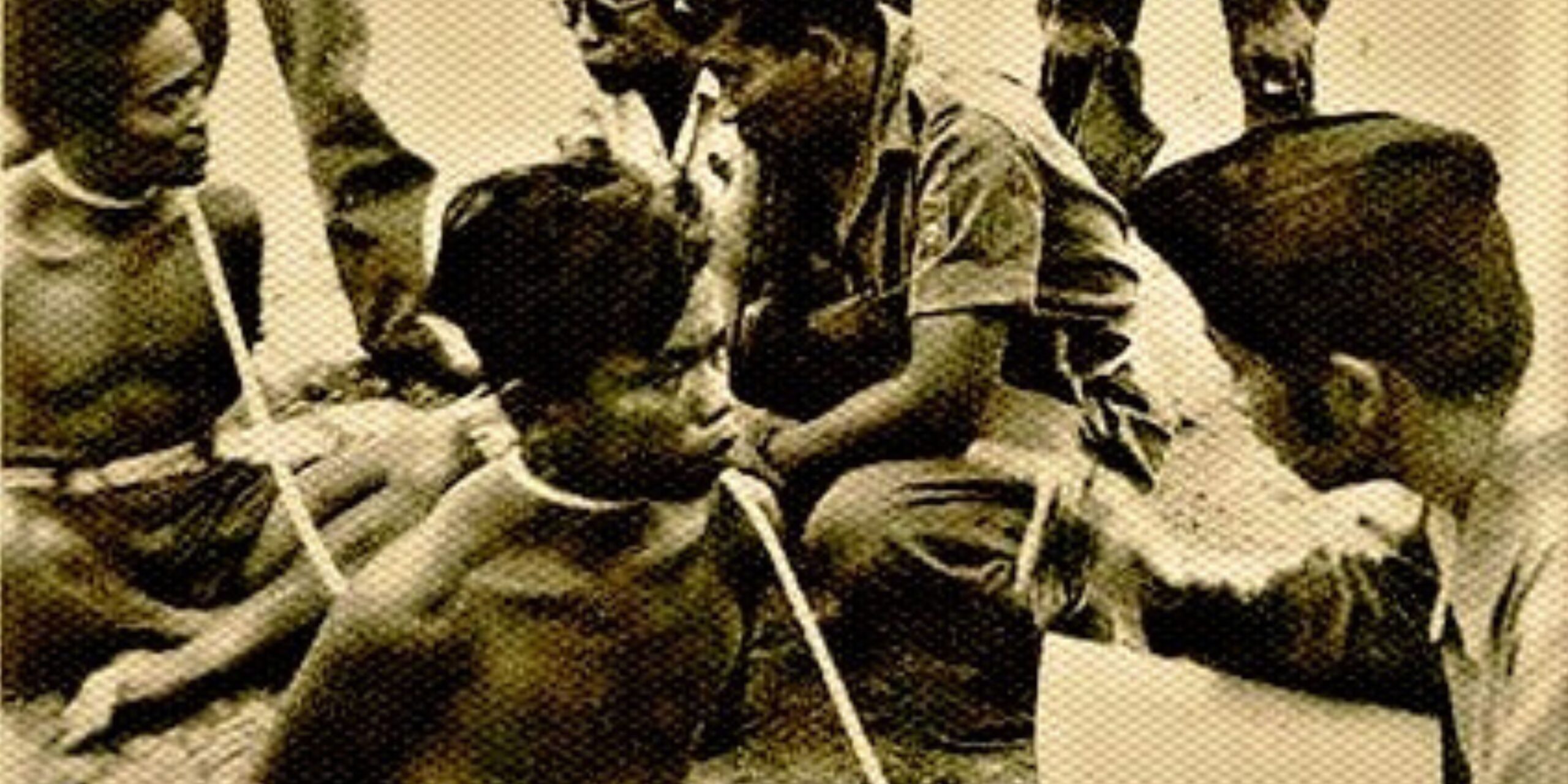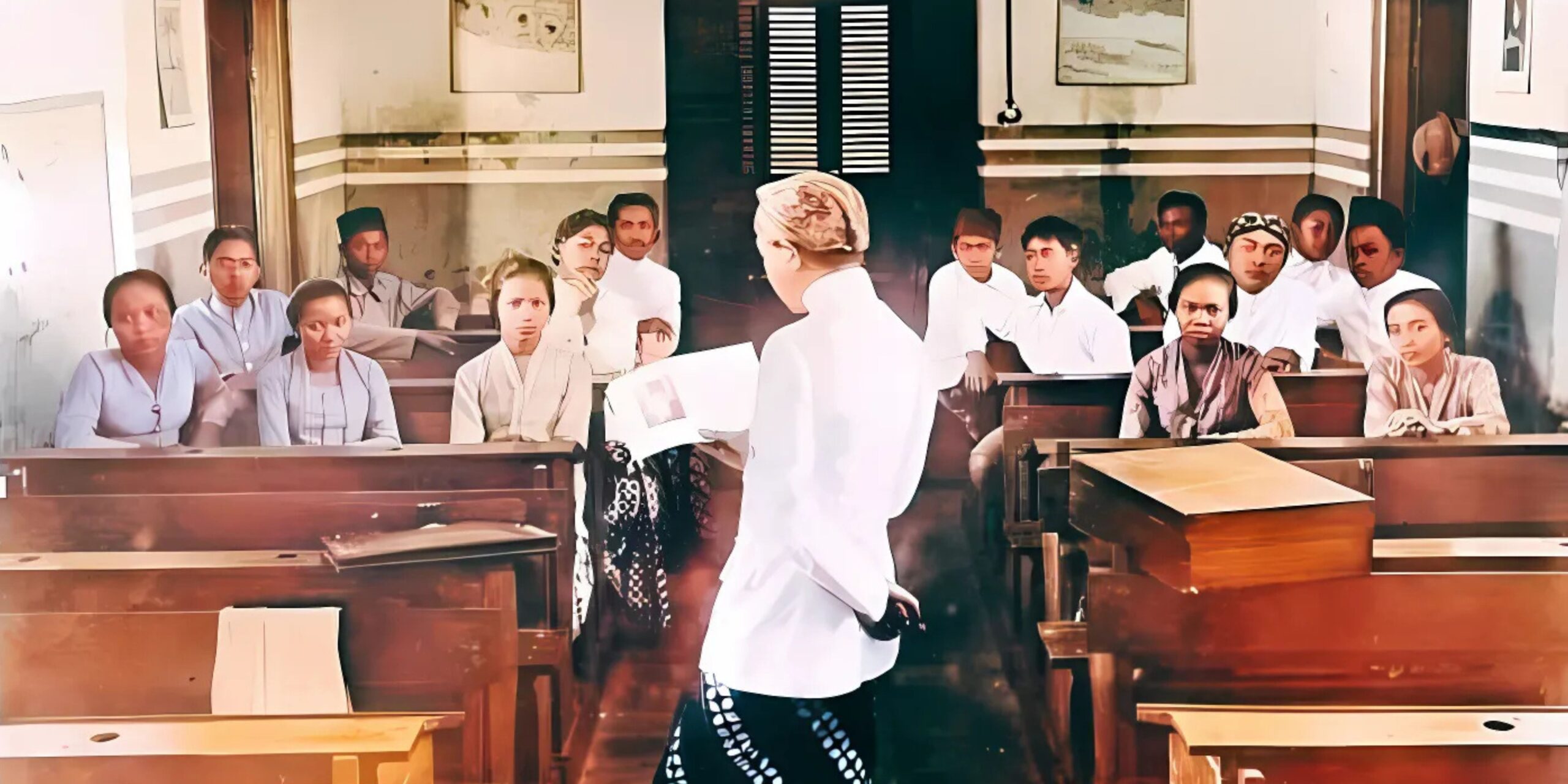Dari Sinar Laut: Mencari Akar Sejarah Lesbumi
Pada suatu sore yang sejuk di Desa Grogol, Kecamatan Giri, saya bersilaturahmi ke kediaman KH. Nur Salim. Di usianya yang sudah 77 tahun, beliau masih cukup lancar berbicara. Ada banyak kenangan yang bisa diceritakan meski...