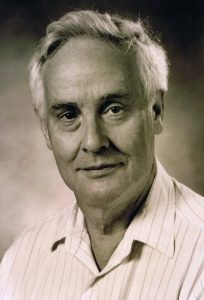Suatu ketika, saya berkesempatan mengunjungi perpustakaan Mangkunegaran, Solo. Biar kelihatan ngintelek, saya serius menanyakan dokumen yang ditulis saat Pangeran Mangkunegoro alias Sambernyowo, pendiri Mangkunegaran, masih jumeneng. “Wah silahkan saja, Mas. Monggo dilihat-lihat,” sila abdi dalem yang menunggu perpustakaan ”hanya, apa njenengan bisa baca aksara jawa?” Saya geleng kepala sambil cengengesan, plus satu kata sakti mandraguna: ”lupa!”. ”Wah gimana tho, Mas? Sekolah tinggi-tinggi kok ndak bisa baca aksara sendiri? Lupa…”, sindir abdi dalem itu.
Saya yakin, saya tidak sendirian. Banyak masyarakat Jawa lainnya yang seperti saya. Tak mampu membaca huruf yang tertera di prasasti, media yang membawa pesan dari masa lampau, namun sangat mampu membaca headline dari New York Times. Bahkan masyarakat Jawa barangkali mampu melafalkan headline itu dengan sangat sempurna; seakan lidahnya sudah rasa Amerika.
Tulisan ini adalah refleksi saya pribadi atas ketercerabutan pengetahuan/kebudayaan Jawa dari diri saya. Ketercerabutan itu tidak melulu perkara kita menggandrungi praktik seni budaya tertentu lalu melupakan seni sendiri, tetapi juga sesederhana apa aksara yang saya gunakan dalam keseharian. Ketercerabutan itu adalah praktik dari imperialism kebudayaan yakni “praktik dominasi dalam hubungan budaya dimana nilai, praktik-praktik dan makna-makna dari budaya luar yang kuat dipaksakan kepada satu atau lebih budaya asli”. Tugas tulisan ini saya batasi untuk sekadar membuktikan bahwa imperialisme budaya tidak hanya melalui isi atau ideologi di balik praktik kebudayaan tersebut, melainkan juga masalah teknis (teknologi) berupa aksara yang seringkali diabaikan.
Kuasa Jawa dan Pembatasan Tulisan Masa Lampau
Raffles dalam History of Java mengatakan bahwa teraturnya administrasi tulisan pada abad 8 di Jawa menjadi pertanda akan munculnya peradaban. Aksara, dengan demikian, juga terhubung dengan pengaturan dan/atau kekuasaan. Pergantian dari aksara Pallawa dengan, misalnya, aksara Arab menandakan adanya kuasa yang berganti. Harold Innis, sejarawan komunikasi dari Kanada, juga menegaskan hubungan aksara dengan masalah pengaturan kekuasaan. Misalnya, pergantian hieroglif Mesir (tulisan symbol) menjadi aksara hieratik adalah karena administrasi kekuasaan Mesir yang kemudian membutuhkan penulisan yang lebih cepat dan efisien.
Aksara, dengan demikian, tidaklah netral. Aksara yang berlaku di Jawa terkait dengan bagaimana mode kekuasaan dijalankan, sehingga memengaruhi disiplin tulisan, atau penggunaan aksara di masa lampau Jawa.
Adalah mungkin untuk menyatakan bahwa menurut cara pandang lama di Jawa, segala hal terpusat pada raja. Kita akan kesulitan untuk membagi bidang-bidang pengetahuan; misalnya menjadi bidang hukum atau bidang agama, karena bagaimanapun teks-teks penulisan dari masa lama, biasanya merupakan percampuran dari penceritaan raja, hukum, juga agama. Raja/penguasa sendiri dianggap mempunyai relasi dengan ketuhanan. Ini terlihat dalam konsep raja-dewa masa Syiwa Buddha, atau konsep darah genealogis dari Muhammad, sebagai pemimpin keagamaan dalam masa Islam.
Isi narasi dari teks yang ditulis selalu berurusan dan berpusat pada raja. Teks-teks tersebut biasanya fokus pada peristiwa kanonik istana dimana aktornya adalah raja, urusan rumah-tangga, atau undang-undang/norma/prinsip hidup yang menjadikan praktik eksistensi raja sebagai sumber hukum. Tulisan adalah monopoli pemimpin, sebab ia dipandang sebagai ‘sudah haknya’. Sehingga barangkali, ciri pertama bagi tulisan dalam masa lampau Jawa dan persebarannya adalah selalu terpusat pada raja dan pembantunya.
Ketika kekuasaan ini dihubungkan dengan agama atau praktik religius, hubungan ini menyediakan sebuah hal khusus yang terkait dengan disiplin penulisan; sebuah metode yang sama sekali tidak dikenali—dan hampir tidak pernah bisa dihancurkan—oleh pengetahuan modern, yakni laku asketik. Entah dengan semedi atau laku tirakat yang kadang berelasi dengan adanya guru gaib, entitas spiritual yang tidak terlihat tapi diyakini memberikan pengetahuan bagi orang Jawa. Hal ini menjadi ciri kedua dari tulisan atau penggunaan aksara di Jawa masa lampau.
Suatu uraian mengenai peran semedi dapat ditemukan di serat Hariwangsa, karya Mpu Panuluh pada abad ke-12. Sesudah melukiskan keratonnya sebagai inkarnasi Wisnu, pengarang kemudian menjelaskan tujuan karya itu, yaitu untuk “membantu mempromosikan ketakterkalahan raja dan kemakmuran dunia”. Pengarang mempertalikan inspirasinya pada dua sumber; raja, yang merupakan pangeran di antara penyair maupun raja universal, dan praktek semedi dan asketisme.
Sebelum menulis serat Hariwangsa, pujangga penulisnya melakukan perjalanan ke puncak sebuah gunung, dengan maksud sungguh-sungguh menyembah Wisnu. Tujuannya adalah untuk membangun kontak langsung dengan Tuhan dan dengan demikian kekuatan magis yang diperolehnya akan membantunya dalam menulis karya sastranya. Selanjutnya, ia melakukan serangkaian ziarah yang panjang, dan akhirnya terjatuh kelelahan karena demikian keras latihan-latihan asketiknya.
Ketika Islam masuk Jawa, penyalinan tangan teks Al-Quran ke dalam sebuah manuskrip, misalnya, selalu dibarengi dengan kegiatan asketis; puasa atau tirakat. Barangkali juga, disiplin ini masih dipraktikkan hingga sekarang, meski dengan narasi legitimasi yang lain.
Dominasi perilaku asketis sebagai metode ini tidak hanya berelasi dengan eksistensi raja dengan aparat keagamaan (raja bahkan menjadi “sayidin panatagama”), akan tetapi juga pada bagaimana pilihan strategi distribusi tulisan.
Sistem pengetahuan Jawa lama biasanya ditandai dengan ketiadaan budaya tulis, meski sebenarnya tulisan ada tetapi ‘dibatasi’ sehingga membuat budaya lisan dominan. Pembatasan tulisan bukan karena bahan material tulisan tidak ada (sebab pada dasarnya tulisan tidak hanya mempunyai basis material kertas atau buku), akan tetapi disiplin yang dikembangkan menuntut adanya pembatasan tulisan dimana salah satu yang terpenting adalah disiplin asketis.
Pendeknya, di dalam sistem pengetahuan lama, pengetahuan itu ‘hidup’ dan ‘datang’ ketika dibutuhkan, tentunya dengan cara atau laku asketis. Kalaupun ada teks empiris, ia akan dimengerti sebagai hal yang berhubungan dengan laku asketis. Mungkin bukan saja karena itu lakunya, akan tetapi laku asketis diperlukan untuk memperkuat status teks empiris yang tidak “lebih penting” daripada “data hidup” guru gaib. Laku asketis tidak hanya berelasi dengan masalah “intensitas penggunaan tulisan”, akan tetapi juga kepada “status kebenaran tulisan”.
Aksara Latin dan Kolonialisme
Persebaran pengetahuan modern di Jawa ditandai dengan masuknya aksara/tulisan latin yang dikenalkan oleh kolonial. Kemampuan baca-tulis aksara latin, menurut Mikihiro Moriyama, peneliti Sunda, tak lepas dari ilham buku-buku sekolah yang terbit di bawah pengawasan pemerintahan kolonial (Belanda). Namun apa yang paling penting dari aksara latin adalah bukan hanya bentuknya. Ia membawa bentuk disiplin tulisan yang lain. Sebuah pengetahuan (knowledge) mengenai tulisan (menulis dan membaca) khas modern yang sangat berbeda dengan disiplin tulisan dalam sistem knowledge lama, seperti dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya.
Persebaran buku bacaan bukan hanya mengenyahkan manuskrip, akan tetapi juga menghilangkan secara perlahan-lahan cara pandang lama terhadap tulisan. Status guru gaib yang dalam pengetahuan lama merupakan alat pengetahuan, dikategorikan tidak empiris dan kemudian “tidak benar”. Sebelum orang Eropa tiba, manuskrip dianggap keramat, ia berrelasi dengan tindak asketis. Akan tetapi orang Eropa, dalam laporan Gonggrijp misalnya, membacanya dengan pandangan yang lain;
“Dhoeloe-kala sabeloemnya orang tahoe ilmoe menera itoe, maka segala kitab djoega tersoerat dengan kalam. Koetika itu segala kitab terlalo mahal arganya dan adalah sedikit orang sadja jang mengerti membatja dan toelis. Tetapi pada sakarang ini Kangdjeng Goebernemen mengaloewarkan kitab yang moerah sakali sopaja orang beroleh goena deri pada batjanja itoe”
Gonggrijp melihat bahwa tulisan adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Ia lalu menghubungkan kuantitas produksi tulisan dengan kemampuan membeli masyarakat terhadap tulisan tersebut.
Tulisan tidak akan berarti jika tidak ada kemampuan membaca sehingga praktik pembacaan pun kemudian turut dibicarakan oleh kolonial. Van der Chisj menulis:
“Penduduk Bumiputera mengenal dua cara membaca; pertama, dengan cara seperti kita, bedanya mereka jarang memahami tujuan resitasi; kedua, membaca dengan cara menyanyikannya (nembang maca). Mereka hanya menggunakan cara pertama, apabila cara kedua tidak mungkin, karena bagi mereka cara kedua pasti sangat digemari dan betul-betul dirasakan sebagai cara yang benar.”
Kemudian, Van der Chijs menemukan apa yang disebutnya sebagai ’pembacaan mekanik’, dimana asumsi utamanya adalah masyarakat hampir tidak mengerti apa yang mereka baca kecuali jika mereka menyanyikannya. Yang mengingatkan kita pada pembacaan Alquran (bahkan hingga sekarang), dimana alquran dibaca tanpa mengerti artinya.
Sangatlah sukar mengharapkan adanya ’interpretasi’ (dalam kerangka rasional-modern) dalam kegiatan membaca di epistem lama, kecuali untuk beberapa aparat epistemik yang terdapat di lembaga agama seperti mandala atau pesantren. Masyarakat dengan pola lama, tidak membutuhkan adanya pengertian, akan tetapi perasaan ketika terhubung dengan bacaan. Pengertian menurut mereka bukanlah pemahaman rasional, akan tetapi sebuah penghayatan dan pengalaman akan “rasa”. Mungkin seperti apa yang disebutkan oleh Manilowski bahwa “fondasi-fondasi kepercayaan dan praktek-praktek tidaklah berasal dari isapan jempol belaka, melainkan bersumber pada serangkaian pengalaman yang sungguh dihayati”
Lembaga yang paling berperan mengangkat elemen-elemen pengetahuan baru seperti status tulisan empiris dan tipologi pembacaaan rasional, sekaligus juga menghancurkan gaya pengetahuan lama, tentu saja adalah sekolah. Meski, dalam beberapa waktu yang lama, ia harus berhadap-hadapan dengan aparat/institusi dalam cara pandang lama; pesantren dan madrasah (dua lembaga Islam, dua lembaga yang dekat juga dengan laku asketis).
Pada Mei 1871 Departemen Pendidikan, Agama dan Industri mengeluarkan Keputusan Pokok Pendidikan yang menghasilkan dua perubahan penting dalam kebijakan kolonial di bidang pendidikan. Pertama, pemerintah bertanggung jawab atas pendidikan setiap orang, tidak hanya dari golongan Bangsawan Bumiputera saja. Kedua pendidikan harus diberikan dalam bahasa-bahasa daerah (Volkstalen) dan apabila di tempat-tempat tertentu hal ini tidak mungkin dilaksanakan, maka pengajaran harus memakai bahasa Melayu.
Kegiatan penulisan juga berubah. Jika sebelumnya ia lebih dekat pada tindakan asketis, maka pada masa kolonial ini, menulis adalah sebuah kegiatan yang bisa dilakukan semua orang, dimana saja dan kapan saja. Untuk latihan menulis, digunakanlah batu tulis dan kapur. Kertas masih merupakan barang mahal pada abad ke-19. Murid-murid menulis abjad di atas daun pisang (pisang-blad) dengan pena bulu unggas yang diruncingkan. Dua bahan itu murah, didapat dengan mudah, dan murid dapat berlatih mengarang dan menulis indah, demikian menurut Van Der Chijs.
Belanda, tulis Moriyama kemudian, secara berangsur-angsur coba mengajari mereka budaya membaca dalam hati. Berdasarkan pengalaman para murid mendaraskan Alquran, tuan-tuan kolonial itu menduga bahwa melagukan teks menghambat pemahaman pada isi. Mereka percaya bahwa pelajaran yang disampaikan dengan “budaya membaca dalam hati” akan membawa hasil, dan “pembaca modern” akan terbentuk
Dengan demikian, cara pandang lama yang persebarannya terpusat pada lingkungan istana (raja dan pujangga) digantikan oleh pengetahuan modern yang disebarkan secara merata, tidak hanya pada lingkungan istana. Serta-merta, tindak asketis, yang mengandalkan pada “olah rasa”, kemudian dinilai sebagai mitos atau irasional atau supra-empiris.
Aksara sebagai bentuk Imperialisme Kebudayaan
Monumen penting dari penerimaan masyarakat kita pada aksara adalah peristiwa 28 Oktober 1928; Sumpah Pemuda. Sumpah yang menyatukan masyarakat di Nusantara, termasuk Jawa, menjadi satu kolektivitas modern bangsa (Indonesia) dan bahasa yang satu yaitu bahasa Melayu yang sudah diganti namanya dengan “bahasa Indonesia. Pertanyaannya adalah: apa aksaranya?
Artinya, Sumpah Pemuda mengikrarkan beberapa perkara dengan jalan menyembunyikan perkara lainnya. Kebungkaman Sumpah Pemuda ikhwal aksara diperoleh dengan menganggap selesai perihal aksara. Hal ini menegaskan aksara latin yang telah banyak dipakai sebagai “aksara Indonesia” yang melancarkan peminggiran aksara lainnya, misalnya aksara jawa, aksara sunda sebagai “aksara daerah” dan aksara arab sebagai “aksara agama”. Sumpah Pemuda adalah pencapaian paling sukses latihan dan disiplin aksara latin pemerintahan kolonial mulai tahun 1800-an melalui sekolah, surat kabar dan bentuk-bentuk praktik aksara latin lainnya.
Sementara Sumpah Pemuda bekerja dengan kebungkaman, lain halnya dengan novel “Sengsara Membawa Nikmat” karangan Tulis Sutan Sati yang kebetulan juga terbit perdana pada tahun 1928. Diceritakan bahwa seorang Midun yang alim dan bersahaja, masuk penjara karena ia cuma kenal aksara pegon arab. Ia tertipu akibat perjanjian yang ditulis dengan aksara latin. Ending-nya, setelah ia dilatih baca-tulis aksara latin oleh seorang narapidana di sebuah penjara, ia berhasil menjadi asisten demang. Dengan novelnya, Tulis Sutan Sati seakan-akan dengan tegas membilang bahwa “kesadaran” hanya bisa dimiliki dengan aksara latin. Aksara pegon arab (bawaan periode Islam) hanyalah membuat bangsa ini tertipu seperti Midun.
Alih-alih mengantarkan bangsa ini mengenali bagaimana bangsa yang hidup di Nusantara ratusan tahun lalu, aksara latin sekaligus memungkinkan kita untuk terus belajar pada bangsa asing. Cukup dengan satu kali pemindahan huruf, maka logika orang Indonesia akan berganti dengan logika orang Inggris. Aksara, yang menjadi modal pengetahuan kita, lebih memudahkan kita belajar pada bangsa yang menggunakan latin. Aksara latin, disadari atau tidak, adalah tahap awal penyatuan “Indonesia” dengan globalisasi barat sebagai pusat dari “imperium aksara latin”. Kalau sudah begitu, meski kita memandang sinis Sutan Takdir Alisjahbana yang mengusulkan pengadopsian kebudayaan barat sebagai model kebudayaan Indonesia dalam Polemik Kebudayaan, pada kenyataannya, usulan itu sudah kita lakukan.
Epilog
Hingga pada tahun 1990-an, saya masih merasakan praktik huruf pegon arab dengan bahasa Jawa di madrasah sore desa saya. Saya juga masih ingat ketika belajar tajwid melalui bahasa Indonesia dengan huruf pegon arab di sebuah quran terbitan Semarang. Bisa jadi, sekarang pun, huruf pegon arab masih dipraktikkan di banyak pesantren-pesantren tradisional untuk sorogan bersama kyai. Nasib Aksara Jawa setali tiga uang dengan aksara pegon. Di SD saya, ia ‘tersingkir’ cuma sebagai ‘sub bahasan’ dalam pelajaran “Boso Jowo”. Masih mending, jika siswanya mengerti dan serius. Kalau muridnya seperti saya, 20 aksara ditambah pasangannya itu paling-paling cuma jadi bahan hafalan saja.
Sekali lagi, tugas tulisan ini adalah untuk menunjukkan bagaimana instrumen teknis seperti aksara menjadi alat imperialisme dan dominasi, bukan untuk kemudian mengajak kembali menggunakan aksara tertentu. Tulisan ini tidak berusaha menyarankan misalnya masyarakat Jawa kembali menggunakan aksara Jawa untuk melawan dominasi aksara latin. Toh tulisan ini telah memperlihatkan bagaimana penggunaan aksara Jawa di masa lampau, merupakan bentuk dominasi atau pengaturan kekuasaan yang juga layak untuk dilawan. Pun, kalau tulisan ini mengajak demikian, tulisan ini ambigu, karena ditulis dengan aksara latin. Tapi biar tidak dinilai tidak memberikan apa-apa, barangkali tulisan ini adalah untuk mengingatkan kembali kebijakan yang perlu di jaman Kalatidha; Sak beja-bejane wong sing lali, isih beja kang eling lan waspada.