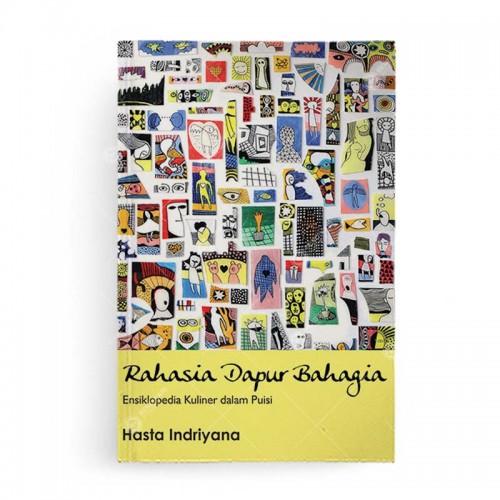Cipasung, Komunitas Pesantren, dan Arus Perubahan
Duniakah yang berubah atau manusia sendiri yang senantiasa berubah. Dari manakah serangkaian terjadinya awal mula perubahan. Apakah ia sebuah gerak zaman tak terhindarkan, atau sebuah...
Duniakah yang berubah atau manusia sendiri yang senantiasa berubah. Dari manakah serangkaian terjadinya awal mula perubahan. Apakah ia sebuah gerak zaman tak terhindarkan, atau sebuah keharusan yang dihadapi manusia untuk bisa bertahan hidup. Lalu pikiran ini berkesimpulan, bahwa satu-satunya kepastian mutlak di dunia ini adalah perubahan. Dan manusia senantiasa dihadapkan pada anomali ketidakpastian. Maka, manusialah yang berubah.
Sebagai seorang yang menghabiskan masa kecilnya di lingkungan sekitaran pesantren, pada batas pengembaraan hidup, saya terhempas oleh kerinduan akar masa kecil bermain di pekarangan pesantren. Sesekali kerinduan itu terdengar memanggil dalam sayup-sayup suara nadom menjelang Magrib, atau suara Marhaba Barzanji di kala malam. Ibarat sebatang pohon yang telah tumbuh dan menjulang seiring waktu yang didapatkan, juga beribu musim yang telah dilalui, lalu ia merindu kembali pada akar benih pemberian para pendahulunya.
Tetibanya di akhir masa perkuliahan, saya dipertemukan dengan seseorang yang mengajak saya ke pondok Cipasung. Sebuah pondok yang menjadi pusat di jantung Kabupaten Tasikmalaya. Corak ragamnya sama dengan pondok-pondok lain di Jawa, seperti Tebuireng, Krapyak, Tegalsari. Penamaan pondok sekaligus mewakili nama daerah tempat pondok berada. Ia tidak memisahkan diri dengan ragam masyarakat sekitar. Di samping itu, pesantren turut mengiringi peralihan zaman, dengan memberanikan dan mencontohkan diri sebagai basis moral masyarakat. Di dalamnya terdapat Kiai atau Ajengan, sebagai simbol kuasa sekaligus subjek moral.
Semerbak aroma Shattariyah tercium senyap, saat Kh. Ruhiyat memilih “Ngaji” sebagai jalan tarikat. Oleh karena memilih ngaji sebagai lakon hidup, di samping ngaji kitab-kitab kuning, maka para pendiri Pondok Cipasung turut melibatkan diri di pusaran perubahan kehidupan berbangsa.
Tercatat Kh. Ruhiyat ikut andil menggerakan diri dan masyarakat di peralihan masa kolonial menuju kemerdekaan Indonesia. Sejak diprakarsai oleh Kh. Hasyim Asy’ari, yang menyerukan bahwa membela bangsa merupakan bagian dari jihad Islam sebagai proto-nasionalisme. Pun di masa awal geliat Indonesia merdeka, yaitu saat mulai munculnya gerakan-gerakan Darul Islam di berbagai daerah, terutama di Jawa Barat, Kh. Ruhiyat tetap teguh memegang prinsip negara kesatuan berbentuk republik hasil konstituante.
Begitu pula dengan KH. Ilyas Ruhiyat, sebagai penerus setelah KH. Ruhiyat, di tahun 1994 turut menjadikan Cipasung sebagai tempat Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27. Tahun genting yang dinilai Gus Dur sebagai masa puncak kesewenangan pemerintahan Orde Baru. Gus Dur yang pada saat itu menjadi sasaran penjegalan operasi, mampu diredam dan dicegah dari operasi target pasukan Suharto. Sebelum keadaan semakin memburuk, dan memuncak pada Mei 1998.
Pesantren sebagaimana kita tahu, merupakan bentuk baru dari tatanan pendidikan lama yang berupa ashram, atau mandala. Fungsi utama keduanya tetap sama, yaitu pendidikan moral.
Pesantren sebagaimana kita tahu, merupakan bentuk baru dari tatanan pendidikan lama yang berupa ashram, atau mandala. Fungsi utama keduanya tetap sama, yaitu pendidikan moral. Karena fungsi utamanya adalah pendidikan moral, maka hal pertama diajarkan sejak belia adalah mengenai budi pekerti. Karena budi pekerti ini yang mengantarkan dan mengintegrasikan satuan utuh setiap diri dalam keberagamaan serta kemanusiaannya, yaitu; iman, islam, dan ihsan.
Rasul Muhammad dalam keterangan hadits termaktub, bahwa sesungguhnya ia diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di kepulauan Nusantara, Islam diwartakan risalahnya salah satunya melalui jalur dagang yang berporos di selat Malaka. Selat ini, lambat laun terus berkembang keterhubungannya dengan berbagai lintasan jalur rempah di hampir seluruh kepulauan Nusantara. Risalah Islam (syariat) yang disampaikan terus menyebar, karena dinilai berkesesuian dengan ajaran-ajaran pokok (tauhid) masa sebelumnya.
Di jalur rempah dan sutra, Islam kemudian berkembang dalam kebudayaan maritim. Nusa Jawa dalam silang budaya (Baca, Denys Lombard) sebelum menonjolnya kesan sebagai negara agraris, pada mulanya bercorak maritim. Anthony Reid menulis Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga1450-1680, mengatakan bahwa kepulauan Nusantara (Negeri di Bawah Angin) pada abad 16-17 M menjadi daerah yang paling urban, dan memiliki penduduk kota yang paling padat di dunia. Sementara, pada abad itulah Islam mulai menyebar dengan pesat di berbagai kota di Nusantara. Artinya, perkembangan Islam pada awal penyebarannya bersifat terbuka dan dinamis dengan arus perubahan.
Terbentuknya komunitas dagang yang berpusaran di selat Malaka, terletak bukan sebatas pengertian geografis yang strategis, namun karena kecakapan penguasa yang pada waktu itu mampu menciptakan komunitas dagang jejaring Islam, yaitu Syahbandar dari kesultanan Aceh. Hal ini kemudian diakui sendiri oleh Portugis, bahwa meskipun armadanya mampu menaklukan selat Malaka, tidak berarti ia bisa menciptakan komunitas dagang yang sudah terjejaring dan meresap sedemikian kosmopolit itu.
Hingga di kemudian masa, komunitas-komunitas dagang ini mulai merangsek ke pedalaman. Ia menemukan corak lokalnya yang telah mapan dalam kultur komunitas masyarakat lama, lebih tepatnya mandala yang kita sebut hari ini sebagai pesantren. Walisanga dikenal sebagai sosok-sosok yang telah menyiarkan Islam dan mempribumisasikannya, khususnya di masyarakat agraris desa yang berpusat di Jawa. Gerak kultural ke dalam ini terjadi seiring dengan semakin kuatnya pengaruh penguasaan Kolonial di jantung kekuasaan dan pusat-pusat kota.
Nancy K Florida dalam bukunya, Jawa-Islam di Masa Kolonial: Suluk, Santri, dan Pujangga Jawa (2020), menegaskan bahwa Islam di pedalaman lebih bercorak sufistik, dan oleh karenanya lebih bersifat fleksibel menerima ‘baju kebudayaan’ lain tanpa kehilangan nafas iman tauhidnya. Sehingga benar yang dikemukakan oleh Irfan Afifi, yang menegaskan bahwa corak keislaman kita hari ini cenderung menekankan pada syariat, sehingga kesulitan menerima standar ‘budaya’ yang lain.
Moral yang berlaku di komunitas-komunitas kultur lama, dan kemudian turut diserap oleh kultur pesantren adalah prinsip keutamaan, yaitu moral yang menekankan apa yang disebut eudaimonia, yaitu sikap laku-etis untuk mencapai hidup yang baik sebagai kausa final. Prinsip etika ini digunakan oleh masyarakat komunitarian yang telah berlangsung secara turun-temurun. Hukum nilai ini terbentuk oleh moral kultural berdasar nilai awal yang sifatnya partikular, kemudian menghasilkan konsensus baru berupa adat sebagai status moral dinamis yang universal.
Nilai moral universal bersifat dinamis dan transformatif. Para cantrik atau santri merupakan kaum terpelajar, yang akan terus menerus memperbaharui konsensus adat seiring bergulirnya zaman. Cantrik atau santri, sedari dini sudah dilatih untuk selalu memperbaharui diri dalam setiap masa untuk menghadapi perubahan zaman, dalam pergumulan dirinya. Maka, nilai dari pergumulan kaum cantrik atau santri ini yang akan mentransformasikan dirinya di pusaran zaman yang terus berubah.
Nilai perubahan inilah yang dalam tesis seorang Arnold Toynbee, suatu peradaban baru akan muncul. A Study of History, buku babon sejarah abad ke-20 yang ditulisnya, Toynbee mengemukakan bahwa suatu peradaban bertransformasi dengan mengatasi tantangan luar, dan stagnasi internal. Peradaban timbul karena pola yang ia sebut sebagai tantangan dan respon, yang dilakukan oleh kreatif minoritas yang menginspirasi massa untuk kemudian meniru inovasi mereka.
Dan kita tahu, sependek yang tercatat dalam historiografi Indonesia modern, kreatif minoritas itu adalah para terpelajar (cantrik/santri). Terhitung sejak sumpah pemuda, proklamasi kemerdekaan, hingga reformasi di akhir masa orde baru. Kreatif minoritas terpelajar inilah yang membawa api sejarah semangat perubahan untuk zamannya. Para terpelajar yang berangkat dari komunitas-komunitas masyarakat (etnik) ini, kemudian menemukan keterjejaringannya dengan komunitas (etnik) lain, yang sama-sama memiliki visi yang sama. Kesamaan visi yang kelak tertuang dalam adagium Bhineka Tunggal Ika.
Para terpelajar yang berangkat dari komunitas-komunitas masyarakat (etnik) ini, kemudian menemukan keterjejaringannya dengan komunitas (etnik) lain, yang sama-sama memiliki visi yang sama. Kesamaan visi yang kelak tertuang dalam adagium Bhineka Tunggal Ika.
Lalu bagaimanakah pesantren sebagai bagian dari komunitas tersebut, mampu melakukan keterjejaringan dan keterhubungannya dengan komunitas-komunitas lain. Pesantren di kepulauan Indonesia, dengan segala kekayaan alam, keragaman dan kebhinekaannya, selain sebagai salah satu medium terbuka, para santri sedari awal sudah dilatih dan dididik dengan pola hidup asketis guna mencapai eudaimonia. Sehingga, ia akan mampu menciptakan jejaring kultural baru yang telah lama tercipta, dan menemukan pergulatannya serta persilangannya dengan situasi global. Dengan demikian, pesantren mampu menciptakan eudaimonia sebagai basis moral dan simpul perekat dari rukun ihsannya, yaitu kemanusiaan.
Maka sikap moral dari rukun ihsan kemanusiaan ini akan terjaga dari dekadensi dan penyempitan. Ia harus terus tumbuh mengarungi arus perubahan zaman. Karena hanya dengan hukum moral, dalam hal ini nilai agama yang diinternalisasi oleh komunitas pesantren, dapat menemukan universalitasnya. Sehingga, nilai moral yang diserap dari agama ini menjadi spirit kehidupan, sekaligus investasi masa depan (akhirat). Ia akan terus tumbuh dan bertransformasi mencapai kematangannya, dan tidak akan mengalami pemutlakan oleh para pemeluknya.
Kini, sudah melewati satu tahun, setelah pertemuan dan ajakan seorang teman yang mengantarkan ke Cipasung, saya tergabung dengan komunitas kecil yang belum lama ia dirikan bersama teman-temannya. Selama rentang waktu satu tahun itu pula, sisa waktu yang saya miliki, di samping aktivitas belajar sendiri dan babantu di rumah, pikiran saya tercurah di Cipasung. Mungkin, Cipasung sebagai simbol dan pusaran, berikut pondok-pondok lain yang melingkupinya di Tasikmalaya, yang menampung kesinggahan para santri untuk kembali ke akar jati dirinya. Sebuah kampung halaman, di mana para santri diingatkan lagi pada sayup-sayup suara nadom dan tembang. Mungkin juga, hanya dengan jalan menepi dan sejenak pulang, seorang santri bisa terjaga dan terselamatkan di batas jalan hidupnya yang tengah mengarungi arus zaman.
Tabik.