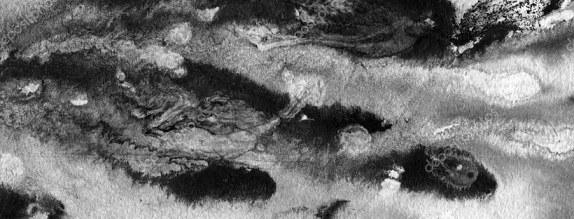Lautan Tinta Tak Pernah Cukup Untuk Menuliskan Kemahaan Allah
Duhai duka cita, Jika kau punya nyali, datanglah padaku. Maulana Rumi Imam At-Thusi niscaya gerah dengan situasi kesyariatan (sebagian) kita hari ini yang...
Duhai duka cita, Jika kau punya nyali,
datanglah padaku.
Maulana Rumi
Imam At-Thusi niscaya gerah dengan situasi kesyariatan (sebagian) kita hari ini yang semakin tuntas membuang ‘dimensi batiniah’-nya. Ia yang dikenal dengan sebutan Syekah at-Thusi tiada lain adalah Muhammad bin Hasan bin Ali bin Hasan, seorang ulama hadits dan fiqh terkemuka dari Iran, hidup di abad ke-9 M.
Kegerahan yang saya maksudkan ialah runtuhnya tahta batiniah syariat Islam yang seyogianya merupakan ruhaninya, nyawanya, jiwanya. Bagai robot, Anda bayangkan, begitulah kita berjalan bila tiada ruh di dalam jiwa kita. Tiada batinnya, hatinya.
Kendati ini perlu pendedahan lebih luas, saya terakan di sani satu saja dari kondisi problematis persyariatan kita hari ini, yakni trend ‘gila pahala’. ‘Gila syariat’ dalam artian semata amaliah lahiriah dengan menyingkirkan dimensi rohaninya.
‘Gila syariat’ dalam artian semata amaliah lahiriah dengan menyingkirkan dimensi rohaninya.
Tapi mari munculkan satu pertanyaan dulu: apa betul amaliah syariat mesti memuat dimensi kebatinannya? Bukankah amaliah syariat adalah lelaku –yang penting menjalankannya dengan taat?
Imam At-Thusi mengatakan bahwa syariat memuat dua dimensi, amaliah lahiriah dan laku batiniah. Yang pertama menampak dalam aktivitas nyata, seperti rajin shalat jamaah, gemar ngaji al-Qur’an, rajin puasa, sedekah, dan sebagainya. Persoalan apakah di hati para pelaku amaliah syariat tersebut terjadi sublimasi nilai amaliah shalatnya yang menjiwai semua pemikiran dan perilakunya di luar konteks ibadah shalat itu, hal itulah yang dimaksud ruhaninya, batiniahnya syariat Islam.
Jamak kita mengerti dari al-Qur’an, misal, bahwa (amaliah) shalat berguna untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Menjalankan shalat di satu sisi adalah amaliah lahiriah syariatnya dan keberhasilan mensublimasikan nilai filosofis takbir, rukuk, sujud, hingga salam merupakan kerja dimensi batiniahnya.
Takbir merupakan seruan pengagungan Allah Swt. Semata. Tiada yang Agung selainnya. Termasuk diri pelaku shalat. Salam pun tiada lain ialah tebaran kebaikan dan kemaslahatan.
Korelasi antara agungnya Allah Swt yang artinya menegasi tegaknya diri secara sosial ternisbatkan dalam praktik kebaikan-kebaikan kepada sesama dan bahkan alam semesta. Begitu.
Tamsil kecil ini menjelaskan bahwa urgensi capaian sublimasi kebatinan shalat pada diri seorang pelaku amaliah shalat akan sangat menentukan seberapa soleh dia bukan hanya secara penegakan ritual tersebut tetapi sekaligus lelampah sosialnya. Logis sekali al-Qur’an menguntaikan fungsi shalat mencegah pelakunya dari kekejian dan kemungkaran.
Sekarang mari kita lanjutkan dengan menyoal diri dalam praktik berislam yang tentunya semua kita memaksudkannya sebagai jalan taqarrub kepada Allah Swt.
Bagaimana Allah kita definisikan? Terjemahkan? Kemudian menjad mindset dan ontologi di dalam kehidupan keseharian kita?
Kepatuhan kita menjalankan amaliah syariat shalat, satu contoh saja, tentulah patut kita syukuri. Itu tanda nyata bahwa kita memenuhi perintahNya. Namun, gerangan bagaimana Allah Swt kita pahami, bahkan tatkala kita sedang menjalankan syariat shalat?
Al-Kahfi 109 –di ayat lain juga tertera dalam Luqman ayat 27—mengilustrasikan dengan menunjam: umpama lautan dijadikan tinta lalu dengannya kita menuliskan kalimat-kalimat Allah.
Al-Kahfi 109 –di ayat lain juga tertera dalam Luqman ayat 27—mengilustrasikan dengan menunjam: umpama lautan dijadikan tinta lalu dengannya kita menuliskan kalimat-kalimat Allah (yakni, mendefinisikan dan menerjemahkan Allah Swt dalam bahasa manusia), akan keringlah lautan tinta itu sebelum Allah Swt usai dituliskan. Bahkan jika didatangkan satu lautan tinta lagi sepertinya.
Saya merenungkan takwil ilustratif tersebut dengan cara begini: suatu hari duduklah saya di sebuah pantai terpencil di Pacitan, menghadap laut. Ombak bergulungan tanpa lelah. Menyentuh kaki saya. Sesekali saya jamah air laut berbuah itu dalam genggaman kedua telapak tangan saya.
Saya mulai menuliskan kesan rohani saya tentang Allah. Saya ambil segenggam air laut lagi. Saya tuliskan lagi di atas pasir. Lagi. Lagi. Lagi. Hingga saya tumbang terlentang. Dan air laut itu tak berkurang secuil pun. Dan nama-nama agung Allah Swt yang berdenyar di dalam pikiran dan hati saya tak kunjung berkurang. Jangankan habis, berkurang saja tidak. Malah semakin melimpah, meruah, membah.
Kini bagaimana mungkin saya menghabiskan air lautan itu? Mustahil. Bahkan untuk mengurangi saja kesan-kesan rohani saya tentang Allah tiada mampu.
Lalu, seketika saya merasa malu sendiri: apa gerangan hak otoritatif saya untuk menyatakan Allah Swt adalah begini, bukan begitu, seperti ini, bukan seperti itu, sesuai pendapat saya, bukan pendapatmu dan pendapatnya?
Bagaimana bisa saya berani mengkungkung Allah Swt dalam suatu definisi yang berkelebat di kepala saya, pikiran saya, hati saya, entah atas pembacaan saya pada suatu teks ataupun hasil dengar saya pada suatu pengajian langsung atau online, padahal bahkan pada diri saya sendiri pun takwilnya amat tak terbatas –apalagi pada takwil orang lain, kelompok lain, hati orang lain, pengalaman orang lain, worldview orang lain?
Bagaimana bisa saya berpongah hati atas pandangan dan keyakinan saya terhadap definisi tentang Allah Swt?
Bagaimana bisa saya berpongah hati atas pandangan dan keyakinan saya terhadap definisi tentang Allah Swt?
Bagaimana lalu saya jemawa menegasi pandangan dan keyakinan orang lain yang tak sama dengan pandangan dan keyakinan saya?
Tegasnya, bagaimana berani lancangnya saya mereduksi kemahaan Allah Swt?
Untuk itulah, kiranya di hadapan Allah Swt dalam segala pandangan, tafsir, takwil, dan resepsi setiap kita tiada lain yang paling patut untuk kita kedepankan dalam kebersamaan kecuali kerendahan hati untuk menerima realitas mejemuk taqarrub ilallah itu sebagai bukti keagunganNya. Usaha menepis realitas tersebut jelas bertentangan dengan sunnatullahNya, kehendakNya, fakta-fakta kemahaanNya.
Ada Uwais al-Qarni yang mengabdikan hidupnya untuk merawat ibunya yang lmpuh. Itu adalah satu jalan taqarrub kepada Allah. Ada Imam Syafii yang mengabdikan hidupnya kepada ilmu pengetahuan Islam, itu satu jalan taqarrub kepada Allah. Ada Imam Busiri yang mengabdikan hidupnya pada cinta kepada RasulNya, itu satu jalan taqarrub kepada Allah. Ada Rabiah Adawiyah yang mempersembahkan hidupnya untuk hanya mencintai Allah dalam segala keadaan, suka dan duka, itu satu jalan taqarrub kepada Allah. Ada Maulana Rumi yang berpilin dalam tarian semanya, itu satu jalan taqarrub kepada Allah. Ada Quraish Shihab yang mengabdikan hidupnya untuk menafsir al-Qur’an, itu satu jalan taqarrub kepada Allah. Ada orang-orang yang mengabdikan hidupnya untuk menfghafal al-Qur’an, menghafal hadits-hadits, memberikan pengajian-pengajian menenteramkan, bersedekah, itu semua merupakan satu jalan taqarrub kepada Allah.
Ada yang melukis, menulis, menari, bermusik, dalam spirit merayakan kemahaan Allah Swt, itu satu jalan taqarrub kepada Allah.
Ada orang yang bertani dan menemukan Allah dalam setiap desah napasnya, itu satu jalan taqarrub kepada Allah. Ada yang berbisnis dengan spirit tolong-menolong, itu satu jalan taqarrub kepada Allah. Ada yang menjadi abdi negara untuk melayani masyarakat, itu satu jalan taqarrub kepada Allah. Ada yang menjadi guru untuk mengajari iqra’ hingga bahasa Inggris, itu satu jalan taqarrub kepada Allah. Ada yang melukis, menulis, menari, bermusik, dalam spirit merayakan kemahaan Allah Swt, itu satu jalan taqarrub kepada Allah. Dan sebagainya, dan lain sebagainya, dan segalanya, yang tak mungkin kita mampu jangkau semuanya bahkan dengan imajinasi terluas dan terjauh yang mungkin kita peluk.
Begitulah lautan kemahaan Allah, kalimatullah, memancar ke alam raya ini, kepada setiap kita, dengan jalan masing-masing. Semuanya adalah bagian dari air laut itu, bagian dari kalimat-kalimatNya.
Pada akhirnya, apa pun jalan yang kita temukan, genggam, dan lakonkan, begitulah Allah mengejawantah pada hidup kita. Bertajalli. Bahkan tatkala mata kita menyaksikan suatu kemaksiatan kepadaNya, Allah pun ada di sana….
Jakarta, 3 Februari 2019