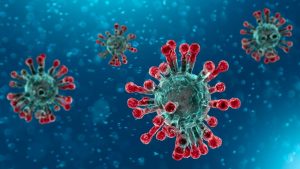Melodia Umbu Landu Paranggi
Sebuah pesan disampaikan Mira MM Astra—penyair asal Bali—kepadaku, kurang lebih begini: “Kamu harus belajar musik”. Bagiku, pesan itu terlalu pendek. Tapi, aku tidak bisa meminta...
Sebuah pesan disampaikan Mira MM Astra—penyair asal Bali—kepadaku, kurang lebih begini: “Kamu harus belajar musik”. Bagiku, pesan itu terlalu pendek. Tapi, aku tidak bisa meminta penjelasan dari pesan itu setelah Mira MM Astra mengungkapkan bahwa dirinya hanyalah penyampai pesan dari pembuat pesan. Aku terkejut mengetahui pembuat pesan adalah Umbu Landu Paranggi—penyair asal Bali. Entah kenapa, gara-gara mengetahui nama Umbu Landu Paranggi, aku menganggap pesan itu sebagai masukan untuk proses kepenyairan.
Aku lupa tahun berapa Mira MM Astra menyampaikan pesan dari Umbu Landu Paranggi. Yang jelas, aku masih berstatus mahasiswa, barangkali antara tahun 2016 s.d. 2017. Dan, aku menyetujui pesan itu, meski tidak memahami belajar musik. Apalagi, aku tidak memiliki kemampuan bermusik, yaitu: menyanyikan lirik lagu dan memainkan alat musik. Perihal mendengarkan lagu, aku hanya menerima apa saja. Toh, aku tidak betul-betul menggandrungi lagu yang dibawakan penyanyi atau grup band tertentu.
Sial, memang, pesan dari Umbu Landu Paranggi terlalu “gelap” untuk aku amalkan. Sehingga, aku memahami musik sebatas terombang-ambing suasana akibat lagu yang disetel orang lain, misal mendengar lagu dangdut di kabin bis antar provinsi. Atau, aku terhanyut oleh lagu tema pada sebuah tontonan. Padahal, dalam terombang-ambing serta terhanyut, aku bisa saja menghapalkan lagu yang terdengar, atau menelisik unsur lagu yang menempel di telinga, tapi aku enggan menganggap hal tersebut sebagai belajar musik.
Pada 6 April 2021, Umbu Landu Paranggi meninggal di RSUD Bali Mandara. Dunia sastra Indonesia berduka. Para sastrawan berbelasungkawa di media sosial. Juga, beberapa sastrawan mengenang pribadi Umbu Landu Paranggi lewat kisah. Meski tidak pernah bertemu, aku turut mengenang Umbu Landu Paranggi sebagai pengamat yang mengharapkan potensi penyair. Contoh harapan potensi penyair adalah pesan dari Umbu Landu Paranggi yang disampaikan Mira MM Astra kepadaku.
Dua tahun kemudian—sejak Umbu Landu Paranggi meninggal—aku mendapatkan buku puisi Melodia (2023) yang diterbitkan Pustaka Ekspresi bekerja sama dengan Jatijagat Kehidupan Puisi. Buku puisi Melodia adalah kumpulan puisi karya Umbu Landu Paranggi yang disusun oleh Wayan Jengki Sunarta. Ketika aku membaca judulnya, aku merasa buku puisi Melodia berhubungan dengan pesan dari Umbu Landu Paranggi. Hubungan yang menarik diriku secara tidak langsung ke penjelasan belajar musik.
Belajar Melodia
Wayan Jengki Sunarta—dalam Pengantar Penyusun—menerangkan bahwa pemilihan judul Melodia merujuk dari salah satu judul manuskrip kumpulan puisi karya Umbu Landu Paranggi; serta merujuk puisi Melodia yang menggambarkan sosok dan kehidupan Umbu Landu Paranggi.[1] Apa yang diterangkan Wayan Jengki Sunarta bikin aku lega. Sebab, aku menganggap belum mengamalkan pesan dari Umbu Landu Paranggi. Jadi, buku puisi Melodia dapat menjadi pintu masukku menuju musik yang dimaksud oleh Umbu Landu Paranggi.
Sekarang, aku menilik baris tiga dan empat di bait pertama dalam puisi Melodia, yaitu: “/baiknya mengenal suara sendiri dalam mengarungi suara-suara/ dunia luar sana/”[2] Penilikan dua baris itu menyadarkan aku agar lebih mengenal suara sendiri ketika menjumpai aneka suara dari luar.
Tafsirku: korek suara sendiri yang mendengungkan realitas. Pengorekan suara sendiri dapat menandakan kesadaran penyair untuk mengendapkan “sesuatu” sebelum mengeluarkanya sebagai dunia-yang-menjadi pada hasil penciptaan puisi.
Perihal pengendapan imaji, aku mengingat pengantar Rantau, ‘Sparring Partner’, Silaturahmi yang ditulis oleh Raudal Tanjung Banua dalam buku puisi Gugusan Mata Ibu (2005). Pada pengantar itu, aku membaca salah satu pengalaman Raudal Tanjung Banua di Sanggar Minum Kopi, yaitu: Umbu Landu Paranggi yang kejam memuat satu puisi dari segepok puisi milik rekan penyair. Raudal Tanjung Banua menulis alasan keputusan Umbu Landu Paranggi: “…tingginya pengulangan dan keseragaman, atau kurangnya pengendapan….”[3]
Apa yang dinilai kejam oleh Raudal Tanjung Banua terhadap keputusan Umbu Landu Paranggi yang memuat satu puisi dari segepok puisi milik rekan penyair telah memberikan pelajaran penting bagiku. Pelajaran penting itu adalah keteledoran penyair yang terjebak menjadi mesin ala konfeksi. Sehingga, jika terjadi pengulangan dan keseragaman, tidak ada perbedaan antara puisi pertama dengan puisi kedua—juga puisi yang lain—di hadapan pembaca. Serta, pembaca tidak mendapat “gereget” pada puisi yang kurang pengendapan.
Pengalaman Raudal Tanjung Banua mengenai keputusan Umbu Landu Paranggi dalam pengantar Rantau, ‘Sparring Partner’, Silaturahmi turut memberikan pemahaman bagiku ketika membaca baris lima, enam, dan tujuh di bait ketiga dalam puisi Melodia, yaitu: “/begitu berarti kertas-kertas di bawah bantal, penanggalan penuh/ coretan/ selalu sepenanggungan, mengadu padaku dalam manja bujukan//”[4] Aku menangkap pembacaan tiga baris itu adalah penggambaran penyair yang memperlakukan puisi-puisinya selayak makhluk hidup.
Aku membayangkan bagaimana keintiman penyair yang memperlakukan puisi-puisinya selayak makhluk hidup. Keintiman lewat penentuan diksi yang tepat, penggubahan realitas ke imaji, hingga penyajian penuh kalkulasi. Seolah, penyair tidak akan melepas puisi-puisinya, hanya selalu bermesraan belaka, juga saling bertukar cakap dan kemauan. Apabila mampu berbekal dan kuat berpetualang, penyair bersuka cita mengantarkan puisi-puisinya ke lidah pembaca, membiarkan puisi-puisinya berganti tinggal dari penyair ke pembaca.
Lewat puisi Melodia, aku menakwil pesan dari Umbu Landu Paranggi sebagai simbol. Bukan musik yang menunjuk komposisi nada, menggaris alasan kemerduan, menyebut sumber bunyi, hingga mengukur gelombang bunyi. Tapi, keberadaan musik yang harus disadari penyair agar tahu kapan waktu menggetarkan pita suara, membunyikan bahasa, serta mengampukan tempo. Dan, keberadaan musik yang bikin penyair dapat menggubah setiap puisi dengan perbedaan corak yang beragam warna.
Etos Kerja Penyair
Bagiku, buku puisi Melodia bukan sekadar dokumentasi puisi-puisi karya Umbu Landu Paranggi. Justru, sangat penting, jika aku menengok Umbu Landu Paranggi yang misterius, seperti kesanku membaca keterangan Putu Fajar Arcana ketika mewawancarainya: “Umbu relatif tidak tercatat sebagai penyair dalam sejarah sastra Indonesia. Karya-karyanya tidak banyak dikenal karena memang ia jarang memublikasikannya. Tetapi, anehnya, semua seniman, setidaknya generasi 1960-an sampai 2000-an, mengaku pernah bersentuhan dengannya…”[5]
Lain itu, Umbu Landu Paranggi mengungkapkan kenapa pilihan kepenyairannya tidak seperti penyair yang disebut oleh Putu Fajar Arcana: “Semua punya peran masing-masing. Kalau semua seperti Chairil atau Sutardji, mungkin dunia kepenyairan dan kebahasaan kita tumbuh lamban. Berbahasa Indonesia bukan sesuatu yang mudah bagi sekalangan orang Jawa dan Bali dan orang-orang yang bukan Melayu. Karena itulah, Sumpah Pemuda itu puisi mantra. Ia ibarat amarah suci sebuah angkatan… 17 tahun kemudian terbukti terjadi proklamasi.”[6]
Pilihan kepenyairan Umbu Landu Paranggi lebih sesuai disebut “kehidupan puisi”, sebuah idiom merujuk pengakuan Emha Ainun Nadjib dalan esai Presiden Malioboro untuk Umbu yang ditayangkan Kompas (16/12/2012).[7]
Dalam buku puisi Melodia, aku mencermati “kehidupan puisi” yang ditampakkan Umbu Landu Paranggi adalah etos kerja penyair ketika menciptakan puisi. Barangkali, Umbu Landu Paranggi berpendirian bahwa puisi-puisinya memiliki jalan berbeda sehingga tidak ada karya yang final meski telah dipublikasikan di media tertentu.
Jalan berbeda puisi-puisi karya Umbu Landu Paranggi bisa aku tengok pada empat puisi yang memiliki versi dalam buku puisi Melodia, antara lain: Percakapan Selat (tiga versi); Sajak Kemarau (tiga versi); Kuda Merah (dua versi); dan Kuda Putih (dua versi). Wayan Jengki Sunarta—pada Pengantar Penyusun—menerangkan bahwa empat puisi yang memiliki versi dalam buku puisi Melodia mengalami swasunting.[8] Sekarang, aku meraba etos kerja penyair yang dilakukan Umbu Landu Parangi lewat analisis tiga versi puisi Percakapan Selat, yaitu:

Keterangan: Tiga versi puisi Percakapan Selat karya Umbu Landu Paranggi dalam buku puisi Melodia.
Sumber: Umbu Landu Paranggi (2023), Melodia, Bali: Pustaka Ekspresi. (Percakapan Selat Versi 1, Hal: 43); (Percakapan Selat Versi 2, Hal: 45) dan (Percakapan Selat Versi 3, Hal: 60).
Setelah memerhatikan tiga versi puisi Percakapan Selat di atas, aku memberikan beberapa warna pada badan puisi. Berikut penjelasanku perihal arti beberapa warna: biru berari ada kesamaan diksi, frasa, dan baris pada versi 1, versi 2, dan versi 3; hitam berarti tidak ada kesamaan diksi, frasa, dan baris pada versi 1, versi 2, dan versi 3; merah berarti ada kesamaan diksi pada versi 1 dan versi 2; hijau berarti ada kesamaan diksi dan frasa pada versi 2 dan versi 3; serta oranye berarti ada kesamaan diksi versi 1 dan versi 3.
Kalau memperhatikan versi 1, pink bukanlah fokus analisis, sebab hanya menandakan kecurigaan perihal kata “burung” yang seharusnya tidak terpotong dengan baris “/namun membujuk jua langkah, pantai, mega lalu burung-/”. Meski begitu, pink seharusnya bewarna hitam karena tidak ada kata “burung” atau “burung-burung” dalam versi 2 dan versi 3. Aku sangat menyayangkan andai alasan penempatan kata “burung” adalah tipografi puisi Percakapan Selat versi 1 tidak dapat menyesuaikan lebar buku puisi Melodia.
Aku memperhatikan bentuk tipografi: Pada versi 1, bait pertama dan kedua sama-sama berisi empat baris dan sama-sama berpola rima /a-a-b-b/, sedangkan bait ketiga berisi tujuh baris yang berpola rima /a-a-b-b-a-c-a/; lalu pada versi 2 dan versi 3, tiga bait sama-sama berisi empat baris dan sama-sama berpola rima /a-a-b-b/. Juga, aku memperhatikan penggunakan huruf kapital, yaitu: Pada versi 1 dan versi 3, huruf kapital menjadi kata pertama pada baris pertama setiap bait; sedangkan, pada versi 2, huruf kapital ada pada baris pertama dan baris ketiga setiap bait.
Ada keanehan ketika aku memperhatikan perbedaan tarikh, yaitu: versi 1 dan versi 2 sama-sama bertarikh 1966 (tanpa menyebut tempat penciptaan); sedangkan versi 3 bertarikh 1968 (tempat penciptaan di Yogya). Aku tidak tahu kenapa ada perbedaan tarikh yang terpaut dua tahun. Apakah Umbu Landu Paranggi memaknai swasunting versi 3 sebagai kelahiran baru? Sangat sulit menjawab pertanyaan itu setelah aku mengetahui pemuatan muktahir justru versi 2 di Pusara, No. 43/3 (Maret 1974), bukan versi 3 di Sinar Harapan (9 Oktober 1972).
Setelah memperhatikan secara saksama, aku mulai menganalisis setiap versi puisi Percakapan Selat di atas. Lewat biru, aku mengamati setiap kata, frasa, dan baris tetap dipertahankan Umbu Landu Paranggi pada versi 1, versi 2, dan versi 3. Tapi, lewat hitam pula, aku menyadari ada kata, frasa, dan baris yang hanya dimunculkan Umbu Landu Paranggi pada versi 1, versi 2, dan versi 3. Sehinga, hitam pada versi 3 seolah akhir swasunting puisi Percakapan Selat lewat kabaruan kata, frasa, dan baris yang tidak ada pada versi 1 dan versi 2.
Aku tertarik mengamati merah, hijau, dan oranye. Sebab, lewat merah, kata “sampai” dan “menderu” dari versi 1 sempat dipertahankan Umbu Landu Paranggi pada versi 2, sebelum dihilangkannya pada versi 3. Atau, lewat hijau, banyak kata dan frasa dimunculkan Umbu Landu Paranggi pada versi 2, dan dipertahankannya pada versi 3 meski mengalami modifikasi susunan baris. Sedangkan, lewat oranye, Umbu Landu Paranggi kembali menyisipkan kata “resah” pada versi 3, padahal kata “resah” ada pada versi 1 dan dihilangkannya pada versi 2.
Apakah Umbu Landu Paranggi yang menyisipkan kata “resah” pada versi 3 adalah kebetulan? Pertanyaan itu muncul akibat pemungutan kata “resah” dari versi 1, padahal telah dihilangkan pada versi 2. Jawabanku: Barangkali tidak kebetulan. Atau, barangkali Umbu Landu Paranggi menyimpan puisi-puisi sebelum swasunting demi pertimbangan ke depan. Sebab, aku membaca puisi Percakapan Selat karya Umbu Landu Paranggi yang tayang di Bali Post (2/11/2014).[9] Di bawah ini, perhatikan puisi Percakapan Selat yang tayang di Bali Post, yaitu:

Keterangan: Puisi Percakapan Selat karya Umbu Landu Paranggi versi Bali Post dan penampakan buku puisi Melodia serta kliping puisi-puisi Umbu Landu Paranggi yang tayang di Bali Post.
Sumber:Bali Post (2 November 2014), rubrik Apresiasi, halaman 19.
Oh ya, dalam tulisan ini, aku menyebut Percakapan Selat yang tayang di Bali Post sebagai versi Bali Post, bukan versi 4. Sebab, versi Bali Post tidak masuk dalam buku puisi Melodia. Aku ingin menghindari kerancuan. Lalu, berbeda dengan versi 1, versi 2 dan versi 3, justru versi Bali Post memiliki tipografi tidak berbait atau kuatrin; huruf kapital pada awal kata di setiap baris, dan tidak memiliki tarikh. Dan, aku mencermati, ternyata isi puisi pada versi Bali Post hampir sama dengan versi 1, bukan versi 2 atau versi 3.
Perbedaan isi puisi antara versi Bali Post dengan versi 1 adalah penggunaan kata “selalu” pada baris kedua versi Bali Post; dan penggunaan kata “lalu” pada baris kedua versi 1. Sehingga, dalam versi Bali Post, aku membaca: “/Sepi yang selalu dingin gumam terbantun di buritan/”; sedangkan, dalam versi 1 (termasuk versi 2 dan versi 3), aku membaca: “/sepi yang lalu dingin gumam terbantun di buritan/”. Lebih lanjut, tidak ada baris “/saat pulau-pulau lengkap berbisik, saat haru mutlak biru//” pada versi Bali Post, padahal baris itu ada pada versi 1.
Versi Bali Post menunjukkan hasil swasunting versi 1. Seolah, versi 1 adalah batang; versi 2 dan versi Bali Post adalah cabang dari batang versi 1; dan versi 3 adalah ranting dari cabang versi 2. Tapi, Umbu Landu Paranggi tidak mengerjakan swasunting puisi secara kontinu. Maksud kontinu adalah puisi yang selalu diperbarui dengan menghilangkan bekas revisi. Sebab, versi 2 masih menjadi pilihan Umbu Landu Paranggi untuk memublikasikan ke media tertentu, padahal versi 3 sudah pernah tayang.
Aku membayangkan Umbu Landu Paranggi tetap selalu menyimpan puisi-yang-pertama sebagai embrio yang dapat ditumbuhkan ke versi terbaru, dari versi terbaru yang dapat ditumbuhkan ke versi terbaru lagi.
Tapi, versi terbaru atau versi terbaru lagi tetap kuat mempertahankan isi puisi-yang-pertama, meski mengalami perubahan struktur. Beragam versi puisi Percakapan Selat seolah merefleksikan jawaban Umbu Landu Paranggi ketika diwawancara oleh Putu Fajar Arcana: “…Seni itu sangkan paraning dumadi. Mempertanyakan kembali kedirian kita….”[10]
Kenapa harus mempertanyakan kedirian kita? Bukankah akan menghasilkan kesia-siaan, mirip ilustrasi perihal keraguan seorang “penulis hebat” yang tidak pernah lagi menerbitkan karyanya. Ilustrasi itu ada pada esai Menulis Sungguh-Sungguh dan Menulis Pura-Pura dalam buku Solilokui (1984) karya Budi Darma, yaitu: “…Karena itulah dia menyibukkan diri dengan menulis kembali naskah-naskahnya. Dia dapat mengubah-ubah satu naskahnya sampai beberapa kali, kalau perlu sampai puluhan kali. Akhirnya dia tidak pernah menyelesaikan apa-apa.”[11]
Aku tidak boleh gegabah membandingkan jawaban Umbu Landu Paranggi ketika diwawancara oleh Putu Fajar Arcana dengan ilustrasi “penulis hebat” (mengacu tulisan Budi Darma). Sebab, latar belakang dari ilustrasi “penulis hebat” itu adalah bertindak dengan napsu, tapi ragu-ragu atas tindakannya. Sebaliknya, Umbu Landu Paranggi sering menggumamkan kata “tanam” dan “taman”, yang sama-sama memiliki kesan: “Dua patah kata filosofis yang mengandung kedalaman renungan. Dua patah kata yang menggetarkan jiwa.”[12]
Daftar Pustaka
Budi Darma (1984), Solilokui, Jakarta: Gramedia.
Raudal Tanjung Banua (2005), Gugusan Mata Ibu, Yogyakarta: Bentang.
Umbu Landu Paranggi (2023), Melodia, Bali: Pustaka Ekspresi.
Emha Ainun Nadjib (Kompas, 16 Desember 2012), Presiden Malioboro untuk Umbu, hal: 20.
Putu Fajar Arcana (Kompas, 18 November 2012), Umbu Landu Paranggi Berumah dalam Kata-Kata, hal: 23.
Umbu Landu Paranggi (2 November 2014), Percakapan Selat; Sajak Kecil; Solitude; Kata, Kata, Kata; Sabana; dan Ibunda Tercinta, Hal 19.
[1] Agar lebih memahami keterangan Wayan Jengki Sunarta, aku menulis ulang satu paragraf utuh pada Pengantar Penyusun dalam buku puisi Melodia karya Umbu Landu Paranggi: “Saya memilih judul Melodia untuk kumpulan puisi ini dengan merujuk pada judul salah satu manuskrip kumpulan puisi ULP. Selain itu, puisinya yang berjudul Melodia juga sangat legendaris dan sering dibacakan atau dijadikan mesikalisasi puisi oleh para pencinta sastra. Puisi itu juga mampu menggambarkan sosok ULP dan kehidupannya sebagai penyair. (Hal: ix).
[2] Umbu Landu Paranggi (2023), Melodia, Bali: Pustaka Ekspresi. (Hal: 56).
[3] Raudal Tanjung Banua (2005), Gugusan Mata Ibu, Yogyakarta: Bentang. (Hal: viii).
[4] Umbu Landu Paranggi (2023), Melodia, Bali: Pustaka Ekspresi. (Hal: 56).
[5] Putu Fajar Arcana (Kompas, 18 November 2012), Umbu Landu Paranggi Berumah dalam Kata-Kata, Hal: 23.
[6]Ibid. Hal: 23.
[7] Dalam esai Presiden Malioboro untuk Umbu (Kompas, 16 Desember 2012), Emha Ainun Nadjib menulis: “…Umbu tiap saat berjalan kaki menjauh dari segala sesuatu yang semua orang di muka bumi mengejarnya. Ia menyebut seluruh keputusannya itu dengan idiom “kehidupan puisi”. Saya mengenalinya sebagai “zuhud”: berpuasa dari kemewahan dan gegap gempita dunia. Ia meninggalkan harta, kekuasaan, wanita, kemasyhuran, dan menyimpan uang dalam bungkusan plastik dipendam di tanah.” (hal: 20).
[8] Wayan Jengki Sunarta pada Pengantar Penyusun dalam buku puisi Melodia karya Umbu Landu Paranggi menulis: “Pada saat proses pengumpulan puisi, saya menemukan beberapa puisi ULP mengalami swasunting, dari revisi ringan hingga berat. Puisi-puisi tersebut dimuat di media yang berbeda. Dalam buku ini, saya tampilkan beberapa puisi yang mengalami swasunting dengan menambahkan kata “versi” pada judul puisinya….” (hal: vii-viii).
[9] Bali Post (2 November 2014), rubrik Apresiasi, halaman 19, menayangkan enam puisi karya Umbu Landu Paranggi, yaitu: Percakapan Selat; Sajak Kecil; Solitude; Kata, Kata, Kata; Sabana; dan Ibunda Tercinta.
[10] Putu Fajar Arcana (Kompas, 18 November 2012), Umbu Landu Paranggi Berumah dalam Kata-Kata, Hal: 23.
[11] Budi Darma (1984), Solilokui, Jakarta: Gramedia. (Hal: 86).
[12] Umbu Landu Paranggi (2023), Melodia, Bali: Pustaka Ekspresi. (Hal: 138).