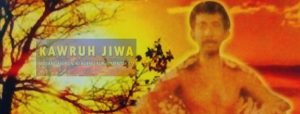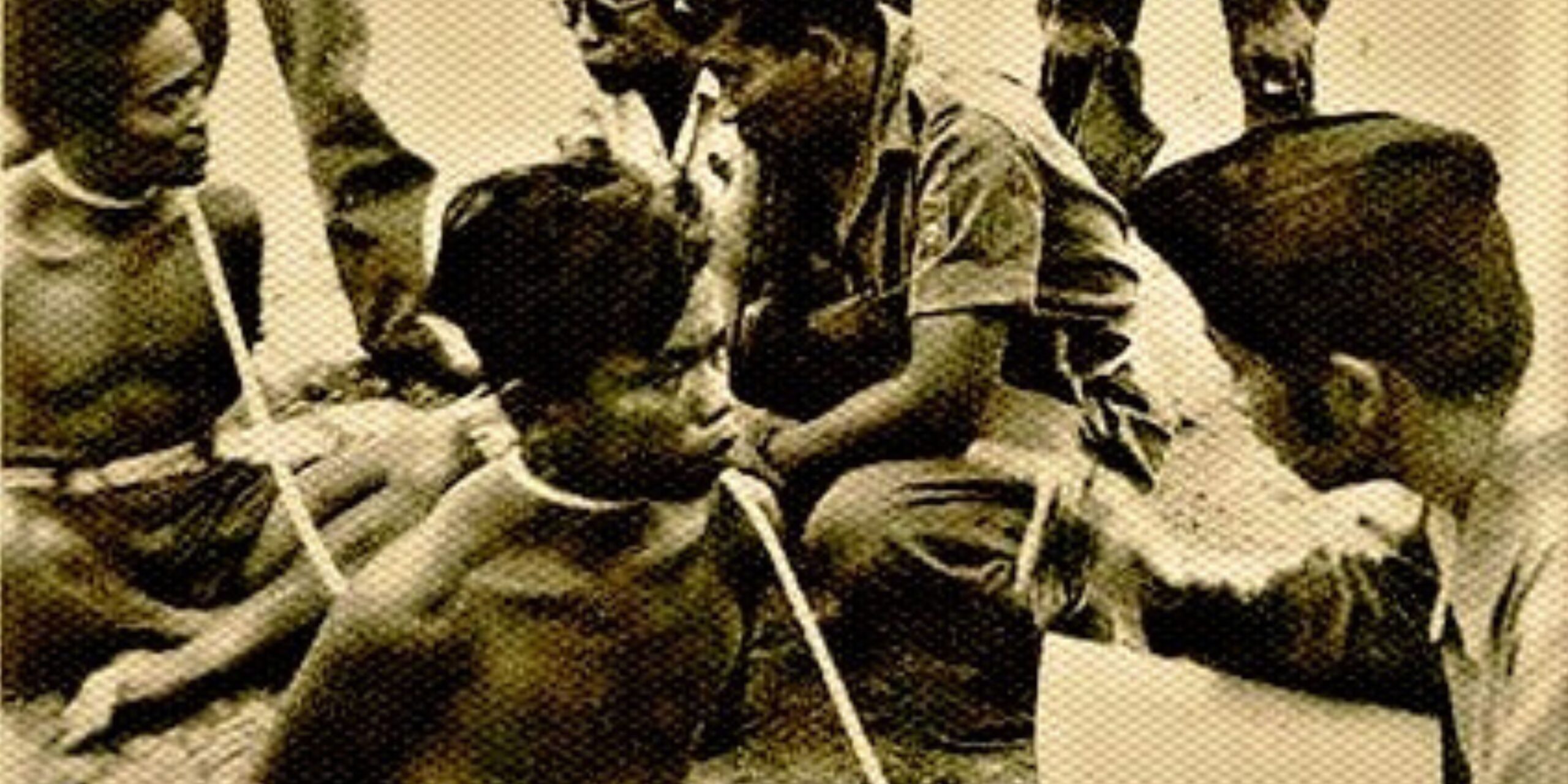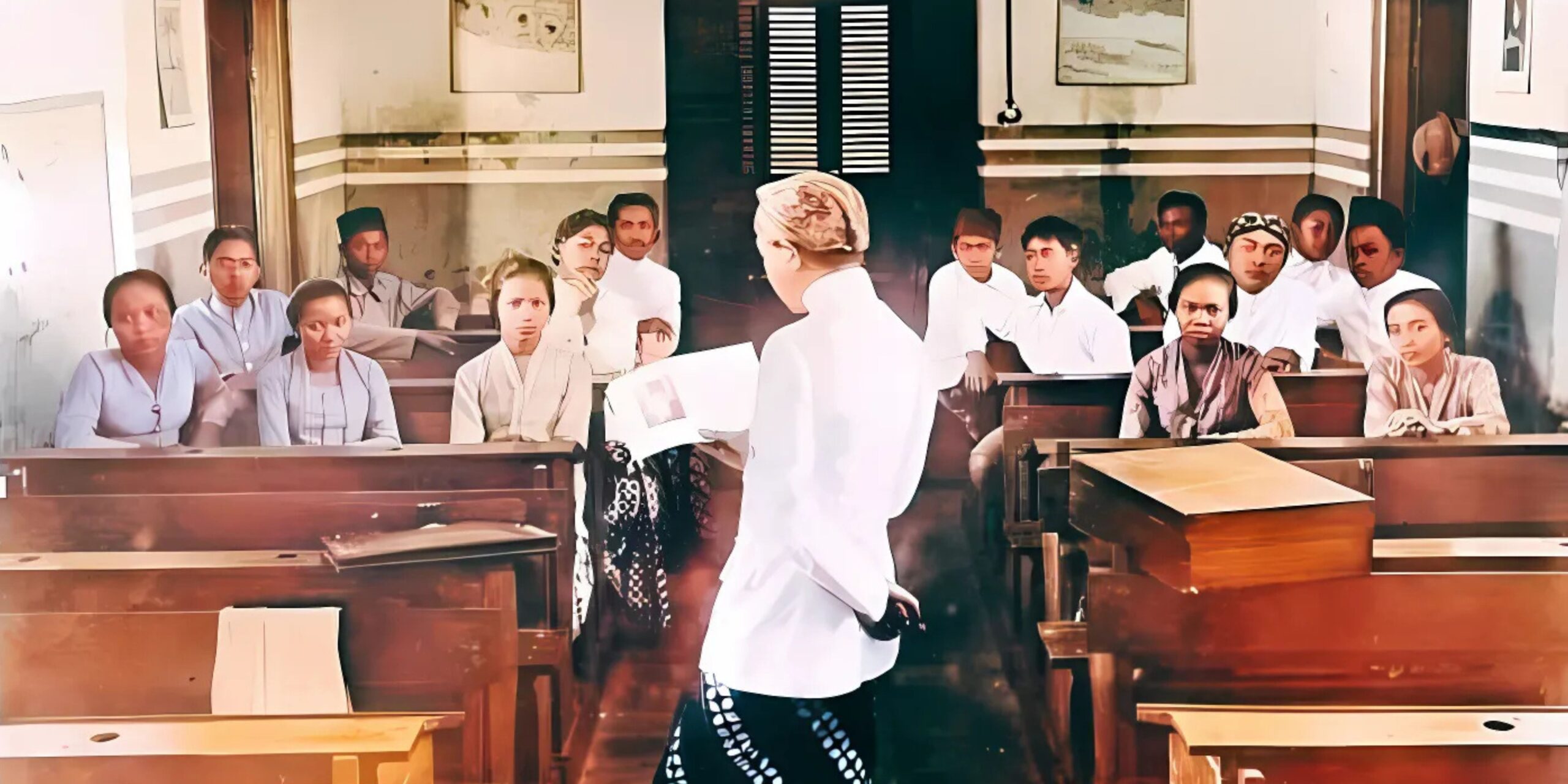Ki Ageng Suryomentaram: Pangeran dan Filsuf dari Jawa (1892–1962) Bagian IV – Habis
Tulisan Marcel Bonneff ini versi aslinya berbahasa Prancis: “Ki Ageng Suryomentaram, Prince et Philosophe Javanais,” dimuat pertama kali di Archipel 16 (1978), hal. 175–203. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Susan Crossley, “Ki Ageng Suryomentaraman,...