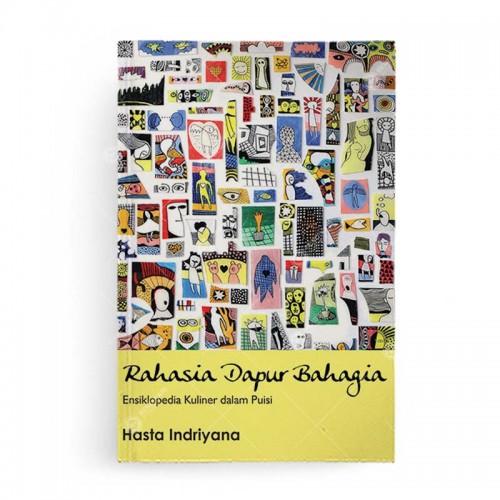Hasta Indriyana, penyair kelahiran Gunungkidul, Yogyakarta, barulah pada usia 26 memikirkan kemungkinan kalau makanan patut saja memasuki semesta puisi. Itu pun ia mesti lebih dulu membuang tubuhnya dari tanah kelahiran. Mata yang sedari bayi mengakrabi Gunungkidul itu barangkali sinis, tak mungkin ada puisi di sepanci tiwul. Ketika berada di Palembang, Sumatera Selatan, matanya terbelalak. Pepes belida mengantarnya ke momen puitik. Di buku Rahasia Dapur Bahagia (Gambang, 2017), puisi Pepes Belida jadi anak sulung sekaligus paling panjang proses pembuahannya. Ia mulai ditulis pada 2003 dan dirampungi pada 2015.
Tahun 2015 jadi tahun paling banyak makanan tercecer di puisi Hasta. Barangkali Hasta baru sadar, upaboga juga berkait dengan kolonialisme, sejarah, peristiwa komunal, identitas, dan lain-lain. Makanan tak cuma jadi “masa-kini”. Selalu ada potensi puitik yang terselip di atas meja makan. Namun di puisi Pepes Belida,kita membaca makanan masih nyaris sekadar peristiwa soliter. Masa silam hanya hadir sepintas: Belida yang pipih/ Dari cokelat kali Palembang/ Dibelit daun pisang dililit rempah/ [ ]/ sejenak kita susuri Musi seperti/ Membaca Sriwijaya yang dilayari/ Kapal dagang dan pelancong. Ironisnya, di puisi dengan penggarapan terlamanya itu, mengalami sejarah kala makan cuma jadi jenak.
Dengan sejenak kita susuri Musi seperti membaca Sriwijaya, aku-lirik sepertinya malu-malu mengakui identitas turisnya. Ia tak mau dianggap sebagai manusia dengan masa-kini belaka. Maka, di bait ketiga ia menggotong masa silam Palembang. Ketidaktahuannya segera ditutupi dengan sejenak. Ia berharap lekas mendapat permakluman pembaca terhadap matanya, misalnya, yang tak memandang warna merah di sungai Musi. Dari sungai itulah pada 1659 Palembang dialiri api. Belanda murka sebab Palembang menawan dan membunuh orang-orang mereka. Catatan Johan Nieuhof (1618-1672), seorang seniman yang menjalin kontrak kerja dengan VOC, mengisahkan perjalanan kapal yang dipimpin laksamana sekaligus jenderal Belanda, John Vander Laen. Palembang langsung menghadang kapal Belanda dengan mesin-mesin api yang mengapung di sungai dan tembakan meriam. Sayangnya pertahanan Belanda alot. Belanda terus merangsek dan kemudian keadaan berbalik ketika John Vander Laen berhasil menemukan anak sungai yang menjadi tempat strategis untuk melabuhkan kapal. Dalam catatannya, John Nieuhof menulis, Anak sungai tersebut mengarah ke tempat yang sangat aman dari tembakan musuh. Kami mendarat dengan seluruh pasukan, dan dengan gagah berani kami bergerak ke sarang musuh. Kami melemparkan granat ke arah kota yang kemudian menyebabkan rumah-rumah yang berdempetan terbakar, musuh menjadi ketakutan dan meninggalkan tempat mereka (Anthony Reid, 2010).
Dengan posisi serba tanggung, aku-lirik malah terlihat berpretensi. Barangkali ia tak minat menjadi lugu laiknya aku-lirik pada puisi Sajak Sembilan Kota 9 (2015) dari Yudhistira ANM Massardi: Akhirnya! Aku bisa menulis Paris/ Paris yang manis di malam Kamis/ Ketika harum kopi menyapa pagi. Di puisi Yudhistira itu, aku-lirik benar-benar total menatap dari mata turis dunia ketiga. Informasi atas Paris ataupun Prancis mampir melulu dari budaya populer yang terus mereproduksi keromantisannya. Membuat ia menafikan sejarah Prancis yang penuh api, dari Kerusuhan Toulouse pada 1562 hingga Kerusuhan Sipil Perancis pada 2015 (tirto.id, 28 November 2018). Aku-lirik dalam Pepes Belida seperti takut terlihat bodoh jika terlalu girang dengan kota-masa-kini. Meski pada sejenak”itu, pembaca melihat kepayahannya. Ia tak mengenal Musi dan Palembang. Maka, di bait lanjutan, ia segera kembali menatap piring, berpaling dari masa silam, menikmati masa kini: Baiklah, pepes kita buka/ Belida yang disayat, beberapa bagian/ Tubuhnya gosong/ Entah siapa di antara kita memulai/ Mengelupasi kulit dan menempelkan/ Balutan bumbu di lidah kita yang/ Tak lelah-lelah berlayar ke mana-mana. Lima larik sejarah Sriwjaya terasa sekadar jadi ceracauan untuk latar dua orang yang mengemut pepes.
Di buku setebal vxx + 167 itu, tarikh yang tertera di tiap akhir puisi bisa jadi bocoran proses kreatif. Pembaca bisa menduga, pada 2015 Hasta lagi getol-getolnya membuat puisi berkaitan kuliner. Ia mungkin melacak segala dokumen terkait upaboga dengan pamrih demi mengguyur puisi-puisinya dengan beragam makanan. Kelak, ketika buku terbit, sub-judul Ensiklopedia Kuliner dalam Puisi mungkin ia niatkan sebagai pengumuman seberapa uletnya ia dalam menggarap proyek ini.
Kelak, ketika buku terbit, sub-judul Ensiklopedia Kuliner dalam Puisi mungkin ia niatkan sebagai pengumuman seberapa uletnya ia dalam menggarap proyek ini.
Dalam pelacakannya, makanan itu menyatukan keragaman. Di puisi berjudul bahasa Inggris, No Food Is Born Racist, ia berkisah sate jadi jalinan kebhinekaan Indonesia: Kamu dari mana?/ Madura/ Kamu dari mana?/ Betawi/ Kamu dari mana?/ Jawa/ Kamu dari mana?/ Padang/Kamu dari mana?/ Marangin. Hasta ingin beda dari negara. Puisi itu bertitimangsa 2015 dan tiga tahun sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu menjadikan Tumpeng Nusantara sebagai ikon makanan tradisional. Tumpeng menyatukan keberagaman makanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Informasi dicatat Bondan Winarno dalam bukunya, 100 Maknyus Makanan Tradisional Indonesia (2014). Hasta jelas tak pernah baca buku itu. Sebab di puisinya, Hasta mengatakan pula bahwa sate Padang itu eksis. Di buku “Maknyus”, Bondan mengatakan tak ada sate Padang, yang ada adalah sate Padangpanjang, sate Pariaman, dan sate Danguang-Danguang. Ini bukti masakan tradisional tak bersifat provinsial, melainkan terroir.
Lagi pula menganggap makanan tak rasis jelas keputusan naif. Sejarah makanan tak bisa dilepaskan dari ras, strata dan senjata. Anggapan ini makin mensterilkan puisi Hasta dari masa silam. Pada masa kolonial, mulanya orang-orang Belanda tak sudi makan makanan pribumi. Gengsi membuat mereka dan keturunan mereka sebisa mungkin tetap memakan santapan Eropa. Namun, karena pria Eropa menikahi wanita pribumi dan para nyai itu menguasi dapur, akhirnya lidah keluarga Eropa pun luluh. Kelak, ketika Jepang mengusir mereka dari Hindia, lidah-lidah putih itu pun kangen masakan pribumi. Pada masa 1970-an, salah satu dari mereka meluapkan kangen pada upaboga Nusantara dengan menciptakan lagu. Biduanita itu bernama Wieteke van Dort, salah satu bocah Belanda yang sempat mengalami masa kanak di Hindia, dengan tembang berjudul Geef Mij Maar Nasi Goreng (Beri Saja Aku Nasi Goreng). Di puisi, Hasta pun mengutip lagu ini.
Dari 21 baris di puisi Sebuah Lagu dari Radio, 12 baris di antaranya berisi lirik lagu ini. Tapi kita tak akan menemukan latar puisi tersebut di Eropa. Puisi berkisah di sebuah dapur di antah-berantah Indonesia. Tak ada indeks merujuk ke suatu wilayah secara khusus. Ia bisa di Purworejo, Kutai, Nabire, atau Ngawi. Seorang ibu memasak sambil mendengarkan radio dan merasa geli mendengar bule mengucapkan nasi goreng, terasi, serundeng, sate dan lain-lain, dengan pelafalan yang aneh. Tidak ada peristiwa memasak yang magis seperti di novel Like Water for Chocolate (Esquivel, 2018) di mana perasaan hati orang yang memasak, dapat memengaruhi perasaan orang yang kelak menyantap. Di novel, Tita menangis. Kekasihnya mesti menikah dengan kakak kandungnya. Air matanya bercampur di adonan kue. Pada hari pesta pernikahan, orang-orang mual dan pada saat bersamaan, merasakan rindu yang hebat. Di puisi, hanya ada ibu yang terkekeh. Itu saja.
Hasta sepertinya ogah memanfaatkan orang-orang Belanda itu jadi tokoh utama di puisi. Mereka yang pergi dan merindukan tanah di timur jauh yang sudah serasa rumah sendiri, sudah pasti mengalami goncangan dahsyat. Banyak lapisan kisah jika subjek-lirik berdiri pada barisan ini. Meski telah sampai Belanda, di acara-acara seperti ulang tahun, mereka tetap menyajikan masakan khas Indonesia (Rahman, 2011). Saking rindunya dengan Hindia, di pinggiran jalan, mesin penjual makanan otomatis bahkan menaruh menu-menu Indonesia di dalamnya. Dengan satu gulden, mereka meredakan kangen dengan membeli bola mie, bola nasi, sate, sambal, dan lain-lain (Selera, November 1984). Terlalu sulit menempuh perjalanan samudra ke timur, maka mereka cukup memasukan saja Hindia ke dalam mesin penjaja penganan.
Jika mau menarik lebih jauh lagi, malah di Amerika Serikat, senjata paling ampuh para kulit putih untuk menaklukkan suku Indian adalah dengan hewan atau tumbuhan yang kelak menjadi santapan, seperti sapi, babi, apel, gandum (Pollan, 2010). Makanan tak punya sejarah polos. Mereka punya banyak noda. Bahkan makanan turut memberi stigma negatif pada suatu daerah. Di Indonesia, beras jadi makanan utama. Tetapi tak semua daerah bisa menghasilkan beras. Pada 1997, terjadi bencana kelaparan di Irian Jaya. Negara memberi bantuan 10 ribu ton tiwul untuk mengenyangkan lapar penduduk. Bantuan bukan beras. Presiden Soeharto khawatir tiwul makin dianggap sebagai makanan daerah kurang pangan. Di Cendana, ia mengajak para wartawan makan tiwul dan berkata, Kalau makan tiwul jangan lantas diberitakan sudah kelaparan, kekuranan pangan, (Media Indonesia, 4 Desember 1997).
Hasta, penyair kita ini, berasal dari daerah dengan tiwul seolah telah jadi nama tengahnya. Sebab, di tanah Gunungkidul, sangat jauh lebih mudah bertanam ketela (bahan dasar tiwul) ketimbang padi. Meski begitu, akibat citra panjang buruk tiwul, kini orang Gunungkidul pun jarang menjadikan tiwul sebagai makanan utama. Tiwul dianggap punya kedudukan di bawah beras. Tiwul dijadikan masa silam yang kelam dan penuh kesengsaraan (wonggunung, 2018). Menjadikannya makanan pokok barangkali dianggap mengundang kembali masa-masa penuh mala.
Sepuluh tahun setelah pepes belida di Palembang, Hasta akhirnya menulis tiwul di Gunungkidul. Di puisi Sepanci Tiwul Selembar Daun Pisang, Hasta menulis: Sepanci tiwul tumpah diratakan/ Di tampah di atas selembar daun pisang// Sebelum kerja bersama tanpa upah/ Memperbaiki rumah, orang-orang/ Kampung sarapan barengan// Tiwul, gudangan, sayur lombok ijo/ Ikan asin, kerupuk bumbu, peyek/ Kacang, tempe, suwiran ayam/ Dihampar di seluas tampah. Tiwul mendapat sorotan besar di puisi. Ia melingkupi kegiatan gotong royong atau yang masyarakat Gunungkidul sebut dengan sambatan. Satu keluarga sambat ke tetangganya tentang rumahnya yang pengin segera direnovasi. Tak ada upah bagi para tetangga. Hal ini secara tak langsung berarti menihilkan stratifikasi majikan-buruh. Sebagai bentuk penghormatan, mereka patutnya ngingoni (memberi makan), medangi (memberi minum), atau ngrokoki (memberi rokok) para tetangga yang memberi bantuan.
Indeks puisi ini spesifik Gunungkidul. Puisi Hasta tak cuma ditopang tiwul, melainkan pula sajian-sajian lain yang terhampar. Semisal, sayur lombok ijo atau kacang. Sebagai penyair-pengamat, kejelian mata Hasta tak cukup hanya menulis sayur lombok, melainkan harus sayur lombok ijo. Sebab, beda jenis saja menunjukkan perbedaan kelas sosial ataupun besarnya sebuah acara. Sayur lombok ijo itu sajian sederhana. Kuah dan lomboknya banyak, dan isian tempenya sedikit. Sedangkan sayur lombok merah biasanya berisi rambak, kentang, telur puyuh, dan hati ayam. Ia identik dengan acara besar atau kalangan priyayi. Juga kacang. Ia erat hubungannya dengan manusia Gunungkidul. Setelah para petani memanen padi, wiji utama, selalu diteruskan dengan menanam kacang, wiji kedua (wonggunung, 2018). Namun, meski cermat, puisi Hasta telah kehilangan intimasinya. Tak ada tubuh-aku di sana. Sehingga orang-orang bukit hanyalah massa-anonim. Ia bukan tetangga, saudara, atau pun keluarga yang masing-masing memiliki nama. Sebab puisi memandang perisitiwa dari mata kedua. Puisinya cuma jadi sekadar kesaksian, seperti sebuah potret yang diambil turis.
Sebagai penyair-pengamat, kejelian mata Hasta tak cukup hanya menulis sayur lombok, melainkan harus sayur lombok ijo. Sebab, beda jenis saja menunjukkan perbedaan kelas sosial ataupun besarnya sebuah acara. Sayur lombok ijo itu sajian sederhana. Kuah dan lomboknya banyak, dan isian tempenya sedikit.
Di puisi Berita di Tivi, Hasta melakukan manuver. Ia menulis puisi dari mata pertama. Meski manuvernya tak signifikan. Aku-lirik menyempil sebagai anggota keluarga petani cabai dan kepalanya sekadar menoleh dari gerutuan ibu ke ratapan bapak. Mereka miris melihat berita harga cabai melonjak: Ibu menggerutu/ Betapa di meja makan/ Tak akan ada raut megap-megap/ Keringetan// Bapak berkata bahwa petani seperti/ Kami menanam tapi cuma memanen keringet. Di keluarga petani cabai, masalah harga cabai sekadar jadi perkara di meja makan belaka. Seolah urusan pangan tak bisa merembet ke masalah lain. Ia tak mampu menggedor-gedor pintu rumah. Di novel Ulid Tak Ingin ke Malaysia (2009), Mahfud Ikhwan berkisah tentang Desa Lerok. Warga mengandalkan bengkuang dan gamping untuk bertahan hidup. Ketika harga anjlok, warga desa berbondong-bondong mengadu nasib ke negeri jiran. Urusan pangan tak cuma perihal cecap. Semisal membandingkan beberapa baris puisi dengan berpagina-pagina novel dianggap sebagai perbuatan keji, kita patut membaca kembali puisi Wiji Thukul. Di puisi Nyanyian Abang Becak (1984) aku-lirik jadi bagian keluarga tukang becak. Ketika harga minyak naik, lombok jadi hal pertama yang terpikirkan. Tapi ia tak berhenti jadi urusan meja makan. Masalah satu menghantam masalah lain. Dari meja makan, Wiji memperkarakan kehidupan berkeluarga, bertetangga, bernegara, dan bertuhan.
Di setiap hidangan, terhampar banyak jalinan kisah. Urusan makan tak pernah sekadar berakhir di meja makan. Setiap santapan punya kaitan dengan sejarah dan beragam hal yang membentuk masa kini.