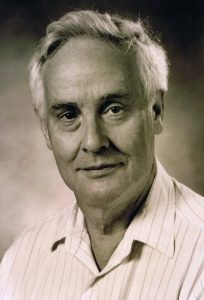Masifnya Posmodernisme
Bersamaan itu pula masyarakat sastra dan seni terus hanyut secara hegemonik dalam pikiran pomodernisme. Beberapa seniman, baik secara personal dan komunitas mulai memperkarakan pusat dan pinggiran. Kemudian lahirlah gerakan “Revitalisasi Sastra Pedalaman” yang digerakkan oleh beberapa sastrawan seperti Kusprihanto Namma, Beno Siang Pamungkas, Triyanto Triwikromo bersama beberapa sastrawan lainnya. Gerakan ini mencoba membangun gerakan subversif, melepaskan dominasi estetika seni atau sastra yang dianggap berpusat di Jakarta (maksudnya industri seni).
Gerakan itu mengingatkan kita pada wacana posmodern yang tengah bergerak seperti gelombang besar. Sebuah gelombang pikiran yang menggeser modernisme, baik dalam sastra, seni, sosial, budaya, dan filsafat, serta arsitektur. Pergerakan ini membawa ciri-ciri tertentu dan mudah ditemukan saat ini. Ketika agenda ”Revitalisasi Sastra Pedalaman” tengah berjalan, di Amerika, Clayton M. Christensen memperkenalkan istilah disruptive innovation dalam artikelnyal “Disruptive Technologies: Catching the Wave” (Havard Business Review, 1995). Istilah itu merujuk pada perubahan besar-besaran yang akan terjadi pada teknologi dan diikuti sistem pasarnya, seperti perubahan media komunikasi yang sudah kita alami saat ini. Media cetak beralih ke media digital, pasar dan mall berubah ke marketplace, dan sebagainya.
Menurut Fredic Jameson, seorang kritikus sastra-budaya yang dihormati, posmodernisme menghasilkan fitur budaya yang jauh bergeser. Jameson menyebut ciri-ciri secara budaya itu adalah seperti bergesernya rasionalitas pada irasionalitas, hilangnya pusat-pinggiran atau kontekstual, lahirnya “kedangkalan” yang disebabkan oleh realitas pencitraan melalui tontonan (spectacle) berupa iklan di pelbagai media, posmodernisme juga ditandai oleh kepura-puraan atau kelesuan emosi atau disebut sebagai ‘the waning of affect’, hilangnya jati diri karena luruh karakter individu dalam kolektivitas media, ahistoris atau terputusnya koneksitas nilai sejarah yang berakibat pada tradisi pastiche. Pastiche adalah aktivitas yang sekadar meniru yang asli tanpa maksud-maksud tersembunyi apapun, tanpa motif kritik maupun parodi atau hilangnya rasa sejarah yang menyebabkan “kanibalisasi atau peniruan acak terhadap gaya masa lalu.” Pastiche juga menjadi salah satu estetika yang sering digunakan dalam sastra posmodernisme, selain metafiksi, intertekstual, dan seterusnya.
Posmodernisme yang melahirkan semacam pasar media global itu juga menghasilkan apa yang disebut sebagai glocaliztion (glokalisasi). Di mana tak ada lagi lokal atau internasional karena semua menyatu dalam satu ruang. Apa yang lokal adalah internasional. Semua itu disatukan oleh media global yang memiliki peran menghubungkan dunia hiburan, periklanan dan akhirnya meleburkan mayarakat dalam ideologi komsumerisme. Posmodernisme juga menghasilkan masyarakat yang mengalami ketakmampuan melihat masa lalu dan masa depan. Akibat terkurung dalam budaya komsumerisme yang seolah menutup pandangan mereka terhadap ruang-ruang di luar masa kini. Istilah yang digunakan adalah ‘temporalitas dan spasialitas paradoks’.
Posmodernisme juga menghasilkan masyarakat yang mengalami ketakmampuan melihat masa lalu dan masa depan. Akibat terkurung dalam budaya komsumerisme yang seolah menutup pandangan mereka terhadap ruang-ruang di luar masa kini. Istilah yang digunakan adalah ‘temporalitas dan spasialitas paradoks’.
Masyarakat dalam ruang ini kehilangan kemampuan, pengalaman menggunakan bahasa sebagai simbol. Ketakmampuan dalam penataan simbol, percakapan, dan bahasa ini dalam istilah Lacan disebut sebagai schizoprenia. Hal ini juga ditandai dengan semakin hilangnya minat baca anak muda terhadap pelbagai jenis buku, terutama sastra. Tradisi baca seolah mati sebelum sempat berkembang baik di Indonesia, karena sebagian besar masyarakat masuk dalam jebakan apa yang Fredic Jameson sebut sebagai ‘global hyperspace’. Ruang yang tampak penuh dengan jebakan dan perangkap yang menggoda, menggiurkan dan sekaligus juga mengkuatirkan. Dalam ruang global hyperspace semacam ini, individu-individu tidak mampu membayangkan masa depan yang berbeda dan tidak mampu memusatkan diri pada cita-cita dan sejarahnya, kecuali hanya terjebak dalam suasana eforia berlebihan terhadap tontonan (spectacle) yang semu, gaya hidup yang superfisial dan citra konsumerisme yang berujung pada kehampaan dan malaise diri.
Fredic Jameson, melihat, seluruh pergerakan atau yang dicirikan dalam masyarakat posmodern tersebut merupakan bagian upaya yang disebut logika kapitalisme. Kajian Jameson dalam buku-bukunya, seperti Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, Postmodernism and the Market beranjak dari tiga tahap perjalanan kapitalisme menurut Earns Mandel dalam “Late Capitalism”. Mandel sendiri membagi fase kapitalisme menjadi tiga tahap hstoris, yaitu: tahap kapitalisme pasar klasik, kapitalisme monopoli (imperialisme) dan kapitalisme multinasional (late capitalism). Tiga tahap itu kemudian menurut Fredic Jameson melahirkan tahap estetika sebagai: realisme, modernisme dan posmodernisme.
Dengan demikian, seluruh kondisi saat ini, seperti luruhnya masyarakat dalam dunia ‘receh’, turunnya minat baca buku (bukan membaca status medsos) adalah bagian dari narasi besar atau tujuan kapitalisme lanjut (late capitalism).
Sastra Lanjutan
Dengan kondisi seperti itulah sastra Indonesia kita berdiri sepi di sudut jalan. Terombang-ambing oleh kekuatan gelombang besar. Gelombang pikiran posmodern yang secara pasti terus melangkah dan memengaruhi pola hidup, budaya masyarakat, dan estetika sastra Indonesia. Selama hampir sekian puluh tahun tak ada karya yang mampu dominan di pasar, kecuali karya-karya Pramoedya Ananta Toer dan Ayu Utami. Karya Ayu Utami dan Pram begitu menguasai pasar. Dua penulis itu mewakili kanon sastra Indonesia, meskipun keduanya memiliki perbedaan genre. Pram adalah penulis generasi masa lalu, di mana ia terlibat dalam revolusi kemerdekaan secara langsung dan revolusi lanjutan di masa 1960-an, serta menjadi tahanan politik baik di masa revolusi dan rezim Orde baru, sedangkan Ayu Utami adalah generasi jauh lebih muda, di mana feminisme tengah menjadi gerakan di negara dunia ketiga. Keduanya adalah produk dari moderenisme. Keduanya juga menjadi representasi dari perspektif kritik feminisme.
Dengan kondisi seperti itulah sastra Indonesia kita berdiri sepi di sudut jalan. Terombang-ambing oleh kekuatan gelombang besar. Gelombang pikiran posmodern yang secara pasti terus melangkah dan memengaruhi pola hidup, budaya masyarakat, dan estetika sastra Indonesia.
Karya-karya Pramoedya merepresentasikan konteks sosial di masanya, yaitu sikap manusia yang tak berdaya berhadapan dengan alam, manusia terjajah yang mencoba melawan penindasan, diskriminasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa lain. Sedangkan karya-karya Ayu Utami merpresentasikan konteks perlawanan perempuan terhadap dominasi dan sistem yang dianggap patriarkis, seperti dominasi laki-laki maupun agama. Melalui tesis Simon de Beauvior dalam “The Second Sex” yang menyatakan bahwa perempuan adalah the other, ‘liyan’ atau lawan laki-laki karena dominasi mereka sepanjang sejarah peradaban manusia, Ayu Utami membangun estetika sastranya dengan lebih bebas terbuka. Novelnya Saman bahkan mendapatkan predikat novel terbaik dalam Sayembara Novel DKJ (Dewan Kesenia Jakarta) tahun 1998. Novel yang dianggap mendobrak ketabuan sosial dan estetika.
Karya ini meskipun mendapatkan kritik dari pelbagai kalangan karena dianggap mengumbar seksualitas, tapi nasibnya lebih lancar dibanding novel Lady Chatterley’s Lover karya D.H. Lawrence yang sempat ditolak di Amerika dan Inggris karena terlalu vulgar di tahun 1960-an. Pendekatan genre, estetika dan artistik novel Ayu bahkan kemudian menjadi kanon sastra yang diikuti oleh banyak penulis Indonesia, terutama penulis perempuan. Bahkan penerbit mayor yang tidak terlalu mendukung sastra kecuali apa yang diterima pasar, ikut menerbitkan dan mempromosikan.
Dengan demikian, setelah Reformasi, pikiran modern mulai bergeser pada pola posmodernisme dan realisme magis semakin berkembang dan mempengaruhi bentuk estetika sastra secara umum di Indonesia. Meskipun sebagian masih berkarya dengan model konvensi lama seperti romantisisme dan realisme abad ke-19. Namun, sebagian menjadi modernis, dan sebagian lain, sadar atau tidak masuk dalam wilayah sastra posmodernisme dan realisme magis.
Setelah era Pramudya Ananta Toer dan Ayu Utami, lahirlah karya-karya sastra baik novel atau cerpen yang memiliki ciri-ciri dalam sastra posmodernisme dan realisme magis. Novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan yang setelah sekian lama tak diperhatikan (2002) tiba-tiba muncul dan mendapatkan pujian-pujian besar dari banyak kalangan, seperti Ben Anderson. Gramedia Pustaka Utama setelah menerbitkannya tahun 2015 mencetak ulang hingga tiga kali. Karya Eka dianggap memiliki sintesa atau gaya penulisan dari pelbagai penulis dunia, seperti Gabriel Garcia Marques, Jorge Luis Borges dengan realisme magis, metafiksi, pastiche, hingga parodi Miguel Carventes. Dalam karya cerpen di koran penulis seperti Triyanto Triwikromo, Anton Kurnia, Seno Gumira Ajidarma bisa digolongkan sebagai penulis posmodernisme. Di luar apakah karya-karya itu dianggap luar biasa atau tidak.
Sastra posmodernisme lahir dengan semangat perlawanan terhadap modernisme, meskipun seluruh rohnya masih pada semangat filosofis modern. Bila modernisme memiliki motif kritis terhadap kaum borjuis abad ke-19 dan seluruh pandangan nilai-nilai sosialnya, posmodernisme hanya melakukan perubahan logika esktrem, bersifat global, dan meskipun anti-borjuis modernisme, tetapi seperti kata Profesor Graft, fiksi posmodern tidak sadar bahwa mereka sendiri terjebak dalam budaya kitsch/pop yang disiapkan oleh kapitalisme lanjut. Hanya beberapa karya posmodernis yang memiliki kekuatan isi dan estetika yang benar-benar mempesona dalam pandangan Graft. Fiksi posmodern, tulis John Barth, ialah semata-mata menekankan kesadaran diri yang “berkinerja” dan merupakan refleksifitas diri modernisme, dalam semangat subversifitas budaya dan anarki. Demikian John Barth mengutip pendapat Profesor Alter, Profesor Ihab Hassan, dan yang lainnya dalam esainya “Literature of Replacenisment” (1984).
Estetika posmodern bersifat lebih populis karena hilangnya batas-batas antara budaya tinggi (high culture) dan budaya massa (mass culture/low art) seperti dipostulatkan oleh Theodore Ardono dan Marx Horkheimer dalam The Dialectical Imagination (1947). Hal demikin juga disadari atau diyakini oleh Seno Gumara Ajidarma. Seno dalam banyak kesempatan wawancara menyiratkan dirinya menjadi bagian dari kaum pos-struktrulis yang tak memberikan batasan-batasan antara fiksi sastra atau fiksi genre. Secara demokratis semua memiliki kesetaraan atau peluang sama untuk diterima publik luas. Semua diserahkan pada mereka mau membaca apa.
Tetapi bahasa demokrasi ini mengandung pardoks dan ironi, di mana dalam kesetaraan yang diusung ternyata tidak selalu seperti itu. Karya-karya penulis pemula menjadi tipis mengakses ruang publik media yang dianggap prestesius. Media besar senantiasa mendahulukan karya-karya penulis yang besar dan memiliki pasar. Dengan kapital yang kecil, seorang penulis tidak mampu bangkit setara. Kesempatan itu menjadi semakin kecil dengan semakin berkurangnya media cetak, baik yang mati atau media cetak yang mengurangi, bahkan menutup rubrik sastranya.
Fenomena itu seolah menambah daftar alasan mengapa minat baca sastra di Indonesia, bahkan dunia semakin menurun tajam. Apakah era ini adalah masa kematian sastra? Wacana ini sebenarnya sudah muncul dalam beberapa dekade ini. Alvin Kanner, misalnya menulis The Death of Literature (1991). Andrew Delbanco, seorang peneliti di Amerika mengatakan bahwa ada trend menurun minat baca dari humaniora (sastra, bahasa, filsafat, musik, dan seni) dari 13,8 persen menjadi 9,1 persen antara 1966 dan 1993. Data sekian dekade itu bila kita bandingkan dengan data PISA 2018 untuk Indonesia seolah mengingatkan tentang istilah ‘kematian’ itu menjadi makna harafiah. Belum lagi, hampir tak ada kritikus sastra di Indonesia yang memadai untuk mengawal kualitas sastra. Selain media tak menyediakan rubrik kritik sastra, peran kritikus sastra juga diambil alih redaktur media yang tak lepas dari subyekivitasnya dan terbatas.
Bila Barth dalam esainya yang pertama (“Literature of Exhaustion”, 1967) mengatakan bahwa bentuk estetika sastra sudah semakin sulit ditemukan kecuali sekadar parodi, pastiche yang hampa makna, kecuali tulisan-tulisan Jorge Luis Borges—Alvin Kernan melihat bahwa ada realitas perubahan secara sosial yang menghamba pada budaya komsumtif yang semakin meluas dan menjangkiti anak-anak muda yang membuat sastra menjadi seolah mati. Dalam sebuah wawancara Kernan mengatakan, “Saya tidak mengerti bagaimana mungkin Shakespeare, Homer, dan Joyce bisa mati. Mereka akan dibaca oleh orang-orang yang berakal sehat.”
Meskipun Karner kemudian juga menjelaskan bahwa apa yang dia maksudkan kematian sastra lebih pada matinya estetika sastra. Klaim kematian itu, baik estetika atau entitasnya, terkesan naif dan tergesa-gesa bila kita membaca pendapat Borges. Sastra, tulisnya, tidak pernah bisa habis, karena tidak ada teks sastra tunggal yang dapat habis— “maknanya” berada seperti dalam transaksi dengan pembaca individu dari waktu ke waktu, ruang, dan bahasa. Mungkin, pendapat Borges yang disampaikan hampir lebih dari setengah abad lalu itu benar sebagai sikap optimistisme. Bahwa bahasa selalu memiliki fungsinya sebagai alat komunikasi manusia dari zaman ke zaman. Bahwa menurunnya minat baca adalah persolan dinamika budaya.
Meskipun demikian, wacana kematian sastra adalah persoalan serius karena jelas memengaruhi sejarah, sikap hidup, kebudayaan, dan akhirnya menjadi fitur peradaban bangsa. Dengan demikian persoalan sastra, dan apa yang mendukungnya, seharusnya menjadi perhatian dan mendapatkan keseriusan menanganinya. Bahwa sastra, seperti keyakinan Jean Paul Sartre dan WS. Rendra, memiliki fungsi etis demi pembebasan manusia dari kehidupannya yang menjadi semakin mekanik, harus juga dipertimbangkan. Meskipun estetika adalah juga pilihan seorang penulis, di luar kesadaran ideologis tertentu dengan melihat pilihannya.
Dalam bukunya Writing Degree Zero Roland Barthes mengatakan bahwa sejarah, kemudian, menghadapkan penulis dengan opsi yang diperlukan antara beberapa sikap moral yang berhubungan dengan bahasa; itu memaksanya untuk menandakan sastra bisa mungkin di luar kendalinya. Kita akan melihat, misalnya, bahwa kesatuan ideologis borjuis memunculkan satu mode penulisan, dan bahwa dalam periode borjuis (klasik dan romantis), bentuk sastra tidak dapat dibagi karena tidak berupa kesadaran; sedangkan, segera setelah penulis tidak lagi menjadi saksi universal, untuk menjadi inkarnasi (sekitar 1850), gerakan pertamanya adalah memilih komitmen bentuknya, baik dengan mengadopsi atau menolak penulisan masa lalunya. Karena itu penulisan Klasik hancur, dan seluruh Sastra, dari Flaubert hingga saat ini, menjadi problematika bahasa.
Pada akhirnya, saya hanya ingin mengatakan bahwa seluruh peta yang terpapar dalam esai ini adalah realitas sejarah yang terus berproses. Bahwa lanskap persoalan, dinamika sastra kita berkait erat dengan seluruh elemen yang membentuknya. Baik itu pandangan ideologis sebagai bangsa atau pribadi, budaya yang dominan, estetika, kreativitas, kesadaran akan kebutuhan, serta kesadaran sejarah. Perkembangan sastra juga membutuhkan menara tinggi untuk melihat cakrawala lebih luas.
Tidak mungkin hanya menyerahkan pada media-media tertentu, terutama pada penerbit yang sekadar melihat pasar. Peran kritikus juga mesti dihidupkan. Kritikus mati ketika tak ada media yang menyiarkannya. Bukankah karya Jackson Pollock abstrak-ekspresionisme menjadi trend dunia ketika ternyata melibatkan dana CIA seperti diberitakan oleh The Independent? Artinya, seluruh energi butuh sinergi yang mampu menumbuhkan secara kokoh sastra sebagai bagian penting dalam peta kebudayaan dan peradaban.
Esai berjudul “Realitas Budaya dan Sastra Kita” ini merupakan bagian ke dua dari dua edisi yang akan di terbitkan Langgar.co