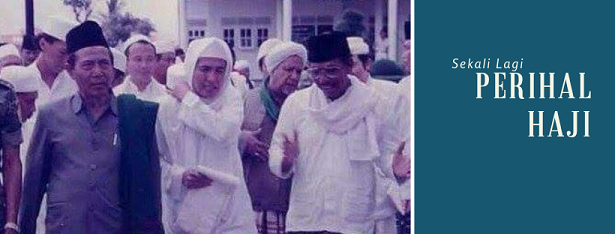Lembar
Pada musim Haji tahun ini ipar saya merasa beruntung bisa menjalankan Ibadah haji. Beruntung sudah diberi kelancaran dan keselamatan dari mulai berangkat ke Makkah sampai kembali lagi ke rumah, ke tanah air Indonesia. Berjumpa lagi dengan suami, anak, dan keluarga.
Ipar saya beruntung karena tidak sedikit jamaah haji yang mendapat halangan. Halangan berupa musibah dan perkara lain yang mengkhawatirkan, seperti terpisah dari jamaah, tersesat tak tau arah penginapan, atau musibah lain seperti kecelakan jatuhnya alat berat yang menimpa jamaah haji pada tahun haji sebelumnya. Ipar saya juga beruntung karena ia bisa berangkat haji dalam kesempatan yang baik, di usia muda, di zaman serba mudah di mana calon jamaah haji tidak perlu lagi menghabiskan waktu setengah tahun di lautan, di atas kapal yang tidak sepenuhnya aman. Tidak jarang kapal karam dihantam ombak atau terdampar di pantai tak dikenal. Ia juga beruntung bisa berangkat cepat, di tengah antrian haji yang begitu panjangnya itu. Karena antrian panjang, tak sedikit calon jamaah haji yang baru bisa berangkat setelah usia mereka sudah sepuh.
Bagi umat Islam Indonesia, ibadah haji sejak lama mempunyai peranan amat penting. Bahkan ada kesan bahwa orang Indonesia lebih mementingkan haji daripada bangsa lain, dan penghargaan terhadap para haji (muslim yang pernah menunaikan ibadah haji) memang lebih tinggi. Bisa diukur dari panjangnya antrian calon jamaah haji dan panggilan “pak haji” atau “bu haji/hajah” bagi muslim yang pernah menunaikan ibadah haji.
Sebenarnya bukan hanya karena haji adalah salah satu bagian dari syariat Islam saja, atau sebagai ibadah yang dijanjikan ganjaran yang melimpah, tapi juga karena ibadah haji dan seorang haji dulu pernah menjadi tanda perlawanan atas kolonialisme, sebagai perangsang antikolonialisme dan juga tanda kedudukan atau kecakapan seseorang atas ngelmu atau ilmu agama.
Sebab menjadi tanda kecakapan dan perlawanan itu, dulu pemerintah kolonial Belanda menaruh perhatian khusus kepada calon jamaah haji. Sampai kemudian pemerintah kolonial mengutus orang-orang terbaiknya berangkat ke Makkah untuk mempelajari apa itu ibadah haji, seorang haji, dan hal-hal yang terkandung di dalamnya. Nama van der Plas dan Snouck Hurgronje termasuk bagian dari utusan itu. Mengenai Snouck Hurgronje tentang Haji, Anda bisa baca dalam tulisan Bagus Pradana berjudul Perihal Haji, yang dimuat dalam langgar.co.
Agak belakangan banyak juga yang menulis tentang Ibadah Haji ke Mekkah, dan apa saja yang bersinggungan dengannya. Misalnya dalam Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat (2012), Martin Van Bruinessen juga menulis satu bab tentang Haji. Dalam judul Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci: Orang Nusantara Naik Haji, ia menyebut beberapa fakta sejarah masa lampau tentang haji dan menariknya fakta-fakta itu tidak jauh beda dengan kenyataan yang bisa kita lihat sekarang ini tentang Haji. Seperti melimpahnya jumlah jamaah haji, jamaah yang memutuskan tinggal lebih lama di Makkah untuk menuntut ilmu, untuk bekerja dan yang lainnya. Dalam Les relations entre les Pays-Bas e le Hidjaz (Hubungan Belanda dengan Hijaz) Van der Plas yang pernah menjabat konsul Belanda di Jiddah itu mencatat, bahwa sekurang-kurangnya ada 10.000 jiwa orang Indonesia yang menetap di sana.
Martin mencatat; Di antara seluruh jamaah haji, orang Nusantara-selama satu setengah abad terakhir- merupakan proporsi yang sangat menonjol. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, jumlah mereka berkisar antara 10 dan 20 persen dari seluruh haji asing, walaupun mereka datang dari wilayah yang lebih jauh daripada yang lain.
Martin juga mengutuip catatan dari Jacob Vrendenbregt, dalam artikelnya, The Haddj: Some off its features an functions in Indonesia, yang menyebut; pada dasawarsa 1920-an sekitar 40 persen dari seluruh haji berasal dari Indonesia.
Pada masa itu jumlah haji dari Indonesia memang sangat besar karena beberapa tahun sebelumnya orang Indonesia tidak bisa naik haji sama sekali. Setelah Sultan Turki memproklamirkan jihad pada tahun 1915, pemerintah Hindia Belanda melarang orang naik haji sampai perang berakhir tahun 1918. Oleh karena itu banyak orang yang terpaksa menunda beberapa perjalanan haji mereka secara massal berangkat ketika haji diizinkan lagi.
Selain jamaah haji yang pulang pergi, ada juga jamaah haji yang kemudian memutuskan bermukim di Makkah atau Madinah. Orang Indonesia yang tinggal bertahun-tahun atau menetap di Makkah pada zaman itu cukup banyak. Keterangan ini bisa kita lihat dari catatan Snouck Hurgronje. Hurgronje yang menghabiskan waktu sekitar lima bulan di Makkah pada tahun 1885 itu mencatat bahwa di antara bangsa yang berada di Makkah, orang ‘Jawah’ (Asia Tenggara) merupakan salah satu kelompok terbesar. Sekurang-kurangnya sejak tahun 1860, bahasa Melayu merupakan bahasa kedua di Makkah, setelah bahasa Arab.
Catatan Hurgronje di atas bisa kita bandingkan dengan catatan-catatan lain, catatan yang ditulis oleh orang ‘Jawah’ sendiri. Seperti catatan perjalan yang ditulis oleh pelopor sastra Melayu modern, Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi. Abdullah naik haji jauh sebelum Snouck berangkat ke Makkah, yaitu pada tahun 1854, tidak lama sebelum kapal layar digantikan kapal api.
Selain Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi, masih banyak ulama-ulama atau murid-murid mereka yang berasal dari Nusantara yang mukim atau menetap di sana, yang setelah merasa cukup mencari ilmu lalu memutuskan kembali ke kampung halamannya. Mereka yang pulang itu lalu mencatat apa saja yang didengarnya dan dilihatnya di Makkah. Tidak sedikit yang menulis karya tulis ilmiah dan catatan-catatan lain yang sifatnya lebih khusus, seperti biografi atau manaqib yang ditulis untuk kalangan terbatas, untuk murid dan keluarganya.
Salah satu catatan khusus itu ditulis oleh Kiai Muhammad ibn Sulaiman, yang mencatat perjalanan pendidikan ayahnya sendiri, Syekh Sulaiman. Dalam catatan itu ia menyebut Syekh Sulaiman pernah berangkat Haji sebanyak enam kali. Kemudian di Makkah dia mengambil baiat tarekat Syadzili kepada Syekh Shalih Kamal. Lalu ia juga jumpa dengan dua guru tarekat Syadzili yang juga murid dari Syekh Shalih Kamal, yaitu Kiai Idris Jamsaren ulama asal Surakarta/Solo, dan Kiai Ahmad Nahrawi al Makki ulama yang berasal dari Banyumas, Jawa Tengah.
Belanda mencatat banyak orang yang telah berangkat ke Makkah tidak kembali lagi. Antara tahun 1853 dan 1858, jamaah haji yang pulang dari Makkah ke Hindia Belanda tidak sampai separuh dari jumlah orang yang telah berangkat haji. Tidak kembali bisa karena memutuskan menetap di sana, atau karena kematian. Simbah Syarifah, Buyut Putri saya meninggal di perjalanan. Jenazahnya ditenggelamkan di dasar laut.
Perangsang Antikolonialisme
Seperti biasa, selain membawa pulang doa yang dianggap mujarab, jamaah haji akan pulang membawa oleh-oleh bermacam-macam ujudnya. Ada kurma, kismis, manisan buah Tin, lalu air zam zam sajadah, dan tasbih. Oleh-oleh itu nantinya akan dibagikan kepada kerabat sanak saudara, dan tamu yang berkunjung ke rumahnya. Sebuah tradisi yang melekat hampir di semua daerah dan sudah lama berjalan.
Dulu pada tahun 2006, kita masih bisa menemui pasar tradisional yang berada tepat di sebelah masjidil haram. Pasar itu oleh jamaah haji Indonesia disebut dengan Pasar Seng. Persis dengan pasar di seputaran tempat peziarahan yang kita kenal di Indonesia, seperti lorong jalan masuk menuju Masjid Ampel Surabaya, pedagang-pedagang itu menjajakan beraneka ragam barang dagangan. Mulai dari kurma, pacar, perhiasan, sampai dengan kadal mesir untuk jamu kuat (stamina). Dari semua dagangan itu, ada dagangan yang hampir selalu tersedia di setiap toko, yaitu tasbih.
Meski sekarang sudah jarang orang menggunakan tasbih, bisa jadi karena sudah tidak lagi mengamalkan wirid, atau karena ada tasbih digital yang lebih praktis, tapi masih saja banyak jamaah haji yang memilih tasbih sebagai oleh-oleh. Ini menjadi bukti, bahwa Makkah dan Madinah menyimpan sejarah panjang mengenai gerakan kaum tarekat, yang identik dengan tasbih, ciri utamanya senang berzikir atau mengamalkan ilmu, dan wiridan atau bacaan zikir tertentu yang diijazahkan oleh seorang guru atau mursyid. Gerakan tarekat inilah yang cukup kental mewarnai sejarah ulama Nusantara lulusan Haramain.
Makkah sebagai pusat kosmis, titik temu antara dunia fana kita dengan alam supranatural, memainkan peranan sentral. Tidak hanya diziarahi sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga dikunjungi untuk mencari ilmu, dan legitimasi politik. Sebagai tempat untuk mencari ‘legitimasi politik’ dapat kita lihat dari catatan sejarah yang menyebut pada pertengahan abad ke-17 raja-raja Jawa mulai mencari legitimasi ke Makkah.
Pada tahun 1630-an, raja Banten dan raja Mataram, mengirim utusan ke Makkah, antara lain, mencari pengakuan dari sana dan meminta gelar ‘sultan’. Agaknya raja-raja tersebut beranggapan bahwa gelar yang mereka peroleh dari Makkah akan memberi sokongan supranatural terhadap kekuasaan mereka (Martin Van Bruinessen, 2012). Pengakuan Syarif Besar, yang menguasai Haramain (Makkah dan Madinah) dipercaya memiliki pengaruh spiritual atas seluruh Dar al-Islam, termasuk Mataram dan Banten yang berada jauh di pulau Jawa.
Rombongan utusan dari Banten itu pulang pada tahun 1638, dan utusan Mataram datang agak belakangan pada tahun 1641. Beberapa waktu kemudian, pada tahun 1674, untuk pertama kalinya seorang pangeran Jawa pergi haji ke Makkah. Ia adalah putra Sultan Ageng Tirtayasa (Banten), bernama Abdul Qahar, yang belakangan dikenal sebagai Sultan Haji.
Makkah sebagai pusat ilmu atau ngelmu, juga disinggung dalam banyak catatan. Seperti misalnya dalam karya berbahasa Melayu, Hikayat Hasanuddin, yang dikarang sekitar tahun 1700 Masehi. Sunan Gunung Jati mengajak anaknya:
“Hai anakku ki mas, marilah kita pergi haji, karena sekarang waktu orang naik haji, dan sebagai pula santri kamu tinggal juga dahulu di sini (mukim) dan turutilah sebagaimana pekerti anakku!”
Dalam hikayat itu juga disebutkan bagaimana Sunan Gunung Jati (salah satu dari anggota dewan ulama di Jawa, Walisongo-Sembilan Wali) mengajari putranya cara menjalankan ibadah haji, dan ibadah lainnya, seperti thawaf, mencium hajar aswad, dan mengunjungi para syekh atau guru-guru di Makkah dan Madinah. Dari para guru tarekat yang diziarahinya, Sunan Gunung Jati dan putranya melakukan baiat tarekat Naqshabandiyah yang disebutnya ajaran ilmu sempurna.
Dalam mitologi Jawa juga menyebut cerita tentang Makkah sebagai pusat spiritual. Ini ada dalam Legenda Tengger yang diceritakan ulang dalam Tengger en de Tenggereezen oleh J.E. Jaspert. Dalam Legenda Tengger itu, disebutkan Aji Saka yang dikenal sebagai pencipta aksara Jawa, kalender Jawa (tahun saka) dan undang-undang Jawa, pernah pergi ke Makkah dan memperoleh ilmu dari Nabi Muhammad saw. Menurut Legenda Tengger, Aji Saka pada awalnya memperoleh ilmu dari Antaboga, sang raja naga. Setelah dikembalikan ke rumah kakeknya, Kiai Kures (Quraisy), sang kakek melihat cucunya luar biasa cakap. “Tetapi ada satu yang lebih cakap dari ia, “ Ujar Antaboga, “namanya adalah Muhammad dan tempat tinggalnya adalah di Makkah. Kirimlah cucumu kepada beliau agar menambah ilmu.” Aji lalu dikirim ke Makkah, dan di sana berguru kepada Nabi Muhammad saw. Setelah selesai belajar, Muhammad memberikannya sebuah kropak (buku lontar) dan pangot (pisau untuk menulis atas lontar), dan mengirimnya kembali ke Timur.
Martin dalam buku yang sama, juga menulis daftar beberapa nama orang Indonesia yang telah naik haji dan mencari ilmu di tanah Suci. Seperti Syaikh Yusuf Makassar berangkat ke Makkah pada tahun 1644 dan baru kembali ke Indoneisa sekitar tahun 1670. Di Makkah Syekh Yusuf belajar kepada banyak ulama besar, terutama ulama tasawuf, ia memperoleh ijazah untuk mengajar beberapa terekat. Selain mempelajari ilmu tasawuf, ia juga mempelajari filsafat, ilmu kalam dan yang lain.
Selain mengajarkan tarekat Khalwatiyah, ia juga punya peranan politik penting sebagai penasehat Sultan Ageng Tirtayasa. Ketika Kompeni Belanda mencoba menyingkirkan Sultan Ageng, Syekh Yusuf membawa pengikutnya ke gunung dan memimpin gerilya melawan Belanda selama hampir dua tahun, sampai akhirnya ditangkap dan dibuang ke Seylon, Sri Lanka.
Selain Syekh Yusuf masih ada banyak lagi orang Indonesia yang pergi haji, mencari ilmu di Makkah-Madinah, lalu pulang berjuang untuk tanah airnya. Dalam Mekka, Snouck Hurgronje mencatat bagaimana orang dari seluruh Nusantara ikut membicarakan perlawanan Aceh terhadap Belanda, dan bagaimana mata mereka dibuka mengenai penjajahan Belanda, maupun Inggris dan Prancis atas bangsa-bangsa Islam. Martin menyebut, saat itu para Haji hidup beberapa bulan dalam suasana antikolonial, yang sangat berbekas.
Pemberontakan petani Banten 1888 dan pemberontakan Sasak 1982 melawan Bali disebut diilhami oleh pengalaman tokoh-tokoh yang pernah tinggal di Makkah.
Dalam, Jogjakarta under Sultan Mangkubumi, 1749-1792, M.C. Ricklefs menyebut pada tahun 1772, seorang ulama kelahiran Palembang yang menetap di Makkah menulis surat kepada Sultan Hamengkubuwono I dan kepada Susuhan Prabu Jaka. Isinya, rekomendasi bagi dua orang haji yang baru pulang dan mencari kedudukan. Dalam pendahuluan surat itu ada pujian terhadap raja-raja Mataram terdahulu yang telah berjihad melawan Kompeni. Surat-surat ini dapat dibaca sebagai anjuran untuk meneruskan jihad melawan penjajah.
Ulama-ulama seperti Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfudz Tremas, dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, yang mengajar di Makkah pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, mengilhami gerakan agama di Indonesia dan mendidik banyak ulama yang kemudian berperan penting di tanah air.
Dari contoh di atas kita melihat beberapa fungsi sosiologis haji. Orang Indonesia mencari ilmu di Haramain (Makkah dan Madinah) dan setelah pulang ke tanah air mereka mengajarkan kepada masyarakat ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari. Sebagian dari mereka merasa tidak cukup hanya mengajar saja, mereka juga merasa perlu membuat wadah untuk menyatukan sesamanya. Maka lahirlah organisasi-organisasi Islam seperti Sarekat Islam (SI), Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kiai Hasyim Asy’ari dan Kiai Ahmad Dahlan, keduanya adalah alumni Haramain, murid dari Nawawi Banten, Mahfudz Tremas dan Ahmad Khatib Minangkabau.
Saya sepakat dengan Martin van Bruinessen, bahwa Islamisasi di Indonesia sudah berlangsung sejak abad ke-13 dan masih terus berlanjut sampai sekarang. Entah siapa yang pertama-tama membawa Islam ke Indonesia, apakah orang India dari Gujarat, Arab, atau malah Cina (soal Cina, bisa lihat penjelasan Buya Hamka), yang jelas sejak abad ke-17 peranan utama dimainkan oleh orang Nusantara sendiri yang telah belajar di tanah suci.
*****
Bagus Sigit Setiawan
Kartasura, September 2018
Pada 1913, Tjitpto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Surjaningrat berangkat ke Belanda, risiko atas keberanian mendirikan Indische Partij dan pembuatan selebaran Als ik eeens Nederlander was… Di mata penguasa kolonial mereka pembuat onar. Pilihan ke Belanda akibat politik. Pada tahun itu pula, berangkat lelaki bermimpi jadi modern dan menuai berkah zaman “kemadjoean”. Lelaki berasal dari Mangkunegaran (Solo), bernama Soeparto. Kedatangan ke Belanda mendahului Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat. Ia tak hendak berpolitik meski saat di Solo turut di Boedi Oetomo dan menulis di Darmo Kondo. Di Belanda, ia ingin menempuh studi bahasa dan sastra agar terhormat dan memiliki pijakan membaca dunia modern.
Perjalanan ke Belanda mendapat restu dan sokongan para sarjana dan pejabat kolonial: Rinkes, Van Wijk, dan Van Deventer. Soeparto seperti sedang menjalankan tugas suci agar menjadi juru penerang saat kembali ke Jawa (Harry A Poeze, Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950, 2008). Ikhtiar besar dimulai dengan menulis catatan harian berdalih terbit menjadi buku. Sebelum meninggalkan Jawa, Soeparto dan Rinkes bermufakat bakal mengadakan buku berisi kisah perjalanan. Soeparto dianjurkan rutin menulis dan mengirimkan ke Rinkes. Tulisan-tulisan mau diterbitkan oleh Commisie voor de Volkslectuur. Perjalanan ditempuhi 14 Juni-17 Juli 1913. Buku terbit pada 1916. Soeparto mendapat honor besar. Rinkes lega berhasil menerbitkan buku mengabarkan Eropa atau Belanda melalui pengalaman Soeparto untuk dibaca kaum bumiputra.
Semula, buku terbit dalam aksara dan bahasa Jawa. Buku berusia seratus tahun hampir tak mendapat pembaca pada abad XXI. Buku lama terlupakan. Kini, buku tak lagi menjadi penghuni sepi di Mangkunegaran. Kerja penerjemahan ke bahasa Belanda dan bahasa Indonesia diinginkan mengundang pembaca menilik masa lalu. Buku berhasil terbit dalam edisi terjemahan bahasa Indonesia oleh Frieda Amran berjudul Kisah Perjalanan Pangeran Soeparto, Jawa-Belanda, 14 Juni-17 Juli 1913 (Penerbit Buku Kompas, 2017). Buku mengantar pembaca ke pengandaian naik kapal, berpisah dari Jawa, melintasi pelbagai negeri, dan merasakan ketakjuban pada Eropa. Kita membaca dengan mata masa lalu.
Pada 14 Juni 1913, Soeparto meninggalkan Solo menuju Semarang. Ia hendak pergi ke Belanda.
Di Semarang, ia naik kapal Wilis untuk menempuhi perjalanan jauh, selama sebulan. Pada saat naik perahu menuju kapal Wilis, Soeparto mencatat: “Di sebelah selatan, sejauh mata memandang, tampak siluet Semarang, kota cantik di pinggir laut melambangkan kemakmuran Jawa.” Pujian sempat ditulis dalam kalimat bersahaja dan puitis, sebelum ia meninggalkan Jawa. Ia pun berpisah dari keluarga. Seoparto mengaku pilu setelah adegan terakhir: ia di kapal bergerak dan keluarga melambaikan topi atau sapu tangan.
Kepergian ke Belanda tak bermisi pelesiran tapi pelajaran. Di negeri jauh, Soeparto ingin maju dengan mempelajari bahasa, sastra, dan militer. Jawa telah berubah. Soeparto pun ingin turut dalam “doenia bergerak” dengan bekal ilmu dan tata cara hidup baru. Perpisahan sedih pada keluarga dan Jawa ingin digantikan “sukacita melihat negeri kecil tetapi berani sehingga mampu menjajah negeri lima puluh kali lebih besar dan berpenduduk tujuh kali lebih banyak.” Negeri kecil itu Belanda. Negeri besar itu Hindia Belanda.
Pada saat meninggalkan pelabuhan Pekalongan, Soeparto melihat Jawa dengan sedih bercampur pujian. Perasaan dituliskan mirip pendefinisian Jawa: “Pulau itu, pulau kelahiranku, tersohor di seluruh dunia karena kesuburan dan kemakmuran.” Ia pun mengakui jika kemonceran Jawa mengakibatkan bangsa-bangsa asing berdatangan mencari untung berlimpahan. Soeparto mencatat nasib tanah jajahan “menjadi mutu manikam di mahkota Kerajaan Belanda.” Kemakmuran dimiliki Belanda, dicipta dan didatangkan dari Hindia Belanda selama ratusan tahun. Soeparto tentu tak gamblang memberi kritik ke Belanda. Catatan itu sengaja dihindarkan dari bahasa politik.
Di kapal bernama Wilis, Soeparto adalah penumpang di kelas dua. Perjalanan selama sebulan memerlukan ketabahan dan siasat melawan bosan. Sedih meninggalkan Jawa dan impian lekas menginjak tanah di Belanda perlahan menjadi alinea-alinea apik, puitis, dan bertaburan pesan. Soeparto bercerita keadaan di kapal: “… penumpang menghabiskan waktu dengan mengobrol, bergurau, atau membaca buku.” Penumpang berhak meminjam di perpustakaan di kapal. Tata cara hidup modern atau Eropa berlaku di kapal. Soeparto “menuruti” meski tak semua hal memberi girang selaku manusia Jawa. Urusan makan, busana, musik, bacaan, dan bahasa selalu mengesankan “pemaksaan” mengikuti aturan-aturan Eropa.
Kapal Wilis sempat singgah ke Batavia selama tiga hari. Soeparto turun dan mengelilingi Batavia. Ia sudah pernah berkunjung ke Batavia. Catatan pun tampak penuh keterangan akibat pengalaman dan ingatan ke pelbagai sumber berita.
Ia memilih menceritakan pakaian dikenakan orang-orang di Batavia. “Kaum perempuan biasa mengenakan kebaya katun berwarna dasar putih dengan motif bunga-bunga warna-warni. Mereka juga mengenakan gelang, giwang kecil, dan peniti tumbuk tiga disematkan di kebaya,” tulis Soeparto. Pengamatan tak melulu ke perempuan. Catatan untuk pakaian kaum lelaki: “Kaum lelaki mengenakan jas putih dan celana serupa dengan pakaian lelaki Eropa. Tetapi, di atas celana itu, lelaki Batavia melilitkan sebuah sarung dilipat dua sehingga kaki celana cuma tampak di bawah lutut. Kepala mereka tertutup oleh kain dibelit khas Batavia.” Pengisahan itu tak bakal membuat pembaca pusing. Soeparto bertugas mengisahkan, tak bermaksud pamer pemikiran atau renungan.
Soeparto tak serampangan berimajinasi Belanda.
Selama di Jawa, ia sudah bergaul dengan kalangan sarjana dan pejabat kolonial. Embusan modernitas di Jawa memicu perubahan-perubahan dan memungkinkan kebaruan tercipta, hasil persilangan Jawa-Eropa. Keadaan Jawa pada awal abad XX menjadi latar ambisi kemajuan Soeparto melalui perkumpulan modern, pers, pekerjaan, dan sastra. Pemenuhan kehendak ke Belanda adalah bukti membentuk diri modern tanpa meninggalkan kejawaan. Soeparto tetap manusia Jawa tapi memiliki nalar dan imajinasi baru saat menjadi penerus kekuasaan di Mangkunegaran, sepulang dari Belanda, 1916. John Pemberton (2003) dalam buku berjudul “Jawa” mengakui hasrat maju atau modern itu malah mengejawantahkan pemulihan semangat Jawa di Mangkunegaran. Soeparto atau Mangkunagoro VII menjadi teladan di Jawa dalam adonan pemberlakuan Politik Etis, modernisasi Jawa, dan deru nasionalisme.
Sejak lama, orang-orang dari tanah jajahan pergi ke Belanda dengan pelbagai misi. Pada akhir abad XIX, studi ke Belanda mulai jadi lumrah. Kita mengenang Sosrokartono, Di Belanda, ia berpedikat mahasiswa dan berlanjut menjadi wartawan. Kartini sempat iri tapi gagal menuju Belanda. Pada awal abad XX, orang-orang dari pelbagai pulau mulai berkuliah ke Belanda, mempelajari kedokteran, hukum, teknik, pendidikan, dan sastra. Soeparto ada di urutan agak belakang untuk mendapat julukan elite terpelajar. Kita bisa menilik tata cara menjadi modern dan perwujudan kesarjanaan itu melalui buku Robert van Niel berjudul Kemunculan Elite Modern di Indonesia.
Pada hari-hari menjelang tiba di Belanda, Soeparto sempat merenung mengandung minder. Pada usia masih muda seribu impian menghuni di kepala. Semua demi pamrih maju dan modern. “Apakah ada sekolah di Eropa mengajarkan kefasihan berbicara? Sepanjang kuketahui, semua orang Belanda yang pernah belajar di Eropa mudah memulai obrolan dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka juga fasih memberi sepatah kata ketika harus berpidato,” tulis Soeparto. Renungan itu sebelum ia menjadi tokoh moncer di Jawa bergelar Mangkunagoro VII. Kedudukan terhormat memastikan harus fasih bicara dan berpidato di muka umum. Di mata pemerintah kolonial, Mangkunagoro VII berkemungkinan melawan bermodal kemahiran berbahasa dan ketekenunan bersastra berjiwa kebaruan.
Pada saat turun dari kapal dan melangkahkan kaki di Marseille (Prancis), Soeparto sempat gelisah memikirkan Jawa ketimbang mengimpikan kenikmatan hidup setiba di Belanda. Marseille itu keajaiban. Soeparto tak usai takjub. Di hati, Soeparto menemukan situasi berbeda ada di Jawa. Pada pertengahan Juli 1913, ia menulis: “Saat ini, orang-orang Jawa sangatlah miskin sehingga terkesan mereka tidak memiliki kekuatan maupun kekuasaan.” Belanda sudah dekat tapi perasaan Soeparto terasa sedih berkepanjangan. Takjub pada Eropa dan sedih pada Jawa.
Pada perjalanan sampai di Afrika, pengisahan mulai menimbulkan penasaran ke pembaca. Kondisi tanah, cuaca, penghuni, dan situasi kota-kota di Afrika membuat Soeparto terkejut. Ia gampang teringat Jawa molek, subur, dan makmur. Di Laut Merah, Soeparto malah tekun menulis di buku catatan mengenai kagum langit. Di kapal, mata melihat langi sering berubah warna. “Aku tak dapat menemukan kata-kata tepat untuk menggambarkan aneka warna langit itu. Tak mungkin bisa mengungkapkan. Lagi pula, warna-warna itu tida begitu saja berubah menjadi warna lain, tetapi perlahan mengalir, bersatu dan berpisah lagi.” Langit pun lekas mengingatkan pada Jawa. Ia menulis bukan sebagai pujangga. Tulisan mirip kesan penglihatan: “Di Jawa, keindahan langit dipengaruhi oleh awan disinari matahari terbit atau terbenam.” Pengisahan langit mungkin agak menuntun pembaca di Jawa ke imajinasi memukau pada negeri-negeri jauh.
Pada hari-hari mendekati Belanda, Soeparto mulai kagum pada negeri-negeri di Eropa.
Selama di kapal, ia sudah menganggap penumpang Eropa memiliki adab tinggi dan tertib. Mereka merasa unggul ketimbang bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Soeparto mengagumi meski memiliki kebencian akibat lakon kolonialisme. Di buku, Soeparto menulis dan meramalkan diri: “Alangkah bahagia hatiku bila tercapai mimpiku untuk dianggap setara dan sederajat dengan orang yang menjajah Jawa, tanah kelahiranku.” Pikat Eropa telah memunculkan mimpi muluk bagi lelaki asal Jawa. Kita mungkin menuduh Soeparto memiliki identitas ambigu: ingin tetap menjadi Jawa tapi berhasrat modern sesuai selera Eropa.
Soeparto berhasil tiba di Belanda, berjumpa para mahasiswa tergabung di Indische Vereniging. Ia pun berjumpa para profesor dan pejabat Belanda. Kehidupan di Belanda tampak terang dan makmur. Ingatan pada Jawa adalah kebalikan sulit dimaklumi. Di Belanda, Soeparto menunaikan studi, tak kental berpolitik. Perjumpaan dan persahabatan dengan Noto Soeroto, pujangga asal Jawa menulis berbahasa Belanda, menghasilkan buaian sastra. Politik nasionalisme tampak ada di kejauhan. Soeparto memilih membaca dan menerjemahkan puisi-puisi Rabindranath Tagore ke bahasa Jawa. Ia keranjingan mempelajari peradaban Timur-Barat ketimbang sibuk berpolitk dan mengumbar kritik ke pemerintah kolonial. Pilihan sikap itu terbukti saat pulang ke Jawa menjadi Mangkunagoro VII. Biografi telah berubah, tak lagi harus tergantung pada kalimat-kalimat di buku perjalanan atas pesanan Rinkes. Buku itu masa lalu.
Seratus tahun berlalu, pembaca ada di hadapan buku terjemahan perjalanan Soeparto, dari Jawa ke Belanda. Kita membaca sambil membuka buku-buku sejarah. Kita ingin mengenali tokoh dengan membuka daftar ratusan nama elite terpelajar selaku penggerak “kemadjoean” sejak awal abad XX. Soeparto berhasil menjadi tokoh. Pulang dari Belanda, ia adalah Mangkunagoro VII: penggerak Jawa di jalan kemodernan dengan kekuasaan, busana, bahasa, pers, dan kesusastraan. Begitu.
Bandung Mawardi
Kuncen Bilik Literasi
Penulis buku Omelan: Desa, Kampung, Kota (2018)
Berbicara Sejarah Banyuwangi, tak bisa terlepas dari arsip-arsip Belanda. Terhitung sejak 1767, kolonialisme Belanda telah bercokol di Bumi Blambangan. Lebih-lebih, tak banyak sumber lokal yang bisa dirujuk sehingga hal ini menempatkan arsip Belanda menjadi sumber primer.
Celakanya, arsip-arsip Belanda tersebut, melahirkan dua kesulitan sekaligus. Pertama, arsip-arsipnya hampir tak ada yang tersimpan di Banyuwangi. Jika tidak di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta, ya ada di Lieden, Belanda. Butuh waktu, tenaga dan juga biaya, bukan?
Soal bahasa adalah ihwal yang lebih menyulitkan lagi. Semua arsip tersebut, sudah barang tentu berbahasa Belanda. Bahasa yang berlaku pada masa itu. Tak banyak penggiat sejarah di Banyuwangi yang memiliki kompetensi tersebut.
Di tengah kesulitan demikian, datanglah seorang bernama Pitoyo Boedi Setiawan. Ia dilahirkan dari pernikahan seorang serdadu sukarelawan berkebangsaan Belanda yang menikahi blesteran Jawa-Negro. Ia lahir dan tumbuh di Purworejo, Jawa Tengah bersama kelima saudaranya.
Pada masa Jepang, ia bersama beberapa saudaranya sempat di tahan. Kemudian, dilepaskan setelah pasukan Dai Nippon itu hengkang usai Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Tiga saudaranya, mengikuti kewarganegaraan sang ayah dan tinggal di Belanda, sedangkan Pitoyo bersama seorang saudaranya memilih tetap menjadi warga Indonesia.
Pitoyo tinggal di Surabaya, ia bekerja di pelayaran sekaligus memiliki biro travel. Di kota itu ia membangun biduk rumah tangga pertamanya. Meskipun akhirnya harus bercerai, namun perceraian itu menjadi titik balik bagi kehidupannya. Setelah bercerai dengan istri pertamanya, ia memutuskan untuk pindah ke Banyuwangi. Ia meminang seorang gadis yang dikenalnya kala mengantar tamu dari Perancis untuk berwisata di Banyuwangi dan Bali. Perempuan yang disuntingnya tersebut adalah Artatik. Seorang janda dari seniman Banyuwangi, Fatrah Abal.
Keputusan Pitoyo menikahi Artatik dan memilih tinggal di Banyuwangi, mengantarkan hidupnya pada takdir yang lain. Kemampuannya berbahasa Belanda (dan juga Inggris) sejak kecil, menjadikannya sebagai penerjemah arsip-arsip Belanda tentang Banyuwangi.
Dwi Pranoto, seorang penggiat sejarah di Banyuwangi mendapat tugas untuk mencari sejarah lahirnya Banyuwangi. Ia pun mengakses arsip-arsip Belanda di ANRI. Arsip-arsip tersebut kemudian diserahkan kepada Pitoyo untuk diterjemahkannya. Bisa jadi, Pranoto mengetahui kemampuan Pitoyo itu dari Fatrah Abal. Meskipun telah bercerai, ia masih menjalin hubungan baik dengan bekas istrinya itu, bahkan dengan suami barunya.
Sampai saat ini, hasil terjemah dari Pitoyo tersebut, masih berupa manuskrip. Tulisan tangan, yang pernah diterbitkan – sejauh pengetahuan penulis – hanya Blambangansch Adatsrecht.
Dengan penuh ketekunan, Pitoyo menerjemahkan arsip-arsip tersebut. Bahkan, ia meminta saudaranya di Belanda untuk mengakses arsip-arsip lain yang tersimpan di Belanda. Atas jasa-jasanya inilah, banyak kisah tentang Banyuwangi yang terkuak. Mulai dari peperangan Puputan Bayu (1771 – 1772) hingga perkembangan tari Gandrung yang menjadi ikon Banyuwangi.
Hasil terjemahan dari Pitoyo itulah kemudian menjadi rujukan para penulis dan penggiat sejarah di Banyuwangi. Seperti terjemahnya atas De Indische Gids II yang ditulis oleh C. Lekkerkerker (1923), Blambangansch Adatsrecht karya Dr. Y.W. de Stoppelaar (1926), hingga Gandroeng van Banjoewangi karya John Scholte (1927).
Sampai saat ini, hasil terjemah dari Pitoyo tersebut, masih berupa manuskrip. Tulisan tangan, yang pernah diterbitkan – sejauh pengetahuan penulis – hanya Blambangansch Adatsrecht. Karya tersebut diterbitkan oleh Pusat Studi Budaya Banyuwangi (PSBB) pada 1991 dengan judul Hukum Adat Blambangan.
Selain itu, karya terjemah Pitoyo hanya ditemukan dalam kutipan di artikel karya penulis-penulis Banyuwangi. Seperti Hasan Ali, Fatrah Abal, Dwi Pranoto, Armaya dan lain sebagainya.
Karya terjemah Pitoyo atas arsip-arsip Belanda itu, kini kembali menggema. Sengker Kuwung Belambangan, sebuah NGO kebudayaan berbasis di Banyuwangi kembali menerbitkan karya terjemah Pitoyo. Kali ini adalah terjemah jilid kesebelas dari De Opkomst van het Nederlandsch gezag in Nederlandsch-Indie/ Java yang disunting oleh Jhr. Mr. J.K.J de Jonge dan M.L. van Deventer.
Terjemah yang diterbitkan dengan judul Belanda di Bumi Blambangan: Naskah-Naskah Arsip Kolonial Lama yang Belum Diterbitkan (Oktober: 2018) itu, memang tak keseluruhan. Hanya beberapa bagian buku saja yang diterjemahkan. Utamanya yang berkaitan langsung dengan Banyuwangi. Paling banyak adalah arsip berupa surat yang ditulis oleh seorang Gubernur Jendral Hindia Belanda G.J Petrus Albertus van der Parra (w. 1775), ada delapan surat yang diterjemahkannya. Adapula empat arsip yang ditulis oleh Johannes Vos, seorang Gubernur dari Pesisir Timur Laut Jawa yang menjabat pada 1761-1765.
Setidaknya, ada tiga orang yang turut berjasa dalam mewujudkan buku primer dalam kajian sejarah Banyuwangi ini. Ialah Kang Munawir dan Banjoewangi Tempoe Doeloe (BTD) yang telah meluangkan waktu untuk mengarsipkan manuskrip terjemah karya Pitoyo dan mengetiknya ulang. Kemudian, Mas Emha Aji Rawamidi yang mengeditorinya, serta Mas Antariksawan Jusuf yang berusaha untuk mewujudkannya sebagai buku.
Waba’du, buku ini amat penting untuk para pengkaji sejarah Banyuwangi. Menyajikan sumber-sumber primer. Namun, bagi kalangan pemula (awam), membaca buku ini perlu bacaan-bacaan pendamping agar bisa mengerti alur ceritanya dengan baik. Selain Ujung Timur Jawa 1763-1813: Perebutan Hegemoni Blambangan (Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2012) karya Sri Margana, juga ada Suluh Blambangan 1 & 2 (Banyuwangi: SKB, 2017) karya M. Hidayat Aji Rawamidi.
Selamat Membaca.
Kenangan yang paling lekat musabab menghadiri penutupan Festival Film Merdeka (FFM) 2018 ialah absennya film-film karya sineas Solo dalam daftar putar. Sebagian besar film yang diputar di tahun kedua FFM justru datang dari Kota Yogyakarta. Walaaah. Dari sembilan jumlah film yang diputar di beberapa titik putar sasaran FFM, hanya tiga buah film yang diproduksi oleh sineas luar Yogyakarta. Ketiga film itu: Hit Love (2017) karya sineas Tangerang, Ibnu Rusd L; Amak (2017) karya sineas Padang, Ella Angel; dan JiDullah (2017) karya sineas Jember, Alif Septian Raksono. Ketiga film itulah yang menolong FFM tahun ini tak terjebak pada buai Yogyakarta sentris.
Sayup-sayup obrolan bersama beberapa teman ngrasani geliat Kota Yogyakarta muncul di pintu telinga. Tidak lama lagi Yogyakarta akan bertarung melawan Jakarta utamanya dalam dunia industri kreatif. Demikian kami berbuih-buih mengobral obrol di angkringan. Perkara film, kita sama-sama bisa melihat Yogyakarta terus tumbuh menjadi laboratorium film masyhur di Indonesia. Begitu kami meneruskan obrolan. Sampai secangkir kopi, es teh kampul dan aneka bakaran habis, kami lupa mengingat Solo dalam obrolan membahas film. Solo terlupakan.
Solo gagal basah oleh pujian berkait film. Berbeda dengan ratusan festival dengan sematan nasional atawa internasional yang terus menggoda minat wisatawan. Film barangkali dinilai tak cukup mumpuni diberi wadah berjuluk festival “legal” khas pemerintah kota. Oleh karenanya, sampai tahun kedua penyelenggaraannya, FFM belum masuk di kalender kegiatan tahunan ciptaan pemerintah kota.
Sejak mula, FFM yang pertama kali diadakan tahun 2017 nampak betul berambisi mulia menjadikan gelaran ini sebagai milik masyarakat di kantong-kantong kampung Kota Solo. Pelaksanaan FFM tahun lalu menghasilkan candu. Dalam selebaran, panitia menulis dengan tinta bahagia, “Berhasil merangkul enam kampung di lima kelurahan di Solo pada bulan Agustus yang penuh kemerdekaan untuk membaur bersama memutar dan menonton film…”
Tahun ini ada enam titik putar yang menjadi sasaran FFM. Titik-titik itu meliputi Rumah Baca Sangkrah, Pasar Kliwon, Rumah Baca Tumpi Boyolali, Kampung Ngasinan, Kampung Batik Laweyan, dan Pelataran Pasar Triwindu. Jika festival-festival yang sudah ada dominan diselenggarakan di pusat kota, FFM memungkirinya. Gelaran ini menghampiri sudut-sudut kampung seperti lapangan dan rumah baca. Model gelaran seperti inilah yang rasa-rasanya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan juga geliat kampung yang bersangkutan. FFM merupa sumber mata air di tengah jengah menghadapi keseragaman beragam festival di Kota Solo yang bermotif politis-ekonomis.
Amak, The Unseen Words, Incang-inceng, dan Ruah bergantian ruang di layar putih di pelataran Pasar Triwindu Ngarsopuro Solo. Sutradara asal Padang, Ella Angel menceritakan nasib perempuan tua yang tak dapat mengelak dari kesendirian. Dalam tradisi Minangkabau, seorang perempuan seharusnya menjadi Bundo Kanduang yang tinggal di rumah untuk menjaga harta pusaka yang kelak diperuntukkan kepada turunannya. Tradisi Bundo Kanduang perlahan tetas oleh gegar zaman di mana anak-anak perempuan Minang kian berminat pergi merantau. Di rumah, amak menghalau sepi dengan album foto dan kenang-kenangan sebelum ia tinggal di rumah seorang diri.
Dalam The Unseen Words, kesepian para penyandang tunanetra lebur jadi semangat berkarya. Sanggar Distra Budaya Yogyakarta sepenuhnya beranggotakan para penyandang tunanetra. Di sanggar itulah, mereka terus berlatih melawan keterbatasan. Hal-hal yang umumnya dikerjakan orang-orang dalam kondisi fisik normal nyatanya bukan hambatan bagi mereka. Tekad dan kerja sama yang solid antar-anggota sanggar kendati tak selalu menghasilkan rupiah yang memadahi, nyatanya menyehatkan jiwa mereka.
Kerja sama yang solid juga menjadi nilai penting dalam Incang-inceng. Anak-anak berbeda kepribadian yang sama-sama minim teman akhirnya menjadi sebuah tim sepakbola antar-kampung dan berhasil sampai pada babak final. Kesolidan tim diuji ketika salah satu pemain gagal menendang bola ke gawang saat mendapat kesempatan pinalti. Sempat dicecar karena gagal mencetak gol, teman-teman satu timnya toh tak membiarkan si gagal ini dihadang tim lawan saat perjalanan pulang. Incang-inceng membawa narasi besar dengan kemasan sederhana. Bahwa sejak masa anak-anak pun usaha optimal tak selalu membuahkan hasil yang diharapkan. Sejak menjadi anak-anak rupanya manusia sudah banyak sekali belajar nilai-nilai hidup. Apa itu usaha, kerja sama, kekalahan, juga keberhasilan yang ujudnya senantiasa bayang-bayang.
Keberhasilan dalam film Ruah merupa cilaka. Haji Halim yang kaya harta bermaksud menikahi janda muda meski tanpa restu istrinya. Haji Halim berdalih pernikahan keduanya sebagai ibadah sosial. Padahal sejatinya lebih kepada pelampiasan nafsu jalangnya kepada perempuan. Setelah pernikahannya yang kedua, Haji Halim masih lirik sana-sini. Ruah ialah sikap sineas Makbul Mubarak menghadirkan fenomena yang demikian santer belakangan ini. Orang-orang yang telanjur dikenal masyarakat saleh ritual berambisi saleh sosial –menurut kaca mata pribadinya—melalui pernikahan-pernikahan lanjutan. Menikahi perempuan-perempuan yang katanya “butuh” pertolongan.
Haji Halim mewakili sosok-sosok dalam kehidupan kini yang saleh ritual tapi gagal saleh sosial menurut pandangan masyarakat. Ialah potret lelaki yang mengunggulkan maskulinitas dan abai pada femininitas. Ia menganggap perempuan sekadar sebagai pelayan dan pemuas hasrat kelelakiannya. Bukan sebagai pasangan hidup yang berhak dihargai suaranya. Sosok-sosok seperti Haji Halim ini jelas jauh dari sosok Nabiyullah Muhammad SAW.
Prof. Dr. H. Quraish Shihab, M.A dalam bukunya yang berjudul Perempuan (2018) menguraikan sebab-sebab rasul menikah lagi. Semua perempuan yang dinikahi Rasul sudah tidak muda lagi usianya, kecuali Aisyah ra. Di antara para perempuan yang tak lagi muda itu ialah perempuan-perempuan yang terancam keselamatan dan kesejahteraannya di masa perang. Yang perlu menjadi perhatian kita ialah Rasul baru berpoligami setelah sekian waktu Khadijah meninggal. Hidup Rasul bermonogami jauh lebih lama dibanding hidupnya saat berpoligami. Kepada Haji Halim dan lelaki-lelaki sejenis di dunia mutakhir, pertanyaan Abi Quraish dan para perempuan seperti saya kemudian ialah: Apakah benar kalian (para lelaki yang bertekad saleh sosial) benar-benar ingin meneladani Rasul dan pernikahannya? (Hlm. 187). Tsah! []
Jauh sebelum Nusa-Antara ini berbentuk negara-bangsa dan Bahasa persatuannya belum lagi dirumuskan, sastra populer dalam bahasa lingua-franca Melayu Rendah sudah memulai debutnya memenuhi hasrat literasi orang banyak. Memang, di sisi lain muncul lebih awal khazanah Sastra Melayu Klasik yang bagi sebagian pihak dianggap tonggak awal lahirnya sastra Indonesia. Sebutlah Hikayat Abdullah karya Abdul Kadir Bin Munsyi yang manuskripnya berhuruf Jawi sudah selesai tahun 1849. Begitu pula karya-karya Hamzah Fansuri yang digubah dalam abad ke-16 dianggap A. Teeuw memiliki rintisan syair modern. Akan tetapi saya beranggapan karya Melayu Klasik tetaplah Melayu Klasik, alih-alih sastra daerah sebagaimana suluk Ronggowarsito atau kabanti Muhammad Idrus Kaimuddin di Buton .
Singkat hikayat, sebelum “sastra kanon” yang dengan hormat kita sebut sastra Indonesia modern lahir, pada tahun 1875 sudah muncul roman Lawah-Lawah Merah yang menandai tonggak Kesusasteraan Melayu Rendah.1 Penamaan ini merujuk realitas penggunaan bahasa Melayu Pasar dalam pergaulan sehari-hari, sehingga ada yang menyebutnya bahasa Melayu Kerja (untuk membedakannya dengan Melayu-Sekolah, yang formal). Semua golongan masyarakat, mulai pribumi, Belanda totok, peranakan Tionghoa dan Indo, menggunakan bahasa ini. Otomatis, ketika digunakan sebagai bahasa tulis, para penulisnya juga berasal dari berbagai latar belakang etnik, bangsa dan Budaya.
Melihat pemakaiannya yang luas, Pramoedya Ananta Toer, seperti biasa, memiliki kemampuan menamainya dengan ungkapan lebih sublim: Sastra Lingua-Franca.2 Potensi lingua-franca inilah yang hendak direngkuh kolonial Belanda, tapi dari aspek Bahasa Melayu Tinggi, sembari menolak realitas lingua-franca Melayu Rendah—demi politik bahasa yang akan menyatukan daerah jajahan, dengan agen kaum terpelajar.
Munculnya Penerbit Balai Pustaka (BP) menandai proyek ini, dengan produk pertamanya Azab dan Sengsara Seorang Gadis (1919) karya Merari Siregar.3 BP juga mempunyai majalah dwi-mingguan bernama Pandji Pustaka dengan rubrik andalan “Memajukan Kesusasteraan” asuhan Sutan Takdir Alisjahbana (STA). Sejak itu, jalur literasi Indonesia bersimpang dua: satu bertahan dengan bahasa Melayu Rendah yang produknya digolongkan sebagai sastra populer, dan kedua sastra Melayu Tinggi sebagai representasi bahasa kaum terpelajar, intelektual dan mengandung nilai keindahan yang dianggap menitis dalam sastra Indonesia modern (untuk mempermudah pembahasan saya sebut sebagai sastra non-populer).
Peranan Pemuda
Para pemuda terpelajar-nasionalis kemudian “mengambil-alih” proyek kolonial ini. Tentu tanpa mengabaikan bahwa gagasan yang sama, dalam waktu yang sama atau mungkin lebih awal, juga sudah berkecambah di benak mereka. Tapi apa pun, “proyek” kolonial mempercepat atau mempertegas upaya “pengambil-alihan”. Tak pelak, para pemuda menjadikannya sebagai proyek kebangsaan yang memunculkan produk sosial-budaya-politik Sumpah Pemuda, Oktober 1928. Sejak itu, disadari atau tidak, simpangan sastra populer dan sastra non-populer kian menajam, oposisi lingua-franca Melayu Rendah vs Melayu Tinggi kian menjadi (sekalipun dalam kajian cultural-studies belakangan tak ada batas-batas yang jadi halangan).
Sumpah Pemuda yang berhasrat menjunjung tinggi bahasa persatuan (Bahasa Indonesia) serta kolonialis Belanda yang menyokongnya di satu sisi—belakangan diketahui setengah hati—membuat dunia literasi akhirnya merujuk penuh bahasa lingua franca ala Melayu-gedong. Balai Pustaka sendiri sebenarnya bukan hanya institusi yang mereproduksi standar estetika sastra, namun juga menyasar, jika bukan menyensor, sisi ideologis sebuah karya. Itulah misalnya yang terlihat dari dua karya Abdul Muis. Menurut C.W. Watson (via Jakob Sumardjo, 2004: 32), novelet Abdul Muis Saidjah (1913) yang ditulis dalam bahasa Melayu Rendah, tidak pernah dilirik Balai Pustaka untuk diterbitkan. Sebaliknya, novelnya yang sudah ditulis dalam Bahasa Melayu Tinggi, Untung Surapati, juga ditolak karena berisi kisah pemberontakan.
Contoh lain adalah ketika STA diterima bekerja di BP, konon ia langsung disukai pimpinan BP, Dr. Drewes, karena bahasa Indonesia STA dianggap kebelanda-belandaan (meskipun bahasa novel-novelnya sangat ke-Minangkabau-an). Ini bagian upaya Belanda untuk mengikis pengaruh gaya bahasa Minangkabau yang dominan dalam bahasa Melayu Tinggi, khususnya melalui buku-buku terbitan BP. Selain menyukai bahasa Melayu beraroma Belanda, pejabat BP juga merekrut redaktur dari etnik non-Minangkabau seperti H.B. Jassin (Gorontalo), L.K. Bohang (Minahasa) dan Achdiat Kartamihardja (Sunda).4 Mereka lupa bahwa STA adalah juga keturunan Minangkabau!
Sampai di sini, para pangreh praja kebudayaan Belanda berhasil mengendalikan, atau setidaknya meminimalisir kehadiran “bacaan liar” (sebutan untuk sastra Melayu-Rendah) dan “benih perlawanan” (istilah saya untuk visi ideologis teks sastra) dengan menekankan pemakaian bahasa Melayu Sekolah sambil terus membina kerjasama dengan pengarang non-populer, tanpa sadar sebagai “bunuh diri politik”. Dalam prosesnya kemudian, Balai Pustaka pun menjadi alamat kritik karena dianggap mapan serta perpanjangan tangan kolonial. Armjin Pane dan Amir Hamzah, termasuk pegawai kesayangan BP, STA, pada tahun 1933 lalu mendirikan institusi alternatif: Pujangga Baru. Wadah ini dianggap lebih membebaskan, baik dalam hal teknis pengelolaan penerbitan, maupun pemakaian gaya bahasa dalam tiap karangan yang diterbitkan.5
Akibat rentetan peristiwa itu, pengguna Bahasa Melayu Rendah menyusut hanya di kalangan Orang Tionghoa atau Peranakan saja, namun mereka masih terus melanjutkan profesi kepengarangan dengan percaya diri sehingga karya mereka kemudian dikenal sebagai Sastra Peranakan Tionghoa. Lebih dari itu, bahasa Melayu Rendah menurut saya sudah menjalankan fungsi oposisinya dengan baik, sekalipun perannya telah menyusut. Ibarat lilin yang membuka jalan terang meski dengan tubuh hancur.
Apa lacur, bahasa Melayu-Rendah yang tinggal sebatas bahasa Peranakan itu pun akhirnya “punah” pasca Peristiwa 65. Salah satu penyebabnya ialah Keputusan Presiden Soeharto tentang pelarangan bahasa/aksara Tionghoa dan pembubaran sekolah Tionghoa (1967). Bukan hanya bahasa etnik yang bisa punah, bahasa lingua-franca juga bisa menyusut untuk kemudian lenyap. Peristiwa 65 tidak hanya menghilangkan tubuh manusia, melainkan juga bahasa manusia, sekaligus menjadi titik nadir perjalanan sastra Indonesia modern (non-populer), dengan dua simpangan pula—tanpa mengabaikan adanya simpangan lain. Yakni sastrawan yang berada di tubuh Lekra dan sastrawan Manifes Kebudayaan—serta sastrawan lain yang netral atau tak berkubu, semisal Rendra atau Ajib Rosidi. Kita tahu dalam banyak kajian, karya sastrawan Lekra kemudian dilarang tampil dan para pelakunya banyak yang menjadi eksil tak bisa pulang.
Bagaimana dengan sastra popular Indonesia pasca-65? Tidak ada yang menyinggung nasibnya sama sekali.6 Betapa pun sepanjang perjalanannya sejak awal abad ke-19, Bahasa Melayu Pasar telah melahirkan banyak karya dengan berbagai ragam gaya dan fenomena. Selain karya-karya pada periode awal Sastra Melayu Rendah (1875-1882), juga ada kisah-kisah per-nyai-an (1900-1924), sastra Peranakan Tionghoa (1920-1966), Roman Pergaulan (1938-1941), Roman Medan atau Roman Picisan (tahun 1930-1950) di samping cerita rakyat (fabel atau legenda) yang ditulis berdasarkan selera masyarakat kota. Kesemuanya itu menjadi antitesis dari bahasa dan sastra Indonesia modern yang mapan dan tertib.
Bahasa dan Sastra tak Berumah
Berbagai macam nama yang disematkan pada masa kelahiran hingga pertumbuhan sastra populer kita, apakah sastra Melayu Rendah, Melayu Pasar atau Lingua Franca, sebenarnya menunjukkan tiadanya “rumah kebangsaan” buat mereka. Tidak ada rujukan tempat dan alamat yang jelas menyertai penyebutan itu. Dalam batas tertentu ini berbanding terbalik dengan sastra non-populer yang beroleh rumah kebangsaan dari Balai Pustaka dan dilegitimasi oleh peristiwa Sumpah Pemuda.
Ada pun sastra berbahasa Melayu Rendah dan sebangsanya, sejak awal tidak memiliki tempat dan alamat pasti. Mungkin satu-satunya nama yang mengikat secara tempat adalah Roman Medan. Ini merujuk pada perkembangan sastra popular (meliputi roman, drama, juga komik) yang marak sekitar tahun 50-an di Kota Medan. Akan tetapi itu pun dalam konteks pinggiran (pheripery). Medan yang menjadi kota besar orang Melayu, sekaligus kota terbesar kedua di Indonesia, dianggap berada di bawah Jakarta dalam hal capaian kebudayaan.
Sebutan Roman Medan itu (kadang disebut juga Roman Picisan) jelas untuk merendahkan, hal yang membuat Hamka dan pegiat seni di Medan mencoba melawan. Hamka yang telah ikut meramaikan sastra periode Roman Pergaulan, mencoba mendudukan perkara ini dari persfektif kebudayaan nasional.7 Nasib Roman Pergaulan sendiri, yang sejatinya menyusupkan cita-cita kemerdekaan,8 justru lenyap dari pembicaraan.
Itu satu potret yang menyiratkan bahwa sastra populer sejak awal masa kelahirannya sampai berkiprah sepanjang hampir dua abad, tidak memperoleh pengakuan, hal yang kemudian menempatkan pandangan noise terhadap kehadirannya. Seolah-olah sastra populer bebas dari pergulatan, yang tidak memiliki akar tradisi dan visi sama sekali. Pemahaman ini berlanjut sampai sekarang, sehingga karya sastra popular dianggap sepenuhnya lahir dari kuasa Dewa Industri yang berideologikan hiburan dan uang. Saya kira, kita perlu menyadari akar historisisme sastra popular (di) Tanah Air untuk melihat keberadaannya yang tidak serta-merta, melainkan berproses sedemikian panjang. Periode ini boleh disebut sebagai masa perumusan dan berkecamuknya identitas kebangsaan.
Dengan menyadari ini, kita tidak akan menafikan munculnya visi-visi fundamental yang menyeluruh dari berbagai produk kebudayaan. Peran sastra populer di masa itu berhasil mengakomodasi bahasa pasar/pergaulan menjadi bahasa tulis (cetak) yang memunculkan bahasa (sastra) sebagai salah satu medium pembentukan (pembayangan bangsa) ala Ben Anderson. Sebab, dunia tulis inilah kemudian melahirkan deretan jurnalis dan memunculkan penerbitan pers yang sangat signifikan dalam penyemaian benih nasionalisme dan pergerakan.
Para wartawan yang turun ke lapangan, selain menulis dalam bentuk laporan atau berita, juga menulis cerita sebagai bentuk persaksian sehingga banyak di antara wartawan yang sekaligus juga sebagai pengarang, jika kata sastrawan dianggap terlalu mentereng. Konsepsi “fakta-fiksi” yang mengemuka dalam sastra mutakhir kita atau “ketika jurnalisme dibungkam sastra harus bicara” ala Seno Gumira Ajidarma sudah ada sejak dulu.
Karena itulah kita masih menemukan karya-karya sastra popular yang memiliki aktualitas hingga hari ini seperti Hikayat Siti Mariah, Hikayat Kadiroen, Student Hijo, Pacar Merah Indonesia, dan seterusnya. Bahkan bisa dikatakan, kesemarakkan kesusasteraan Melayu Rendah maupun sastra Peranakan Tianghoa yang berbarengan dengan tumbuh-kembangnya dunia pers itu, membuat Belanda merasa perlu mengimbanginya dengan menciptakan “institusi” bahasa resmi yang, langsung atau tidak, membuka jalan bagi lahirnya bahasa Indonesia dan sastra non-populer Tanah Air.
Pertanyaannya kemudian: bagaimana signifikansi sastra popular kita sekarang? Masihkah ia memuat ideologi dan visi kebangsaan, seperti pada masa dahulu, atau tak lebih serupa musik dangdut yang berpotensi besar tapi berakhir di panggung dan label industri?
Sedang dengan sastra non-populer pun kita enggan “berbagi”: terlalu banyak kepentingan yang membuatnya mampus dikoyak-koyak sepi—apatah lagi sastra popular yang menyasar pasar cum selera massa. Walahu’alam bissawab.
Catatan:
1 Ini merupakan roman terjemahan karya Pont Jest, pengarang Prancis, yang dikerjakan dalam Bahasa Melayu Rendah oleh H.D. Wiggers, ayah pengarang Melayu Rendah terkenal FDJ Pangemanann . Lihat Jakob Sumardjo, Kesusasteraan Melayu Rendah Masa Awal (2004: 2)
2 Katrin Bandel, “Kesastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia”, Sastra, Nasionalisme, Pascakolonialisme (1013: 29)
3 Jakob Sumardjo, ibid (2004: 1)
4 Subagio Sastrowardoyo, “Pendahuluan” dalam Bunga Rampai Kenangan pada Balai Pustaka (1992: 12)
5 Lihat Keith Foulcher, Pujangga Baru, Kesusasteraan dan Nasionalisme di Indonesia 1933-1942 (1991: 18).. Armjn Pane misalnya mengkritik karya terbitan Balai Pustaka terlalu officieel (kaku, resmi). Untuk kerjasama penerbitan tetap dilakukan dengan perusahaan milik orang Belanda, Kolff & Co, namun dianggap sebagai pihak yang kooperatif.
6 Pada November 2013 Penerbit Marjin Kiri, menerbitkan buku Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film, namun tidak dibicarakan di situ nasib sastra popular, terutama yang berasal dari Peranakan Tionghoa.
7 Lihat Marije Plomp, “Pusat Roman Picisan dan Pusat-Pusat yang Lain; Kehidupan Budaya di Medan 1950-1958” dalam Jennifer Lindsay dan Maya H.T. Liem (penyunting), Ahli Waris Kebudayaan Dunia, Menjadi Indonesia 1950-1965 (2011: 429)
8 Lihat Sudarmoko, Roman Pergaulan (2008: 3)
Bila diamati secara serius dan lapang rasa, sedekah adalah inti amal orang Jawa. Bedanya –seperti disalah-pahami oleh banyak kepala– orang Jawa tidak bersedekah hanya kepada manusia, akan tetapi kepada semua makhluk Gusti Allah. Termasuk binatang dan makhluk gaib dari berbagai jenis. Ini terkait dengan kosmologi Triloka atau pandangan dunia orang Jawa dalam keseluruhannya yang dianut oleh keseluruhan orang-orang Nusantara.
Sejauh ini, kesatuan pandangan dunia di Nusantara biasanya berbasis pada bilangan tiga. Kemudian dalam perkembangannya untuk melihat peristiwa kemanusiaan yang berbeda-beda, bilangan tiga mengalih-rupa menjadi; empat (catur), lima (panca), delapan (hasta), sembilan (sanga). Pandangan dunia triloka ini secara fisik bisa dilihat dari atap rumah atau atap masjid kuno yang bersusun tiga, lima, dan sembilan.
Tri artinya tiga. Loka artinya dunia/tempat/hutan/ruang. Kadangkala istilah triloka ini beralih-rupa dalam istilah lain semisal Tribuana dan Tripurusa. Tiga dunia atau tiga ruang itu adalah; dunia atas, dunia tengah, dunia bawah. Epistemologi triloka dalam narasi tradisi Keislaman di Nusantara ini dibangun di atas sebuah ayat dalam al-Quran, Surat al-Naml: 17:
“Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Burung adalah lambang dari dunia atas. Manusia adalah lambang dunia tengah. Jin adalah lambang dunia bawah. Bagaimana konsepsi ini lahir? Tentu saja dari pengalaman berkebudayaan atau kesadaran tentang realitas serta keadaan geo-kultural-spiritual. Lain kesempatan akan dibicarakan.
Dunia Atas
Dunia atas adalah dunia langit. Menghargai dunia atas adalah dengan memantapkan kehambaan. Bahasa al-Quran-nya hablun minallah. Dalam narasi keilmuan Wali Songa, dunia langit ini disebut dengan istilah; baitul ma’mur. Pemegang perkara ini adalah Sunan Bonang. Ketersambungan dan kemenyambungan dengan dunia atas bagi orang Jawa diungkapkan dengan istilah manembah. Dalam perkakas simbolik sehari-hari, interaksi dengan dunia atas merupa dalam ibadah-ibadah mahdhah dan ibadah sosial-budaya, satu di antaranya: tumpengan. Tumpeng artinya tumuju ing pengeran (menuju kepada Allah Tempat Sandaran). Di atas nasi tumpeng yang berbentuk kerucut itu ada brambang/bawang dan cabai/lombok. Brambang artinya upaya memasuki dunia ambang atau dunia langit. Seperti halnya bawang yang artinya masuk ke dunia awang.
Langit ada tujuh lapis. Memasuki setiap lapisan-lapisan itu dilambangkan dengan lapisan-lapisan kulit bawang yang sangat tipis. Bentuk amal konkret memasuki tiap lapis langit itu adalah; pengakuan dan permohonan ampun atas tujuh; ‘ujub, sum’ah, riya, takabbur, kibr, hasud, dan kikir. Orang yang masih berpakaian tujuh dosa itu –bagi orang Jawa– doa-doanya akan lama sampai ke langit ketujuh. Cabai atau lombok itu sendiri melambangkan perintah untuk lumbu atau bersegera mendekat kepada Allah (wa sari’u ila maghfiratin min rabbikum [bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah….]). Di bawah nasi kerucut itu ada banyak simbol-simbol dalam bentuk sayur-mayur dan lauk-pauk. Kesempatan lain akan dibabarkan.
Sedekah untuk dunia atas berbentuk zikir-zikir. Baik tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hawqalah (la haula wal quwata). Sebagaimana anjuran nabi bahwa setiap sendi manusia yang berjumlah 360 itu ada sedekahnya. Orang yang tidak pernah berzikir, berarti tidak pernah bersedekah untuk dunia langit. Para wali menyumberkan amal sedekah langit ini dari al-Quran, Surat al-Mu’minun ayat 7:
“(Malaikat-malaikat) yang memikul ‘Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (Seraya mengucapkan): “Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala.
Dunia Tengah
Dunia tengah adalah dunia manusia, disebut juga dengan baitul muharram. Sunan Kalijaga adalah wali yang membawahi perkara ini. Dunia manusia, bagi orang Jawa adalah dunia rasa. Amal memahami dunia rasa ini biasa disebut dengan istilah; at-tashaddur (pen-dada-an/merasakan dengan rasa]. Bagian ini disimbolkan dengan bagian dada manusia. Bergaul dengan sesama manusia tidak membutuhkan kalkulasi rasional, melainkan kalkulasi rasa. Bahasa arabnya itu tadi; at-tashaddur.
Sedekah kepada sesama manusia adalah sumbu pembuktian dari kesungguhan bersedekah kepada langit dan dunia bawah (akan diterangkan di bawah). Di atas telah disebutkan bahwa inti dari setiap ibadah atau upacara apa saja dalam Budaya Jawa adalah; doa dan terlebih lagi sedekah. Mau membangun rumah, menaikkan atap, masuk rumah, ada doa dan sedekahnya. Begitu juga mau nikah, mau sunatan/tetakan, tedak siten (bayi yang berumur setahun dan mulai berjalan menginjak tanah), khatam ngaji, dan mau apa saja, bagi orang Jawa semua ada sedekahnya. Hafal lafal doa untuk setiap hajat atau tidak, terkadang tidak terlalu dipusingkan oleh orang Jawa. Yang terpenting adalah; sedekahnya itu.
Karena itu, materi sedekah orang Jawa menempati derajat; sulit untuk diganggu-ganti. Ia terkait dunia rasa. Soalnya setiap hidangan sedekah, ada makna-maknanya yang berhubungan dengan ketulusan niat dan hajat si tukang sedekah. Nasi kuning, kacang panjang, ayam ingkung, telur, dan entah apa lagi namanya, semuanya adalah lambang dari zikir-doa-hajat-dan terlebih lagi upaya orang Jawa untuk; karyenak tyasing sesami (mengenakkan hati/tyas sesama manusia) atau amal penyelerasan diri dengan keseluruhan alam semesta (rahmatan lil ‘alamin).
Untuk diri sendiri, mengenakkan hati ini dilakukan dengan terlebih dahulu menghalau ketakutan akan kehabisan harta karena bersedekah. Karena itu, materi sedekah orang Jawa itu pasti yang mahal-mahal. Mulai dari ayam, kambing, sampai kerbau. Apa maksud dari itu semua? Kata guru saya:
“…Kalau mau bergaul dan mengenakkan hati sesama itu jangan tanggung-tanggung…. Kalau mau bersedekah itu jangan yang murah-murah…yang mahal sekalian..!!! Kowe serius po ra nyedhaki Gustimu lan anggawe enak-ing ati sedulurmu [kamu serius apa gak mendekati Tuhanmu dan mengenakkan hati saudaramu?]. Sedekah kok cari yang paling hemat…!!!”
Pada kasus-kasus tertentu, penitik-beratan sedekah pada derajat dunia sosial ini seolah menempati tingkat yang lebih penting dari pada sedekah untuk dunia atas. Bahasa kasarnya; terkadang di Jawa ada banyak orang yang baik kepada sesama dan tetangga tapi amat jarang terlihat “di masjid”. Berbaik sangka merupakan kata kunci di sini.
Dunia Bawah
Dunia bawah adalah baitul muqaddas/maqdis. Wilayah ini diampu oleh Sunan Giri [versi sebelumnya, ada yang menyebutkan diampu oleh Sunan Kudus]. Dunia bawah merupakan dunia makhluk-makhluk gaib dan para saudara dari bangsa binatang. Secara jasadiah, ia disimbolkan dengan kelamin manusia. Mengurusi perkara dunia bawah ini merupakan bagian yang sangat penting bagi orang Jawa. Orang Jawa harus akrab dengan dunia gaib, dunia mistik. Soalnya itu juga bagian dari kelengkapan kemanusiaan orang Jawa. Jin dan bangsa-bangsa binatang bukan musuh. Bila mereka berada di rumah seseorang, akan diajak untuk bermusyawarah; silahkan tinggal di sini tapi jangan mengganggu, saling menghormati. Sebagaimana halnya manusia; bangsa jin dan hewan juga tidak suka kekerasan “doa”.
Bagi orang Jawa, setelah bersedekah dan mengenakkan hati sesama manusia, maka sedekah juga diniatkan untuk para saudara sesama makhluk Allah dari bangsa gaib dan bangsa binatang. Untuk mereka, materi sedekahnya tidak seperti materi sedekah kepada manusia. Melainkan dalam bentuk tulang-belulang, sisa-sisa makanan/minuman yang tidak termakan ketika acara sedekah dilangsungkan. Terkadang juga dalam bentuk pembakaran kemenyan/dupa dan bunga-bunga yang sudah didoakan.
Apakah sedekah untuk mereka itu dilakukan supaya bangsa jin dan hewan-hewan itu melindungi manusia? Dengan kata lain; apakah sedekah untuk mereka itu dikeluarkan dengan niat meminta perlindungan kepada mereka? Tidak. Tentu saja tidak. Anggapan demikian adalah sangkaan yang ditudingkan oleh banyak kalangan, dan jelas keliru di sini. Bersedekah untuk bangsa dari dunia bawah diamalkan semata-mata karena mereka juga dianggap sebagai sesama makhluk Allah yang harus merasakan nikmat dan berkahnya menyantap hidangan yang terlebih dahulu telah didoakan dengan zikir, salawat, dan pepuji pada Illahi.
Menjadi wajar bila sampai hari ini, kita masih berjumpa dengan para sesepuh yang sebelum membangun rumah, mereka terlebih dahulu menanam tulang kepala kerbau di bagian tengah rumah. Lalu tulang- belulang lainnya ditanam di setiap sudut rumah dengan terlebih dahulu dagingnya dimasak dan dibagikan kepada para tetangga. Jika tidak kerbau, biasanya kambing, ayam, atau bahkan ikan. Terserah apa materinya. Intinya, mereka juga dianggap harus merasakan nikmatnya makan-minum yang terlebih dahulu telah dioles dengan doa-doa dan zikir-zikir. Kanjeng nabi sudah bilang bahwa makanan bangsa jin adalah tulang-belulang, bunga-bunga, dan semacamnya. Selain disantap oleh bangsa jin, nanti seluruh sedekah itu akan disantap juga oleh makhluk Allah lainnya seperti semut, cacing, dan semacamnya.
Dalam Shahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata; bahwasanya ia pernah membawakan pada Kanjeng Nabi SAW sebuah wadah berisi air wudhu dan hajat beliau. Ketika ia membawanya, Kanjeng Nabi saw bertanya; “Siapa ini?”. “Saya, Abu Hurairah”, jawabnya. Kanjeng Nabi saw pun berkata; “Carilah beberapa buah batu untuk kugunakan bersuci. Dan jangan bawakan padaku tulang dan kotoran.” Abu Hurairah berkata; kemudian aku mendatanginya dengan membawa beberapa buah batu dengan ujung bajuku. Hingga aku meletakkannya di samping beliau dan aku berlalu pergi. Ketika beliau selesai buang hajat, aku pun berjalan menghampiri beliau dan bertanya; “Ada apa dengan tulang dan kotoran?”.
Kanjeng Nabi saw menjawab; “Tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nashibin dan mereka adalah sebaik-baiknya jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan” (HR. Bukhari no. 3860)
Tentang Dupa dan Saudaranya
Dupa, kemenyan, dan bunga-bunga, juga tidak hanya disajikan untuk para saudara-saudara sesama makhluk dari bangsa gaib. Ia juga mengandung makna simbolik yang khas. Jangan lupa –bahwa bagi orang Jawa– makna dari segala hal itu, ada tujuh lapis. Mulai dari yang paling harfiah sampai yang paling lungid (makna tingkat langit). Upacara rasulan yang melibatkan pembuatan nasi tumpeng, itu tidak hanya bermakna harfiah, namun juga makna tingkat langit yang terkait dengan hubungan rohani antara manusia dan pencipta. Bahasan ini di lain waktu akan dibabarkan.
Banyak orang salah memahami dupa dan kemenyan yang dibakar dalam upacara tertentu. Perlu dipahami dulu bahwa dupa itu merupakan benda simbolis yang dipergunakan atau dilibatkan dalam sebuah upacara tertentu sebagai ungkapan maksud-maksud mulia yang berdasar. Artinya, dupa dibakar bukan sebagai benda asal-asal bakar. Ia punya makna-makna tersembunyi yang bila dikaji akan tampak sangat rasional. Harap diperhatikan di sini, bahwa semua benda-benda tradisi, selalu merupakan simbol. Benda-benda itu –misalnya dupa– adalah sesuatu yang dipakai untuk mengatakan sesuatu yang lain. Dalam penelusuran saya, setidaknya ada beberapa makna dupa, kemenyan, dan bunga-bunga yang dibakar dalam berbagai upacara.
Pertama, dupa sebagai pernyataan bahwa upacara tersebut bersumber dari hati yang wangi. Kewangian hati itu diungkapkan dengan dupa, kemenyan, dan bunga-bunga yang memang juga wangi. Maksud “hati yang wangi” itu adalah hati yang tulus, ikhlas, bersih, tidak berharap apa-apa selain ridha Allah. Kedua, sebagai pernyataan bahwa para hadirin yang datang pada ritual tersebut merupakan orang-orang baik, yang hatinya wangi, persis wanginya dupa, kemenyan, dan bunga-bunga. Ketiga, upacara tersebut merupakan rangkaian doa. Doa pasti wangi, kecuali doa yang dipanjatkan untuk keburukan. Kewangian doa itu diungkapkan atau disimbolkan dengan dupa. Jadi, kalau di sana ada dupa dan kemenyan dibakar, serta bunga-bunga disajikan, itu artinya ada doa yang akan atau sedang dipanjatkan itu semata-mata untuk memohon kebaikan.
Keempat, dupa sebagai penegasan permintaan agar doa dikabulkan. Yang disasar pada bagian ini adalah kebul-nya si dupa atau asapnya itu. Kebul dimaksudkan di sini merupakan simbol dari harapan agar doa dikabulkan, hal ini digambarkan dengan kebul atau asap yang naik ke langit. Kalau sudah naik ke langit, ke arah mana lagi ia ditujukan kalau bukan kepada Tuhan? Begitulah doa. Ia terus melangit bersama rapalan doa yang dipermantra. Untuk maksud ini, di zaman ini terkadang dupa sebagai sebuah pralambang harapan keterkabulan doa diganti dalam bentuk rokok. Intinya tetap sama, yaitu ada asap yang dikebulkan. Bunga juga tetap dipakai.
Tentu saja ada makna-makna mulia lainnya di balik semua ini. Termasuk upacara sedekah laut dan sedekah bumi dan semisalnya. Semua makna upacara itu harus dibaca dalam tujuh tingkat makna atau saptanama. Intinya bahwa semua maksud di balik upacara itu ada hal-ihwal yang tidak sesepele tuduhan kemusyrikan. Jadi, jangan sembarangan menuduh yang bukan-bukan dulu. Lebih baik dikaji, dipelajari, dan ditabayyunkan.
Sunnah Nabi
Upacara keagamaan-kebudayaan yang dilakukan oleh orang Jawa hari ini boleh saja dituduh sebagai warisan peradaban pra-Islam. Ada pula yang menudingnya sebagai warisan kebudayaan Jahiliyah. Meski tuduhan itu bermasalah, akan tetapi harus diingat, bahwa pada masa Wali Songa, semua upacara warisan zaman sebelumnya itu telah mengalami Islamisasi seperti halnya tradisi memotong kambing orang Arab pra-Islam untuk menyambut kelahiran bayi, bahkan mereka tidak hanya memotong hewan. Nantinya darah hewan tesebut dialirkan ke kepala bayi yang baru dilahirkan. Lalu dagingnya dipersembahkan untuk berhala-berhala. Seperti halnya juga kumpul-kumpul pada hari Jumat yang jamak terjadi di kalangan bangsa Arab.
Ketika Islam datang, Kanjeng Nabi mengislamisasi kebudayaan tersebut. Upacaranya tetap dilangsungkan. Hewan Qurban untuk kelahiran anak tetap dipotong, akan tetapi, darahnya tidak dialirkan ke kepala bayi, melainkan dialirkan ke tanah. Lalu rambut bayi dicukur, dan daging hewannya dibagikan untuk dimakan bersama. Tradisi kumpul-kumpul hari Jumat juga tetap dijalankan, namun, diganti dengan ibadah salat Jumat di masjid. Dari sini, tampak bahwa merangkul kebudayaan lokal merupakan sunnah nabi. Tentu dengan penyesuaian-penyesuaian kreatif yang tiada henti berdasarkan kosmologi agama dan kosmologi masyarakat setempat.
Untuk Kanjeng Nabi SAW dan ahli bait-nya serta para wali di tanah Nusantara, Al-Fatihah.
Wallahu a’lam.
* Penulis adalah seorang muslim Jawa