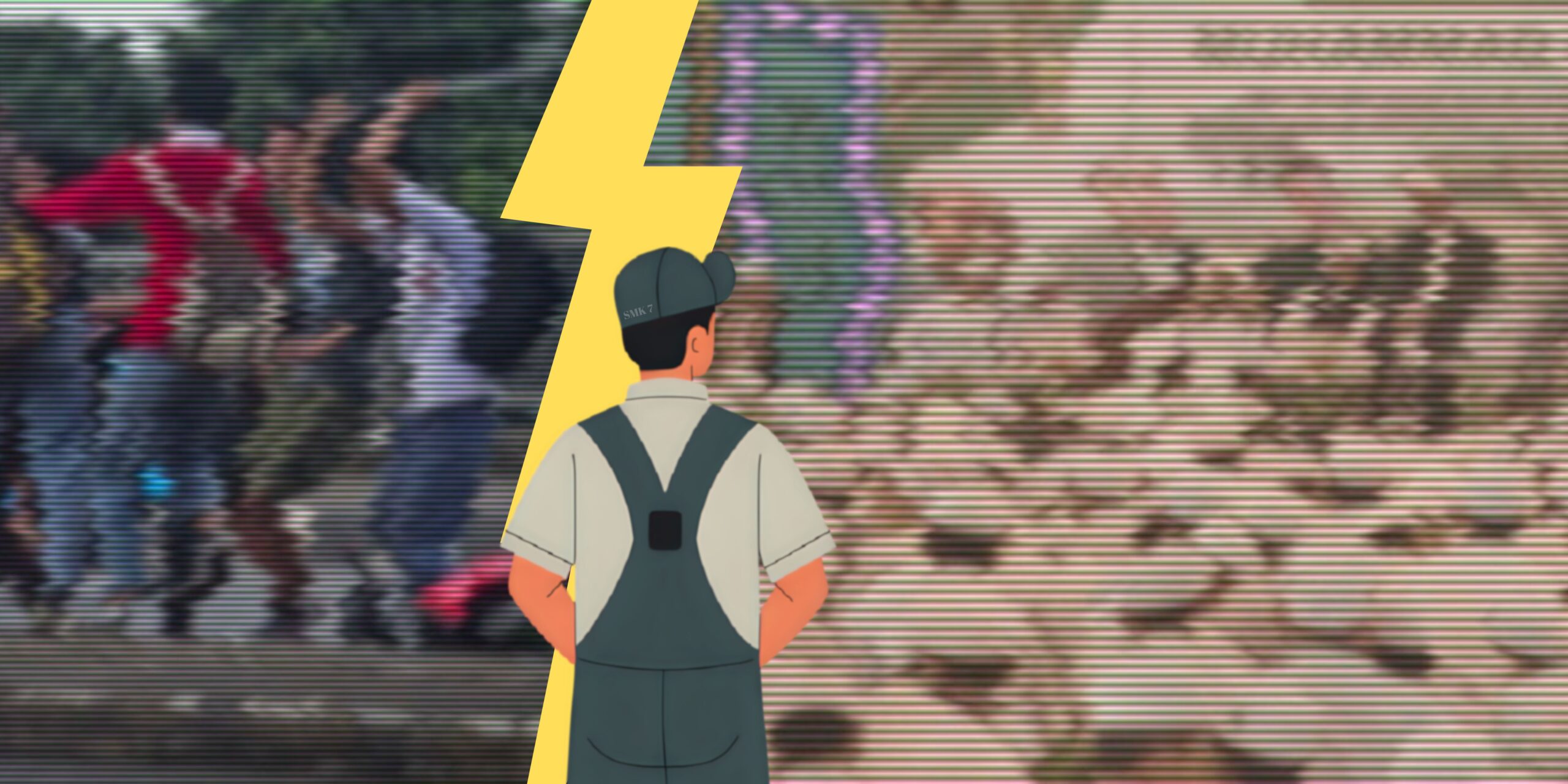Mesin, Agama, dan Maulid
Tulisan ini bukan tulisan ilmiah, melainkan sebuah catatan pengalaman. Bicara pengalaman, tentu sangat subjektif. Sudut pandangnya pun berangkat dari diri seorang yang mengalaminya. Dalam hidup,...
Tulisan ini bukan tulisan ilmiah, melainkan sebuah catatan pengalaman. Bicara pengalaman, tentu sangat subjektif. Sudut pandangnya pun berangkat dari diri seorang yang mengalaminya. Dalam hidup, setiap orang sangat pasti memiliki pengalaman, entah itu pengalaman yang bahagia atau tidak, sehingga pada satu keadaan terkadang pengalaman itu disebut sebagai titik balik.
Tulisan ini sengaja saya beri judul, “Mesin, Agama, dan Maulid”, bukan tanpa alasan, sebab melalui tiga kata itulah pengalaman hidup bermula. Pengalaman ini bukan tentang kesuksesan, seperti umumnya yang menceritakan hidup dari susah kemudian menjadi sukses dan kaya raya. Ini soal cara bagaimana memaknai dan mensyukuri hidup.
Perjalanan Sebagai Pelajar SMK
Sebagai anak semata wayang, orang tua di seluruh jagat sebagaimana umumnya pasti menginginkan anaknya bertumbuh kembang dengan baik. Apakah di masa depan anak itu sukses (kaya dan berpangkat) atau tidak, itu urusan Gusti Allah Swt.
Sebagai anak yang lahir di kota metropolitan seperti Jakarta. Harapan orang tua untuk anaknya menjadi baik, nampaknya “hampir” pernah tidak terpenuhi. Pasalnya sejak duduk di bangku SMP, saya sudah terhitung bandel. Bandel yang dimaksud adalah malas belajar. Maunya hanya bermain-main saja.
Berpikiran hanya untuk bermain-main ternyata berdampak pada sekolah saya. Tidak seperti teman-teman yang mampu masuk SMA terbaik di Jakarta, saya justru masuk SMK (Sekolah Menegah Kejuruan) pada tahun 2005. Mending jika SMK-nya negeri dan favorit. SMK saya hanya swasta: SMK Satya Bhakti I, Jakarta Timur, jurusan teknik mesin atau otomotif. Alih-alih berubah, masuk SMK justru membuat saya semakin liar bandelnya.
Salah satu kebandelan yang pokok—bukan membenarkan, namun sudah menjadi “tradisi”—adalah tawuran di sekolah. Sedangkan di rumah, alih-alih belajar, saya malah main modif-modif motor. Jika membicarakan tawuran pelajar di Jakarta, tidak bisa tidak, SMK berada di urutan pertama yang mesti disebut. Nama-nama SMK seperti, Boedoet, Bonser, Chaptoen, Bonzer, dan Kapal menunjukkan bahwa SMK tersebut menjadi pemain krusial yang membikin tawuran pelajar di Jakarta tak ubahnya budaya yang melekat pada pola pikir para pelajar.
Sebagai pelajar SMK, beberapa kali saya juga turut menjadi bagian budaya tawuran tersebut, meski tidak pernah mencelakakan lawan, namun tawuran untuk saat ini tidak pernah dibenarkan. “Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga”, ungkapan itu mungkin menggambarkan. Sepandai-pandainya saya menyembunyikan kata “nggak pernah tawuran” di hadapan orang tua, tetap saja ketahuan. Harapan orang tua untuk anaknya menjadi baik sempat saya lukai. Orang tua saya marah besar. Bahkan sempat dalam marahnya “hampir” membuat saya tidak diakui sebagai anak.
“Hampir” tidak diakui anak ternyata membekas di hati saya. Sedih, frustasi, dan kecewa meliputi hati saya. Percuma keren di luar, tapi jika tidak mendapatkan ridho orang tua, apalah artinya hidup. Sebab jamak diketahui bahwa ridho Allah adalah ridho orang tua.
Pada saat-saat sedih dan frustasi itu, tiba-tiba pada tahun 2007, salah seorang kawan mengajak saya untuk ikut pengajian. Awalnya saya menolak, sebab bagaimana mungkin orang yang masih senang dengan pencarian identitas melalui tawuran dan main motor, tiba-tiba diajak ngaji. Namun, karena terus memaksa akhirnya saya menurutinya. Ada kata-katanya yang masih saya ingat sampai saat ini,
“Mas, ayo ikut ngaji enak, cuma duduk saja, nanti habis ngaji ada makan nasi kebuli. Habis itu terserah loe mau ikut lagi apa nggak”.
Mengikuti Majelis Para Habaib
Dengan menaiki kereta listrik, akhirnya saya dan teman saya pergi ke pengajian tersebut. Pengajiannya terletak di daerah Citayam, Bogor, Jawa Barat. Sebagai pelajar yang bukan berlatar belakang pondok pesantren, saya tidak memiliki pengetahuan soal ilmu agama yang luas. Sehingga saya tidak pernah tahu pengajian apa yang akan didatangi.
Sesampainya di sana saya menemui banyak sekali orang yang memakai peci putih dan sarung. Sebagai yang pertama kali hadir, sepanjang pengajian, saya hanya duduk, membaca maulid, sholawat, mendengar ceramah, makan nasi kebuli, dan pulang. Entah apa yang saya alami, namun kegiatan yang hanya baca sholawat, dengerin ceramah, dan makan membuat hati saya jadi senang. Awalnya saya tidak tahu soal habib-habib-an. Saat itu saya baru tahu bahwa ternyata majelis pengajian itu bernama al-Busyro pimpinan Sayyidil Walid al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qodir Assegaf, Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Setelah acara selesai, sejak saat itu saya berkata kepada teman saya, dan saya masih ingat betul kata-kata saya sendiri, “Ternyata enak ya ngaji begini, besok kalau ada acara seperti ini, hadir lagi yuk”. Bahkan bukan saja saya semakin senang dengan pengajian tersebut, di antara kesenangan lainnya adalah saya semakin sering mengikuti pengajian sholawat para habaib dan mulai mengikuti orang-orang dengan memakai peci putih, sarungan. Dan anugerah terbesar yang saya alami setelah menghadiri pengajian itu adalah perubahan orientasi pendidikan saya.

Di sekolah saya mulai berubah, tidak lagi mengikuti tawuran—Meski harus saya akui bahwa saya masih malas belajar. Namun, pengajian itu membawa dampak penting atau titik balik dalam hidup, yakni saya semakin ingin belajar mendalami agama. Seakan-akan itu merupakan kenyataan yang memang dan harus disyukuri, keinginan saya untuk belajar agama akhirnya dipenuhi oleh Allah Swt melalui jalur pendidikan tinggi UIN Syarif Hidyatullah Jakarta jurusan Perbandingan Agama tahun 2009.
Banyak orang, dan bahkan orang tua saya sendiri kaget, bagaimana mungkin dari SMK Teknik mesin bisa ke jurusan Perbandingan Agama? Sampai-sampai penguji ujian masuk UIN Jakarta, Pak Surya yang di kemudian hari menjadi dosen Bahasa Arab saya mengatakan, “kamu dari SMK ke jurusan ini, kayak loncat tanaman”. Jawaban paling logis atas perubahan itu mungkin bisa diringkas bernama “hidayah”.
Maulid dan Sebuah Catatan
Perubahan dimanapun bukan sesuatu ujug-ujug terjadi, pasti ada awal dan sebab. Jauh setelah mengikuti pengajian majelis para habaib itu, dan alhamdulillah setelah selesai kuliah hingga S2 di Universitas Gadjah Mada, saya semakin sadar. Dan, sekali lagi, hidup harus patut disyukuri (apapun kondisinya). Ada satu penjelasan yang saya temukan di Instagram milik Pusat Studi Quran tertanggal 27 Mei 2025. Penjelasan itu dimulai dengan pertanyaan, “rasanya semakin jauh dari agama, kapan yah aku dapet hidayah?”
Kemudian di slide selanjutnya dijawab, “kadang hidayah Allah Swt datang dalam bentuk sederhana, salah satunya lewat ada teman tiba-tiba ngajak pergi kajian”.
Ajakan sederhana untuk ikut majelis taklim bukanlah perkara sepele. Pasalnya banyak dari teman-teman saya yang SMK itu mengalami perubahan hidup. Atau sebagian orang di dunia ini mengalami hidup yang cukup ekstrem. Dalam konteks SMK, momentum perubahan hidup terjadi ketika tawuran, lalu ditangkap polisi. Atau ketika tawuran kena sabetan benda tajam kemudian cacat. Atau ketika main motor ikut kebut-kebutan di jalan kemudian mati. Teman saya tidak mengajak saya berubah lewat hal-hal yang berat, seperti suruh baca filsafat, misalnya. Bagaimana mau baca filsafat wong saat itu saya masih kelas 3 SMK dan belum memiliki media sosial seperti saat ini.
Terlepas dari personal nasab atau anda membenci habaib, namun, peran majelis taklim bagi kehidupan saya sangat penting. Betul sebagaimana dikatakan oleh salah satu tokoh kiai besar negeri ini yang mengatakan, “dalam konteks perumusan hukum Islam di Indonesia atau Bahtsul Masail, habaib tidak ada”. Namun, kehadiran habaib jelas terasa dalam hidup saya. Sebagai contoh, tidak mungkin anak SMK seperti saya yang tidak memiliki pengetahuan agama tiba-tiba disuruh mikir. Wong, belajar saja males. Nah, untuk merubah itu tentu caranya juga harus sederhana, yakni duduk, maulidan, sholawatan, dengerin ceramah, dan makan. Dalam konteks saat itu, yang ada di pikiran saya hanya “alhamdulillah bisa ikut maulidan.”
Cara-cara sederhana ini saya kira juga dialami oleh beberapa orang terkenal di negeri ini. Sebagai contoh, adalah gitaris Sheila on 7 Sakti Ari Seno atau Salman al-Jugjawy dan Gito Rollies. Dalam kasus Sakti, menurut wawancara ia berubah hanya karena melihat majalah berjudul kematian saat dirinya ingin naik pesawat. Ada perasaan takut saat dirinya ingin naik pesawat, takut apakah pesawat ini akan baik-baik saja atau tidak. Dalam kasus Gito Rollies, ia berubah dan mendapat hidayah hanya karena melihat orang berbondong-bondong Jumat’an.
Anda mungkin boleh membenci habaib atau kehabib-habiban (itu pilihan, tapi juga tidak berlebih-lebihan). Karena mungkin ada habaib yang dawir (tukang minta-minta) atau ceramah dan perilakunya yang tidak mencerminkan akhlak Nabi Saw. Namun, kehadiran mereka dan masih banyak lagi yang baik-baik dan santun yang hanya menyelenggarakan maulidan, sholawatan, dan makan-makan tidak bisa dipungkiri keberadaannya.
Oleh karena itu, sekali lagi, pengalaman selalu bersifat subjektif. Tidak bisa dihakimi hanya karena berbeda tempat dan waktu. Mungkin hari ini, seiring perkembangan waktu dan media sosial, banyak orang yang berubah dan mendapat hidayah melalui postingan online. Namun, saat itu tahun 2007, saat media sosial belum seriuh sekarang, ajakan seorang sahabat yang saya alami adalah cara Tuhan paling sederhana memperkenalkan sesuatu yang baik. Sebab mungkin kembali pada jawaban Pusat Studi Quran bahwa hidayah Allah Swt memang datang lewat cara-cara yang sederhana.