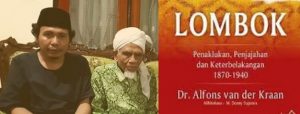Tulisan Marcel Bonneff ini versi aslinya berbahasa Prancis: “Ki Ageng Suryomentaram, Prince et Philosophe Javanais,” dimuat pertama kali di Archipel 16 (1978), hal. 175–203. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Susan Crossley, “Ki Ageng Suryomentaraman, Javanese Prince and Philoshoper,” dimuat di Indonesia 57 (April 1994).

Kawruh Jiwa" width="150" height="150" /> Afthonul Afif, Peneliti Kawruh Jiwa
Versi bahasa Indonesia tulisan ini diterjemahkan oleh Afthonul Afif dari versi Inggrisnya atas izin Marcel Bonneff. Tulisan ini juga menjadi apendiks dalam buku Matahari dari Mataram, karya Afthonul Afif dan kawan-kawan. Afthonul Afif adalah seorang peneliti Kawruh Jiwa Ki Ageng Suryomentaram. Dua bukunya tentang Ki Ageng Suryomentaram yaitu: Matahari dari Mataram; Menyelami Spiritualitas Jawa Rasional Ki Ageng Suryomentaram (2012) dan Ilmu Bahagia menurut Ki Ageng Suryomentaram (2012). Ia juga aktif menulis tema psikologi kebahagiaan di berbagai media massa.
“Sang Pemimpin” dan Para Pengikutnya
![]() idorong oleh perhatian yang nyata terhadap “pengajaran”, KAS merefleksikan secara panjang lebar perihal pendekatan yang perlu dipakai oleh seseorang yang mempelajari “Ilmu Jiwa”.[1] Yang pertama, dia harus menyadari bahwa ilmu ini sangat sederhana dalam ajaran-ajarannya, namun (sekaligus) sangat sulit ketika akan dipraktikkan.
idorong oleh perhatian yang nyata terhadap “pengajaran”, KAS merefleksikan secara panjang lebar perihal pendekatan yang perlu dipakai oleh seseorang yang mempelajari “Ilmu Jiwa”.[1] Yang pertama, dia harus menyadari bahwa ilmu ini sangat sederhana dalam ajaran-ajarannya, namun (sekaligus) sangat sulit ketika akan dipraktikkan.
Sederhana dalam hal cara dia menggambarkan pikirannya. Hal tersebut diujarkan dalam perumpamaan, di mana setiap gagasan ditampilkan melalui peristiwa sehari-hari, meski sering kali mengandung risiko, karena hal itu di hadapan kita nampak sebagai sesuatu yang remeh-temeh. “Hal pertama kali yang mesti seseorang lakukan untuk memastikan keberlanjutan keturunannya adalah memiliki mertua, istri, lalu anak, kondisi yang tidak berlaku bagi sapi-sapi, misalnya, karena mereka tak perlu memiliki mertua dan istri.”[2] Menciptakan secara konstan perumpamaan-perumpamaan seperti itu sesuai dengan gagasan bahwa pengalaman seseorang merupakan sumber utama bagi kebangkitan kesadarannya.
Elemen-elemen dari setiap pernyataan yang berbeda secara hati-hati didefinisikan dan dianalisis satu per satu. Alasan-alasan disampaikan melalui serangkaian antitesis, dirancang secara dialektis, untuk menggugah para pendengar dan pembacanya tentang citra harmoni dalam setiap argumen yang dia sampaikan.
Sangat sedikit kata-kata dalam bahasa asing, bahkan Indonesia sendiri, yang bisa ditemukan. Meski KAS menemukan sendiri istilah-istilah yang digunakannya (kramadangsa, ukuran kaping sakawan, raos sewenang-wenang, dan lain-lain), namun secara umum dia sebenarnya menggunakan kosa-kata yang sederhana untuk menghindari perangkat-perangkat literer yang baku. Jika kalimat yang dia gunakan kemudian tidak selamanya baku, hal ini tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa versi asli ceramah-ceramahnya bersumber dari bahasa lisan, sama halnya dengan kegemarannya menggunakan ungkapan-ungkapan yang paradoks.
Adalah sebuah kesalahan ketika ajaran Kawruh Jiwa dianggap sebagai pendekatan yang bersifat doktriner atau sebuah “Mantra Suci”. Yang lebih penting di sini adalah ketulusan maksud dari para pembelajar, begitu juga bagi pengajarnya. KAS tidak ingin ajarannya mengebiri semangat atau menimbulkan fanatisme pada para pengikutnya; dia ingin nasihat-nasihatnya tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan kemampuan mental mereka. Sementara pengetahuan tentang sistem filosofi atau keyakinan dalam ajaran kebatinan justru menghambatnya.
Pendek kata, teknik-teknik gaya bahasanya menarik perhatian penulis. Hal itu merefleksikan bagaimana sikap pengajarannya yang menunjukkan sebuah penekanan untuk merasionalkan hal-hal, sesuatu yang sangat berbeda dengan “bualan” yang dapat ditemukan di berbagai ajaran kebatinan; hal itu juga menegaskan rasa hormat Ki Ageng terhadap para pengikutnya. Hal-hal tersebut Ki Ageng sampaikan dalam bahasa krama, sambil tetap berhati-hati untuk menghindari penggunaan istilah-istilah yang berlebihan (krama inggil) yang berkonotasi feodalistik. Sebaliknya, dia menggunakan bahasa ngoko (bahasa Jawa yang dipakai sehari-hari oleh orang biasa) untuk percakapan-percakapan pendek atau komentar-komentar mendadak dalam ceramah-ceramahnya semata-mata sebagai tanda dari sebuah keakraban, sehingga menciptakan suasana santai ketika dia sedang berbicara dalam pertemuan-pertemuan tersebut.
Bagi orang Jawa, nada bicara (dalam percakapan) dan kata-kata yang digunakan sangat penting maknanya, karena hal itu berdampak secara emosional. Dalam kata pengantar edisi bahasa Indonesia, Ki Oto Suastika memberikan sejumlah peringatan: “Kesulitan-kesulitan yang dijumpai dalam penerjemahan karya ini bersumber dari banyaknya istilah-istilah pengungkapan dan bentuk-bentuk ujaran dalam bahasa Jawa yang menggunakan konsep rasa.”[3] Begitu juga dengan Ki Sangoebrangta (Ki Pronowidigdo), salah seorang yang pertama kali menyebarkan ajaran-ajaran Ki Ageng (atau nasihat-nasihatnya, yaitu wejangan), menyebutkan dalam sebuah pengantar untuk pembaca di majalah Poesara, bahwa dia tetap mempertahankan penggunaan bahasa Jawa supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap wejangan-wejangan KAS “seperti yang berhubungan dengan pemahaman tentang konsep kepekaan (rasa) dan perangai”, meski dia akhirnya juga memberikan pemakluman terhadap penggunaan huruf latin ketimbang huruf Jawa.[4]
Memahami Ajaran KAS
Bagi para pengikut Kawruh Jiwa (pelajar), ajaran-ajaran KAS, baik yang terucap maupun tertulis, baru merupakan langkah pertama. Memahami ajaran-ajaran tersebut dalam kaitannya dengan situasi kehidupan nyata (setelah mampu menguasai prinsip-prinsip umumnya dan memiliki pemahaman yang mencukupi untuk mempraktikkannya selama proses belajar) itu lebih penting. Seorang pelajar harus mampu “memahami caranya memahami” (ngertos carane ngertos) agar mendapatkan inti pemahaman tentang hal-hal (nandhes), yaitu mencapai pemahaman yang kokoh (kekah pangertosanipun). Mungkin agak bermasalah jika anjuran tersebut dibakukan dalam sistem pengajaran, sebab anjuran-anjuran tersebut lebih sebagai asupan bagi pikiran. Apa yang kemudian penting bagi para pengikut Kawruh Jiwa adalah mereka perlu memperdebatkan gagasan-gagasan yang terkandung dalam ajaran-ajaran tersebut. Pelajar yang lebih berpengalaman akan membimbing para pelajar baru dalam sebuah “pertemuan” (bahkan meski hanya dilakukan oleh dua orang) yang dikenal dengan Junggring Salaka.[5] Pada hakikatnya periode pembelajaran tersebut bersifat seumur hidup; setiap kali menjumpai ketidakberuntungan (raos cilaka), kondisi ini perlu dilihat melalui sudut pandang ajaran, yang kemudian akan memungkinkan perasaan seseorang tentang dirinya menjadi lebih jernih. Namun demikian, adalah sebuah kesalahan ketika ajaran Kawruh Jiwa dianggap sebagai pendekatan yang bersifat doktriner atau sebuah “Mantra Suci”. Yang lebih penting di sini adalah ketulusan maksud dari para pembelajar, begitu juga bagi pengajarnya. KAS tidak ingin ajarannya mengebiri semangat atau menimbulkan fanatisme pada para pengikutnya; dia ingin nasihat-nasihatnya tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan kemampuan mental mereka. Sementara pengetahuan tentang sistem filosofi atau keyakinan dalam ajaran kebatinan justru menghambatnya.
Ada dua jenis pertemuan di antara para pelajar: pasinaon dan jawah kawruh. Yang pertama adalah kesanggupan untuk belajar (sinau) dan mengembangkan teknik-teknik analisis diri. Ketika mereka telah sampai pada tahap menguasai prinsip-prinsip dan istilah-istilah dalam ajaran, para pelajar kemudian dapat melanjutkan pada jenis pertemuan yang kedua, yaitu “kehujanan ilmu” (papanggihan jawah kawruh). Tahapan ini berupa upaya-upaya memberikan bantuan kepada mereka yang menderita akibat gangguan psikologis tertentu dengan secara teliti menganalisis penyebab-penyebab masalah mereka itu (ngudari reribed). Untuk jenis psikoterapi ini (mungkin bisa diistilahkan demikian), sangat penting untuk menguasai dimensi keempat (ukuran kaping sekawan), yaitu kemampuan “merasakan apa yang orang lain rasakan” (feel what others are feeling).
Ki Ageng menciptakan sendiri sejumlah tembang (uran-uran) dalam bentuk macapat dan beberapa panembrama (tembang-tembang sambutan) yang dirancang untuk membantu para pelajar mengingat bagian-bagian terpenting dari nasihat-nasihatnya.
Secara umum, terlepas dari pertemuan-pertemuan yang memiliki konsekuensi-konsekuensi praktis dan langsung tersebut, seorang pelajar harus mampu, melalui contoh yang dia tentukan sendiri dan dengan kemampuan yang dia miliki sendiri, memberikan pengaruh yang bermanfaat bagi lingkungan sosialnya.
Akhirnya, untuk melihat peran dari ajaran-ajaran Kawruh Jiwa, perlu juga dilihat suplemen-suplemen yang terkandung di dalamnya, yaitu syair dan drama. Ki Ageng menciptakan sendiri sejumlah tembang (uran-uran) dalam bentuk macapat dan beberapa panembrama (tembang-tembang sambutan) yang dirancang untuk membantu para pelajar mengingat bagian-bagian terpenting dari nasihat-nasihatnya.[6] Tembang-tembang itu dibaca dan disenandungkan secara bersama-sama dalam pertemuan. Sementara untuk drama, dalam sebuah pentas alegoris—Raos Mlenet (perasaan tertekan)—KAS mengulang kembali gagasan terpentingnya tentang pernikahan: bahwa seseorang harus bebas memilih siapa yang bakal dia nikahi. Diceritakan dalam sebuah keluarga terdapat tiga tokoh protagonis: ayah, ibu, dan anak perempuan, di mana masing-masing pihak telah memiliki pilihan perihal calon suami untuk si anak perempuan. Hal itu kemudian melahirkan konflik di antara mereka. Si anak mengancam akan bunuh diri jika orang tuanya tetap memaksakan pilihan mereka (perlu dicatat bahwa dorongan untuk bunuh diri adalah sebuah gangguan psikologis, seperti yang disebutkan dalam karya-karya KAS). Konflik tersebut akhirnya bisa terselesaikan berkat bantuan salah seorang Pelajar Kawruh Jiwa yang membimbing mereka untuk memahami bahwa konflik tersebut terjadi semata-mata karena masing-masing pihak kurang memiliki pemahaman terhadap motivasi mereka dan memiliki egoisme di antara mereka.
Telah disebutkan sebelumnya bahwa KAS menemukan sosok pendukung setia bagi gagasan-gagasannya pada diri Prawirowiworo. Ki Prono, mantan anggota Perkumpulan Selasa Kliwon, juga bisa disebut sebagai salah seorang yang pertama-tama memberikan dukungannya. Bagi Ki Haditomo, salah seorang pengikut KAS, dua orang itu bersama dengan Ki Ageng, merupakan semacam tritunggal, di mana Ki Prono mewakili pikiran (cipta), Ki Prawiro mewakili hati (manah), dan Ki Ageng adalah tubuhnya (raga).[7]
Warisan KAS Untuk Bangsa
Salah satu ceramah publik pertama KAS diterbitkan dan diberi komentar oleh M. Soedi,[8] kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh R. Imam Moehni dengan judul Inwijding tot het eeuwigdurende geluk van B.R.M. Soerjomentaram (Pengantar untuk Kebahagiaan Abadi, terbit 9 Maret, 1930).[9] Penerjemah memberikan sebuah penjelasan tentang istilah-istilah Jawa yang digunakan KAS dalam sebuah pengantar panjang, serta memberikan komentar-komentar atas pernyataan-pernyataan KAS, yang waktu itu masih menyandang sebutan “Pangeran.” Dengan cara yang sama, di Surakarta pada 1931, dasar-dasar ajaran KAS juga diterbitkan namun dalam bentuk yang lebih lengkap.[10] Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa sejak saat itu KAS telah memiliki sejumlah pengikut yang menyebarkan gagasan-gagasannya.
Pada 1932 dilanjutkan dengan pertemuan yang bertajuk Junggring Salaka Agung—sebuah pertemuan tahunan untuk mempertemukan perwakilan-perwakilan dari perkumpulan pelajar di berbagai daerah.[11] Namun, KAS dan para pengikutnya menolak untuk membuat sebuah perkumpulan yang terstruktur: perkumpulan-perkumpulan tersebut tidak terbentuk secara formal, para pengikutnya tidak diwajibkan membayar iuran masuk dan dapat keluar dari perkumpulan sewaktu-waktu ketika mereka menghendakinya—perlu disebutkan bahwa kelompok belajar itu dapat diselenggarakan hanya oleh dua orang, bersifat luwes (non-directive), dan tak seorang pun diperkenankan mengklaim dirinya sebagai guru, bahkan Suryomentaram sendiri, yang oleh para pengikutnya hanya disebut sebagai “bangkokan”.[12] Meski begitu, sejenis panitia lokal tetap dibutuhkan untuk bekerja sama dan menjalin koordinasi dengan panitia umum (Panitya Umum) yang berkedudukan di Surakarta.
KAS juga menyampaikan ceramah yang beraroma nasionalistik (Raos Pantja Sila merupakan ceramah yang disampaikan pada 1955).
Hanya sedikit organisasi atau bahkan nyaris tidak ada yang bisa dianggap sebagai wadah bagi penyebaran pemikiran-pemikiran KAS. Yang muncul di tahun 1930-an hanyalah sejenis gerakan, seperti sebuah pertemuan yang diikuti dengan pertemuan lainnya (meskipun demikian, hal ini tetap penting untuk dilihat sebagai penanda bagi perluasan gagasan-gagasan KAS waktu itu—penerj.). Pertemuan-pertemuan awal tersebut mengundang sejumlah opini bernada mengejek, meski kemudian segera lenyap. Bagaimanapun juga, setelah Junggring Salaka Agung menyelenggarakan sejumlah diskusi dan publikasi, ajaran-ajaran KAS kemudian menjadi lebih mapan. Pertemuan di Yogyakarta pada 1937 merupakan yang terakhir diselenggarakan sebelum perang. Apakah kemudian gerakan tersebut kehilangan momentum? Selama pendudukan Jepang, memang benar bahwa situasi negeri ini tidak memungkinkan bagi tumbuhnya diskusi-diskusi filosofis tentang kebahagiaan personal sebagaimana yang dilahirkan KAS. Seperti yang sudah diungkapkan, KAS yang disibukkan oleh perlawanan terhadap kekuasaan penjajah ikut terlibat dalam arena politik dan mendukung semangat perlawanan yang bisa dilihat dari keikutsertaannya dalam perlawanan terhadap kembalinya Belanda. Namun Ki Ageng tidak kekurangan pengikut. Pada 1948, setelah terjadi Peristiwa Madiun, dia menyampaikan sebuah seruan untuk persatuan kepada para pengikutnya melalui Djawah Kawruh, terbitan berkala yang dia dirikan namun hanya mampu terbit selama dua bulan. Sejak awal 1950-an, ketika suasana damai mulai terwujud, dia mulai sering berkunjung ke daerah-daerah untuk menghidupkan kembali perkumpulan-perkumpulan di daerah. Dia memberikan sejumlah kuliah di Jawa Barat (Jakarta, Bogor, Cianjur, Bandung) untuk mengenalkan gerakannya.[13]
Pada penyelenggaraan Junggring Salaka Agung di Megelang tahun 1953, dia menjelaskan dasar-dasar tentang dimensi keempat (ukuran kaping sekawan), sebuah gagasan yang disebarkan dalam majalah Dudu Kowe, publikasi lainnya yang juga berumur pendek.[14] Pada 1953 juga berdiri yayasan penerbitan Windu Kentjana di Surakarta, yang menerbitkan atau menerbitkan ulang ceramah-ceramah KAS. Bersamaan dengan itu, di Magelang Ki Djasoewadi juga mendirikan perusahaan dengan nama CV Harapan yang menerbitkan karya-karya KAS. Sejak saat itu, penyebarluasan gagasan-gagasan filosofis KAS semakin berkembang dan telah memberikan pemasukan rutin bagi perkumpulan. KAS sendiri kemudian berterima kasih atas penerbitan itu karena sedikit banyak dia juga menerima pemasukan darinya.[15]
Meski Ki Ageng sering kali membuat (pernyataan) serangan-serangan terhadap irasionalitas yang diajarkan dalam kebatinan, dan secara terang-terangan memisahkan dirinya dari kecenderungan tersebut, namun dia (ternyata) tidak bisa sepenuhnya menghindari penilaian yang menganggap bahwa gerakan Kawruh Jiwa juga sebuah aliran di mana dia sendiri bertindak sebagai seorang guru.
Dapatkah gerakan ini dikatakan sepenuhnya memisahkan diri dari kehidupan politik, sebagaimana dikehendaki oleh para pemimpinnya? Untuk menilai hal ini, kita bisa melihat misalnya melalui selebaran yang dibuat oleh Panitya Kawruh Jiwa Klaten di tahun-tahun menjelang pemilu 1955. Ternyata perkumpulan ini tidak sepenuhnya steril dari politik, karena dalam selebaran tersebut terdapat sebuah syair yang disenandungkan dengan diiringi gamelan (sendhoman) yang menyerukan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Keterlibatan tersebut merupakan wujud sumbangsih bagi perkembangan negeri, serta sarana untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan rakyat (wong cilik).[16] Seperti yang bisa dilihat, pada tahun-tahun itu KAS sendiri juga menyampaikan ceramah yang agak berbeda, yaitu ceramah yang beraroma nasionalistik (Raos Pantja Sila merupakan ceramah yang disampaikan pada 1955).
Selama masa kolonial dan pendudukan Jepang, beberapa kali gerakan Kawruh Jiwa menjadi sasaran kecurigaan. Ketika kemerdekaan telah diraih, pelajar disarankan untuk menunjukkan rasa hormat dan kepedulian kepada mereka yang ingin mengenal gerakan ini: semua buku yang dipelajari, di mana KAS sendiri yang sepenuhnya bertanggung jawab, harus ditunjukkan secara jujur kepada mereka yang kemungkinan akan atau ingin meneliti.[17]
Meski Ki Ageng sering kali membuat (pernyataan) serangan-serangan terhadap irasionalitas yang diajarkan dalam kebatinan, dan secara terang-terangan memisahkan dirinya dari kecenderungan tersebut, namun dia (ternyata) tidak bisa sepenuhnya menghindari penilaian yang menganggap bahwa gerakan Kawruh Jiwa juga sebuah aliran di mana dia sendiri bertindak sebagai seorang guru. Apakah hanya kesalahan penilaian yang dibuat oleh para pengamat, atau semata penilaian berdasar fakta yang nampak dari luar dan dari perilaku-perilaku tertentu yang ditunjukkan oleh para pelajar, gerakan ini bisa dibilang menunjukkan semua ciri dari sebuah “aliran kebatinan”. Dalam sebuah kesempatan, Clifford Geertz memasukkan gerakan Kawruh Jiwa ke dalam aliran kebatinan, berdasarkan pada pengamatannya dan komentar-komentar yang disampaikan oleh seorang guru Kawruh Jiwa dari Pare (sebuah kota kecamatan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur). Namun demikian, bagi Geertz sendiri gerakan ini lebih memilih menggunakan “analisis fenomenologis” (untuk menemukan/mencapai kebenaran—penerj.) ketimbang meditasi/semedhi, sebuah teknik yang merupakan bagian terpenting dari ajaran-ajaran kebatinan.[18] Ketika Ki Ageng meninggal, sebuah tulisan yang dimuat di terbitan berkala Varia menyebutkan bahwa dia merupakan “tokoh di dalam dunia kebatinan”.[19] Dalam sebuah entri “Surya Mataram, Ki Ageng” yang tercantum dalam Ensiklopedi Umum (hal. 1270–71), disebutkan informasi: ‘Pangeran Surya Mataram yang kemudian menggunakan nama Ki Ageng adalah guru dari aliran kebatinan yang dikenal sebagai Ilmu Begdja. Pengikutnya tersebar luas dan berasal dari berbagai daerah, meski kurang ada informasi dan organisasi yang bisa menjelaskan gerakan ini. Ajarannya disampaikan melalui ceramah-ceramah di hadapan para peserta yang duduk “lesehan” (Jawa: duduk di atas lantai/tanah)….’ Namun pada 1953 gerakan Kawruh Jiwa tidak dimasukkan sebagai aliran kebatinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.[20]
Pada pertemuan Junggring Salaka yang terakhir, digelar di Purwokerto[21] tahun 1959, dibagikan buku kecil kepada para peserta yang di dalamnya terdapat fakta-fakta menarik seputar pertemuan dan informasi berharga tentang latar belakang sosial serta asal-usul para anggota.
Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh panitia lokal yang diketuai Ki Notoamidjojo. Setelah upacara pembukaan dan semua tamu telah menempati tempatnya, KAS memberikan sebuah ceramah. Selain itu, sebuah sandiwara dengan judul Tjipta Djiwa juga dimainkan selama dua hari saat pertemuan berlangsung. KAS memimpin debat dan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan komentar yang disampaikan oleh pelajar kepada sejumlah pembicara (KAS sendiri, Ki Kartosumanto, dan Ki Prono). Para peserta kemudian diminta untuk menyampaikan kesulitan-kesulitan serta perkembangan yang telah mereka capai dalam mempelajari “Ilmu Jiwa” di perkumpulan mereka masing-masing.
Nama para pelajar biasanya didahului oleh partikel ki untuk laki-laki dan nyi untuk perempuan (sebagaimana juga berlaku dalam gerakan Taman Siswa).
Dalam publikasi tercatat 257 nama dan alamat anggota panitia lokal yang berasal dari lima puluh kota di Jawa, baik kota besar maupun menengah. Terdapat sejumlah kota besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang bertanggung jawab menyebarluaskan informasi tentang pertumbuhan gerakan ke berbagai daerah. Di Temanggung, Magelang, juga Jember, terdapat lebih banyak panitia lokal daripada di kota-kota lainnya. Kota-kota dari bagian barat Pulau Jawa juga memiliki panitia, seperti Jakarta, Bogor, dan Bandung. Dalam dokumen tersebut juga tercatat perwakilan dari Madura dan Lampung.
Kecuali untuk Suryomentaram (Ki Ageng) dan Pronowiworo (Kyahi), nama para pelajar biasanya didahului oleh partikel ki untuk laki-laki dan nyi untuk perempuan (sebagaimana juga berlaku dalam gerakan Taman Siswa); jumlah peserta perempuan jauh lebih sedikit dibanding peserta laki-laki. Disebutkan juga perihal latar belakang profesi para peserta: pegawai, guru sekolah rakyat, kepala desa, mantri pengairan, dan bahkan dalang. Meski sejumlah pegawai tinggal di kauman, sangat sedikit yang menggunakan nama-nama bernuansa Islam. Nama-nama Cina juga jarang; namun kontribusi keuangan mereka, yang bisa dilihat dari iklan-iklan yang tercantum dalam selebaran publikasi tentang sejumlah usaha yang mereka kelola (batik, percetakan, otobus, dan pusat-pusat perbelanjaan), tetap penting. Perlu juga disebut bahwa tidak ada nama yang berakhiran ningrat (sebuah indikasi kehormatan), dan berdasarkan nama serta profesi yang telah tercatat, mereka umumnya berasal dari golongan priyayi kelas menengah atau rendah.
Setelah penyelenggaraan kongres yang terakhir ini, KAS hanya menyisakan tiga tahun waktu hidupnya, dan dalam beberapa bulan dia dalam keadaan sakit. Setelah kematiannya, para pengikutnya di Yogyakarta kemudian mengumpulkan karya-karya KAS dan menerbitkannya dengan Ki Atmosutidjo sebagai pemimpin dan pemberi dukungan moral. Beberapa publikasi selanjutnya diedarkan.[22]
Hari ini (merujuk tahun ’60-an, setelah kematian Ki Ageng—penerj.), di kota tempat pemerintahan Kesultanan Yogyakarta pada zaman dulu, perkumpulan Kawruh Jiwa yang dipimpin oleh Ki Haditomo, selalu menyelenggarakan pertemuan setiap 35 hari, yaitu setiap Minggu Pon, hari di mana sang Filsuf wafat. Terlihat juga Nyi Suryomentaram, janda KAS, berperan dalam menyebarluaskan ajaran-ajaran suaminya. Sementara Grangsang (putra dari pernikahan pertama KAS) dianggap sebagai pewaris ajaran spiritual sang ayah dan sosok yang akan melanjutkan gerakan tersebut. Meski tanggung jawab profesionalnya (Grangsang adalah dokter di kesatuan Angkatan Laut berpangkat letnan kolonel) sering kali membuatnya harus meninggalkan tugas memimpin perkumpulan, namun dia tetap berusaha menghidupkan gagasan-gagasan ayahnya dengan dibantu oleh Ki Oto Suastika dan Yayasan Idayu; dia juga berkomitmen untuk membangun/mengembangkan gerakan yang telah ayahnya rintis.
Bersambung…
Baca juga:
Ki Ageng Suryomentaram: Pangeran dan Filsuf dari Jawa (1892–1962) Bagian IV – Habis
Ki Ageng Suryomentaram: Pangeran dan Filsuf dari Jawa (1892-1962) Bagian I
Ki Ageng Suryomentaram: Pangeran dan Filsuf dari Jawa (1892–1962) Bagian II
Catatan Kaki:
[1.] Bagian yang paling menjelaskan prosedur ini terdapat dalam Tandesan.
[2.] Raos Pantja Sila, hal. 5.
[3.] Cf. Filsafat Rasa Hidup, hal. 7.
[4.] Ki Sangoebrangta, “Pendidikan oentoek ketentraman doenia, wedjangan Toeankoe Pangeran Soerjamataram (Kiai Ageng Beringin),” dalam Poesara 1: 10 (Januari 1932).
[5.] Dalam wayang, Junggring Salaka dijelaskan sebagai rumah para dewa dan tempat mereka menyelenggarakan pertemuan.
[6.] Dalam bagian Uran-uran Bedja.
[7.] Dari sebuah wawancara dengan Ki Haditomo (Mei 1975).
[8.] M. Soedi, Ngelmi–Kawruh–Pitedah. Edisi keenam karya ini menyertakan sebuah pengantar tertanggal 15 April 1929. Sulit untuk menyusun kronologi terhadap publikasi-publikasi yang paling awal; seperti Uran-uran Bedja dan Pangawikan pribadi (kemungkinan ditulis oleh Prawirowiworo), kemungkinan terbit tahun-tahun itu juga.
[9.] Penulis berterima kasih kepada Mr. Tsuchiya yang telah menyediakan tulisan ini.
[10.] Wedjangan.
[11.] Junggring Salaka yang pertama diselenggarakan di Salatiga; pada 1933 diselenggarakan di Surakarta, 1934 di Kudus, 1935 di Madiun, 1936 di Wonosobo, dan 1937 di Yogyakarta. Setelah jeda selama tiga belas tahun, Junggring Salaka yang ketujuh diselenggarakan di Magelang pada 1953, kemudian di Surabaya pada 1954, di Semarang pada 1956, di Tulungagung pada 1957, dan yang terakhir di Purwokerto pada 1959. Dalam buku peringatan untuk pertemuan yang terakhir ini (21, 22, 23 Maret), sebuah tulisan Kjai Pronowidigdo menjelaskan tentang sejarah gerakan Kawruh Jiwa (“Riwajatipun Kawruh Djiwa”).
[12.] Istilah ini digunakan untuk merujuk binatang tertentu yang karena kekuatan dan usianya kemudian dianggap lebih mampu untuk memimpin kelompoknya. Istilah tersebut dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai “patriarch”.
[13.] Pada 1952 di Jakarta dia berbicara kepada Panitya Filsafat dan Kebatinan (Philosophical and Kebatinan Commitee), kepada Yayasan Hidup Bahagia (Happy Life Foundation) yang diketuai oleh Mr. Wongsonegoro, dan kepada perkumpulan masyarakat Cina, yakni Sam Kauw Hwee dan Khong Kauw Hwee.
[14.] Peristiwa tersebut juga dimuat dalam terbitan berkala Siaran.
[15.] Dari wawancara dengan Ki Haditomo.
[16.] Sendona bab Pemilihan Umum.
[17.] “Manawi Junggring Salaka kedhatengan wakiling Pamarintah ingkang gadhah tugas naliti pakempalan-pakempalan dan grombolan-grombolan kanca-kanca cekap namung nyaturaken buku-buku Kawruh Jiwa wau….” (Buku Peringatan).
[18.] Clifford Geertz, The Religion of Java, 2nd ed. (Chicago dan London: University of Chicago Press, 1976), hal. 344–345.
[19.] Varia 5: 206 (28 Maret 1962). Tulisan tersebut ditulis oleh Siauw Tik Kwie, seorang Pelajar Kawruh Jiwa yang kemudian menjadi penerjemah karya-karya KAS yang diterbitkan oleh Yayasan Idayu dengan nama Ki Oto Suastika.
[20.] Republik Indonesia: Daerah Istimewa Jogjakarta (Jakarta: Kementrian Penerangan, 1953); cf. hal. 675–82.
[21.] Lihat catatan 54.
[22.] Ki Atmosutidjo, Gandulan… ; Ki Djojodinomo, Ular-ular… ; Ki Suwardi Partosardjono, Sadjimpit Hatsil… (diterbitkan oleh Panitya Kawruh Jiwa di Magelang yang tetap aktif pada 1970).